LANGIT seperti terbelah di ujung ufuk. Sebongkah bintang besar melayang di tengah cakrawala, menyemburatkan pendar cahaya dari sisi paling timur Pulau Bali. Laut yang semula gelap, mendadak bersinar seperti lembaran perak cair yang dipulas tangan tak terlihat.
Ketika bintang bulat sempurna itu terang-terangan menggantung di sana, aku melihat segala sesuatu di bawahnya perlahan berubah. Ada cercahan warna menyatu dengan ombak yang datang ke titik pertemuan dua samudra dari Pasifik dan Hindia, menciptakan pantulan berkilauan seturut waktu berdetak yang di dalam dadaku.
Yang saat itu aku lihat dengan mata kepalaku sendiri adalah persilangan ombak dan samudra yang menghasilkan irisan-irisan berwarna kuning, merah, dan biru, sementara angin membiasnya dari semenanjung Selat Lombok. Lamat-lamat semua berangsur menuju ke tepian di bawahnya—garis pantai ini, tempat di mana aku dan penduduk setempat memanjatkan doa dan mengadu nasib kami pada alam. Sebagai bagian dari keseharian nelayan Pantai Karang yang diwariskan para pendahulu di desa ini, aku merasa seakan-akan semua orkestrasi yang tersaji di hadapanku ini, telah mengintai kami sejak jutaan tahun lamanya—diam-diam dan penuh rahasia.
Meski momen-momen seperti ini sudah puluhan tahun kusimak, ia tak pernah gagal mengubahku kembali menjadi bocah yang baru saja menemukan ketakjuban pertama di dalam hidup—sama seperti masa kecilku dulu, saat keluargaku masih hidup.
Di sini, saat ini, seketika aku ingat Abang. Bersama Ayah, mereka berdua selalu melaut pagi-pagi dan kembali di sore hari dengan tangkapan ikan yang banyak. “Berkat insting abangmu yang makin terasah di selat, kita makan banyak hari ini, Nak,” ucap Ayah sambil memamerkan hasil tangkapan mereka. Dipuji Ayah begitu, Abang menaikkan satu alisnya sambil melirik ke arahku, seakan berkata bahwa suatu saat aku juga bisa melakukannya.
Tapi sampai lewat kepala tiga di umurku sekarang, aku belum pernah mencoba melakukannya. Aku belum dan mungkin tak akan berani mencobanya. Sebab selat yang Ayah dan Abang maksud itu bukan selat biasa. Aku mengingatnya lagi, sama seperti aku mengingat cerita dari seorang nelayan tua dari negeri jauh yang membeberkan betapa wilayah tempat tinggal kami lebih dari sekadar garis demarkasi. Pasalnya, garis pantai Desa Karang diapit Laut Bali yang membentang 270 derajat di sisi timur ke selatan dengan triangulasi deretan pegunungan yang melengkapi panorama dari barat ke utara.
“Alkisah di suatu masa, ada satu titik selat yang bisa dicapai melewat pantai tersembunyi dan hanya sejumlah nelayan saja yang tahu dimana persis letaknya. Bila nelayan berangkat melaut menuju titik selat itu lewat pantai rahasia tadi, kelak mereka akan pulang dengan hasil tangkapan ikan yang banyak. Yang perlu jadi catatan, momen terbit dan tenggelamnya matahari di pantai rahasia itu kerap tertukar berganti peran dan bersaling-silang. Kita dan siapa saja yang melihatnya, akan keliru membedakan mana waktu fajar mana waktu senja sebab dimensi waktu tak bergerak secara linear di wilayah itu. Yang terjadi kemudian, satu persatu dari kita dan siapa saja yang melihatnya hanya mampu terdiam dengan mulut menganga, mata membelalak dan tubuh berkedut-kedut. Sontak, kita dan siapa saja yang melihatnya akan mengeluarkan liur, air mata, kotoran telinga, hingga tahi tanpa henti sampai sekujur tubuh memuncratkan darah hitam dari seluruh kelopak panca indera. Hitam, sekelam pasir pantai yang diinjak di bawahnya. Karena ia dianggap membahayakan oleh petinggi adat, sejak saat itu akses ke pantai rahasia pun ditutup untuk publik. Keberadaannya lantas disembunyikan untuk menjaga kesuciannya. Konon gara-gara perkara anomali geografis tersebut, pantai terlarang itu kemudian hanya diperuntukkan sebagai tempat upacara rahasia,” ucap nelayan tua.
Entahlah, aku sendiri masih kurang paham. Bertahun-tahun setelah cerita nelayan tua itu kudengar pertama kali, aku mulai sadar bahwa selama ini banyak lelaki nelayan di desa kami yang dikabarkan hilang saat melaut. Mungkin mereka nekat melintas ke pantai larangan dan beranjak melaut menuju selat dari sana dengan harapan mendapatkan banyak tangkapan ikan. Menurut hematku dari pelajaran yang kudapat dari guru geografi di sekolah dasar, semenanjung garis pantai di Bali bagian timur memang rentan ombak pasang, angin kencang dan batu karang menjulang. Tetapi semua penduduk di sini, sudah bertahun-tahun lampau menganggap semua lelaki yang menghilang itu disembunyikan oleh lelembut.
Seiring angin fajar berhembus, aroma garam yang masuk dengan tajam ke sela-sela hidung membuat kepalaku pusing setiap kali mengingat hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu. Angin yang sama juga mengantarkan dinginnya air berangsur-angsur merebah ke sela jari-jemari—seolah-olah mereka semua ingin membangunkanku dari kekosongan yang perlahan merayap di sela-sela pikiranku karena selalu bergerak lebih cepat dari semesta.
Aku terkesiap dari lamunan. Jantung berdegup cepat seiring keringat menetes dari telapak tanganku. Dan begitu tapak kakiku mulai menindih pasir berwarna hitam pekat di titik pantai ini persis seperti yang digambarkan sang nelayan tua, fragmen-fragmen ingatan tentang mitos desa Karang seketika menyeruap ke udara. Terlebih ayah dan abang sudah lama tak kujumpai sejak mereka dinyatakan meninggal karena menghilang di tengah laut dan jasad mereka tak pernah ditemukan.
Di sela-sela jemari, aku menggenggam secarik kertas yang kubawa dari rumah. Sudah lama kutemukan secara tak sengaja sobekan kertas di buku catatan lama ayah. Kini, tulisan hampir pudar itu menjadi satu-satunya penuntunku yang tersisa.
8°21’52.7″S 115°42’2.4″E
Nyanin ring panggilan lintang, ulihange irika ia magunggu.[1]
Di balik carik lusuh itu, tinta hitam mulai pudar menampilkan coretan angka yang seperti dibuat tergesa-gesa. Di baliknya, ada kalimat yang tak sepenuhnya kumengerti. Garis-garis samar menyerupai peta menunjuk ke sebuah lokasi asing. Dengan modal perhitungan sederhana dari bintang dan pengetahuanku yang serba terbatas, aku memutuskan mengikuti petunjuk itu.
Dan di sinilah aku sekarang. Di momen menjelang fajar dari sebuah titik yang aku yakini sebagai Pantai Larang: tersembunyi di hadapan laut yang luas dan sunyi. Tempat ini terasa asing dan nyaris mustahil ditemukan, namun terasa akrab dalam mimpi-mimpiku. Pasir hitamnya berkilau halus dalam cahaya samar. Rupa-rupanya catatan ini membawaku ke sebuah titik di hadapanku sekarang yang seumur-umur tak pernah aku kunjungi, sebuah tubir pantai yang sepi dan tampak tak berpenghuni.
Wangi dupa tercium semakin jelas entah dari mana asalnya. Jantungku berdegup lebih cepat. Ini bukan sekadar pantai biasa. Tubir pantai ini memiliki aura berbeda, hampir seperti melangkah ke dunia lain. Sejuta pertanyaan sontak menyerang: Apakah ini pantai rahasia yang dulu kudengar kisahnya dari nelayan tua? Salahkah aku menginjakkan kaki di tempat yang sepertinya sakral dan hanya dibolehkan untuk upacara adat? Atau mungkinkah ini titik cerah bagi diriku setidaknya untuk menemukan secuil titik terang hilangnya Abang dan Ayah?
Namun, aku tak memiliki pilihan lain. Selama berbulan-bulan, hal yang sama terus menghantuiku. Aku terpaksa melakukannya karena sudah beberapa bulan ini aku memimpikan hal sama berulang-ulang: abang terkatung-katung di tengah laut berteriak meminta pertolongan. Jukungnya[2] terbelah, terjebak di atas karang.
Wajah itu, adalah wajah yang penuh harap berteriak memanggil-manggil, seolah aku adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Mimpi itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dan gambarannya cukup terasa nyata sampai aku bergidik terbangun dini hari sekali.
***
Dini hari sekali Ayah membangunkan Abang. “Nak, ayo ikut. Kita akan melaut lebih pagi dari biasanya,” bisiknya, tegas dan mendesak. Abang mendusin. Suara grusak grusuk kemudian terdengar dari gudang di luar rumah. Postur Ayah yang tinggi besar tampak mondar-mandir seperti menyiapkan sesuatu yang tidak biasa.
Dari bilik kamar mereka yang cuma sepetak, bayangan ayah melintas di sela-sela redup lampu bertenaga minyak. Adik masih terlelap di balik ketiak ibu semenyara ayah memanggilnya berulang-ulang sambil bolak-balik membangunkan abang. Begitu genting, begitu nyaring, seperti keadaan yang sedang darurat.
“Tak ada waktu. Bersiap cepat!” Suara Ayah membuyarkan fantasi abang untuk lanjut tidur. Abang menyeret langkahnya sambil mengucek-ngucek mata keluar rumah. Berjalan ratusan meter sudah di belakang ayah, abang merasa ia berjalan ke arah yang tidak biasa tempat jukung mereka diparkir.
Jelang fajar nan gelap belum memburai di hadapan abang ketika langkah lakinya mencoba mengejar tapak-tapak kaki ayah yang tertinggal di atas pasir. Abang heran, mengapa pasir disini begitu kelamnya, berbeda dengan pasir di Pantai Karang tempat mereka biasa mulai melaut.
Ayah di depannya melaju, abang tak mau ketinggalan. Lagi, ia menyimak hal yang tak biasa: Ayah bergegas sambil mengangkat ponsel di tangan, bercakap memelas ke ujung lawan bicaranya. Bibirnya gemetar. Raut wajahnya kusut, seolah tak bisa menghindar.
“Sumpah, saya tidak sengaja. Video itu memang saya yang merekamnya, tapi saya tidak sadar kalau ia terunggah sendiri dan menjadi viral di media sosial. Tolong kami,” tandas Ayah.
Di antara gelap lantaran langit masih terlalu pagi, kilatan wajah Ayah berbicara menghadap ponsel terlihat jelas. Dari gawainya itu, Abang mengintip sebuah video terpampang diputar: seekor paus sperma mendarat di sebuah sudut pantai yang tak pernah ia lihat. Dari yang Abang simak, paus itu tak bergerak dan mati mengenaskan disorot dari dekat.
“Saya harus segera pergi. Koordinat lokasinya sudah saya tentukan,” tutup Ayah mengakhiri percakapan.
Abang makin tak mengerti apa yang ayah bicarakan. Baru kali ini Abang melihat Ayah seserius itu di telepon. Tapi jelas ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kematian paus yang Ayah bicarakan. Setengah mengantuk, abang mencoba berpikir, mengait-ngaitkan percakapan Ayah, menebak sesuatu dalam benaknya, tetapi semakin ia pikirkan, semakin jauh pula jawaban itu datang kepadanya. Ia harus menerima sesuatu yaitu banyak yang belum ia pahami. Tetapi ia membiarkan dirinya larut di dalam ketidaktahuan itu. Ia hanya percaya pada langkah kakinya, dan langkah kaki Ayah saja.
Di pantai asing itu, Ayah mengurut tali jangkar ‘Preman Laut’, nama jukung warisan keluarga yang tahu-tahu sudah ada di sana. Abang semakin heran, entah kapan Ayah memindahkannya dari pantai Karang ke pantai tak berpenghuni ini. Gelapnya langit di pantai ini memang terasa berbeda. Padahal normalnya, fajar sudah akan datang sesaat lagi.
Semakin dekat dengan ‘Preman Laut’, semakin keras pula keinginan abang untuk mengumpulkan semua pikiran-pikirannya yang tercecer carut marut. Bagai hantu gentayangan yang mencoba menjejak tanah, begitu pula berkali-kali ia mencoba untuk mengembalikan pikirannya sendiri dan mencoba benar-benar membuka matanya.
Dalam kantuknya yang masih tersisa, abang mulai bertanya-tanya dalam dirinya, mengapa di pantai ini waktu tidak seperti biasanya? Dan di sini, ia dapati sungguh hal-hal yang di luar biasanya. Apakah ini mimpi? Tetapi ketika Abang melihat sosok Ayah yang nyata di hadapannya, ia begitu yakin, bahwa ini bukan mimpi. Nyata ataupun tidak wilayah ini, di sinilah ia sekarang: tersembunyi di hadapan laut yang luas dan sunyi. Tempat ini terasa asing dan nyaris mustahil ditemukan, namun terasa akrab dalam ingatan-ingatannya. Pasir hitamnya berkilau halus dalam cahaya samar. Rupa-rupanya Ayah membawaku ke sebuah titik di hadapanku sekarang yang seumur-umur tak pernah Abang kunjungi, sebuah tubir pantai yang sepi dan tampak tak berpenghuni.
Wangi dupa tercium semakin jelas entah dari mana asalnya. Jantung abang berdegup lebih cepat. Ini bukan sekadar pantai biasa. Tubir pantai ini memiliki aura berbeda, hampir seperti melangkah ke dunia lain. Sejuta ingatan sontak menyerang: abang ingat sebuah pantai rahasia yang dulu pernah Ayah ceritakan ulang dari kisah seorang nelayan tua yang menghilang di tengah laut.
Abang terkesiap dari lamunan. Keringat menetes dari telapak tangannya. Dan begitu tapak kakinya terus menindih pasir berwarna hitam pekat di titik pantai ini persis seperti yang digambarkan sang nelayan tua, fragmen-fragmen ingatan tentang mitos desa Karang seketika menyeruap ke udara. Abang yakin di sinilah ia sekarang. Di momen menjelang fajar dari sebuah titik yang ia yakini sebagai Pantai Larang.
Namun, Abang tak memiliki pilihan lain. Di kejauhan, abang melihat sebuah gapura kecil yang berada di tengah-tengah laut bertorehkan aksara kuno[3]:
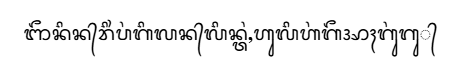
Jukung mereka berjalan menuju ke arahnya seiring jantung abang yang berdegup lebih cepat lagi. Ayah kali ini benar-benar menarik jangkar Preman Laut dan membawa mereka berdua melarung laut dari tubir Pantai Larang.
Bau dupa kembali menyengat, bau yang sama seperti yang dicium Abang saat masuk ke Pantai Larang. Dan anehnya, kali ini wanginya jelas-jelas berasal dari dalam laut. Di saat bersamaan, langit seperti terbelah di ujung ufuk. Sebongkah bintang besar melayang di tengah cakrawala, menyemburatkan pendar cahaya dari sisi paling timur pulau Bali. Laut yang semula gelap, mendadak bersinar seperti lembaran perak cair yang dipulas tangan tak terlihat.
Ketika bintang bulat sempurna itu terang-terangan menggantung di sana, abang melihat segala sesuatu di bawahnya perlahan berubah. Yang saat itu ia lihat dengan mata kepalanya sendiri, muncul barisan siluet-siluet rancak berbaris melewati gapura. Siluet-siluet itu tampak seperti barisan manusia yang semakin lama makin mirip dengan warga Banjar. Tampak sosok seorang pemangku adat muncul paling depan, berjalan hikmat seiring puluhan pemedek[4] mengikutinya dari ujung garis pantai di belakang. Mereka berduyun-duyun berbaris dari pantai menuju jalur yang tegak lurus menembus gapura sampai ke titik di bawah laut. Semua tampak mengenakan pakaian adat lengkap dengan kain, kamen, selendang, udeng dan baju putih berjalan beriringan menuju ke lokasi yang ternyata sebuah Pura terletak tepat di bawah jukung mereka.
Kali ini Abang benar-benar membelalakkan mata karena langit mulai terang. Pantulan matahari meyakinkan dirinya kalau ia tak salah lihat. Berada tiga puluh meter di bawah permukaan laut, ada sebuah pura di bawah laut dengan ornamen gerbang Candi Bentar, patung-patung Hindu seperti Ganesha dan Buddha, serta pelinggih yang menyerupai Pura di daratan. Mulut abang menganga melihat jelas prosesi selanjutnya.
Abang tahu kalau ini adalah sebuah upacara adat seperti ngaben yang biasanya dilakukan warga banjar, tapi ini bukan prosesi umum upacara ngaben yang ia kenal. Samar-samar ia melihat ibu dan adik berbaris di antaranya. Abang merasa ia pasti berhalusinasi.
Tepat di titik ini, di koordinat yang tak jauh dari pura bawah laut tadi, tiba-tiba terdengar bunyi keras menggelegar. Jukung yang abang dan Ayah naiki menabrak sesuatu yang besar dan tajam. Jukung mereka berguncang hebat, kayunya berderak seakan hendak retak, dan ombak yang semula tenang tiba-tiba beriak liar di sekeliling mereka. Abang terhuyung, hampir saja ia terlempar ke laut kalau tidak dengan sigap mencengkeram tepian jukung.
Dentuman itu tidak hanya mengguncang tempat ia berdiri, tetapi juga seakan merobek ruang di sekitarnya. Air laut di bawah mereka berpendar sesaat—seperti kaca yang retak—menciptakan riak yang tidak seharusnya ada. Waktu terasa melambat. Suara ombak mendistorsi, berubah menjadi dengungan panjang yang menggema di udara.
Lalu, di bawahnya, hal mustahil terjadi.
Berpuluh-puluh jukung lain muncul, saling menabrak dalam kekacauan yang seolah tak mengenal batas waktu. Dentuman kayu dan besi beradu bertalu-talu, membentuk simfoni paling mengerikan yang pernah abang dengar. Di atas masing-masing jukung itu berdiri sosok-sosok lelaki—diam, kaku, dan kosong. Puluhan pasang mata menatapnya, tatapan yang tak mengenal dunia ini lagi.
Di balik pecahan realitas itu, abang tak tahu kalau semua sosok ini adalah lelaki-lelaki yang pernah menghilang di tengah laut, terjebak dalam pusaran waktu yang tak pernah mencatat nama mereka. Ada yang memakai kain sarung nelayan dari abad lampau, ada yang ada yang berbaju seperti awak kapal dagang Belanda, berseragam prajurit Jepang, sampai ada pula yang kurus bertelanjang dada dengan luka memanjang di punggungnya dan selebaran merah pudar bergambar palu arit di saku celana lusuhnya. Mereka semua datang dari era yang berbeda-beda, namun bernasib sama. Dan kini mereka semua menatapnya. Seolah Abang adalah bagian dari takdir mereka yang belum selesai.
Merasa ketakutan luar biasa, Abang berteriak ke arah Adik dan Ibu di Pura bawah laut yang makin lama makin menjauh.
Sejenak, segalanya berhenti.
Laut seperti menahan napas. Udara jelas tertahan dalam sorak sorai riang yang sunyi. Riak ombak yang seharusnya menyusul tubrukan itu justru tak datang-datang. Seperti ada sesuatu yang menahan waktu.
Tidak ada suara air, tidak ada seruan kaget, tidak ada dentuman kayu pecah yang seharusnya menggema. Hanya ada ruang kosong yang menganga.
***
Hanya ada ruang kosong yang menganga sebelum langit kami belah. Di ujung ufuk, kami layangkan sebongkah bintang besar ke tengah cakrawala. Semburat cahaya berpendar dari sisi paling timur Pulau Bali. Dan laut ini, laut yang semula gelap, akan mendadak bersinar seperti lembaran perak cair berkat pulasan tangan kami.
Kalau kalian sudah bisa menebak bagaimana bintang itu membulat sempurna dan terang-terangan menggantung di sana, mungkin kalian juga mulai melihat lebih jelas segala sesuatu di bawahnya—perlahan-lahan berubah sejak kisah ini dimulai dari paragraf pertama.
Tentu kami tak perlu mengulang lagi ocehan tentang bagaimana cercahan warna menyatu dengan ombak. Keduanya sudah pasti datang dari titik pertemuan dua samudra, menciptakan selat dengan tangkapan ikan paling banyak bagi mereka yang berhasil menemukan jalur tepat dari Pantai Larang. Pantai ini, sudah pasti adalah pantai rahasia yang sama yang diceritakan nelayan tua dan dilarang pemuka adat. Sebab bagi kami, melangkah ke dunia lain, dari satuan waktu ke satuan waktu berbeda, bukanlah hal sulit. Begitu pula kemampuan kami berpindah dari satu bagian ke bagian lain dalam kisah yang sedang kalian baca ini.
Bagi sosok astral seperti kami, menyaksikan secara paralel bagaimana lelaki-lelaki lain—abang-abang lain, ayah-ayah lain—di segala zaman menghilang di tengah laut, bergerak dalam semestanya masing-masing, saling berkelindan dengan cara yang halus adalah hal yang sudah digariskan. Setidaknya, demikian yang diinginkan oleh sang empunya semesta cerita, yang konon tak bisa kusebutkan namanya di paragraf ini.
Yang tak bisa kami terima sampai sekarang adalah bagaimana kaum manusia menyalahkan kami atas hilangnya lelaki-lelaki itu di tengah laut. Dalam rangka itulah kami terpaksa hadir di penghujung kisah ini, untuk mengungkapkan suara kaum terpinggirkan seperti kami. Sebab kebanyakan kaum manusia di pulau ini lebih suka menyebut nama kami dengan nada takut, menunjuk tanpa bertanya, dan memaknai kehilangan dengan satu jawaban yang mudah. “Mereka disembunyikan lelembut,” begitu kata mereka yang enggan berpikir lebih dalam. Seakan hanya muslihatlah yang bisa menjelaskan segalanya. Seakan-akan hanya kami yang pantas menjadi kambing hitam.
Padahal kalau disimak logika, selat yang kalian simak di kisah ini memang jalur yang berbahaya untuk melaut. Wajar kalau mereka hilang karena gelombang laut besar yang datang menuju daratan bertemu dengan garis pantai yang kemudian mengalir ke samping. Sementara gelombang lain menyebabkan arus saling bertabrakan dan kembali mengarah ke laut lepas. Arus balik ke laut inilah yang berbahaya karena memiliki tenaga dan kecepatan yang luar biasa dibandingkan dengan kekuatan alat transportasi laut dan kemampuan berenang manusia.
Yang membuat ini menjadi rumit, setiap zaman punya alasannya sendiri-sendiri mengapa banyak lelaki yang hilang disana. Di masa pra-kolonial, keterbatasan navigasi dan teknologi transportasi laut sudah menjadi kendala. Kemudian, di masa akhir Perang Dunia II—saat adik dan abang bertemu dengan prajurit Jepang yang terdampar di pantai Karang—banyak dari mereka lenyap akibat perlawanan para gerilyawan yang menyerang kapal perang US dan Jepang, menyabotase, dan menenggelamkan kapal-kapal itu hingga ke dasar lautan.
Pantai Larang pun menyimpan luka sejarah yang dalam. Di masa penghilangan paksa simpatisan partai tahun ’65, ratusan lelaki dihukum tanpa proses pengadilan, dibawa ke pantai itu untuk dieksekusi dengan metode penyiksaan yang tak terbayangkan.
Tak ketinggalan, di era oligarki seperti sekarang, ketika pemerintah berkolusi dengan pengusaha asing untuk mengeksploitasi alam, kematian sejumlah paus yang ditemukan di Pantai Larang hanyalah salah satu pertanda bahwa keseimbangan alam telah terganggu sejak lama.
Kami tak tahu berapa banyak lagi lelaki manusia yang akan hilang atau dihilangkan oleh sesamanya. Yang jelas dalam waktu dekat—di tubir pantai yang tak akan lagi jadi rahasia berkat eksploitasi atas nama pembangunan—turis asing akan berbondong-bondong melihat keindahan subtil Pantai Larang versi lain dengan mulut yang kian menganga: untuk pertama kalinya dalam sejarah kaum manusia, mereka akan menyaksikan fajar dan senja diiringi gelombang sampah plastik beradu dan saling berayun menghasilkan irisan-irisan kuning bekas bungkus margarin, irisan-irisan merah bekas wadah deterjen dan irisan-irisan biru hasil sobekan label botol mineral.
Botol-botol plastik akan mengambang di air. Plastik kresek bakal tersangkut di antara biota laut. Kaleng-kaleng minuman hendak terguling di pasir dan berbunyi nyaring ketika ombak menyentuhnya. Tak ada lagi kesunyian, tak ada lagi kesucian. Hanya pantai yang dipenuhi sampah, riuh suara manusia yang datang berbondong-bondong, merayakan penemuan ini tanpa menyadari bahwa mereka telah membunuhnya.
Lamat-lamat sampah plastik akan berangsur menutup seluruh tepian di bawahnya—sekujur garis pantai ini, tempat kaum manusia terus memanjatkan doa dan memohon ampun pada semesta. Dan kami yang mengintai orkestrasi segalanya sejak jutaan tahun lamanya ini, sudah tidak bisa diam-diam lagi, sudah tak perlu rahasia-rahasia lagi. [T]
[1] Ke mana arah bintang memanggil, di sana ia menunggu.
[2] Perahu kecil bercadik kayu
[3] Nyanin ring panggilan lintang, ulihange irika ia magunggu. Idem.
[4] sebutan untuk orang yang melakukan persembahyangan di pura
Penulis: Pry S.
Editor: Adnyana Ole





























