JIKA saja pengarang B.M. Syamsuddin masih hidup, kemungkinan ia akan menulis cerita tentang orang-orang Pulau Rempang yang hendak digusur penguasa dan pengusaha (bahasa sekarang: oligarki) dengan eufisme relokasi. Orang-orang kecil penghuni kampung-kampung tua sejak masa nenek moyang itu bukan saja diserbu secara fisik dengan pentungan dan gas air mata, tetapi juga melalui stigma yang kembali mengapungkan aroma busuk rezim masa lalu. Melalui tuduhan-tuduhan tak berdasar warga disudutkan sedemikian rupa, mulai sebagai provokator dan memulai tindakan anarkis, tak punya sertifikat, penolak pembangunan hingga ungkapan kasar lagi garing: piting. Dan itu ramai-ramai dilakukan oleh pejabat tinggi negara hingga jendralnya, seolah masyarakat Rempang adalah musuh negara nomor satu yang meminta semua pejabat Jakarta hingga Batam angkat suara.
Meski demikian, jauh-jauh hari sebenarnya B.M. Syamsuddin sudah mengingatkan betapa tak ada ampunnya tangan-tangan kapital dan penguasa mata duitan mengayun palu godam di antara orang-orang pulau yang hanya mengandalkan kayuhan sampan dan kapal-kapal kecil bermesin tempel. Pembangunan industri, pengembangan kawasan, daerah tujuan wisata dan segala macam tetek-bengek sebutan itu sejatinya tidak memasukkan orang-orang kecil di pulau-pulau kecil sebagai daftar subjek-bernyawa, kecuali statistik-angka-angka. Jangankan untuk ambil bagian, untuk secelah akses lapangan kerja saja belum tentu mudah mereka dapatkan. Itulah yang dialami masyarakat pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Kalajengking yang dulu hanya punya satu titik kecil keramaian, dan kini populer sebagai akronim Pulau Batam (Batu Ampar).
Pulau Rempang juga sudah ia sebut sekilas dalam sebuah cerita yang amat menoreh batin, tentang seorang perempuan Melayu lokal yang terpaksa hidup jadi wanita penghibur…
Rum Kadariah semakin hanyut bersama tenggelamnya bayangan-bayangan rembulan yang mulai kelam di pangkal malam sedang berawan tebal. Pandangannya hanyut diterpa riak-riak membuih dipermainkan anak gelombang, tatkala perahu motor kaum penjaring lewat di perairan Sekupang arah ke Bulang-Rempang…(“Rum Kadariah”).
Di sisi lain, masyarakat pulau digiring untuk patuh memenuhi hasrat penguasa atas alam. Termasuk dalam menentukan rupa-rupa komoditi tanaman rakyat yang laku di pasaran dunia, meskipun dengan itu mengorbankan hakikat dasar tanaman suatu pulau. Sehingga dengan begitulah Pulau Natuna yang dulu terkenal sebagai pulau nyiur melambai berubah menjadi pulau cengkeh. Lantas tata-niaga cengkeh itu pun dirusak oleh BPPC, perusahaan jadi-jadian yang mengatur hidup-mati para petani. Begitu pula upaya mengeruk alam kepulauan, berbanding terbalik dengan upaya membangun manusia pulau melalui pendidikan yang layak di mana guru-guru dibiarkan bertarung di tengah lautan lepas untuk menangani pendidikan anak-anak pulau dengan fasilitas amat terbatas.
Inilah yang dialami Bu Guru Rahimah, seorang guru SD Inpres yang mengabdi di pulau terpencil di Laut Cina Selatan. Suaminya, Guru Kasim, dulu menjadi kepala sekolah dan sama-sama mengajar dengannya, lenyap ditelan ganasnya angin barat ketika memancing di atas perahu demi mendapat uang tambahan—gaji sebagai guru jauh dari cukup. Sejak itu Bu Rahimah menjadi janda dua anak, bertekad mengentaskan mereka dari belitan nasib, sendirian. Ia tak hendak menerima pinangan lelaki lain. Perhatiannya ditujukan untuk mengajar, bahkan dengan ligat ia ambil-alih tanggung jawab suaminya sebagai kepala sekolah—karena pihak terkait memang tak ambil peduli soal itu. Bersama tiga orang guru lain—hanya bertiga—Bu Guru Rahimah bertahun-tahun bertahan mendidik anak-anak pulau, tinggal di rumah kopel sederhana. Minimnya fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar, berkait-kelindan dengan nasib Bu Guru Rahimah yang berhadapan dengan soal-soal manusiawi. Rasa sepi dan terpencil. Ingatan tak pernah usai pada sang suami. Dan gugatan-gugatan batin pada pemerintah yang abai pada pendidikan pulau-pulau terpencil.
Pesan-pesan tragedi kemanusiaan itu menjadi inti sebagian besar cerpen B.M. Syamsuddin, namun tentu saja ia khatam menerapkan unsur-unsur kesusasteraan sehingga karyanya tetap kuat sebagai entitas sastra, tanpa kehilangan gugatan pada isinya.
Pengarang Penuh Empati
B.M. Syamsuddin atau B.M. Syam, demikian ia kadang menulis namanya, dari nama lahir Bujang Mat Syamsuddin, kelahiran Sedanau, Kepulauan Natuna, 10 Mei 1935. Ia meninggal di sebuah rumah sakit di Bukittinggi, 20 Februari 1997, atau dalam usia 61 tahun. Rentang waktu berkarya yang panjang, membuat penulis prolifik ini menghasilkan beragam karya, mulai puisi, cerita pendek, novel, cerita anak, cerita rakyat hingga buku-buku pengantar seni budaya.

.

.

Sejumlah buku cerita rakyat susunan BM Syamsuddin
Tahun 1990-an merupakan masa produktif B.M. Syam, terutama melalui publikasi cerpen di surat kabar terbitan Riau dan Jakarta. Saya punya tiga kliping cerpennya yang pernah dimuat Kompas, yakni “Perempuan Sampan” (dimuat 30 Desember 1990), “Gadis Berpalis” (18 Agustus 1991) dan “Rum Kadariah” (4 September 1994).
Ada nuansa tersendiri yang terasa khas saat membaca kliping koran ini, bukan saja aromanya (biblisoma), jenis font dan jejalur kolom termasuk ilustrasi Ipong Purnamasidhi yang terkesan sederhana namun mengena. Tak kalah penting, koran mengingatkan suatu masa di mana sumber bacaan langsung dapat diraba, dilipat dan direntang, dan untuk mendapatkannya harus berburu di lapak-lapak trotoar, kios, atau kalau untung, berlangganan. Masa yang mengingatkan bagaimana rezim bisa melipat koran, menutup kios, dan membengkokkan isi berita—dan kenapa pada masa digital ini watak itu tak hilang juga?
Sebenarnya dulu saya punya empat kliping cerpen B.M. Syamsuddin, sebuah cerpen yang sangat saya sukai, “Cengkeh pun Berbunga di Natuna” (29 September 1991). Sayang koleksi itu hilang. Tapi untunglah cerpen tersebut tidak terlalu sulit dicari. Selain masuk dalam Cerpen Pilihan Kompas 1992: Kado Istimewa, cerpen ini juga dimuat dalam kumpulan cerpen B.M. Syam, Jiro San, tak Elok Menangis (Yayasan Sagang, 1997), dan lebih terbantu lagi karena cerpen itu dimuat pula dalam buku 100 Tahun Cerpen Riau (editor: Sutrianto, Yosrizal Zen dan Fedli Aziz, Dikbudpar Riau, 2014).
Apa yang menarik dari empat cerpen tersebut adalah konsistensinya bercerita tentang derita orang-orang kecil yang tinggal di pulau, justru ketika pulau yang ditempati sejak turun-temurun dari moyang mereka didesak dan digasak oleh kekuatan luar. Apa yang sekarang terjadi di Pulau Rempang—ketika kekuatan oligarki bersatu menggencet warga kampung-kampung tua demi membentang karpet merah bagi investor—hanyalah puncak gunung es yang sebelumnya sudah banyak disuarakan B.M. Syam. Akan tetapi tak dianggap. Bukankah penjualan pasir laut yang menggerus pulau-pulau kecil di laut Kepri dan menggembungkan Singapura, sudah sejak lama diramaikan dan malah belakangan ada izin untuk membuka ekspor pasir laut?
Derita dalam Cerita
Jika TVRI tempo dulu punya siaran “Dunia dalam Berita” yang menyampaikan berbagai berita dari seluruh penjuru dunia kepada pemirsa Tanah Air, maka dalam dekade yang sama B.M. Syamsuddin boleh dikatakan tampil dalam publikasi “Derita dalam Cerita”. Semua bersumber dari kehidupan masyarakat kepulauan, di mana persoalan tanah dan air begitu konkrit, dan itu disampaikannya kepada para apresian di mana pun berada, tak sebatas Riau, lantaran ia bersifat universal alih-alih kontekstual.
Cerpen “Perempuan Sampan” berkisah tentang anak-anak dara Suku Laut yang tinggal di Pulau Ngenang. Suatu waktu, mereka memutuskan datang ke Pulau Batam hendak melamar pekerjaan. Mereka dipimpin oleh Yang Imbang, putri batin Enam Suku Pulau Ngenang. Mereka cekatan berdayung karena memang sudah sangat terlatih hidup di laut. Begitu juga saat merapat di Pelabuhan Kabil, Batam, mereka cekatan naik ke darat dan dengan kepercayaan diri yang tinggi mereka datangi sebuah perusahaan di kawasan industri.
“Assalamu’alaikum,” segala perempuan sampan berusia muda, bersalam-bertabik, memulai permohonan lisan hendak berkenalan dengan dunia Batam masa kini.
Berucap salam dengan security, ditimbang-timbang dengan rembugan setengah lusin Satpam, akhirnya mereka dibolehkan masuk menemui pimpinan. Akan tetapi justru setelah diizinkan masuk, mendadak para dara itu merasa ‘longsor’; mereka seolah memasuki dunia lain yang bertolak belakang dengan dunia mereka sehari-hari. Rasa asing menggasing diri mereka tiba-tiba, seolah mereka terlempar ke sutau tempat yang tak dikenali.
Teluk-tanjung di zaman kuno telah puas mereka jelajahi. Memungut hasil pekarangan laut dan bersendaugurauan dengan ombak-gelombang. [….] Merentas ombak-gelombang yang berpuncak tujuh, ribut membadai di musim Barat sekali pun, perempuan-perempuan sampan itu belum pernah merasa takut. Sebaliknya, ketika memasuki gerbang industri Pulau Batam negerinya itu, mereka benar-benar kelihatan gugup.
Selanjutnya berlangsunglah percakapan-percakapan senyap di antara kekokohan dinding dan gemuruh mesin-mesin:
“Aduh, seperti masuk ke pintu neraka rasanya,” putri Batin Enam Suku Pulau Ngenang menyurutkan langkahnya. “Kukira neraka seperti dijelaskan oleh Tuan Ustaz itu pun, masih sedap dilewati jika amal ibadat kita kuat. Ada kelonggarannya bila iman di dada tidak goyah.”
“Kukira Batam bukan lagi tempat kita,” desis Yang Imbang menyeka keringat. “Baru akan menghadap pemimpin pekerjaan saja sudah begini susahnya. Belum lagi meminta pekerjaannya.”
“Iya, karena di sini orang masuk pakai payung daun sekolah,” Yang sena, putri Dukun Tunjang menyahut.”Daun sekolah itu kata Cikgu Kadir yang mengajar di es-de inpres kita dahulu, lebih menentukan nasib kita.”
“Tetapi pekerjaan yang kita harapkan ini bukankah cuma industri pengolah rumput laut? Memungut agar-agar, dan hasil pekarangan lainnya, sudah merupakan pekerjaan kita turun-temurun,” gumam Minah dan Limah yang seiring sejalan, nyaris bersentuh tumit dengan Yang Imbang.
“Iya, karena di pantai dahulu ada tuk Batin,” sela Yang sena. “Kini kepada siapa kita percakapkan?”
“Memang, pantai terasa roboh dikarenakan tidak berbatin.”
Dari percakapan yang polos, kadang memuat keluhan itu, kita dapat membayangkan apa yang terjadi dengan para perempuan sampan itu ketika hendak mencari pekerjaan pada sebuah perusahaan agar-agar di pulau nenek moyang mereka, Batam, alias Pulau Kalajengking. Ada rasa teralineasi karena pembangunan Batam yang begitu gencar, berbanding terbalik dengan pembangunan manusia di sekitarnya di mana mereka tidak berijazah sekolah tinggi (atau dalam istilah Syam, tak punya kesempatan memamah “daun sekolah”) sebagaimana disyaratkan oleh kantor-kantor personalia industri.
Tak kalah menyedihkan, mereka tak lagi punya tempat mengadu karena batin (kepala suku) mereka sudah tidak ada lagi. Atau mungkin ada, namun tak dapat lagi menjalani fungsinya sesuai adat karena sudah tergencet oleh perubahan besar di sekitar yang tak memungkinkan infrastruktur adat bekerja sebagaimana sebelumnya. Hal ini mengingatkan saya pada kehidupan suku Talang Mamak, di Riau daratan, yang memiliki struktur adat lebih-kurang sama dengan masyarakat Enam Suku—dengan batin dan dukun—namun fungsi dan peran mereka tergerus seiring lenyapnya hutan ulayat berganti lautan kelapa sawit.
Hal ini terbukti dari pengakuan Yang Imbang yang perih,”Selama Batam terletak di tangan orang pandai-pandai, aku tak pernah lagi memiliki kesempatan bersama ayahku, Batin Pulau Ngenang, untuk memikiri ladang-pemeliharaan gamat-tripang, memelihara pasir pantai supaya disenangi penyu bertelur pada musimnya.”
Pada akhirnya, Batam memang bukan tempat yang nyaman bagi dara Suku Laut itu. Ketika langkah mereka goyah menghadap pimpinan perusahaan, saat itu pula jam istirahat tiba. Seorang satpam berteriak,”Jam istirahat sudah tiba, Tuan Direktur tidak akan menerima kedatangan tamunya lagi! Apalagi orang-orang yang hendak melamar pekerjaan.”
Meski menyadari keadaan, sebagai pimpinan rombongan, Yang Imbang tetap merasa tersudut dan malu terhadap rekan-rekan senasib. Dialah yang mengajak mereka untuk ikut mencecap manisnya kue pembangunan Batam. Sebab mulanya ia menduga tidak sulit untuk diterima bekerja di kawasan yang konon dibuka demi anak-anak bangsa itu, apatah lagi mereka pemilik pulau. Kini ia teringat apa yang pernah dikatakan kekasihnya, Awang Deraman bahwa lapangan kerja itu bukan buat mereka karena mereka dianggap orang bodoh. Tidak sekolah dan tak berijazah.
Yang Sena kemudian menyadarkannya,”Jadi sekarang Kak Imbang masih mau juga berpikir untuk mengajak kami memasuki dunia peradaban?”
Jawaban Yang Imbang sungguh di luar dugaan: tak menyerah. Bagaimana pun, ‘peradaban’ adalah masa depan umat manusia. Hal mana setara dengan penghormatan atas ilmu pengetahuan dalam prosa Pramoedya Ananta Toer. “Iya, untuk kita semua,” katanya.
“Kakak mengira patutkah dunia peradaban bagi kita?”
“Patut, tentu patut sekali.”
Meski percakapan ini sedikit tendensius, dogmatik, yang jika tak terimbangi oleh cakap-cakap metaforis akan jatuh pada streotipe. Dan Syam saya kira mampu mengimbanginya, dengan tetap meloloskan satu-dua kalimat pamungkas sebagai penegas pesan cerita. Bahkan sebuah paragraf cukup ‘berat’ bagi dara Enam Suku, yang diucapkan Yang Sena, ia suguhkan tanpa ragu, demi inti cerita yang dituju.
“Tetapi Kak Yang Imbang tidak mengkaji terlebih dahulu, salangkan orang Melayu saja, jika tidak memiliki ilmu pengetahuan yang dikeluarkan dari bilik sekolah, mereka tersingkir. Kini apatah lagi kita memang sudah jelas-jelas orang terasing, masih di belakang garis kemajuan seperti dikatakan guru kita, Cik Gu Kadir di es-de inpres dahulu. Sebaiknya kita undur sajalah Kak Yang,” pinta Yang Sena dan disetujui rekan-rekannya.
Sementara Yang Imbang hanya menarik nafas tersengal-sengal sambil mendehem, melilitkan selendang di leher, lalu merangkul kepala dayung untuk pulang ke teluk-pulau pemukiman mereka, Yang Sena terhantar pada dunia alternatif yang bisa menenangkan gundah. Bagi Yang Imbang, pulang ke pulau adalah keputusan terbaik saat itu, tapi sebagai pemimpin ia harus punya jawaban atas keadaan, termasuk langkah apa yang mesti ditempuh. Sedangkan bagi Yang Sena, sebagai tandem Yang Imbang, ada dunia lain buat berpaling tatkala hidup terasa sempit. Itulah dunia pengaduan kepada Maha Pencipta, melalui kalimah-kalimah makrifat dan mantra-mantra warisan nenek moyang, di mana Yang Sena sendiri mendapatkannya dari ajaran kekasih, Katan Mak Semah, saat duduk bersama di bawah pohon ketapang Duri Angkang, sambil menanti badai angin utara mereda.
Inilah dunia itu:
Kun kata Allah
Ya kun kata Muhammad
Sarikun kata Jibril
Sapan-sapi, aku meletak pembungkam
Jin segala manusia
Hai, segala manusia!
Kau jangan berhawa salah
Harimau belang tiga, tunduk ke bumi
Gajah seberang menjaga aku
Kuasa Allah, kuasa Muhammad
Aku duduk dalam kalimah
Lai illahaillallah…
Ada pun Yang Imbang, di tengah dunia konkrit yang ia hadapi, ia dapatkan jawaban tak kalah menenangkan: “Kita kembali saja berladang gamat-tripang, bila kering sudah disalai, menyeberanglah seperti dahulu ke Negeri selat. Sebab di bilangan Rochoor, atau Geilang, atau Jurong, masih ada tauke. Biar Awang Deraman yang menjadi taikong, dan Katan Mak Semah kita percayakan sebagai jurutera.”
Demikianlah, perempuan sampan itu berkeputusan. Sambil berkayuh, mata mereka melirik ke arah bandar yang dahulu kerap dikunjungi bersama-sama, Singapura, negeri sepuak orang Laut Enam Suku di perbatasan. Pada akhirnya kepada negeri seberang juga harapan ditumpangkan, karena apa yang ada di negeri sendiri tak berpihak kepada masyarakatnya. Bukankah ini pula yang tetap berlangsung hingga kini dengan banyaknya pekerja migran menyerbu negeri jiran?
Derita tak Bersudah
Masih bagian dari “Derita dalam Cerita”, di mana Batam masih menjadi pusat kisah, kita bertemu dengan sosok Rum Kadariah, dalam cerpen berjudul sama. Rum, seorang perempuan penghibur yang terpaksa memilih hidup getir itu karena tak punya lagi tempat bersandar. Suaminya, Kasrin, sudah lebih setahun ditahan polis di Camp Tower, Malaka, karena masuk negeri jiran sebagai pendatang haram. Tebusan pembebasan suaminya meminta delapan ratus ringgit, hal yang tak mungkin terpenuhi oleh Rum Kadariah. Meski sebagai perempuan penghibur yang mangkal di hostel milik Mr. Siu Hok Chai harga booking-nya mencapai seratus lima puluh dollar Singapura, namun hanya tiga puluh ringgit saja yang ia terima. Dan uang itulah yang harus ia gunakan untuk hidup sehari-hari, termasuk merawat diri supaya tetap menarik, dan tak kalah penting menabung untuk biaya sekolah anak semata wayangnya, Wati.
Sangat terasa, seperti apa pun pembangunan Batam dikebut bahkan oleh badan otorita khusus, namun negara jiran terasa lebih menjanjikan. Itu lantaran pembangunan di kampung sendiri tidak membuka akses yang pantas kepada warga sekitar, alih-alih melempar mereka ke jurang pinggiran. Mereka yang tak makan bangku sekolahan tak boleh ambil bagian, padahal dalam banyak kasus, dunia pendidikan formal kurang mampu menjangkau seluruh pulau secara memadai, baik fasilitas maupun mutu.
Cerita tentang derita Rum Kadariah yang ditinggal suami jadi tahanan di negeri orang—yang di masa lalu sama-sama milik bangsa serumpun—mengalir bening di hadapan seorang pelanggan yang hening, “aku”. Si “aku” begitu sabar mendengar tangis tertahan Rum Kadariah menceritakan nasibnya, bertepatan dengan ingatannya pada putri tercinta. Kebetulan hari ketika ia di-booking “aku” adalah hari ulang tahun sang putri.
“Genap sudah usia Wati putri sulungku tujuh tahun pada hari ini,” tiba-tiba bibir tipis memerah gincu gemetar di sebelahku. “Putri tercinta harus masuk sekolah. Ia jangan sampai menjadi wanita sebodohku, ibunya yang bergulat dengan nasib,” desir bayu ikut menerpa gulana sang perempuan muda dengan bibir seakan bergetah, lembut dan bersahaja membiuskan kata-kata.
Dan “aku” tak dapat berbuat apa-apa selain ikut hanyut dalam derita tak bersudah seorang perempuan malang dibalut malam. Untuk membangkitkan empati, berulang kali “aku” memuji bahwa bagaimana pun, Rum adalah ibu rumah tangga yang mencintai anak dan seorang istri yang setia.
“Saya betul-betul memuji kau seorang istri yang biasa kesepian sepertimu Rum Kadariah! Istri ditinggal suami melebihi idah. Dua puluh empat bulan bukanlah peluang pisah yang enak dikenyam, namun Rum Kadariah masih teringat anak-suami. Wati dan Kasrin, satu di kampung halaman dan yang seorang di rantau seberang.”
“Hai, indah di labuah—bak kata orang Minang pula—mulut lelaki memang begitu. Seperti puja-puji Abang begitu, kenyang sudah Rum rasakan..Abang, Abang!”
Membaca cerpen ini, jujur, ingatan saya memang melayang ke tanah Minang. Cantolan itu menguat pada novel Tanah Ombak (2002) karya Abrar Yusra, penulis seangkatan Syam, berkisah tentang perempuan Minang yang menjadi hostes. Kenyataan itu coba ditutupi, jika mungkin ditampik, oleh para penjaga moral. Salah satunya dengan memberi izin diam-diam bar milik Tante Upita beroperasi di Pantai Padang, sambil para petingginya meminta di-service khusus. Di situlah mangkal wanita penghibur, Yasmi salah seorang. Dan di tengah kemunafikan itu, hanya Yasmi yang mengaku terus-terang sebagai wanita penghibur, dan sekaligus begitu tulus mendampingi Abim, seorang wartawan yang berhasrat mendekatinya dengan hati.
Sikap untuk tidak munafik juga terlihat dari pengakuan Rum tentang siapa dirinya seakan menolak pujian laki-laki yang membayarnya. “Rum memang kerap menjadi penampung orang-orang penjaja mimpi. Membungkus segala rayuan nestapa, terkadang tidak lebih daripada sebuah petaka rumah tangga.”
Terhadap profesi yang dilakoninya, ia pun bersikap profesional, sehingga ia terus membujuk “aku” untuk segera berlabuh di ranjang hostel. “Abang, apalah artinya Abang telah bayar seratus lima puluh dollar pada tauke? Rum rasanya tak rela, kasihan dengan Abang. [….] Semakin bodoh rasanya kita menjadi manusia perahan begini,” katanya tulus.
Tapi sepanjang malam “aku” hanya mengajak Rum berbual, hingga hujan rintik-rintik turun, entah memberi kesejukan atau justru tusukan-tusukan tajam. Menjelang subuh Rum Kadariah terbaring dan pijar matanya, antara gerimis tangis mengumpul rupiah seduit demi seduit,”Wati putri tercinta sudah saatnya masuk sekolah…” ia mengigau-igau. Alam bawah sadar sebagai perempuan tak berpendidikan agaknya memunculkan igauan Rum Kadariah, sebagai sinyal betapa tragiknya pembangunan sebuah kawasan tanpa membangun manusianya.
Habis Manis Sepah Dibuang
Perlakuan tangan-tangan kapital atas sumber daya alam sendiri tidak berterima kasih. Hasil bumi habis dikeruk seperti timah di Dabok-Singkep tinggal menyisakan polong-polong (lobang bekas penggalian timah), memampangkan wajah bumi penuh luka menganga. Sementara di Natuna, kelapa sebagai tanaman asli pulau diganti dengan tanaman baru, cengkeh, demi memenuhi pasaran dunia, tapi lalu tangan-tangan tak bertanggung jawab merusak tata-niaga dengan jurus monopoli dan notabene dilindungi negara.
Kedua luka-derita inilah yang dibuka oleh B.M. Syam dalam “Gadis Berpalis” dan “Cengkeh pun Berbunga di Natuna”. Pulau Dabok yang kaya kandungan timah, telah digerayangi tangan maskapai kompeni sejak masa kolonial, dan semakin gencar setelah kekuasaan Sultan Riau-Lingga dimakzulkan tahun 1911. Lalu apa yang bersisa bagi penduduk pulau di tepian Selat Berhala itu? Boleh dikatakan tak ada. Setelah sumber daya habis, Dabok ditinggalkan begitu saja, habis manis sepah dibuang. Yang tersisa hanyalah polong (di Bangka disebut kolong), kampung-kampung yang mati suri, pensiunan karyawan tambang tak berdaya menghadapi masa depan anak-turunan, dan warga yang kesulitan sumber air bersih.
Keluarga Sri Banun, sang gadis berpalis (artinya: gadis yang mengerlingkan mata), hidup dalam kepungan situasi yang menyengsarakan itu. Ia terpaksa mengambil air dari polong dan memanggulnya dalam kaleng berisi sekitar dua puluh lima liter. Mengangkat kaleng air di pinggul, tidak dijinjing sebagaimana lazim dilakukan orang laki-laki, memang sengaja dilatih sejak kecil. Dimulai memanggul seperempat kaleng, menyusul setengah kaleng air, dan lama-kelamaan sekaleng melimpah. Tradisi yang diajarkan kepada anak-anak Pulau Singkep itu, sekaligus menunjukkan bahwa kehidupan yang sulit telah diwarisi sejak lama, dan tak ada yang berubah.
Ayah Sri Banun, Encik Tauran, adalah karyawan tambang yang mengalami pensiun dini karena hasil timah dianggap tak memadai lagi. Ibunya, Encik Taksiah, ibu rumah tangga biasa, masih bingung menghadapi masa pensiun kepala keluarga. Dalam situasi ngelangut, suami-istri itu hanya dapat memandang putri mereka yang melangkah payah ke polong, sambil berkeluh-kesah tentang nasib yang kait-berkait dengan kepayahan lain.
“Negeri berair, tetapi sukar mendapat air minum,” desis Encik Tauran memalis pandang ke arah putrinya,”Telaga-telaga di Dabok untuk air mandi pun rasa bergetah. Tidak serap bersabun, disebabkan pasir berbijih timah.”
“Jadi hendak Abang larang Sri Banun mengangkut air minum itu, artinya?” tukas Encik Taksiah berpaling ke arah suaminya.
“Tidak pula begitu, Taksiah…”
“Maksud Abang?”
“Maksudku, pulau timah berpolong-polong sudah. Dabok Singkep kaya dengan kolam air, tetapi miskin air bersih.”
Kesulitan mendapat air bersih, itu satu soal. Soal lain yang tak kalah mengibakan adalah gumam-gumam tertahan Encik Tauran. “Ehm, gadisku…[…] Sepatutnya Sri Banun memanggul tas pergi kuliah pagi-pagi begini…”
Dan bagi Encik Taksiah, sumber kesedihan itu lain lagi. “Sekiranya bijih timah masih dikerok di Pulau Singkep, tentu Abang masih punya pekerjaan tetap. Tentu pula Sri Banun secepatnya dapat memasuki jenjang perkawinannya, pestanya pun sanggup kita meriah-meriahkan.”
Percakapan berseling gumam terus berlanjut mengiringi langkah kaki si anak gadis. Derita batin sepasang suami-istri itu—boleh jadi representasi berpasang-pasang suami-istri di seantero pulau—tercermin buram, bagai terpantul air lumutan di kolam bekas galian timah. Mereka merasa betul-betul tak ada yang bersisa buat mereka berikan kepada anak cucu. Bahkan,”Di perbukitan melatarbelakangi perkampungan, pohon-pohon keremunting membelukar tanpa warna kesuburan. Jauh di depan perkampungan kaum pensiunan itu, laut luas terbentang.”
Kehidupan mereka seolah terkepung di tengah pulau yang kehabisan sumber daya. Dan sayup suara camar, kedengaran cekikikan bagai mengejek, kadang bagai suara tercekik, tapi juga dapat diartikan pemberi semangat,”Cekikik…kiak, cekikik…kiak…”
Dalam bahasa Melayu, “kiak” artinya “angkat”, “kiak-kiak” artinya semut besar yang hitam warnanya, dan jika sedikit dibelokkan menjadi “kial” atau “berkial-kial” itu artinya bekerja keras sampai habis tenaga.
Artinya lagi, ada banyak situasi yang dapat dimaknai dari kehidupan kampung bekas tambang itu, dan ada banyak asosiasi yang terbangun dari bebunyian camar laut tersebut. Untuk mengentas dari keterpurukan—B.M. Syam memang selalu menyelipkan sedikit-banyak jalan keluar—tidak lain adalah harapan. Wan Talib, pemuda kakak kelas Sri Banun di SMA, nun di seberang polong, sepagi hari biasanya sedang memarangi daun pandan berduri yang membelukar. Selama ini tanaman itu terbuang-buang saja, jarang ditoleh orang.
Sri Banun memalis ke seberang mencari sosok pemuda yang menarik hatinya itu. Jadilah ia yang tadi dipandang oleh emak-bapaknya, menjadi ia yang memandang Wan Talib. Dan jika tadi emak-bapak bergumam menahan-nahan kesedihan, maka dara remaja itu bergumam menahan-nahan kebahagiaan.
Dan Syam segera memberi atmosfir pada suasana hati yang demikian, seperti biasa, melalui citra alam, begini rupa: Pandan berdaun lembut, pudak berbunga. Harum semerbak pada musimnya. Warna putih bunga pudak harum mewangi, suntingan sanggul kesenangan gadis desa pada usia remaja. Pelebat rambut di kepala, pengharum bantal ketiduran…
“Ehm, tentulah Wan Talib ada di seberang. Di pangkal jembatan, sekuntum bunga pudak tentu pula disiapkannya untukku…”
Tapi pagi itu, yang muncul mendadak adalah toke panglong, pengusaha arang kayu bakau. Mobilnya yang meluncur di pangkal jembatan penyeberangan polong direm mendadak begitu melihat Sri Banun. Meski sang toke menanyakan perihal si ayah, dan menjanjikan ada pekerjaan, tapi jelas itu motif tersamar untuk mendekati putri Encik Tauran. Sri Banun mencoba berkelit dengan mengatakan bahwa ayahnya tak ada di rumah. Ia bersikap seramah mungkin dan bilang bahwa sang ayah sudah dua hari pergi memantau kebun rumbia, kalau-kalau sudah berbatang sagu akan dipotong, lumayan ada perusahaan memborong sagu tual. Si toke melongo dan permisi pergi dengan kendaraan yang mengepulkan debu tanah kering ke udara.

BM Syamsuddin
Pandan dan sagu, inilah sumber daya alam pulau yang tak banyak dilirik, karena hasilnya pasti jauh dibanding galian tambang. Tapi Syam menyodorkan kedua tanaman yang terlupakan itu sebagai pembawa harapan. Bagi Wan Talib, sementara mengisi masa menganggur karena setamat SMA tak bisa kuliah, sebagaimana halnya Banun, pandan menjadi bahan anyaman yang menghasilkan uang saku. Banun pun gadis yang pandai dan tekun menganyam. Maka dapat dibayangkan bahwa percintaan kedua remaja itu mungkin akan tersambung oleh pandan berduri sebagai harapan hari depan, termasuk kebun sagu si ayah yang akan menyelamatkan ekonomi mereka. Tapi mungkin pula hubungan keduanya bisa usai jika sang toke arang bakau tetap bersileweran dalam hidup mereka, dan kebun sagu tak cukup mampu menopang pendapatan. Siapa kira si emak-bapak tak terpikat godaan lamaran seorang toke?
Entahlah. Syam membiarkan pembaca menerka. Namun dari judul cerita,”Gadis Berpalis”, yang diberi keterangan di akhir cerpen sebagai “melongos, membuang muka, dan mengerlingkan mata”, kita dapat menempatkan berpalisnya si gadis dalam sejumlah konteks. Ia akan berarti melongos dan membuang muka jika yang datang orang tak disukainya, dan ia akan mengerlingkan mata untuk orang yang disukainya. Tapi apa yang menjadi hak penuhnya itu—menggerakkan dan mengekspresikan organ tubuh sendiri—tetaplah dalam situasi ambigu: apakah ia akan tetap bebas dengan tubuhnya, beserta pilihan dan masa depannya?

Kliping cerpen BM Syamsuddin di Kompas Minggu tahun 90-an | Koleksi Rumahlebah
Sementara cerpen “Cengkeh pun Berbunga di Natuna”, pernah saya tulis di Kompas (Sabtu, 12 Agustus 2017: 24). Dalam cerpen tentang nasib petani cengkeh ini, B.M. Syamsudin terlebih dulu menyinggung pohon komoditas lain: kelapa. Sejak 1870 rakyat Natuna bertanam kelapa. Agustus 1945, Hatta berkunjung dan menyebut Natuna “Pulau Kelapa”. Era 1970-an, Natuna disulap jadi “Pulau Cengkeh” karena tergiur harga tinggi, kemudian anjlok. Akibatnya, petani cengkeh seperti Siti Hamlah, janda beranak lima, hidup tersengal-sengal.
BM Syam mengkritik permainan harga cengkeh. Ia menyebut “bunga cengkeh” untuk “buah cengkeh”. Seingat saya, bunga cengkeh tak lagi bisa dijual. Ini bukan kebetulan. Bunga sesuatu yang indah, tapi tidak untuk cengkeh. Analog dengan ironi Derek Walcott tentang “sejarah pahit gula” bagi petani tebu Karibia. Itulah kekuatan cerita B.M. Syam, alam yang kaya jadi paradoks di tengah miskinnya visi manusia.
Gaya Bahasa sebagai Kekuatan Cerita
Kekuatan tak kalah menarik dati cerita Syam adalah gaya bahasanya. Sangat khas dan indah. Bukan saja karena kalimatnya penuh irama, kata-katanya terpilih seolah ia sedang menulis puisi naratif—maklum pada mulanya B.M. Syam adalah penyair yang kemudian lebih banyak menulis prosa. Kadang keindahan bahasa itu seolah kontras dengan realitas yang diceritakannya. Namun itu bukan bermaksud membenturkan realitas apalagi membuatnya jadi abu-abu, melainkan pengaruh situasi alamiah di satu sisi—kekuatan bahasa ibu-Melayu yang memang indah—dan di sisi lain, tempat bahasa itu tumbuh mengalami penggerusan. Sederhananya ini analog dengan pulau-pulau kecil Riau yang indah secara alamiah, namun nasibnya tak seindah fisiknya.
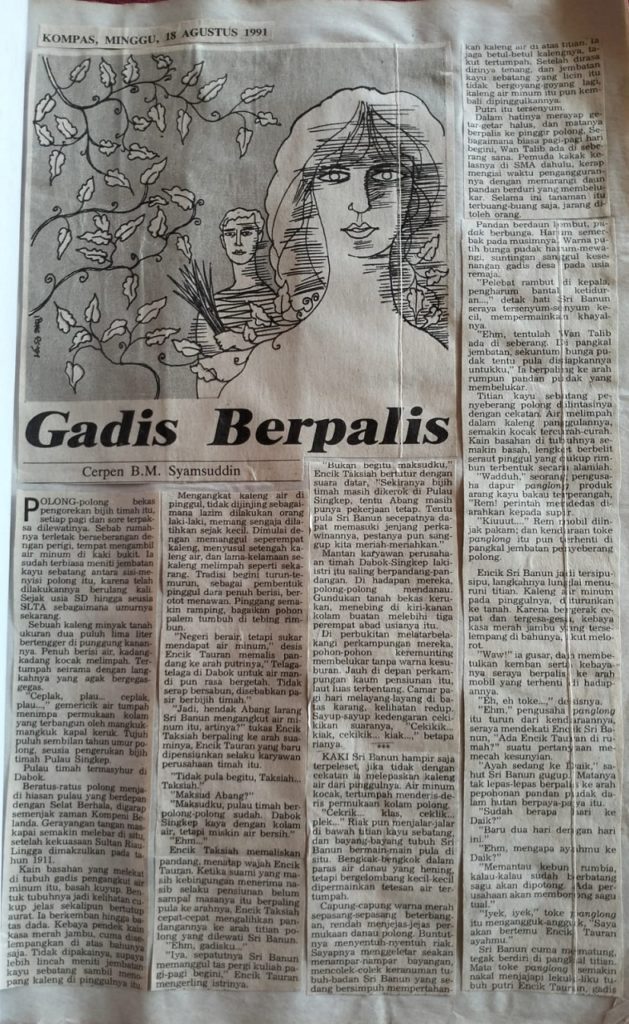
Kliping cerpen BM Syamsuddin di Kompas Minggu tahun 90-an | Koleksi Rumahlebah
Tak heran, melalui gaya bahasa yang terjaga, hal-hal mengandung kesedihan dan sejenisnya, tersampaikan dengan wajar dan natural. Ia tak mengorbankan bahasanya untuk menggambarkan amuk dan putus asa; alih-alih dengan begitu ceritanya menjadi sangat menyentuh, menggugah.
Simaklah pembuka cerpen “Perempuan Sampan” yang simpel namun kaya nuansa: Perempuan muda itu datang bersampan. Pakaiannya serba ringkas. Bertapih kain batik tenunan Kedah, terkenal murah. Kebaya melekat di tubuhnya, cita Cina tembus pandang. Kutang berenda pelapis kebaya bagian dalam, kelihatan jelas bergambarkan sepasang itik berenang, bersulam benang sutera. Warna merah, hijau dan kuning amat dominan. Hasil kerajinan sulam-menyulam perempuan sampan Pulau Ngenang.
Keanggunan dara Enam Suku bukan hanya tergambarkan melalui pakaian Melayu yang ia kenakan, tapi juga dikontraskan dengan suasana dan keadaan alam yang dihadapi: Leher jenjang yang tertumpang pada bagian atas dada sedikit bernas, sengaja dililiti dengan selendang pelangi biru muda. Terlayang-layang ujungnya ditiup angin. Angin siang di Pelabuhan Kabil, Batam Timur, memang jarang reda berhembus. Tajam mendiris datangnya dari laut lepas, Lautan Cina Selatan.
Apa yang membuat bahasa Syam terasa simpel tapi sekaligus penuh nuansa, saya kira karena kemampuannya mengabstrasikan sifat alam kepada sifat dan tindak-tanduk manusia penghuninya. Alam bukan sekadar latar menghidupkan cerita, namun sekaligus menghidupkan tokoh-tokohnya. Lihatlah, ketika mereka, para perempuan sampan itu, digasing rasa asing di tengah tembok industri. Syam berhasil menghubung-kaitkan dengan sejumlah situasi sehingga lewat satu paragraf, dua-tiga nasib pulau terlampaui:
Dara-dara itu saling bersandaran sesamanya, beradu pinggul, dan bertemu bahu ke bahu. Mereka bertahan tegak supaya tidak tertumbang roboh, seperti bertimbang oleng-kemoleng sampan di saat ribut barat membadai. Cuma itulah ilmu yang terbekal pada kehidupannya, yang tidak seberapa banyak mempunyai kesempatan memamah daun sekolah.

Kliping cerpen BM Syamsuddin di Kompas Minggu tahun 90-an | Koleksi Rumahlebah
B.M. Syam menguasai sangat baik titik-titik geografis kawasan, mungkin bagian dari naluri jurnalistiknya, profesi lapangan yang ia tekuni seiring-sejalan dengan dunia kepengarangan. Bentangan geografis itu ia lengkapi dengan suasana panaromik yang hidup meski ngelangut, seperti tertuang dalam pembuka cerpen “Rum Kadariah” berikut ini: Cerobong-cerobong asap industri seakan menikam langit, dan ujung-ujung tempiasnya bagaikan bulu kuas menyapu-nyapu rimba yang masih kelihatan rimbun melingkungi lembah Muka Kuning. Tetapi agak gerah rasanya sekitar perkampungan elit Batam Center, demikian pula pusat perbelanjaan Bukit Nagoya sampai ke pekan ramai Jodoh Tanjung Pantun.
Lebih lanjut bisa kita nikmati, rentetan gambaran yang kian pekat: Lidah-lidah hitam menjilat langit Pulau Batam bersama pekatnya debu jalan berterbangan sore-sore, terseret angin senja ke arah Tanjung Riau yang senantiasa kemarau dan berlabuh dalam sebuah perkampungan pantai. Selat hening dipermainkan arus kelihatan gelisah, rentasan pasang air laut dari pesisir Sekupang hingga ke selat Sambu Belakang Padang. Cahaya lampu mercury di pangkal malam penghujung senja, menggapai-gapai dari arah bandar niaga Singapura, seakan nanar kemilaunya menyilaukan pandangan mata. Cahaya siang paling akhir jadi terselit di sebalik gugus pulau-pulau Segantang Lada, ketika matahari bergulir jatuh lamban tetapi pasti ke pesisir timur Sumatera.
Ia tahu betul musim-musim di laut, perangai angin dan titik letak pulaunya, seperti terlihat dalam cerpen “Bu Guru Rahimah” ini: Musim teduh ulu timur antara Mei-Juni selama empat puluh empat hari saat itu, perairan di Laut Cina Selatan cukup tenang tidak berombak. Cuma sesekali kelihatan ekor gelombang pasang berbelit di kepala karang, memutih buih, berputar-putar dan menderu-deru. […] Di sanalah Pak Guru Kasim, kepala SD negeri proyek Inpres terpencil, pada koordinat empat derajat Lintang Utara, seratus delapan derajat Bujur Timur…[…] Musim barat bergelombang, selang teduh sejenak sebelum membadai, merupakan saat ikan tongkol sejenis tuna ganas merenggut pancing. Para nelayan turun ke laut memacu koleknya…
Detail dan naturalnya cerita Syam, menarik pula dicermati dari upayanya mengeksplorasi bunyi-bunyian alam yang memberi atmosfir pada suasana. Bisa disimak misalnya dalam “Gadis Berpalis” berikut: “Ceplak, plau, ceplak plau, plau…” gemercik air tumpah menimpa permukaan kolam yang terbangun oleh mangkuk-mangkuk kapal keruk. […] Camar pagi hari melayang-layang di batas karang, kelihatan redup. Sayup-sayup kedengaran cekikikan suaranya,”Cekikik…kiak, cekikik…kiak..” betapa rianya. […] “Cekrik…klas, ceklik…plek…,” riak pun menjalar-jalar di bawah titian kayu sebatang, dan bayang-bayang tubuh Sri Banun bermain-main pula di situ. “Kiuuut…,” rem mobil diinjak pakam; dan kendaraan toke panglong itu pun terhenti di pangkal jembatan penyeberang polong. Cerpen-cerpen lain juga penuh dihiasi oleh bebunyian alam yang kaya resonansi dan asosiasi.

Kliping cerpen BM Syamsuddin di Kompas Minggu tahun 90-an | Koleksi Rumahlebah
Sekalipun plot cerita B.M Syam rata-rata sederhana dan mudah diikuti, akan tetapi berkat gaya bahasa yang khas, kekuatan cerita B.M. Syam terpancar tiada dua. Ini mengingatkan kita kepada keindahan gaya bahasa prosa-prosa Wildan Yatim. Hanya pada Wildan narasinya lebih “rimbun”, seolah gambaran pedalaman Mandailiang-Natal dan Pasaman yang lebat hutan yang banyak menjadi latar cerita Wildan. Sedangkan pada Syam kalimat-kalimatnya lebih simpel, sebagai pantulan lanskap alam kepulauan yang lebih panas di tengah arus selat dan lautan lepas. Tapi keduanya sama-sama menghadirkan lanskap alam secara detail, di mana bahasa bersipongang mencipta atmosfir dan memantulkan watak tokoh-tokohnya.
Pula, contens cerita Syam menggenapkan ketaksaannya sebagai pembawa derita orang-orang kecil jauh di pulau yang tersingkir atau disingkirkan. Dan cerita Syam, selalu berkelit menyebut mereka sebagai manusia kalah, sebab harapan, marwah dan semangat hidup, masih mereka genggam erat, termasuk melawan jika ditindas! [T]
- BACA artikel TATLITERAT yang lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA










![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)
![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)

















