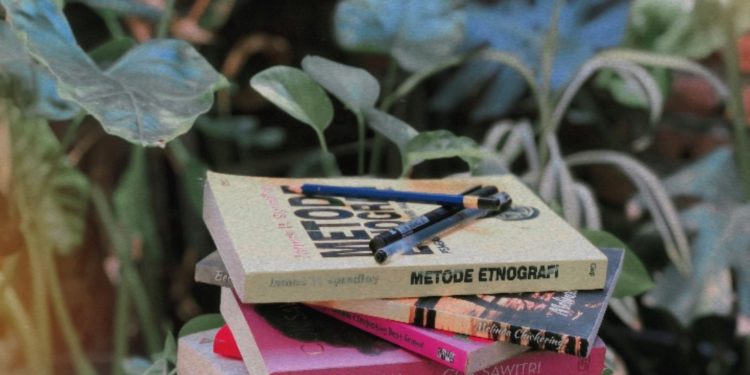SAYA SEMPAT GAGAL memahami esensi esai saat mahasiswa dulu. Mengulas gagasan-gagasan keren dengan hiasan-hiasan kutipan ilmiah yang nyatanya kering. Mimpi mengubah dunia yang tak menyentuh dunia sedikitpun. Fana.
Berbagai pernyataan-pernyataan ilmiah para ahli dengan bangganya saya kutip hanya menjadi hiasan belaka. Tidak ada urgensinya sebenarnya, hanya untuk menambah daya “kelimiahan” seakan membuat tulisannya makin berbobot. Jangankan menyalakan lilin, koreknya pun malah gagal menyala. Duhhh.
Sengaja saya tulis esai ini untuk merepresentasikan “ini nih!” yang menggelora dalam dada saya saat membaca tulisan Dr. I Wayan Artika, M.Hum. dosen kesayangan saya. Bertahun saya mencoba mengenali apa itu esai, dan bias yang saya temukan sama persis dengan yang dosen saya tulis itu.
Saya membaca esai-esai Seno Gumira Adjidharma, yang membuat saya -mbatin- “loooh kok esai seperti ini?” Sangat-sangat berbeda dengan esai yang saya temui di kejuaran-kejuaran esai tingkat nasional.
Kok bisa Seno menuliskan esai dengan judul “Kampungan yang mesra?” Harusnya “Identifikasi sifat kampungan dalam kajian Sosiologi.” Atau tulisannya yang lain berjudul “Kesambet.” Kenapa bukan “Isu Mental Health dengan unsur-unsur Klenik.” Kenapa penulis kondang menyalahi aturan-aturan esai untuk bisa juara nasional?
Belum lagi esainya yang sering dibubuhi emotikon 😊. Sungguh sangat tidak taat asas penulisan esai dalam lomba esai nasional Wakanda 2023!
Galau ini masih membiru. Sampai-sampai, saya sengaja mengikuti kelas penulisan esainya Setyaningsih dari Boyolali yang termasuk dalam emerging writers dalam UWRF 2021.
Di kelas daring itu saya tanyakan, kenapa ada bias antara esai-esai populer kita dengan esai yang ada di arena lomba? “Saya juga bingung, kenapa esai di lomba-lomba itu sangat ilmiah sekali. Oleh karena itu, saya malah menghindari lomba-lomba esai” begitu pungkasnya.
Menjadi penulis sejati, tanpa embel-embel kejuaraan sepertinya menjadi jalan ninja menjadi esais yang sesungguhnya. Melawan dunia seperti judul lagunya Noah.
Sama seperti yang dikatakan dosen saya dalam kolom komentar: “Selamat, tapi menjadi penulis di arena sesungguhnya jauh lebih mengagumkan” begitu kira-kira. Begitu saya pikir-pikir, eh jadi kepikiran. Buku harusnya lebih berharga dari piala dan piagam buat penulis.
Menulis esai adalah menyalakan lilin. Dan dosen saya yang keren ini sudah berhasil menyalakannya, dalam relung hati saya. [T]