Tampaknya perpolitikan Indonesia masih jauh dari kata ramah terhadap kehadiran perempuan. Pilkada 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 hanya diikuti oleh 10,6 persen keterwakilan perempuan sebagai calon kepala daerah. Menurut catatan LIPI, dalam pemilihan gubernur tercatat ada 5 perempuan dan 45 laki-laki. Pemilihan Walikota diikuti oleh 26 perempuan dan 126 laki-laki. Sedangkan dalam pemilihan bupati terhimpun ada 128 perempuan dan 1.102 laki-laki. Angka-angka tersebut jauh dari kata cukup untuk menggambarkan keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Maskulinitas menjadi karakteristik yang kuat tergambar dalam perpolitikan Indonesia saat ini. Lalu apa yang sebenarnya menyebabkan semua ini terjadi?
Glass Ceiling Membelenggu Gerak Perempuan
Glass ceiling adalah sebuah metafora yang mengasumsikan adanya penghalang buatan terhadap progresivitas kaum perempuan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Hymowitz dan Schellhardt (1986) untuk menggambarkan hambatan dalam hierarki organisasi suatu perusahaan, tepat di bawah level manajemen puncak, yang mencegah atau membatasi wanita untuk naik ke jajaran manajemen senior. Glass ceiling adalah bentuk garis demakrasi yang dalam dan mencerminkan ketidaksetaraan pekerjaan yang dibedakan berdasarkan ras atau gender bukan dibedakan pada kualifikasi pendidikan atau pengalaman kerja. Beberapa penyebab munculnya glass ceiling ini tidak lain terbentuk karena masih melekatnya sikap bias gender, prasangka, dan stereotyping dalam komunitas masyarakat modern.
Hambatan glass ceiling tidak hanya terbalut dalam struktur organisasi suatu perusahaan. Di Indonesia, istilah ini dapat dipakai untuk melihat salah satu faktor yang membuat rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik. The Federal Glass Ceiling (1995) membagi hambatan-hambatan tersebut ke dalam tiga kelompok, yaitu societal barriers (hambatan sosial); internal structural barriers (hambatan struktur internal); dan governmental barriers (hambatan pemerintah). Dalam konteks perpolitikan Indonesia, ketiga hambatan ini membuat ruang gerak perempuan dalam politik menjadi terbatas.
Societal barriers mengacu pada hambatan yang tercipta dari sikap stereotyping dan bias gender. Kehadiran perempuan dalam perpolitikan Indonesia masih sangat lekat dengan anggapan ini. Dalam masyarakat terbangun citra yang menganggap perempuan memiliki keterbatasan dalam hal kepemimpinan. Bias gender dalam politik tidak lain muncul karena internalisasi nilai-nilai patriarki dalam masyarakat. Maskulinitas dalam masyarakat membentuk pandangan bahwa laki-laki adalah kaum yang memiliki kuasa lebih daripada perempuan. Dalam konteks hubungan keluarga, masih banyak kelompok masyarakat yang mendudukkan laki-laki di atas perempuan. Pembuatan keputusan penting lebih banyak didasarkan atas cara pandang laki-laki dalam keluarga. Konteks patriarki yang telah membudaya ini membuat adanya hambatan bagi perempuan untuk maju, khususnya di ranah politik. Masih adanya stigma yang menganggap perempuan belum cukup capable dalam menentukan keputusan pada kelembagaan. Karena terlemahkan oleh stigma, banyak perempuan memilih mundur dari ranah politik.
Internal structural barriers kerap diasosiasikan sebagai hambatan yang muncul dari dalam lembaga atau organisasi masyarakat yang ada. Ada keengganan untuk mengkader perempuan menjadi pemimpin suatu jabatan tertentu. Kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk upgrading kemampuan diri bisa menjadi salah satu penghalang untuk berkembang. Minimnya kemampuan perempuan dalam berkomunikasi, berpikir kritis, dan literasi tidak banyak dapat diakomodir dalam suatu komunitas masyarakat. Kewajiban mengurus pekerjaan rumah tangga bagi kebanyakan perempuan membuat akses terhadap hal-hal di atas menjadi sangat terbatas.
Selanjutnya jika berbicara soal governmental barriers, hambatan nampak jelas pada maskulinitas dunia perpolitikan Indonesia saat ini. Walaupun pemberian kuota 30% terhadap keterwakilan perempuan sudah diberlakukan, namun aturan tersebut terkesan hanya sebagai pelengkap. Keterwakilan suara perempuan masih belum dapat dihitung sebagai prioritas. Tidak diindahkannya pengesahan RUU PKS menjadi salah satu bukti bahwa isu yang berkaitan dengan perempuan masih dinomerduakan. Keadaan ini justru semakin menambah luka bagi perempuan. Secara tidak langsung, keadaan tersebut menambah skeptimisme perempuan terhadap dunia perpolitikan.
Potensi Kekerasan Struktural dan Kultural dalam Budaya Patriarki
Budaya patriarki yang terpatri dalam struktur masyarakat sejak lama semakin memperbesar ruang kesenjangan. Asumsi bahwa laki-laki harus di atas perempuan telah menempatkan budaya patriarki sebagai sebuah budaya yang telah mengakar dalam masyarakat. Johan Galtung, seorang sosiolog dan pakar studi perdamaian melihat bahwa patriarki menjadi penyebab utama timbulnya kekerasan, baik kekerasan kultural dan struktural. Adanya dominasi laki-laki kemudian menempatkan perempuan sebagai obyek. Patriarki sebagai bagian dari kekerasan struktural maupun kultural secara nyata semakin menegaskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak hal. Contohnya terbaginya peran perempuan dalam ranah privat dan publik. Kerap perempuan diidentikkan dengan pekerjaan yang bersifat domestik, seperti urusan anak dan keperluan rumah tangga semata. Sedangkan laki-laki mendapat porsi lebih dalam meningkatkan kapabilitasnya di ranah publik, misalnya menduduki jabatan penting di daerahnya.
Kekerasan struktural dan kultural terhadap perempuan juga dapat dilihat dalam dua konteks yaitu marginalisasi peran perempuan dan menstigmakan peran perempuan. Marginalisasi ini kerap dihubungkan dengan terbatasnya sumber daya dan akses perempuan terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Masih banyak pandangan yang melemahkan posisi perempuan dalam pilihan-pilihan mereka setelah menjadi dewasa. Misalnya kewajiban menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Marginalisasi yang secara harfiah berarti menempatkan ke pinggir, maka pilihan perempuan dalam banyak hal kerap juga terpinggirkan. Sayangnya marginalisasi ini membuat perempuan menjadi tidak percaya diri. Paksaan dari budaya patriarki dan marginalisasi semakin membatasi produktivitas perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Hilangnya semangat untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang selanjutnya menjadi faktor psikologis lainnya mengapa keterlibatan perempuan dalam politik masih sangat rendah.
Menstigmakan berarti menandai seseorang dengan stigma tertentu. Acap kali labelisasi ini mengarah kepada perempuan. Paradigma yang menganggap perempuan adalah kelompok yang rentan seolah-olah menempatkan perempuan untuk tidak mampu mengambil peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi mengingat dalam masyarakat modern saat ini perempuan kerap memainkan peran ganda, sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Lagi-lagi perempuan diharuskan memilih, terkadang pilihan-pilihan yang tersedia sangat sulit untuk dikorbankan salah satunya. Bukan tidak mungkin hal ini mampu menggiring perempuan untuk kehilangan posisi tawarnya dalam banyak hal.
Proyeksi Perempuan dalam Politik Indonesia di Masa Depan
Atas berbagai hal tersebut, penting rasanya kita menakar bagaimana proyeksi perpolitikan Indonesia khususnya bagi perempuan di masa depan. Terjun dalam perpolitikan akan menjadi kesempatan bagi perempuan untuk memperjuangkan keterwakilannya. Bila kita ingin membuat politik Indonesia ke depan semakin inklusif, pertama-tama yang harus dihapus adalah stigma terhadap perempuan itu sendiri. Budaya patriarki yang selama ini langgeng sedapat mungkin harus dikonstruksikan dengan pemikiran baru yang dapat menghapus kesenjangan gender. Pemberian kuota keterwakilan perempuan dapat menjadi langkah awal yang baik untuk membuka ruang bagi perempuan dalam ranah politik. Tampaknya ada harapan bagi perempuan dalam politik di masa depan. Asalkan perspektif lama soal domestikasi peran perempuan harus segera direduksi. [T]
Referensi:
- Cotter, D., Ovadia, S., Hermsen, J. (2001). The Glass Ceiling Effect, Social Forces, vol. 80, no.2. pp. 655-682.
- Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas RI. (2020). Keterwakilan Perempuan di Pilkada Dinilai Masih Sedikit. Diakses pada 14 Desember 2020 dari http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=992
- Eriyanti, L.D. (September, 2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme, Jurnal Hubungan Internasional, vol. 6, no. 1.
- API Kartini. (2018). Perempuan dan Langit-Langit Kaca di Dunia Politik. Diakses pada 15 Desember 2020 darihttp://www.apikartini.org/2018/03/14/perempuan-dan-langit-langit-kaca-di-dunia -politik.html.
- Sakina, A.I., Siti, D.H. (2013). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia, Social Work Journal, vol. 7, no. 1, pp. 1 – 229.
- The Federal Glass Ceiling Commission. (1995).
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, Politea, vol. 1, no.1, pp. 68-83.


















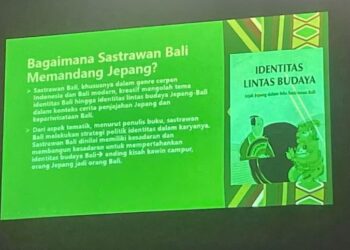


![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)











