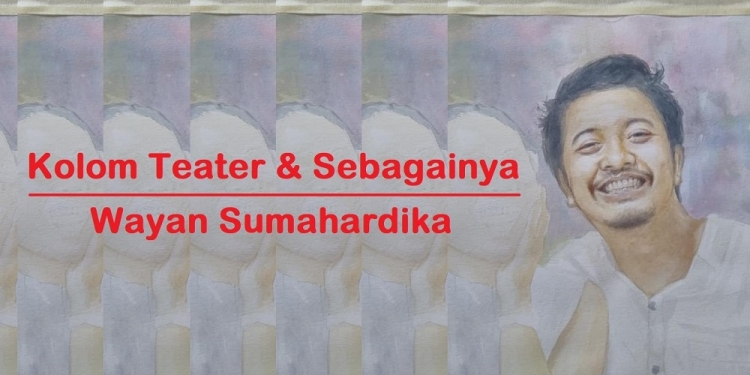Banyak yang bilang, mari menyongsong tahun baru yang lebih baik. Yang buruk dibiarkan lalu. Kita bawa cita-cita baik menuju tahun mendatang. Hal-hal yang terjadi di tahun lalu, kita namai masa lalu, mengingatnya kini sebagai kenangan. Sementara tahun baru adalah masa depan. Tempat tumbuh harapan yang kita andaikan sebagai buah capaian diri. Maka masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah tiga rangkaian waktu yang bergerak seperti sungai. Di atasnya adalah tubuh kita. Daun apung yang pasrah mengikuti alir waktu.
Oleh Agustinus, seorang filsuf abad pertengahan, waktu dikategorikan menjadi dua, yakni waktu objektif dan waktu subjektif. Waktu-luar dan waktu-dalam. Waktu objektif adalah waktu kolektif di luar diri manusia yang ditandai dengan hitungan tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Sementara waktu subjektif adalah waktu di dalam diri. Waktu eksistensial yang khusuk pada kualitas persepsi manusia sebagai dasein (aku yang meng-ada, aku yang me-waktu). Dalam pandangan lain, manusia bisa dikatakan sebagai pusat waktu. Tak ada hulu bernama masa lalu, tak ada hilir bernama masa depan. Yang ada hanya aku-waktu. Setiap hari adalah hari ini yang terhayati sepenuh-penuhnya, terhayati sesungguh-sungguhnya.
Jika dipikir, tentu begitu tegang manusia mengalami dua macam putar arus waktu ini. Waktu-luar menuntut kita menjadi bagian dari arena kultural sebuah peradaban. Percepatan, ketangkasan, efesiensi adalah standar yang mesti diperhatikan agar nilai kita tak tertinggal dan senantiasa sejajar dalam masyarakat sosial. Sementara waktu-dalam justru melarutkan kita pada dunia diri. Ruang renung yang suntuk mengeloni kualitas penghayatan diri sebagai individu. Kedua hal ini saling tarik menarik dan menjadikan manusia bingung, manakah sejatinya waktu yang mesti dipercaya?
Aktor teater barangkali merupakan salah satu yang paling terbuka menjadi ruang tatap manusia sebagai makhluk yang mewaktu. Sebab pada kerja aktor teaterlah, masa lalu, masa kini, dan masa depan hadir berkelindan pada satu dunia aktor bernama panggung. Masa lalu ditandai dengan tokoh dalam naskah yang akan dipentaskan, dengan konteks sosial yang terjadi di zaman naskah itu diceritakan dan dibuat. Masa kini adalah proses aktor menghayati dirinya sebagai manusia dengan segala biografi hidupnya, ditambah identitas sebagai aktor, serta proses penciptaan tokoh yang akan dimainkan. Sedang masa depan adalah hasil aktualisasi aktor terhadap tokoh yang dihadirkan di atas panggung pertunjukan.
Bisa dibayangkan, bagaimana tubuh aktor mengandung begitu banyak waktu di dalam tubuhnya. Waktu hidup sendiri sebagai aku-diri, waktu proses dalam menjalani latihan keaktoran sebagai aku-aktor, lalu waktu peran yang akan dimainkan sesuai konteks dan sejarah naskah sebagai aku-tokoh. Pada panggung pertunjukanlah, penonton dapat melihat waktu manusia yang begitu panjang jika dijalani pada kenyataan sehari-hari, kini dimampatkan dalam rangkaian alur, plot, babak, adegan dan durasi pentas dalam tubuh aktor.
Pada panggung pertunjukan pula hadir tawar menawar durasi pentas agar sesuai dengan batas waktu kuat penonton untuk khusuk menyaksikan pentas. Di sinilah kepiawaian aktor dituntut untuk mengelola segala waktu yang hadir dalam panggung. Bagaimana sang aktor membawa waktu-diri, waktu-aktor, dan waktu-tokoh di atas panggung, berinteraksi dengan waktu pemain lain, merespon waktu pentas, dan mengatur waktu gerr dan haru para penonton. Semua waktu terpusat pada diri aktor, sebagai tokoh yang bertugas mengemban gagasan pertunjukan agar mampu memprovokasi cara pandang penonton atas kenyataan hidup sekitarnya.
Di Bali, pada 2019 lalu, kita cukup berbahagia karena disuguhi begitu banyak ragam pentas yang mengingatkan kembali, bahwa panggung teater adalah ruang yang paling mewaktu. Ada Abu Bakar dengan Teater Bumi yang mementaskan ‘Detik-detik Proklamasi’, menghadirkan waktu sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan. Ada Putu Satriya Kusuma dengan Teater Selem Putih mementaskan ‘Budak dari Bali Untung Surapati’ berdasarkan riset tentang perdagangan budak di Bali pada waktu kolonial, serta Nanoq da Kansas dengan Bali Eksperimental Teater yang mementaskan ‘Pan Balang Tamak Reborn’, hasil dekonstruksi cerita rakyat Bali yang cukup populer di masa lalu.
Semua pentas yang telah disebutkan mempunyai kecenderungan sama yakni menghidupkan kembali tokoh-tokoh masa lalu sebagai tema pertunjukan. Membawa waktu masa lalu ke dalam waktu panggung hari ini. Ditambah lagi karena semua pertunjukan dipentaskan pada rangkaian acara Festival Bali Jani 2019. Sebuah festival yang khusus menyajikan seni-seni pertunjukan kontemporer Bali hari ini. Tentu jadi menarik untuk dikuliti, bagaimana hubungan tema pertunjukan yang diangkat dengan gagasan dalam festival? Apakah pemilihan tokoh yang diangkat ini terjadi hanya karena keterpengaruhan seniman Bali satu sama lain, cara pandang dunia yang mirip, atau memang kebutuhan untuk menghadirkan tokoh-tokoh masa lalu dalam menjawab segala macam kenyataan yang hadir di Bali saat ini?
Pada panggung yang berbeda, kita juga disuguhi pentas ‘Pembelaan Dirah’ karya Cok Sawitri. Naskah yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1999 ini kemudian dipentaskan kembali pada tahun 2019 dalam acara Borobudur Writers and Cultural Festival. Meski memunculkan ‘Dirah’ yang juga sebagai tokoh dari masa lalu, pentas jadi punya varian gagasan lain ketika Cok menariknya pada persoalan ketokohan ‘Dirah’ pada naskah dan keaktoran ‘Cok’ mememerankan tokoh pada rentang jarak 20 tahun. Bagaimanakah perkembangan gagasan tokoh dan aktor kemudian? Apa saja yang tumbuh dan berubah? Atau sejatinya 20 tahun yang terlewati tak melahirkan perkembangan gagasan apapun lagi?
Lain daripada itu, patut dipertanyakan pula strategi para sutradara dalam mentransfer penghayatan akan waktu-luar dan waktu-dalam dirinya kepada para aktor. Sebab aktor adalah pusat waktu dalam pertunjukan. Sama seperti manusia sebagai pusat waktu bagi dunianya. Aktor tak hanya sekadar robot di atas panggung yang dipakaikan kostum masa lalu, set artistik di masa antah berantah, serta gagasan silang sengkarut antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Apakah para aktor sendiri tahu pada waktu manakah ia berada? Jika tidak, alih-alih mempercayai panggung sebagai ruang yang mewaktu, justru panggung jadi ruang yang kehilangan waktu.
Aktor teater jadi tak ada bedanya dengan manusia-manusia yang kehilangan waktu-dalam dan sibuk dengan runitinas mekanis waktu-luar. Minim kualitas, minim penghayatan. Dalam konteks ini, waktu-dalam dan waktu-luar jadi semakin penting artinya untuk dijadikan sarana melatih kemampuan keaktoran. Waktu-dalam berfungsi sebagai ruang melatih kesadaran, menghayati diri sebagai tokoh utama, yang menggerakan sejarah hidupnya sendiri. Sementara waktu-luar membuat manusia peka atas kedudukannya, sebagai bagian kecil dari sejarah besar peradaban umat manusia.
Alhasil, pentas tak hanya sekadar jadi hitungan angka-angka, meloncat dari panggung satu ke panggung lain, meloncat dari hari satu ke hari lain. Yang seketika kita sadari panggung-panggung telah habis, hari-hari telah terlewati dan tahun tiba-tiba saja sudah berganti baru. Demikianlah kemudian kita baru merasa kehilangan waktu. Maka, agar tak hilang lagi waktu di tahun 2020 ini, atas segala doa dan harapan kawan-kawan teater menyongsong tahun baru, saya pun turut berdoa dan berharap biar panjang waktu membuat pentas-pentas baru. Semoga saja, pentas-pentas yang baru ini bisa membuat penonton berdecak, “ini baru yang namanya pentas! Untung saja aku luwangkan waktu buat menontonnya!” [T]
Denpasar, 2020