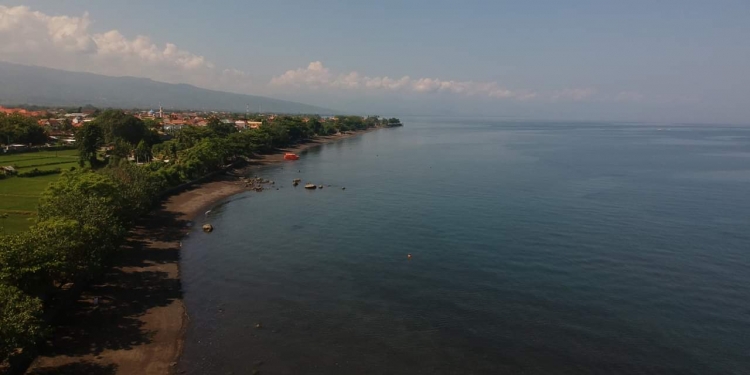JIKA alam semesta ini adalah ruang perenungan, sungguh melimpah sumber renungan yang tersaji apik – menampakkan dirinya. Sumber itu tidak jauh dari diri kita, keberadaan kita, keseharian kita, dekat sekali – nenten doh, paek sajan – kata tetua Bali.
Alam senantiasa menyiratkan pesan purba nun filosofis, membabarkan di depan mata kita semesta makna, yang tidak hanya bisa dilihat, diraba, dirasa, dicium baunya, tetapi juga dibaca, dipikirkan, direnungkan, dimaknai, dibathinkan dalam hening.
Kadang kita alpa belajar dari alam, sesuatu yang paling dekat. Terlalu jumawa manusia ini, menggurui alam, memunggungi alam, mengubah alam, hanya karena merasa punya pikiran yang canggih.
Kita juga bangga, belajar pikiran-pikiran besar para filsuf nun jauh di sana. Kita mencari ‘air spiritual’ pelega dahaga bathin nun jauh di sana. “Yang jauh di sana selalu lebih megah dari yang disini”. Begitu kebiasaan kita. Saya tidak belajar dari yang jauh di sana, tetapi yang dekat di sini. Sangat dekat, bahkan ia adalah aku!
Mari kita renungkan, adakah yang lebih ikhlas dari pertiwi – tanah? Adakah yang lebih nrimo daripada tanah? Pesan filosofis purba apa yang bisa kita singkap dari tanah? Bukankah kita menyebut ‘rumah’ bangsa kita ini tanah air?
Ada apa dengan tanah? Cukupkah tanah dibaca sebatas menghasilkan rupiah dengan cepat? Bukankah tanah memicu sumber konflik? Bukankah tanah dipergunjingkan oleh para pencari kuasa bangsa ini? Sudahkah mereka belajar dari tanah? Ada pertanyaan lagi? Cukup sampai di sini dulu.
Peradaban bathin dan spiritual Bali, sangat dekat dengan tanah sebagai sumber kehidupan. Tanah seolah menjadi guru spiritual mereka yang ‘diam’. Mereka selalu menyisakan kesadaran untuk menjaga keseimbangan, siklus alam, dengan sangat apik.
Cobalah simak ritual-ritual mereka, mantra-mantra mereka, seha-seha mereka, tidak jauh-jauh dari rasa syukur kepada semesta: ibu purba kita.
Bathin spiritual mereka, diperkaya kosa kata-kosa kata kosmik. Mereka tidak memperlakukan alam sebagai obyek, melainkan sebagai subyek. Mereka membiarkan alam hening sejenak – dalam waktu sehari (Nyepi) – memperbaiki raganya yang tercemar.
Tetua kita belajar, betapa alam punya cara sendiri menyembuhkan diri. Tak perlu dokter pikiran. Cukup jeda, di titik hening, nol, kosong, sipeng!
Begitu pula tanah – pertiwi, mengajarkan kita apa itu ikhlas – filsafat keikhlasan. Ada keikhlasan dalam unsur yang kasar. Bukan hanya di unsur yang halus. Kekasaran dan keikhlasan berhubungan sangat dekat.
Tanah tak pernah meminta jenis akar yang tumbuh, tanah tak pernah meminta jenis air yang meresap, tak pernah meminta jenis manusia yang dikubur, tak pernah jua meminta jenis makhluk renik yang berumah di dalamnya.
Coba kita buka lagi lembar-lembar teks Jawa Kuna khususnya bergenre tutur atau tatwa, di sana tanah dikisahkan sebagai unsur paling kasar dalam lingkar panca maha bhuta. Sebut saja yang paling halus adalah ether. Karakternya berada di puncak, meresapi semuanya, namun ia tidak diresapi apapun itu. Ether hanya punya satu kualitas halus: bunyi. Unsur yang halus, memiliki kualitas yang halus pula.
Memang teori-teori penciptaan dalam teks Jawa Kuna yang dipengaruhi filsafat Nyaya, Waisesika dan Sankhya, ada penjenjangan vertikal unsur-unsur materiil dari yang halus sampai kasar dengan kulitas masing-masing. Di sana disebutkan yang halus selalu meresap ke dalam yang kasar.
Menariknya, semakin kasar, justru memiliki kualitas yang lebih komplit. Sebagai unsur kasar, tanah disebut tidak meresapi apapun, tapi ia diresapi oleh apapun: air, udara, api, gas. Ia berada di dasar. Tidak seperti ether, air, dan api, tanah memiliki lima kualitas sekaligus: bunyi, sentuhan, bentuk, bau, dan rasa. Berbeda dengan ether yang hanya memiliki satu kualitas.
Di titik ini, tanah ibarat “rumah” segala asas, istana segala kualitas unsur-unsur halus. Tanah adalah ruang keragaman, kebhinekaan, keanekaan, tempat segala sesuatu yang plural. Tanah menerima segala unsur halus di dalamnya dengan sangat ikhlas. Di dalam dan di atas tanahlah segala sesuatu tumbuh, menumpuk.
Patimbhunan tatwa kabeh – begitu teks Dharma Patanjala. Ikang prthivitattva ya patimbunan ing tattwa kabeh”, begitu teks tutur lain menyebutnya. Tanah adalah tempat sarwa tatwa tumbuh sangat subur.
Meski ia disebut asas atau unsur yang paling kasar, tetapi tanah punya sifat menerima peresapan-peresapan unsur yang lebih halus darinya. Ia seolah tidak ‘punya sifat’ meresapi, tetapi ditakdirkan untuk menerima peresapan. Sifat menerima inilah yang bisa kita berikan kepada tanah.
Justru di dalam sifat menerima itulah, ia memiliki kualitas yang jamak – sarwa tatwa. Jika dibaca dengan perenungan, sebenarnya dari tanahlah kita bisa belajar banyak tentang kebhinekaan, keragaman, menumbuhkan sikap nrimo, ikhlas atas apapun yang meresapinya.
Jika memang di dalam raga sarira ini memiliki unsur pertiwi atau tanah di dalamnya, bukankah teks filosofis berjudul tanah itu sangat dekat dengan diri kita? Bahkan diri kita itu sendiri?
Mengapa kita lupa membaca dan memaknainya, atau belajar ikhlas darinya? Atau memang kesadaran kita cenderung ke puncak, ke atas, ke yang sangat halus dari yang halus? Ke yang jauh di sana? Padahal yang halus dari yang halus, ikut berumah di tanah.
Sekian, hormat dan pujaku pada pertiwi………..