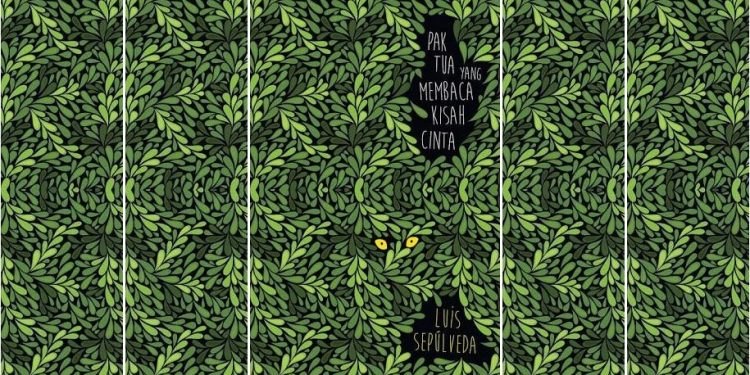- Judul Buku: Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta
- Penulis : Luis Sepulveda
- Penerjemah : Ronny Agustinus
- Penerbit: Marjin Kiri (2017)
- Ketebalan: x + 133 halaman
DI mana-mana, kapitalisme menebar keserakahan. Ia menjadi biang kerok dari kerusakan di bumi. Ya manusia, ya alamnya. Di Indonesia, kapitalisme membabati hutan, menyingkirkan manusia di pedalamannya. Di desa-desa, petani disingkirkan dari tanahnya. Dan di pesisir, laut diuruk, yang memaksa nelayan melaut lebih jauh, atau berhenti sama sekali karena alat tangkap yang tak memungkinkan.
Manusia-manusia itu, ya petani, ya nelayan, dan manusia di pedalaman hutan dipaksa menyerah terhadap “peradaban”. Peradaban yang melayani pemodal. Melayani korporasi, seraya menyingkirkan rakyat kebanyakan.
Buku “Pak Tua Yang Membaca Kisah Cinta” karya Luis Sepulveda seperti sedang membaca kondisi Indonesia, mungkin di mana saja di belahan dunia yang buminya sedang diperkosa kejantanan kapitalisme global. Meskipun sebetulnya buku ini sedang berbicara tentang kapitalisme yang menembusi pedalaman hutan Amazon dari sisi Ekuador. Di mana-mana, wajah kapitalisme tak berbeda. Membabati hutan, untuk meraup keuntungan tambang emas, minyak, perkebunan sawit, kayu, yang dikuasai pemodal.
*
ADALAH Antonio Jose Bolivar Proano. Ia memanggul nama besar Simon Bolivar, bapak bangsa Amerika Latin yang melawan penjajahan Spanyol. Suatu ketika, Antonio tidak betah hidup bersama manusia di desanya, di daerah pegunungan Imbabura, Ekuador.
Peradaban telah membusukkan penduduknya. Suka bergunjing. Istrinya, Dolores Encarnacion del Santisimo Sacramento Estupinan Otavala, nama yang sulit untuk dilafalkan, yang sudah dinikahi selama bertahun-tahun tak kunjung hamil. Maka, Dolores dan Antonio kerap menjadi sasaran pergunjingan.
Ini yang membuat sang istri tertekan batinnya. Suatu hari, muncul saran agar sang istri ikut festival San Luis, yang menyajikan seks bebas di ujung pesta, ketika semua tak sadar dalam kemabukan festival. Kali saja, dari festival itu Dolores hamil. Namun Antonio menolak.
Ia memilih menghindar dari para pencibir. Ikut “transmigrasi” yang dicanangkan pemerintah. Lokasinya di pedalaman hutan Amazon di tepian sungai. Dua minggu menumpang bus atau truk dan perahu. Iming-imingnya, di tempat yang baru, yang disebut El Idilio, itu akan mendapat jaminan kesejahteraan.
Seperti di mana-mana terjadi, lain di mulut pemerintah, lain dalam kenyataan. Di tempat yang masih perawan itu, tidak ada jaminan apa-apa. Mereka bergelut dengan pepohonannya dan semak hutan yang rapat, satwanya yang liar, dan manusia pedalamannya yang udik.
Mereka harus menebang pepohonan hutan Amazon. Harus survive sendiri tanpa bantuan pemerintah. Justru, keganasan hutan Amazon membuat sebagian dari pemukim baru ini meregang nyawa. Termasuk Dolores yang terjangkit malaria. Sedangkan, pemerintah melalui tangan-tangan kekuasaannya terus merangsek lebih dalam hutan Amazon, mengambil minyak di buminya, emasnya, serta perburuan satwa penghuni rimba tanpa ampun.
Ini pula yang membuat suku pedalaman Amazon makin terdesak lebih ke dalam. Dan satwanya terancam. Ekosistem Amazon dirusak oleh tangan-tangan manusia serakah.
Beruntung, Antonio mendapat pertolongan sekelompok suku Indian Shuar, salah satu suku penghuni pedalaman Amazon yang hidup berkelompok, bertelanjang, dan bertahan hidup dari berburu. Ia pun belajar menjadi seperti suku tak “beradab” tersebut. Hidup seperti mereka. Berburu untuk hidup. Berkawan dengan alam Amazon yang liar hingga dimakan usia.
Kematian kawannya, Nushino, oleh pemburu liar berujung panjang. Kematian pemburu pembunuh Nushino menggunakan senapan oleh Antonio bagi suku Shuar sebagai cara yang “tak terhormat”, yang menurut kepercayaan Shuar berakibat roh Nushino tak diterima di alam lain, gentayangan di bumi.
Antonio pun terusir dari suku Shuar. Ia kemudian mencari tempat baru. Menyendiri. Dan selalu terobsesi untuk bisa membaca buku tentang kisah cinta. Yang haru, dan (selalu) berakhir tragis.
Ia bermaksud meninggalkan hutan. Ke Kota El Dorado menumpang sucre, semacam perahu, untuk memenuhi obsesinya membaca kisah cinta. Namun, takdir berkata lain. Perjumpaannya dengan dr Rubicundo Loachamin, seorang dokter mengurungkan niatnya.
Dokter yang biasa mengunjungi El Idilio dua tahun sekali itu berjanji membawakan buku kisah cinta untuk Antonio. Dengan novel-novel picisan yang didapat dr Loachamin dari rumah bordil, itu Antonio membaca pelan-pelan, karena ia memang tidak lancar membaca, dan mengulangi berkali-kali sampai hafal di luar kepala.
*
KERAKUSAN kapitalisme menembus Amazon, mengeruk kekayaannya, dan perburuan terhadap satwa di dalamnya membuat penghuninya marah. Alam membalasnya melalui macan kumbang betina yang mengamuk, dendam, setelah sang jantan dan anaknya dibunuh para pemburu dari orang-orang “beradab”. Beberapa orang, mati oleh amukan macan kumbang betina.
Antonio yang sudah tua, cukup mengenal pedalaman Amazon. Antonio memiliki persoalan dengan walikota El Idilio yang biasa disebut la Babosa, Siput Lendir, karena ia berperawakam tambun, lamban, dan terus berkeringat.
Persoalannya, ia menempati lahan yang diklaim sebagai milik negara, maka Pak Tua terpaksa menuruti sang walikota, ikut dalam tim pemburu macan kumbang betina yang mengamuk, daripada ia diusir dari tanah itu. Medan menuju tempat persembunyian macan kumbang tidak mudah ditembus. Si Siput Lendir membuat perjalanan terasa lamban. Kisah Pak Tua berakhir dengan terbunuhnya macan kumbang. Sesuatu yang sebetulnya tak Antonio kehendaki.
“Maaf, kawan. Bule brengsek itu membuat hidup kita semua serba salah.” Lalu ia menembak. (Hal. 115)
*
BUKU ini tidak hanya menyuguhkan betapa kapitalisme merongrong Amazon. Di dalam buku ini, kita juga seperti diajak mengenal etnografi masyarakat komunal di pedalaman rimba yang menjadi salah satu paru-paru bumi. Suku Shuar khususnya. Contoh yang mungkin lucu, bagi kita, adalah bagaimana suku Shuar tak mengenal ciuman ala Prancis. Bagi suku Shuar, itu tindakan menjijikkan.
Yang membuat kita, sebagai manusia “beradab”, juga harus berpikir dan menanyakan ulang kehidupan kita adalah soal kerja. Orang Shuar menganggap aneh, kita yang bekerja dari pagi sampai petang, berulang terus seperti itu. Mungkin, bagi orang Shuar, ini adalah kerja yang melelahkan. Karena orang Shuar mencari makan dengan cara berburu, sebagaimana kehidupan masyarakat komunis primitif, dengan suka cita. Produksi untuk kegunaan.
Mereka menentukan makanan apa yang ingin ia makan, yang tersedia di alam, berusaha meraihnya, membaginya, dan masuk ke dalam perut. Hari-hari bersantai, juga bersenggama, tentunya, mungkin mendominasi hidup mereka. Sedangkan kita, manusia modern, harus bekerja setiap pagi sampai petanh, begitu seterusnya untuk mendapat upah. Berproduksi untuk dijual.
“…Orang gunung [beradab] tidak berburu.”
“Lalu, mereka makan apa?”
“Apa saja. Kentang, jagung. Kadang babi biasa atau ayam, di hari pesta. Atau marmot di hari pasar.”
“Dan apa yang mereka perbuat kalau tidak berburu?”
“Kerja. Dari matahari terbit sampai terbenam.”
“Goblok sekali! Goblok sekali!” seru orang-orang Shuar itu. (Hal. 32-33)
Ya, mungkin orang-orang Shuar benar menganggap manusia “beradab” itu goblok. Kerja seharian, bahkan lebih bila harus kerja lembur, untuk mendapat upah, sedangkan sebagian hasil produksinya tidak menjadi milik mereka. Melainkan menjadi milik pemilik modal, atau pemilik alat produksi, atau pemilik pabrik, majikan mereka. Buruh, dalam masyarakat “beradab” di bawah naungan kerajaan kapitalisme hanya mengejar upah untuk bertahan hidup.
Lantas kita, yang katanya manusia “beradab” mungkin harus introspeksi diri, menanyakan diri benarkah cara kita hidup sudah menjadi hal yang ideal? Apakah kita, manusia “beradab” tetap menganggap suku-suku pedalaman, termasuk di pedalaman Papua, sebagai manusia barbar, hidup di hutan, yang menurut kita perlu diberadabkan (baca: dikapitaliskan) seperti kita? Melalui MIFEE* misalnya?
Tampaknya, kita harus mau jujur, memikirkan ulang cara berpikir kita. Bisa jadi, manusia yang dikatakan tidak beradab –menurut kita manusia “beradab”, ternyata sudah hidup bersama dengan kecukupan, tidak merasa kekurangan, berbahagia, meski mereka hidup telanjang.
Satu hal yang kurang dari buku ini adalah upaya manusia melawan keserakahan kapitalisme. Perlawanan hanya tampak dari seekor macan kumbang betina. Antonio, misalnya, tidak menghimpun suku pedalaman Amazon, misalnya untuk menahan keserakahan kapitalisme.
Padahal kita tahu, banyak contoh suku-suku pedalaman di Amerika Latin yang berlawan. Pak Tua dalam novel ini tampak hanya lebih berhasrat terus membaca novel picisan kisah cinta yang didapat dari tempat pelacuran, dan tak ada upaya untuk mengubah keadaan.
Bukankah para filosof, termasuk kita, terlalu sering hanya menafsirkan, padahal yang lebih penting adalah bagaimana mengubahnya? Kurang lebih begitu kata mbah brewok, Karl Marx, dalam poin ke-11 dari Tesis tentang Feuerbach. (T)
*) MIFEE, akronim dari Merauke Integrated Food and Energy Estate . Sebuah megaproyek yang membabat hutan jutaan hektare untuk proyek perkebunan dan pertanian yang dikuasai korporasi, dan menyingkirkan suku pedalaman Papua dari hutan yang memberi mereka hidup.