KEGIATAN identifikasi cakepan lontar di rumah Kelian Desa Pakraman Buleleng, Nyoman Sutrisna, di wilayah Delod Peken, Kelurahan Kendran, tepatnya di Jalan Gajah Mada Singaraja, Kamis 16 Maret 2017, sepertinya bukan sekadar aktivitas membaca isi lontar. Kegiatan yang dilakukan anak-anak muda penyuluh Bahasa Bali di Buleleng bersama pemerhati lontar dari Hanacaraka Society, itu seakan sebuah petualangan untuk menembus lorong waktu.
Belasan cakep lontar yang dibaca di rumah itu hampir mirip dengan cakepan lontar yang diidentifikasi di rumah warga lain di Bali. Antara lain kekawin, usadha dan hal-hal yang berkaitan dengan kawisesan. Namun dari isi lontar itu diketahui kemudian tentang intensitas pergaulan para intelektual Buleleng (atau lebih luas para cendekiawan Bali) pada masa yang cukup lampau, yakni pada awal abad ke-20 hingga menjelang Indonesia Merdeka.

Bolehlah dikata masa tahun 1920-1945 adalah masa keemasan cendekiawan Bali dalam merumuskan sekaligus menyilangbenturkan berbagai pemikiran untuk masa depan Bali. Pada masa itu mereka bergaul luas bukan sekadar fisik antara orang pribumi dan orang Belanda. Namun mereka juga bergaul dalam ulang-alik ilmu dari dunia tradisional Bali dengan keilmuan dari dunia modern.
Mari kita masuk lorong waktu menuju tahun-tahun awal abad ke-20.
Sejumlah lontar yang dibaca di rumah Nyoman Sutrisna (juga menjabat Kepala Dinas Pariwisata Buleleng) itu cukup menarik. Ada lontar tertulis tahun 1903 sebanyak dua cakep berisi beberapa naskah tentang pedoman wirasa dan bahasa Jawa Kuno. Tulisannya bagus, tata bahasanya bagus.
Lebih menarik lagi, pada periode 1931 sampai 1944 lontar-lontar itu ditulis ulang atau disalin kembali, Proses penyalinan diduga dilakukan, salah satunya untuk melengkapi koleksi lontar di Gedong Kirtya. Selain, tentu saja, sebagai sarana belajar dan diskusi.
Jadi, bisa dibayangkan pada periode itu, pergaulan para intelektual Buleleng sungguh menggairahkan. Rumah Nyoman Sutrisna di Delod Peken itu hampir dipastikan menjadi tempat berkumpulkan para intektual sekaligus sebagai tempat untuk mengadu ide dan pemikiran.
Pertanyaannya, pada masa emas itu, siapakah intelektual yang menjadi “penjaga gawang” di rumah yang cukup luas dan besar itu?
Jawabannya adalah I Njoman Kadjeng, yang tentu saja masih keluarga dari Nyoman Sutrisna yang kini jadi Kelian Desa Pakraman Buleleng.
Siapa I Njoman Kadjeng? Dia adalah cedekiawan yang tak bisa dilupakan jika bicara tentang riwayat perkembangan dunia pemikiran modern di Bali. Kadjeng adalah salah satu dari sejumlah cendekiawan Buleleng yang menderikan organisasi modern bernama Shanti.
Organisasi itu lahir tahun 1923. Sebuah organisasi yang beranggotakan intelektual Buleleng yang menerbitkan kalawarta (newsletter) bernama Shanti Adnyana, terbit bulanan memuat masalah pendidikan dan agama Hindu Bali (Agama Tirtha).
Terbitan ini disebarkan terutama di kalangan pegawai dan guru. Shantibukan hanya menerbitkan majalah, melainkan juga merupakan sebuah organisasi pergerakan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Pengurusnya, selain Njoman Kadjeng, juga ada Ketut Nasa, I Gusti Putu Jlantik, dan I Gusti Putu Tjakra Tenaja. Shanti Adnyana kemudian disebut-sebut sebagai perintis pers di Bali.
Kiprah intelektual Njoman Kadjeng tak pernah putus. Setelah Shanti Adnyana tak terbit, kemudian sempat digantikan Bali Adnyana dan Surya Kanta, pada tahun 1931 di Singaraja terbit majalahBhawanagara. Majalah ini berbahasa Melayu, diterbitkanYayasan Kirtija Liefrinck van der Tuuk.
Majalah ini mendapat dukungan pemerintah kolonial, tahun 1931 terbit edisi perdanaBhawanagara dengan tebal 40 halaman. Dr. R. Goris bersama I Gusti Putu Djlantik, I Gusti Gde Djlantik, I Njoman Kadjeng, dan I Wajan Ruma, menjadi redaktur majalah ini. Majalah ini punya tag-line: Soerat boelanan oentoek memperhatikan peradaban Bali.
Bhawanagarayang tutup pada tahun 1935 digantikan oleh kehadiran majalah kebudayaan bulananDjatajoe. Mulai terbit 1936 diterbitkan oleh organisasi bernamaBali Darma Laksana. KelahiranDjatajoedisebutkan dipengaruhi oleh majalahPoedjangga Baroe, penuh dengan nuansa kesastraan dan pemikiran kebudayaan yang lebih meng-Indonesia. Pemimpin redaksi pertamaDjatajoeadalah I Goesti Nyoman Pandji Tisna, kemudian dipimpin oleh Njoman Kajeng dan Wayan Badra.
Majalah itu terbit sampai 1941. Tapi hingga kini kita mengenal I Goesti Nyoman Pandji Tisna sebagai pujangga besar dengan novelnyaSoekresni Gadis Bali. Njoman Kadjeng juga meninggalkan warisan penting, yakni terjemahan kitabSarasamuscayayang beredar dengan puluhan kali cetak ulang. Terjemahannya langsung dari teks bahasa Sanskerta dan Djawa-Kuna.
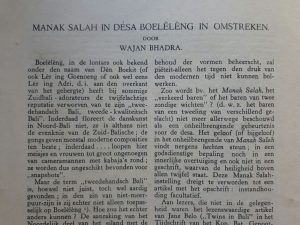
Artikel-artikel Wayan Badra yang ditulis dalam bahasa Belanda dimuat di berbagai jurnal kebudayaan nasional dan international yang menunjukkan kaliber intelektualitasnya. Badra hingga kini dianggap sebagai dedengkot di balik pendirian terbitan-terbitan di Buleleng tahun 1920-1940-an yang juga pernah menjadi Ketua Gedung Kirtya yang sangat disegani para peneliti budaya Bali, baik peneliti Belanda dan negara-negara lain.
BACA SELENGKAPNYA : PARA PERINTIS PERS BALI & KAUM INTELEK BALI UTARA
Rumah Njoman Kadjeng hingga kini masih terpelihara dengan baik. Bangunan kuno itu berada di belakang rumah Nyoman Sutrisna, dan masih berada dalam satu halaman/pekarangan. Di rumah itu juga sempat tinggal Dr. R. Goris, budayawan yang punya perhatian sangat besar pada kebudayaan Bali.
Lontar yang disimpan di rumah Nyoman Sutrisna itu sebagian besar peninggalan Njoman Kadjeng. Jadi, lontar itu bisa dijadikan kendaraan untuk menembus lorong waktu agar bisa masuk ke suasana rumah itu pada masa tahun 1920 hingga 1950-an.
Bisa dibayangkan bagaimana intelektual Bali melakukan diskusi, debat gagasan, dan adu pemikiran, di rumah itu, sehingga lahir sejumlah karya yang dihasilkan secara bersama-sama dalam bentuk penerbitan, maupun karya-karya personal dalam bentuk buku, novel, karya sastra, maupun artikel di media massa lokal dan nasional.

Dengan begitu, bisa dibayangkan juga bagaimana bergairahnya kegiatan pembacaan lontar, penyalinan lontar, sekaligus pelajaran tentang tata cara belajar Jawa Kuno, huruf Bali, penulisan arti dan persepsi dari isi lontar itu, dilakukan di rumah itu dengan atmosfir pemikiran tradisional yang bersumber dari lontar sekaligus atmosfir pemikiran modern yang dihasilkan dari pergaulan dengan dunia barat dalam bentuk buku dan diskusi bersama Dr. R Goris.
Seperti kata Sugi Lanus, temuan lontar-lontar di rumah kediaman I Njoman Kadjeng itu sebagai bukti bahwa cendekiawan di era itu mengakses naskah-naskah leluhur berbahasa Jawa Kuno dan Sanskrit secara langsung. Padahal mereka juga menyongsong dengan naskah-naskah modern yang dihasilkan dari pemikiran orang-orang Barat.
“Cendikiawan kekinian di Bali sangat jarang memasuki perdebatan pemikiran dan persoalan-persoalan modern dengan pijakan naskah-naskah politik, etika, dan filsafat yang tertulis di naskah-naskah Bali. Dunia dan alam pikir masyarakat Bali tidak lagi cukup kuat pijakan akar pemikirannya pada naskah-naskah leluhurnya,” kata Sugi Lanus, pendiri Hanacaraka Society yang hadir saat identifikasi lontar itu.
Kata Sugi Lanus, implikasi dari terlepasnya pijakan dari naskah leluhur itu, kita menjadi gagap ketika diajak membicarakan identitas. Ketika mereka membicarakan “ajeg Bali” entah ajeg bersandar dan bersumber dari acuan mana mereka maksud. Mengajegkan Bali atau “menjaga kebalian” itu wacana yang kabur. “Pariwisata Budaya atau semua emblem budaya yang dijadikan jargon saat ini entah di mana acuan etik, politik dan filosofisnya?” (T)























![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)









