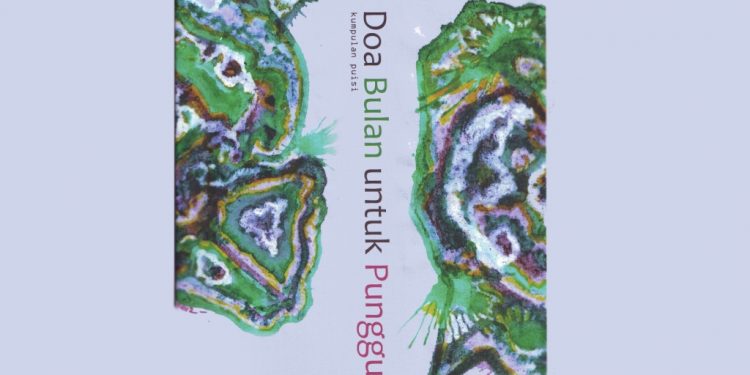KESULITAN terbesar saya ketika harus membicarakan sajak-sajak Nuryana Asmaudi SA yang terkumpul dalam buku “Doa Bulan untuk Pungguk” (DBUP) adalah upaya menghilangkan bayang-bayang wajah penyairnya dari setiap sajak yang saya baca. Kesalahan terbesar saya adalah karena saya mengenal sang penyair cukup dekat, sehingga setiap kata yang ditulisnya saya kenali sebagai hidung, mata, bibir, rambut, tangan, bahkan isi perut Nuryana.
Jadi, maafkan kalau dalam tulisan pendek ini saya tidak sanggup memisahkan DBUP dari pribadi Nuryana. Setiap sajak yang dimuat dalam buku itu seperti selalu mendesak saya untuk menghubungkannya secara langsung dengan penyairnya. Karena itu, karena terlanjur tak mampu memisahkan keduanya, maka sekalian saja saya mulai dengan mencoba melihat Nuryana Asmaudi SA dari persepsi saya.
Nuryana, menurut saya, layak dimasukkan dalam kelompok manusia “aneh”. Pandangan-pandangannya mengenai banyak hal acap kali sangat absurd, sama seperti perjalanan hidupnya yang tak kalah “absurd” dan agak jauh dari kategori normal ala orang banyak.
Lahir di lingkungan ber-Islam yang kuat, menamatkan kuliah di perguruan tinggi Islam (IAIN), sesungguhnya Nuryana memiliki “pilihan bagus dan aman” untuk menjadi guru (kemungkinan juga dosen) agama atau –paling tidak—bekerja sebagai pegawai negeri di kementerian agama. Tapi Nuryana justru memilih ikut petualangan kata. Ia lebih memilih membiarkan dirinya terseret oleh dunia sepi kepenyairan, dunia yang oleh Al Quran disebut menyediakan lubang “celaka” jika kata dibiarkan selesai sebagai kata dan tidak disertai dengan sikap.
Sampai titik itu saja, Nuryana layak disebut “aneh”. Saya sangat yakin akan banyak keluarga dan orang-orang terdekatnya yang “tidak mengerti”. Yang lebih konyol lagi, untuk apa dia pindah ke Bali, menjadi gelandangan, padahal di kampung halamannya ia bisa saja tinggal nyaman di rumah keluarga, menggarap ladang keluarga, toh menulis puisi masih tetap bisa dilakukan.
Latar belakang seperti itu sangat layak dijadikan semacam pemandu untuk memahami sajak-sajaknya. Ia, misalnya, tetap tidak bisa melepaskan dirinya dari keyakinan ke-Islam-an yang kuat, tetapi diungkapkan tidak dengan biasa.
Lihatlah, misalnya, bagaimana dengan “sangat kurang ajar” dia mengaku di-SMS oleh (Malaikat) Maut, menyatakan “Sorry Nur aku gak jadi datang sekarang / kuda kepangnya dipakai jathilan!” (Ketika Sakit Terbayang Maut, hlm 21). Padahal si penyair sudah berharap dia berangkat pada kematian (absurd) mengendarai kuda kepang. Sinting ‘kan? Jika ibunya tahu si anak nakal ini guyonan tentang malaikat, bisa-bisa dia didamprat habis. Mana boleh mempermainkan malaikat seperti itu.
Tapi, ya begitulah, Nuryana senang bermain-main, senang memandang hal dengan enteng, tidak mesti mengernyitkan kening.
Ya sudahlah. Apa boleh buat. Karena saya tidak bisa melepaskan “Nuryana” dari sajak-sajaknya, maka maafkan saya kalau saya katakan, hampir semua sajak yang ditulis dengan sangat jelas menggambarkan watak pribadi Nuryana yang acap kali tidak “normal” itu. Coba perhatikan sajak ini:
Lelaki dan Api
di depan kompor yang enggan menyala
lelaki itu menyalakan kesabarannya, api sedang tidur karena
semalam begadang di dapur rumah makan mungkin juga
api lagi mangkel karena tidak dihargai selalu dihidupmatikan
orang tanpa perasaan
bayangkanlah kalau seluruh api ngambek menyala
apa yang terjadi pada kehidupan manusia? (hlm. 27)
Simaklah kalimat “menyalakan kesabarannya”. Ini ungkapan yang tidak jamak. Kesabaran, bagi pemahaman umum kita di Indonesia, bukanlah api. Kesabaran adalah air. Sedangkan api, biasanya, dilekatkan pada kemarahan atau sesuatu yang berseberangan dengan kesabaran. Lalu, bagaimana mungkin kesabaran dinyalakan dengan api kompor?
Tapi inilah logika seorang Nuryana. Seperti pelukis absurd, ia memberontak dari pandangan umum. Jika gunung seharusnya berwarna biru, maka dengan entang ia bilang, “Lalu kenapa kalau saya melukiskannya dengan warna merah? Sebab saya melihat gunung itu sedang menyala, terbakar. Lalu kenapa jika saya melukiskannya dengan warna kuning? Sebab bukit itu sedang diterpa cahaya senja.” Kita pun kemudian terpaksa memahaminya sebagai kebenaran baru. Apa salahnya kesabaran digambarkan menyala-nyala bak api?
Pengelanaan logika jungkir-balik ala Nuryana ini masih dia lanjutkan dalam bait yang sama pada sajak yang sama. “… api sedang tidur karena/semalam begadang di dapur rumah makan mungkin juga/api lagi mangkel …”.
Yang pertama, sejak kapan api di seluruh dunia ini bersatu hanya dalam satu tubuh sehingga api yang begadang di sebuah rumah makan berakibat pada api yang dinyalakan di kompor yang letaknya entah di mana. Yang kedua, kalimat “mungkin juga” itu menyatu dengan baris yang mana? Kenapa disatukan dengan baris “semalam begadang di dapur rumah makan mungkin juga”?
Lagi-lagi logika kita dipaksa untuk mengikuti kemauan Nuryana. Kita “dipaksa” untuk menerima bahwa api di mana saja merupakan satu wujud. Jika api di rumah makan lelah disuruh begadang, maka api di seluruh dunia ikut merasakannya. Lalu siapa yang bisa membantah? Jangan-jangan memang benar, seluruh api di muka bumi ini sesungguhnya hanya satu. Paling tidak, memiliki satu jiwa. Ilmu pengetahuan alam belum berusaha menguraikannya.
Lalu, prihal “mungkin juga” yang disatukan pada baris “semalam begadang di dapur rumah makan mungkin juga”, padahal logika umum menyatakan, akan lebih pantas jika disatukan pada baris “api lagi mangkel karena tidak dihargai selalu dihidupmatikan” sehingga menjadi mungkin juga api lagi mangkel karena tidak dihargai selalu dihidupmatikan.
Untuk ini saya teringat pada satu ayat Al Quran S. Al Baqarah ayat 2: Dzalik al kitab la raiba (tanda berhenti) fihi (tanda berhenti) hudan lil muttaqin. Nuryana pasti sangat paham pada susunan surat ini. Ada dua tanda pemberhentian sesudah kata raiba dan fihi dengan tanda tiga titik. Itu berarti tanda berhenti itu hanya boleh digunakan salah satu saja. Kalau berhenti pada kata la raiba, tidak boleh berhenti pada fihi. Begitu sebaliknya.
Makna ayat itu: Inilah kitab yang tidak ada keraguan (tanda berhenti) padanya (tanda berhenti) petunjuk bagi yang bertakwa. Pada ayat ini, kata fihi (padanya) bisa melekat pada kalimat sebelumnya, bisa juga melekat pada kalimat sesudahnya.
Jadi, terjemahan ayat itu bisa menjadi Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa atau Inilah kitab yang tidak ada keraguan, padanya petunjuk bagi yang bertakwa. Tampaknya teknik seperti inilah yang –entah sengaja atau tidak—diadopsi oleh Nuryana, sehingga dua baris itu bisa dibaca dengan “(mungkin juga) semalam begadang di dapur rumah makan, api lagi mangkel …” atau bisa dibaca “semalam begadang di dapur rumah makan,mungkin juga api lagi mangkel …”.
Teknik penulisan seperti ini banyak sekali kita temukan pada sajak-sajak Nuryana yang terkumpul dalam buku DBUP. Pada “Stasiun transit”, misalnya. “bersiaplah di gerbang pemberangkatan aku/menjemputmu, kita tempuh perjalanan ke kota nun” (hlm 74). Begitu juga dengan “karena juru kunci telah pergi kami kehilangan/jejak sebelum pepohonan …” pada sajak “Tamsil Merapi” pada hlm 92.
Tidak biasa
Lepas dari persoalan di atas, yang sangat menarik dari sajak-sajak Nuryana adalah cara pandang yang tidak biasa (kalau tidak mau disebut absurd). Simaklah bagian akhir dari sajak “Lelaki dan Api” berikut ini:
api yang masih tidur bermimpi diguyur hujan
hingga basah kuyup dan mengigil, di depan kompor
yang tak mau menyala lelaki itu terus berdoa: “Api
janganlah ikut-ikutan ngambek seperti istriku di saat
aku lagi miskin, ayo menyalalah sekadar mendidihkan
air untuk mie dan kopi!” api sempat terjaga, tapi
tidur kembali karena lelah, hujan dan hawa dingin
membuat tidurnya semakin nyenyak.
Hlm. 27
Cara pandang tidak biasa terhadap masalah-masalah biasa seperti api dan pohon pisang yang dianggap titisan para leluhur, dan karenanya, disetubuhi beramai-ramai saat bermain di kebun, menjadi daya tarik khas dari kumpulan puisi ini.
Pasalnya, pada setiap pengelanaan pikiran Nuryana, kita pun diajaknya merenung, memasuki ruang-ruang tidak biasa, meskipun objek penulisannya adalah hal-hal sederhana yang kita temui setiap hari. Tentang ayunan, misalnya, ia bahkan menulis empat sajak panjang.
Anehnya, terus terang, saya merasa banyak sajak sejenis ini yang sengaja ditulis Nuryana sebagai salah satu cara untuk menceritakan perjalanan hidupnya, keperihan hatinya, kegagalan cintanya, bahkan masa-masa laparnya.
dara muda keturunan raja itu sering datang
ke rumahku meminta menemaninya main
ayunan di halaman belakang. “Maaf aku sudah
jadian dengan ayunan, kami saling mencintai
sejak kanak-kanak,” katanya ketika kuajak jadian
Ayunan II hlm 116
Saya melihat sajak ini tidak melulu curhatan penyairnya yang cintanya ditolak oleh gadis yang disukainya, tetapi juga pengelanaan imaji tentang hidup yang selalu diayun. “Tak mengapa main ayunan sebab pada awal dan/akhir hidup semua diayun agar bahagia.”
Atau ini:
andai aku nanti gagal jadi kupu-kupu
biarkan mati di goa pertapaan, Ibu
agar sempurna derita keterasinganku
dalam semedi kubayangkan engkau
datang membawa sayap untukku
tapi jasadku terlalu lemah
untuk mengangkat sayap itu
kudengar di luar hidup begitu kejam
bagaimana aku bisa menyelamatkan diri?
kalau aku nanti tak jadi kupu-kupu
tungu di alam mimpi, Ibu
mungkin ruhku bisa menziarahi rindumu!
“Sembahyang Kepompong” hlm 24
Kita paham belaka, Nuryana menyuarakan kepedihannya dengan meminjam cerita kupu-kupu. Kita juga dengan mudah bisa memahami bahwa sang penyair sedang merasa dirinya seperti ulat dalam kepompong yang lemah, yang tak yakin bisa menjelma menjadi kupu-kupu. Kita paham itu. Tapi yang juga sangat kita pahami, tidaklah terlalu banyak orang yang tidak menjelaskan kepedihannya dengan kalimat semisal “aku adalah kupu-kupu yang gagal memperoleh sayap.” Semacam itulah.
Juru Catat
Selain sebagai penyair, tampaknya Tuhan telah merancang lelaki belum beristri yang bernama Nuryana Asmaudi SA ini sebagai jurnalis yang tekun. Bahkan sajak-sajaknya pun sangat tekun mencatat kejadian sehari-hari di sekitar atau hal-hal yang –mungkin—dalam pandangan orang lain hanyalah perkara remeh atau perkara sehari-hari yang lewat begitu saja.
Bacalah, misalnya, sajak “Vertigo, Pesawat Terbang di Kepalaku,” sebuah sajak tentang sakit kepala yang ditamsilkan bagai pesawat terbang yang jumpalitan di tengah kepala. Baca pula sajak “Puntung Rokok dan Pengarang.” Nuryana bercerita dengan bahasa sangat sederhana tentang pengarang yang kelimpungan di kamarnya, sementara puntung rokok di asbak sudah tidak bisa dikais lagi (tentu untuk dibakar dan dihisap lagi). Pikiran pun macet. Ia marah pada kertas dan mesin tik …
Inilah juru catat yang dengan sangat baik memberi makna pada hal-hal kecil yang ditemuinya, memberi nilai pada “manusia digigit anjing,” sehingga ia bisa dengan cara yang sangat berbeda berbicara mengenai keprihatinan sejuta umat mengenai penggundulan hutan, misalnya.
Ia menumpahkan keprihatinannya dengan sangat dingin melalui “berita” pohon-pohon yang meninggalkan hutan mengadu nasib ke kota menjadi buvet-divan, meja-kursi, bahkan banyak yang telah kabur ke luar negeri (Selamat Jalan Pohon, hlm. 30).
Pada banyak sajak yang disajikan dalam buku kumpulan ini, saya sangat menyukai kebersahajaan Nuryana. Ia tidak berusaha menggali kalimat-kalimat indah untuk menyajikan perasaannya.
di balik lukisan yang tergantung di kamar
tokek numpang tinggal jadi teman hidup
bujang pandir di rumah rantau
kepada hewan tahan lapar itu si pandir belajar
(Belajar Hidup (1), hlm 36)
Kepada capung yang masuk kamar ia bilang:
“Tumben datang malam-malam?”
Capung memutar-mutar seperti perempuan mabuk
hinggap-terbang hinggap-terbang dari tembok
ke tembok sementara tokek mengintai di sebalik lukisan
(Belajar Hidup (2), hlm 37)
Sungguh sederhana. Bahkan Nuryana tidak berusaha “mengarahkan” pembacanya untuk menafsir-nafsir makna di balik kalimat yang ditulisnya. Ia menghadirkan tokek sebagai tokek yang bersembunyi di balik lukisan. Ia juga membicarakan capung yang datang malam-malam apa adanya sambil menangkap sudut lain, yakni tokek yang mengintai di balik lukisan.
Nuryana secara verbal menyatakan bahwa dirinya sedang belajar kesabaran pada tokek dan belajar kepasrahan kepada capung yang dicaplok tokek. Ini semacam dongeng yang diakhiri dengan kalimat “Yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah …” seperti biasa diucapkan oleh para pendongeng kepada pendengarnya. Hanya saja, Nuryana menyajikan kesederhanaan itu menjadi sajak yang kuat, meskipun lahir tidak dari kerutan kening.
Saya ingin mengulang, Nuryana mampu menyajikan kedalaman di kesederhanaannya. Ia pun acap kali menggali sesuatu di balik hal-hal biasa yang mungkin telah kita lihat berulang-ulang, sesuatu yang kita pandang sambil lalu. Pada sajak “Percakapan di Taman”, misalnya, kita dijerat dan diseret ke dalam percakapan intens dua patung di taman, yakni patung anjing dan patung perempuan.
Percakapan sederhana di antara mereka, lalu nasib yang diterima patung perempuan yang digerayangi tangan lelaki sinting hingga amis, juga tentang anjing yang menggali di tanah di samping sang patung hingga patung itu miring, semua membawa kita pada perasaan duka, rasa kasihan, atau bahkan empati.
Di antara sekian sajak dengan cara pengungkapan penuh kesederhanaan itu, Nuryana juga menyajikan sajak-sajak “indah” dan “sophisticated” semisal “Dari Umbu untuk Ahmucham” (hlm 131). Di sana Nuryana berusaha menyajikan kata tidak melulu sebagai “kata”, tetapi juga sebagai irama, sebagai bunyi, dan menyajikan imaji yang berbeda dengan kecenderungan umum sajak-sajak yang termuat dalam kumpulan ini.
Saya sendiri, sekali lagi mohon maaf, tidak merasakan kehadiran Nuryana dalam sajak-sajak sejenis ini. Saya melihatnya sebagai bagian lain dari Nuryana dan seperti ingin berkata, “Kalau mau, aku juga bisa menulis sajak seperti ini.”
Logika jungkir balik dengan perenungan sederhana, menangkap peristiwa-peristiwa sehari-hari yang sederhana, disajikan dengan ungkapan-ungkapan sederhana, adalah kekuatan sangat khas dari kumpulan ini. Bahkan, berkat kesederhanaan cara ungkap itu, saya dengan sangat cepat bisa tahu teman perempuan yang dijadikannya objek penulisan puisinya.
Ia tidak berusaha menyembunyikan nama. Ia tidak berusaha membingkai kalimat pujian kepada perempuan yang saya kenal dan juga dikenal oleh teman-teman sepergaulan Nuryana. Kendati demikian, saya masih dengan sangat mudah menikmati sajak-sajak itu sebagai sajak.
Semua yang telah saya ungkapkan seperti mendapatkan penegasan pada sajak “Doa Bulan untuk Pungguk.” Jungkir balik pemikiran (kenapa tiba-tiba bulan yang dirindukan oleh pungguk merasa terharu dan memanjatkan doa), kesederhanaan ungkapan, dan objek puisi yang tak terpikirkan sebelumnya beserta kandungan keanehannya, diberi tempat sempurna dalam sajak ini, sehingga ia seperti menjadi “kesimpulan” dari buku ini. Sangatlah cerdik memilih sajak ini sebagai judul buku.
Maka saya ingin mengubah sedikit judul sajak itu menjadi “Doa Bulan untuk Nuryana” dan menjadikannya judul tulisan. (T)
Denpasar, 25 Agustus 2016