DALAM salah satu film serial “Bidaah” dari negeri jiran Malaysia bertema penyimpangan ajaran dan praktik beragama, tokoh utama Walid memperkenalkan konsep “nikah batin” sebuah ikatan yang katanya sah secara spiritual, meski tak diakui secara hukum. Konsep absurd itu dibungkus dengan argumen seolah-olah suci dan lurus, meski kenyataannya timpang dan menyesatkan. Dalam konteks dunia pendidikan hari ini, para dosen di Indonesia menjalani versi lain dari “pernikahan batin” bukan dengan pasangan, melainkan dengan negara. Namanya Tukin Bathin.
Tukin sebagai Simbol Penghargaan Kinerja Dosen
Tunjangan kinerja (Tukin) semestinya menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras dosen dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tukin untuk dosen diberikan tanpa standar yang transparan, tanpa formula yang adil, dan tanpa pengakuan terhadap beban kerja intelektual yang dijalani. Relasi ini sah secara administratif, tapi menyakitkan secara moral. Negara hadir, tapi hanya sebagai pasangan formalitas.
Per 15 April 2025, melalui taklimat media dari utusan pemerintah di tiga kementerian terkait yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Muliani akhirnya mengumumkan pencairan Tukin untuk 31.066 dosen ASN melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2025. Angka yang digelontorkan tidak kecil yaitu Rp 2,66 triliun. Kendati demikian, di balik euforia pencairan di bulan Juli mendatang, terdapat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang belum dijawab: benarkah Tukin ini merupakan bentuk keadilan? Atau sekadar kompensasi birokratik yang menambal krisis kepercayaan dosen terhadap negara?
Kebijakan ini datang setelah bertahun-tahun desakan dari komunitas akademik hingga terbentuknya wadah dosen untuk berserikat di bawah naungan Serikat Pekerja Kampus (SPK), menyusul terbentuknya Asosiasi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) dan komunitas serupa. Sejak amanat Tukin bagi dosen ASN digulirkan dalam Perpres Nomor 153 Tahun 2015 dan turunannya, implementasinya justru mandek di tengah jalan selama hampir satu dekade.
Kini, ketika pemerintah akhirnya menyetujui pencairan Tukin, banyak pihak menilai kebijakan ini datang terlambat dan setengah hati. Tukin hanya berlaku ke depan, tanpa menyentuh masa lalu. Padahal, selama tahun-tahun sebelumnya, dosen tetap menjalankan tugas negara seperti mengajar, membimbing, meneliti, hingga mengabdi dalam berbagai kegiatan dan akreditasi program studi di masing-masing unit kerja. Dimensi retroaktif yang diabaikan ini mengindikasikan ketidakkonsistenan negara dalam menghargai jasa intelektual.
Kompleksitas Kinerja dan Bayang-Bayang Kesejahteraan Semu
Ironisnya tak main-main. Seorang dosen di satuan pendidikan yang berstatus PTNBH dan PTN BLU Remunerasi yang menerapkan sistem remunerasi berdasarkan perpres nomor 19 tahun 2025 tidak menerima Tukin, namun menerima penghargaan atas kinerja berupa remunerasi yang berbeda-beda tiap kampus yang jauh lebih kecil dari pegawai kementerian yang bekerja di balik meja. Padahal dosen memikul beban yang luar biasa seperi mengajar, membimbing, meneliti, menulis jurnal, mengisi borang akreditasi, terlibat dalam beragam kegiatan prodi, fakultas, bahkan universitas. Akan tetapi penghargaan negara terhadap kerja ilmiah ini sangat minim baik dalam bentuk insentif maupun dukungan sistem.
Sistem evaluasi kinerja dosen pun kian menjauh dari substansi. Dosen dipaksa menyesuaikan diri dengan indikator teknokratis yang tak menggambarkan esensi kerja intelektual. Nilai kinerja dihitung dari ketepatan unggah dokumen, bukan dari kualitas gagasan atau dampak keilmuan. Ketika birokrasi menjadi ukuran tunggal, maka kampus hanya akan melahirkan orientasi pemenuhan data borang, bukan pemikir merdeka.
Tukin Bathin sebagai Simbol Ketimpangan Relasi
Fenomena ini melahirkan istilah satir yang layak direnungkan yaitu Tukin Bathin. Seperti halnya “nikah batin” dalam konsep ajaran menyimpang dari pemeran Walid, dosen merasa seolah-olah dihargai, tapi sejatinya dinomorduakan. Tukin diberikan, tapi tidak cukup untuk menopang hidup yang layak. Apresiasi diberikan, tapi hanya di atas kertas.
Tak sedikit akademisi muda yang akhirnya meninggalkan dunia kampus. Bukan karena hilang idealisme, tapi karena kehilangan kepercayaan bahwa negara akan berpihak pada pengetahuan. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia akan menghadapi krisis mutu pendidikan tinggi, dan pada akhirnya melahirkan krisis peradaban intelektual.
Pemerintah perlu menghentikan praktik relasi semu ini. Dosen bukan birokrat. Kinerja mereka tak bisa diseragamkan dengan pegawai struktural. Penilaian Tukin harus kontekstual, substansial, dan proporsional. Reformasi kebijakan Tukin dosen adalah langkah mendesak demi menjaga masa depan bangsa dan dunia akademik kita hari ini.
Jika tidak, maka Tukin Bathin akan terus menjadi simbol relasi timpang antara negara dan kaum intelektualnya. Sah secara administratif, tapi menindas secara bathiniah. [T]
Penulis: Muhammad Idris
Editor: Adnyana Ole
- BACA JUGA:


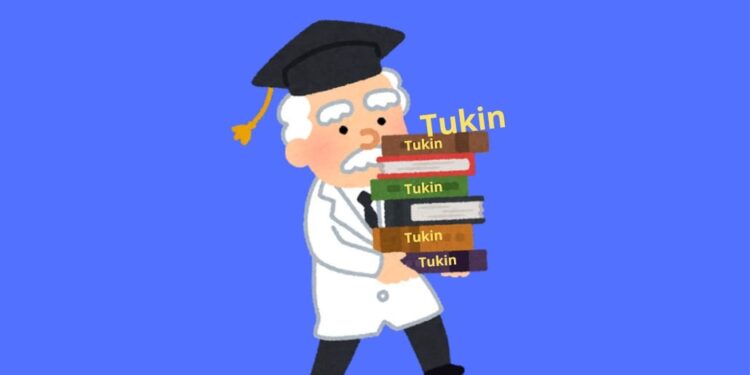





![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-75x75.jpg)















