PADA 1930-an, ada seorang lelaki sedang menjaga hasil panen padi di sawah miliknya. Masa itu, setelah panen, padi tidak langsung dibawa ke rumah—penduduk sekitar biasanya menumpuknya di pematang dan menungguinya sampai hasil panen benar-benar dibawa ke rumah dan diamankan di lumbung.
Lelaki itu bernama Gusti Made Alit. Ia menjaga hasil panen di malam buta di sebuah gubuk rumbia yang sudah reyot. Malam tetap saja gelap, meski lampu sentir masih menyala dan meliuk terbawa angin. Di tengah malam, di tengah kesunyian, Made Alit melantunkan pupuh dangdang gendis—salah satu bagian dari tembang macapat.
Saat melantunkan pupuh itu, semesta seolah ikut serta. Suara-suara sawah di gelap malam, seperti nyaring suara katak, jangkrik, air gemericik, mengiringi tembang yang dilantunkan Made Alit. Saat itu ia merasa sangat tenang dan senang—bahkan mungkin merasakan sebuah perasaan yang belum ternamakan sebelumnya. Yang jelas, ia seperti terbang ke awang-awang. Made Alit mendapatkan sunia.
Keesokan harinya, Made Alit menuturkan pengalaman menakjubkannya itu kepada dua temannya, yakni I Ketut Sridana (akrab dipanggil Pan Madra) dan I Ketut Widra—atau yang lebih dikenal dengan panggilan Pan Kaler.
Pan Madra dan Pan Kaler mencoba menggubah pupuh tersebut menjadi teramat unik dan khas. Kedua tokoh tersebut mencoba menambahkan unsur-unsur suara seperti katak di sela-sela lantunan pupuh. Tambahan unsur inilah yang disebut ongkekan (cecandetan khas suara katak) yang membuat kesenian tersebut terdengar lebih ritmis sekaligus jenaka. Lalu, bersama teman-temannya—seperti Ketut Suka, Sutiaji, Pogot, dan termasuk Gusti Made Alit—Pan Madra dan Pan Kaler mencoba melantunkan dangdang gendis yang sudah digubah, diaransemen itu, secara bersama-sama.
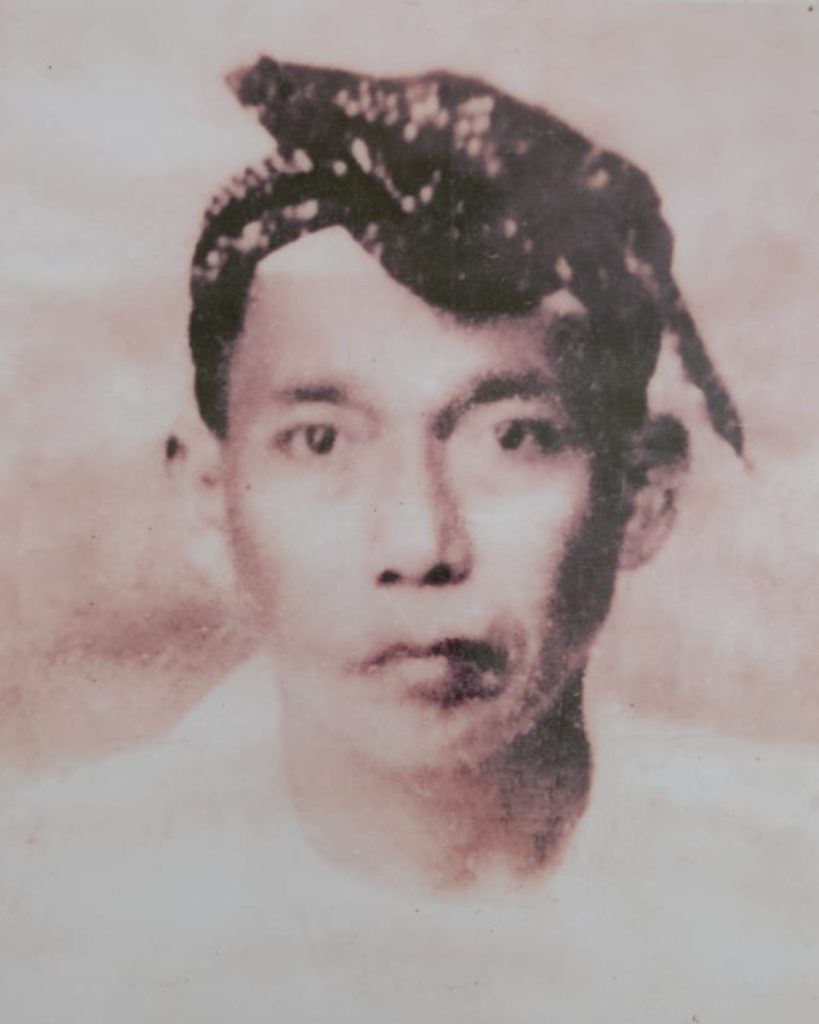
I Ketut Sridana (Pan Madra) | Foto: Dok. Sekaa Renganis Penglatan
Sejak saat itulah muncul ide untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai sebuah bentuk kesenian suara dan sastra lisan yang kemudian hari dikenal dengan nama kesenian Renganis—kesenian yang memadukan berbagai unsur suara, seperti suara gamelan, geguritan, dan suara binatang, yang semua perpaduan itu dimainkan hanya dengan suara mulut.
Sedangkan terkait namanya, beberapa orang menganggap istilah renganis berasal dari dua suku kata, yaitu reng manis—karena pakem dasarnya menggunakan pupuh dangdang gendis. Pendapat lain mengatakan bahwa renganis berasal dari kata renge nis, yang berarti suara dari kesunyian. Terlepas dari itu semua, Renganis kemudian menjelma menjadi kesenian yang, tak hanya sekadar menjadi hiburan, tapi juga sarana spiritual orang-orang Penglatan.
Begitulah Wayan Sukerena, 64, menceritakan asal-usul Renganis di rumahnya yang sederhana di Gang Sukun, sebelah timur SMP Negeri 5 Singaraja di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Sore itu, lelaki sepuh itu menggebu dengan suara lantang bertempo lambat. Sesekali ia terdiam sebelum cerita masa lalu itu mengalir deras dari bibirnya.
“Pada saat itulah, setiap purnama kedasa, pada saat menjelang panen padi, Renganis dijadikan sebagai iringan upacara Ngusaba Nini—ucapan syukur kepada Hyang Widhi dalam perwujudannya sebagai Dewi Sri yang telah melindungi pertanian di Penglatan,” tutur Wayan Sukerena, suaranya bersahut-sahutan dengan kicau burung—yang terdengar timbul tenggelam—dan gonggong anjing yang diikat di pekarangannya.
Tetapi, sambung Sukerena, yang dijadikan sebagai iringan Ngusaba Nini hanya kidungnya, bukan ongkekan-nya. “Jadi, ada yang untuk sarana spiritual, ada juga untuk hiburan,” kata orang tua pensiunan kehutanan itu.
Di Penglatan, Renganis memiliki hubungan erat dengan padi. Pada saat menjelang panen raya padi—beberapa orang Bali menyebutnya kerta masa—penduduk Penglatan, sebagaimana diterangkan Sukerena di atas, akan menyelenggarakan upacara Ngusaba Nini.
Upacara ini selalu diadakan setiap purnama kedasa. Nini diyakini sebagai simbol perwujudan Dewi Sri. Tak sembarang padi bisa digunakan untuk membuat Nini. Hanya padi yang tumbuh di sawah yang terletak di hulu air mengalir—orang-orang setempat menyebutnya sawah pengalapan.
Di sawah-sawah itulah, padi-padi dipetik untuk dibuat menjadi Nini berjumlah dua. Dalam proses pembuatannya, dengan berbagai sesajen menurut kepercayaan penduduk Penglatan, orang-orang secara bersama-sama akan menembangkan kidung Renganis. Beberapa orang yang mampu bahkan menambahkan iringannya dengan gamelan.
Seusai Nini dibuat, petani-petani Penglatan yang membuatnya akan menggotongnya, memundut, sampai ke lumbung masing-masing. Di Penglatan, sebagaimana (mungkin) juga di daerah lain di Bali, ada tiga jenis lumbung dengan nama dan ukuran yang berbeda-beda. Ada lumbung bernama jineng, glebeg, dan klumpu.
Jineng merupakan lumbung padi yang berukuran besar, tinggi, dan bertingkat—semacam rumah panggung yang di bawahnya masih dapat dijadikan sebagai tempat untuk beraktivitas. Sebaliknya, glebeg hanya terbatas sebagai tempat penyimpanan padi. Sedangkan klumpu merupakan lumbung padi yang berukuran lebih kecil daripada glebeg.
Tiga jenis lumbung ini biasanya berkaitan dengan strata sosial dan kemampuan masyarakat di Penglatan. Semakin kaya petani dan memiliki sawah yang luas, misalnya, maka tak mungkin hanya akan membangun glebeg atau klumpu, pasti ia akan mendirikan jineng. Mengingat, selain mampu, juga muat untuk menampung hasil padinya yang melimpah.
Setahun setelah Nini disimpan di lumbung, orang-orang akan menurunkannya. Kini saatnya Nini ditumbuk, dipisahkan kulit dengan bulir berasnya. Proses ini kemudian melahirkan satu kesenian lagi bernama Ngoncang—memukul lesung menggunakan alu.

Wayan Sukerena | Foto: Jaswanto
“Beras itu kami sebut galih,” ujar Wayan Sukerena, Kelian Sekaa Renganis Penglatan. Bulir galih dipercaya telah mendapat karunia dari Dewi Sri. Galih biasanya disimpan di sebuah tempat yang, dalam bahasa Bali, disebut gebeh—semacam tempayan tempat air.
“Setiap masak nasi, orang-orang sini akan mengambil beberapa bulir galih untuk dicampur. Misalnya masak beras sekilo, cukup ambil barang lima atau sepuluh butir galih. Karena dipercaya sudah diberkati oleh Dewi Sri, maka nasinya jadi mesari. Kalau ada upacara besar di desa, penduduk juga menyumbang galih mereka untuk diolah menjadi jajanan,” kata lelaki yang akrab dipanggil Pak Yan itu.
Jika menjelang panen, pada saat Ngusaba Nini orang-orang Penglatan hanya melantunkan kidungnya saja, maka menjelang tanam pagi, saat orang-orang istirahat, penat setelah membajak, mereka akan memainkan Renganis lengkap dengan okekan-nya.
Dalam pakem kesenian Renganis, setidaknya ada tiga jenis ongkekan atau tabuh dalam karawitan, yakni bebatelan, peangklungan, dan gegambangan. Kalau dalam khazanah karawitan, tabuh bebatelan identik dengan sesuatu yang keras, maskulin.
Sebaliknya, peangklungan merupakan sisi lainnya, mewakili sesuatu yang halus, lembut. Sedang gegambangan, menurut Sukerena, diucapkan sebagaimana irama gambang. Renganis mengadopsi irama gambangan, bukan pukulannya, katanya.
Renganis—sebagaimana dikutip dari artikel Renganis, Seni Suara Tradisional Khas Desa Penglatan (2008) tulisan Made Adnyana Ole—dimainkan oleh sekelompok orang yang kalau dalam musik pop bisa dipadankan dengan sebuah kelompok vokal tanpa musik.
Dalam renganis, tulis pensiunan wartawan Bali Post itu, “masing-masing orang memainkan nada yang berbeda-beda sehingga sebuah lagu akan terdengar sangat atraktif, meriah, yang terkadang diselipi nada jenaka. Dalam istilah Bali, lagu-lagu itu dimainkan dengan suara mecandetan”.
Menurut Ole, meski sama-sama menggunakan musik mulut, Renganis sangat berbeda dengan Cak yang berkembang di Badung dan Gianyar atau dengan seni Genjek dan Cakepung yang tumbuh pesat di Buleleng dan Karangasem. Hal ini juga dikatakan oleh Wayan Sukerena.
Jika Genjek lebih banyak memainkan lagu-lagu rakyat yang lebih populer, sebaliknya, Renganis lebih memilih tembang-tembang yang dikreasikan dari kakawin, kidung, dan geguritan. Sedangkan Cak, kata Ole, meski juga memainkan cecandetan dengan suara yang berbeda-beda, namun kata yang diucapkan oleh masing-masing pemain adalah kata yang sama, yakni cak.
“Namun, dalam Renganis, cecandetan atau cecangkitan itu dimainkan dalam sebuah lagu. Nada yang disuarakan pemainnya berbeda-beda dan saling candetin sehingga menjadi satu rangkaian nada yang manis,” tulisnya.
Nada suara dalam seni Renganis menjadi lebih hidup saat dikombinasikan dengan cecandetan yang menyerupai suara katak. Sehingga, dalam Renganis, ada sejumlah pemain yang berfungsi sebagai pengugal, penyandet, atau pengokek. “Itulah Renganis,” kata Sukerena.
Renganis, Setelah Kejayaannya
Pada tahun 1930-an sampai 1980-an, kesenian di Bali memang sedang bergeliat, termasuk kesenian di Buleleng, Bali bagian utara. Orang-orang seperti Gde Manik dan Ketut Merdana dalam khazanah kesenian Gong Kebyar di Buleleng, termasuk seniman pilih tanding dalam rentang tahun itu. Dan pada tahun 50-an, jika di Jagaraga atau di Kedis orang-orang sedang gencar-gencarnya belajar kebyar, di Penglatan kesenian Renganis sedang populer-populernya.
Desa Penglatan bisa dibilang sebagai sebuah laboratorium untuk mengolah berbagai jenis seni suara dan sastra lisan. Memang, sejak tahun 1980-an, kelompok-kelompok pesantian yang menembangkan berbagai jenis seni suara dan sastra, seperti kekawin, kidung, dan geguritan, berkembang pesat di seluruh pelosok Bali. Namun, tampaknya, hanya para seniman di Desa Penglatan yang lebih berani memberi sentuhan nada-nada unik dalam tiap tembang-tembang yang mereka lantunkan.
Atas keberanian itulah kemudian tumbuh sebuah kesenian langka dan teramat khas. Namanya seni Renganis, sebuah seni yang memadukan berbagai unsur suara, seperti suara gamelan, geguritan, dan suara binatang, yang semua perpaduan itu dimainkan hanya dengan suara mulut.
Bahkan, tak hanya sebatas sebagai hiburan, sebagaimana telah dijelaskan Sukerena di atas, kesenian yang murni menggunakan mulut itu juga dijadikan sebagai bagian dalam upacara-upacara penting dan sakral seperti Ngusaba Nini atau piodalan di Pura Taman.
Sebagaimana kesenian Sanghyang, Renganis juga lahir dan tumbuh dari sebuah kultur masyarakat agraris yang punya kecintaan begitu kental terhadap alam dan lingkungan. Maka dari itu, Renganis sangat berhubungan dengan padi—tumbuhan yang tak semata mengusir lapar, tetapi juga memikat mitos. Tumbuhan yang sejak belasan ribu tahun lalu tumbuh di lahan-lahan subur Asia. Tumbuhan yang kini memasok perut lebih separuh warga bumi.
Pada tahun 70 sampai 80-an, di saat sawah dan padi di Penglatan masih luas dan melimpah, sebelum masifnya alih fungsi lahan dan semakin berkurangnya petani, kesenian Renganis seperti telah mencapai puncak kejayaannya—walaupun pada tahun 1963, saat Gunung Agung meletus, kesenian ini tidak lagi dipentaskan karena lahan pertanian rusak dan padi menolak tumbuh. Pada tahun yang sama, upacara Ngusaba Nini juga tidak dilakukan.
“Bagaimana mau diselenggarakan, orang padinya tidak ada,” kata Sukerena sembari tertawa. Tetapi, di balik tawa itu, seperti ada sesuatu yang mengganjal tenggorokannya sehingga ia tercekat. Dan benar, sesaat setelah mengatakan hal tersebut, ia menangis. Terbata-bata ia berkata, “Kami hanya makan singkong.”
Setelah tahun-tahun yang penuh tragedi itu—dua tahun setelah Gunung Agung muntah, terjadi goro-goro kemanusiaan yang masuk dalam catatan kelam sejarah bangsa Indonesia, Gestok atau G30S—Renganis bangkit, eksis kembali meski berkali-kali ”pingsan” dan nyaris ”mati”.
Menanam dan panen padi dirayakan kembali. Menyambut tamu penting, ulang tahun STT, orang-orang bayar kaul (naur sesangi), sampai upacara kematian, Renganis nyaris tak pernah ketinggalan. Pada kisaran tahun-tahun itu, kesenian ini sudah mendarah-daging, menjadi bagian hidup orang-orang Penglatan.
Tetapi, pada tahun 1990-an, saat generasi pertama dan kedua, ketika orang-orang seperti Ketut Suka, Sutiaji, Pogot, Gusti Made Alit, Pan Madra, dan Pan Kaler sudah kembali ke Asal, dan maraknya alih fungsi lahan, juga masifnya kampanye pariwisata di Bali bagian selatan, Renganis seperti dicampakkan oleh sebagian orang Penglatan. Hal ini juga terjadi di dunia kebyar di Buleleng.
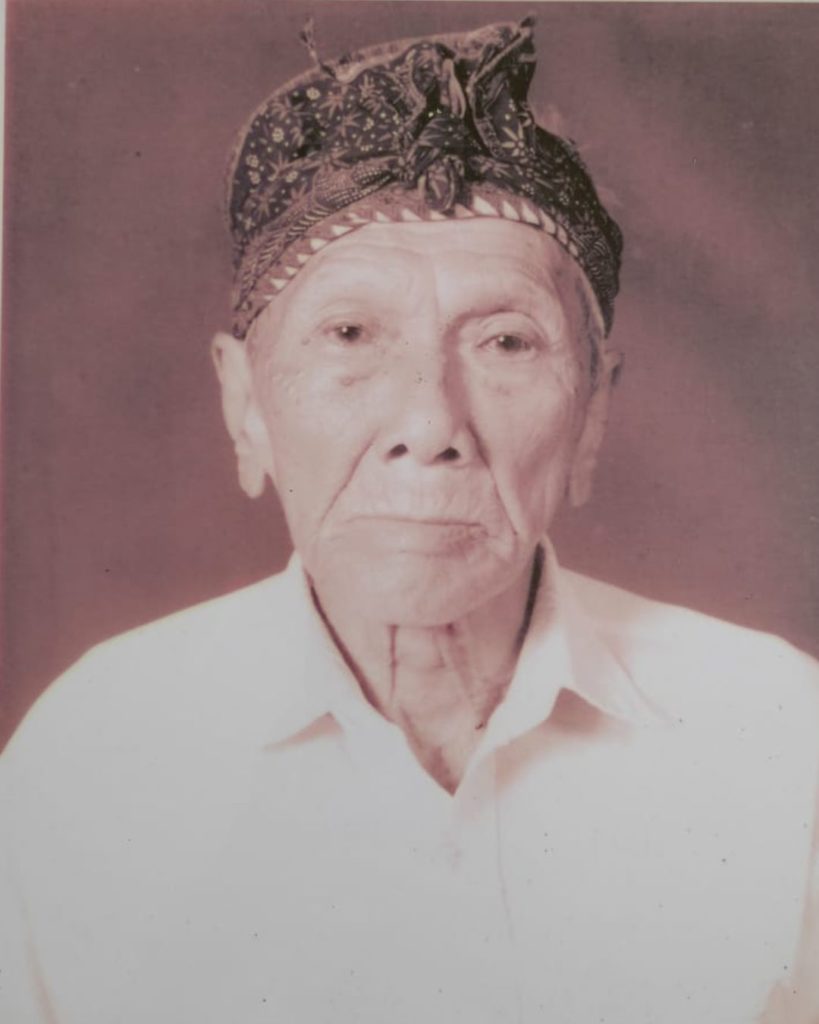
I Ketut Widra (Pan Kaler) | Foto: Dok. Sekaa Renganis Penglatan
Maka dari itulah, menurut Wayan Sukerena, yang notabene sebagai cucu kandung I Ketut Widra—atau yang lebih dikenal dengan Pan Kaler, founding father Renganis—pada tahun 2000-an, Renganis mengalami pergulatan kreasi, kolaborasi, dan modifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat masyarakat dan sebagai sebuah usaha melestarikan kesenian Renganis. Misalnya, mulai masuknya unsur-unsur cerita dalam tiap lagu yang dimainkan.
Cerita-cerita itu biasanya diambil dari kisah-kisah kerajaan atau kisah panji, seperti Raden Putra Kahuripan, Galuh Daha, dan Anglung Semara. Selain itu, jenis-jenis cecandetan-nya juga makin beragam sehingga lagu-lagu yang dimainkan menjadi makin manis sekaligus bernas.
Namun, meski demikian, seperti halnya seni tradisional lainnya, Renganis kini tetap berada di ambang kepunahan. Zaman melesat seperti kijang berlari. Padi seperti nyaris tak bisa dijnakkan. Rencana-rencana swasembada bisa ambruk oleh wabah dan bencana—dan akibatnya bisa fatal secara politis.
Beras adalah topik yang hangat saban tahun, apalagi di musim kampanye saat para politisi berkoar soal perut rakyat yang lapar. Memastikan produksi beras adalah tanggung jawab negara, dan beban itu diletakkan pada pundak kaum petani di desa-desa, termasuk Penglatan. Sayangnya, orang-orang Penglatan sudah tidak hanya berprofesi sebagai petani. Banyak sawah dialihfungsikan. Renganis sudah jarang dipentaskan di sawah-sawah setelah penat membajak.
Renganis menjelma kesenian yang tampak tumbuh secara tertatih. Sistem regenerasinya juga berjalan lambat. Jika pun masih ada anak muda yang mau belajar, jumlahnya sangat sedikit—dan itu pun biasanya masih berasal dari keluarga pendiri dan penciptanya, yang juga merupakan keluarga turunan dari Pan Madra dan Pan Kaler.
Namun, meski kondisinya demikian, Renganis Penglatan tetap menolak punah. Apalagi Pesta Kesenian Bali (PKB) memberikan Renganis kesempatan untuk menunjukkan diri. Dalam PKB tahun lalu, misalnya, Renganis ditampilkan bersama cerita Anglung Semara. Saat itu, kesenian Renganis seperti terpacak kembali dalam ingatan orang Penglatan. “Tahun itu banyak orang yang merasa memiliki Renganis,” kata Sukerena.
Menurut Wayan Sukerena, tokoh kesenian Renganis generasi ketiga itu, di Penglatan kini masih terdapat sekitar 20 anggota Sekaa Renganis yang masih siap tampil jika diperlukan. Anggota Renganis itu biasanya sekaligus masuk dalam satu sekeha pesantian yang biasa ikut ngayah dalam acara-acara suka-duka di lingkungan Desa Adat Penglatan. “Saya berharap anak saya bisa meneruskan tanggung jawab ini,” ujar Wayan Sukerena. Lelaki tua dengan tatapan bak petarung ini tampak serius dengan kata-katanya.[T]
Reporter: Jaswanto
Penulis: Jaswanto
Editor: Adnyana Ole









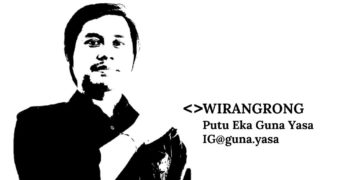












![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)










