FRANS NADJIRA, kawan-kawan seniman Denpasar memanggilnya Om Frans, adalah nama yang lekat dalam dunia sastra dan seni lukis di Bali. Di dunia sastra, ia merupakan tandem Bung Umbu Landu Paranggi dalam kerja-kerja pendampingan, apresiasi dan motivasi. Jika Bung Umbu lebih banyak diam dan manggut-manggut membaca atau mendengar karya seseorang dibacakan, atau “menitip pesan” pada seseorang lain untuk menyatakan “sajak si anu begini, sebaiknya begitu”, Om Frans tanpa tedeng aling-aling akan menunjuk ini dan itu langsung di hadapan si empunya sajak, mencorat-coretnya jika perlu, hingga tinggal sebaris dua dan ia sentak,”Harus kejam pada diri sendiri!”
Di Sanggar Minum Kopi Bali, cara tersebut populer disebut sebagai tradisi sparring partner, konon ia bawa dari Iowa City ketika ia berkesempatan residensi ke sana. Maka tak heran banyak penyair Bali sudah merasakan langsung “lekat tangan” Frans Nadjira yang mengurus sampai ke soal-soal teknis seperti pola pemenggalan dan tipografi.
Cara bicaranya yang lantang dengan logat khas Bugis, niscaya tinggal dalam ingatan banyak kawan yang pernah bersentuhan dengannya. Bertemu Om Frans di setiap tempat di Denpasar, mulai di sekretariat SMK Jl. Wahidin 37, di galeri seni dan tempat di mana suatu acara dilangsungkan (tahun 90-an ia begitu rajin datang), atau saat berkunjung ke rumahnya yang nyaman di kawasan Biaung, Sukawati, Gianyar (pernah juga ia tiba-tiba datang ke rumah saya di Yogya), nada lantang dan logat khas itu akan gampang terdengar. Lengkap dengan tatapan matanya yang tajam serius memandang lawan bicara dan sesekali gerakan tangan untuk membuat penekanan apa yang diucapkannya. Sekilas bagi yang belum terbiasa suasana seolah tegang, padahal di antara nada bicaranya yang menghentak itu tak jarang suara ketawanya membubung lepas.
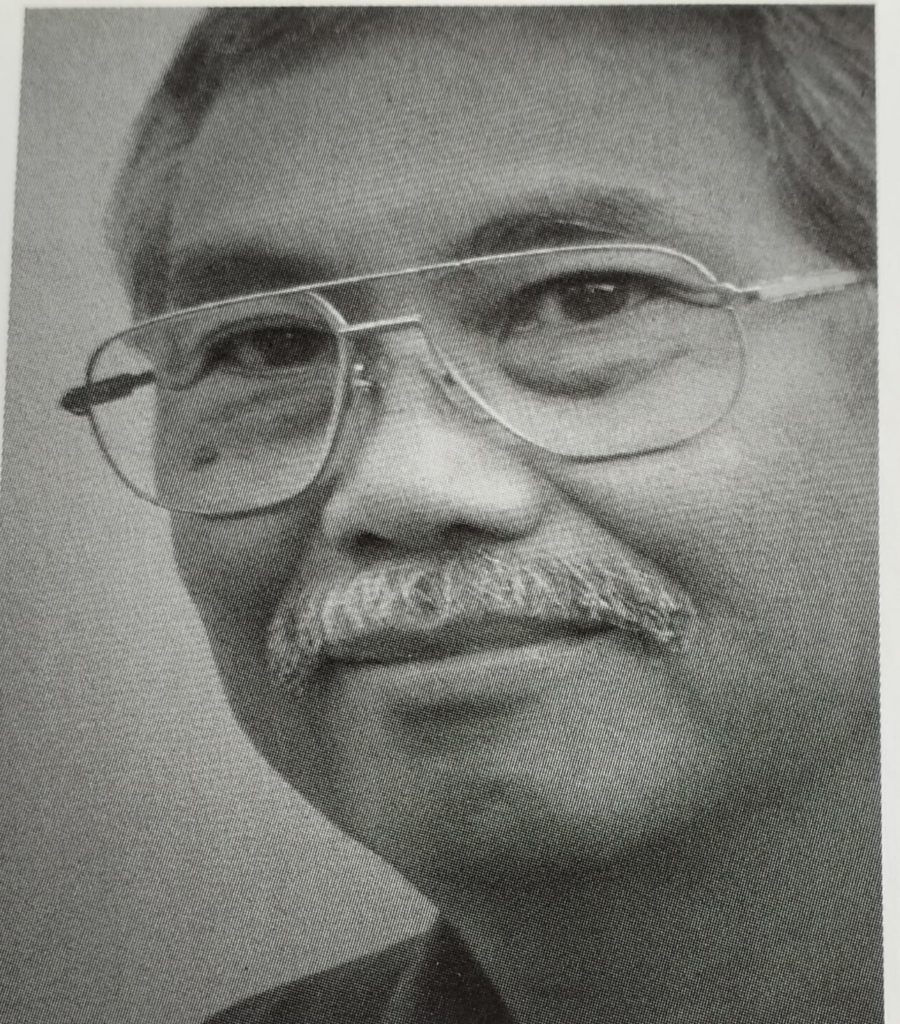
Frans Nadjira / Dok. Raudal
Ya, Om Frans adalah lawan bicara yang mengasyikkan, apalagi jika ia sudah berbagi pengalaman hidupnya. Panjang dan getir. Diintai hantu lapar dan marabahaya, namun ia lolos berkat kelihaiannya berkelit dari kerkapan tangan nasib. Bagaimana situasi yang dialaminya dulu, dapat dilihat dari catatan D. Zawawi Imron yang pastilah sudah pernah mendengar cerita itu dari yang bersangkutan. Sebagai lelaki berdarah Bugis, ia terjun jadi pelaut, dan ia pun dihadang maut ketika kapalnya pecah berantakan di perairan Filipina Selatan di tengah gelombang yang menggila bersama badai. Ia merasakan puncak kesepian ketika tersesat berhari-hari di gelap rimba raya Kalimantan Utara. Meringkuk seorang diri karena malaria di sebuah pulau kecil tak berpenghuni di Belitung (2007: 5).
Dalam biodatanya sendiri, Om Frans tak segan mendedah satu episode jalan hidupnya yang ia sebut bukan sebagai “periode gelap”, melainkan fase “pekerjaan berat”. Ia lahir di Makassar, kota pelabuhan yang ramai di timur tanah air, 3 September 1942. Setamat SMA di kota kelahirannya, ia menghadiri kuliah di Akademi Seni Lukis (ASLI) selama beberapa bulan. Merasa kurang puas, ia memutuskan keluar dan memilih mengembara. Selama beberapa tahun ia mengalami banyak jenis pekerjaan buruh, baik sebagai kuli pelabuhan maupun sebagai penebang pohon besar di hutan rimba Kalimantan. Darah Bugis yang mengalir dalam dirinya kemudian mengantarnya berlayar sebagai awak kapal pinisi ke hampir seluruh kepulauan Nusantara.
Mujurnya, “pekerjaan berat” yang ia jalani tak hanya menjadi eksemplar yang terlewat begitu saja—di mana bahkan tahun kelahirannya pun seolah disambut Nippon penjajah yang menyebar penderitaan di mana-mana. Secara khusus, perngalaman hidup itu memberi bekas yang dalam kepada dunia kesenian yang ia tekuni kemudian..
Cerpen-cerpen awalnya yang muncul di majalah Warta Dunia, Jakarta, sekitar tahun 1961-1962 berangkat dari pengalaman hidupnya yang berat itu. Sementara lukisannya pertama kali muncul di ruang pamer tahun 1970 di Taman Ismail Marzuki dalam pameran bersama Tujuhbelas Pelukis Muda Jakarta ditaja Dewan Kesenian Jakarta, juga menuangkan hasil pengalamannya mengembara. Ia sempat tinggal selama dua tahun di Medan, Sumatera Utara, masa yang mempertemukannya dengan seorang perempuan keturunan Minang yang kemudian ia pinang dan ia panggil dengan mesra: Unda. Panggilan sama dilakukan kawan-kawan dengan sebutan Tante Unda. Bertahun-tahun kemudian baru saya sadari bahwa itu maksudnya (B)unda. Ini mengingatkan saya pada tokoh Manus dalam cerpennya,”Menanti Manus”, tak lain maksudnya Manusia—semacam antitesa dari Menanti Godot.

Buku-buku Frans Nadjira / Dok. Raudal
Sejak tahun 1974 ia memboyong keluarga kecilnya pindah ke Bali, tinggal di sebuah gubuk di pantai Sanur sambil terus mengasah diri di kanvas lukis dan kertas sajak. Menulis dan melukis dua kegiatan seiring sejalan, meski di tengah kepahitan hidup dalam belantara dunia turistik Bali yang mengaburkan batas-batas idealisme seni. Om Frans bertahan di gubuknya, makan nasi-garam sudah biasa. Kanvas, cat dan alat lukis yang terbatas, tak terbeli. Saya pernah mendengar cerita, yang jika saya kenang sekarang seolah muncul dari igauan demam-panas, bagaimana seorang anak laki-laki satu-satunya meninggal karena sakit yang tak kunjung terobati. Ia sangat kehilangan, dan kelak melahirkan banyak sajak duka tentang itu. Sekali waktu ia menulis,”Kehidupan, kujelajahi kau/ dengan naluri hewaniku” (sajak “Waktu”).
Apa gunanya mendengar cerita semacam itu? Mungkin ada yang menggerutu. Tapi bagi saya cerita-cerita pengalaman hidup dari seseorang yang penuh penghayatan, perlu didengar dan diresapi. Sebab saya tahu, cerita tersebut bukan lagi untuk dirinya, namun caranya berbagi untuk mereka yang memilih masuk ke dunia seni—dunia yang tak mudah ini. Ia pernah menulis,”Hanya mereka yang tak waras/ berani menyeberangi batas/ angan milik penyair” (sajak “M.E.”). Maka, mendengarnya bercerita dan sesekali merespon dengan pengalaman kita, ibarat bercermin ke sajaknya yang lain,”Ayo ke laut!/ Pandang bringasnya dengan paham/ Genggam ganasnya dengan diam: Jadikan sajak (“Jadikan Sajak”). Ia juga tak berat hati ketika kami di Komunitas Rumahlebah memintanya menjadi salah seorang redaksi Rumahlebah Ruang Puisi, sebuah jurnal puisi yang sempat terbit sekian edisi.
Baginya dunia seni bukan dunia bim salabim, namun lahir dari penghayatan pada proses dan berani mencoba, sebagaimana ia berani memutuskan mengembara. Begitu pula ketika ia mendapat grant dari pemerintah Amerika Serikat untuk mengikuti International Writing Program (IWP) di Universitas Iowa, Iowa City, ia tak hanya puas dengan membacakan sajak-sajaknya di pusat kota New York atau San Fransisco, namun ia ambil kesempatan itu untuk mengunjungi pelosok negeri untuk melihat realitas yang sesungguhnya, yang mempertemukannya dengan kehidupan pahit kaum Indian.
Dengan cara itu ia memberi gambaran, dan tak kalah penting lecutan atau motivasi. Dan saya sebagai perantau pemula selalu merasa bahwa cerita-ceritanya itu ditujukan kepada saya yang sedang tertatih menempuh gurat nasib di jagad seni yang belum tahu ujung-pangkalnya. Jujur, setiap kali bertemu Om Frans, atau sehabis saya berkunjung ke rumahnya yang tak jarang dengan berjalan kaki menempuh jarak belasan kilo Bedahulu-Biaung bersama Mas Nuryana Asmaudi, kami akan pulang dengan kepala berisi dan dada yang lebih lapang. Dan tentu saja perut yang sangat kenyang, sebab tiap kali berkunjung ke situ, kita akan dijamu makan enak di meja makannya yang bisa berputar dan dengan begitu saya dapat menjangkau dengan mudah menu yang diinginkan.
Setelah itu ia mengajak kami duduk di ruang tengah, di antara lukisan-lukisannya yang tergantung di dinding, yang sesekali ia jadikan rujukan dalam pembicaraan; dari mana titik warna yang menyebar sepenuh kanvas itu bermula. Atau pindah ke serambi depan sambil memandang kebun singkong di sehampar tanah kosong di sebelah rumahnya yang besar. Tanah itu sengaja dimintai tanam kepada seorang petani sekitar, dari siapa ia seolah melihat dirinya pernah bergulat sengit di bawah matahari. Meski saat itu ia sudah melukis di loteng rumahnya yang nyaman, buah kesabarannya menempa dan menempuh hidup.
Buka Jendela Jadikan Sajak
Selain membawa tradisi sparring partner dari Negeri Paman Sam, Om Frans juga membawa puisi “Sungai Mississippi” yang kelak memberi alur baru bagi kecenderungan sajaknya. Dalam sajak panjang dua bagian itu, ia menyorot tergusurnya kehidupan Suku Indian Amerika, di tengah retorika demokrasi dan hak asasi manusia yang dikampanyekan pemerintahannya. Sajak ini menandai metamorfosis Frans untuk perlahan-lahan bergeser dari sajak-sajak imajis yang relatif personal ke sajak bertema sosial yang lebih membuka selubung metafor. Saya sebut perlahan-lahan karena pergeseran itu tidak terlalu tajam; kombinasi antara sajak imajis (yang personal) dan sajak sosial (yang kolegial) masih terasa imbang. Lagi pula, meski secara tematik berisi kritik dan refleksi sosial, namun sejumlah bait tetap dibangun secara imajis dengan metafor-metafor yang segar.
Sajak-sajak imajis dimaksud terutama terdapat dalam buku puisi pertamanya, Jendela, terbit pertamakali tahun 1979. Kecenderungan itu juga dapat dilihat dalam buku cerpennya, Bercakap-cakap di Bawah Guguran Daun-Daun yang hampir bersamaan terbit dengan Jendela, sehingga dalam antologi Laut Biru Langit Biru, antologi puisi dan prosa susunan Ajip Rosidi, kalau saya tak salah ingat, cerpen “Bercakap-cakap di Bawah Guguran Daun-Daun” dimasukkan ke dalam bagian puisi. Itu saking reflektif dan imajisnya cerpen tersebut.
Buku Jendela, setelah digabung dengan antologi baru Jadikan Sajak, terbit kembali dalam buku Springs of Fire Springs of Tears (1998). Buku diwbahasa ini dieditori dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Thomas M. Hunter Jr. Lima tahun kemudian, buku ini diterbitkan ulang dengan judul Jendela Jadikan Sajak dengan tambahan dua puisi baru. Setali tiga uang, tahun 2004, matamerabook—penerbit yang konsisten menerbitkan hampir semua buku Frans Nadjira—kembali menerbitkan kumpulan cerpen Bercakap-cakap di Bawah Guguran Daun-Daun. Tapi saya tidak tahu apakah kumpulan ini persis dengan yang terbit sebelumnya atau ada tambahan cerita lain. Yang pasti, dalam edisi terbaru terdapat esei Arif B. Prasetyo—kritikus yang konsisten memberi catatan buku-buku Frans—berjudul, “Dunia Rumah Tusuk Sate: Perihal Cerpen Frans Nadjira” yang disertakan sebagai penutup (epilog).
Sebagaimana tadi disebutkan, sajak-sajak periode Jendela sangat kental dengan unsur imajisme: tentang seorang perempuan/ berbaju hitam/ menebar jala/ di atas rerumputan// (“Mimpi dalam Demam”); Aku nakhoda dari garam/ lahir di laut tua di angin//(“Mantra”), atau tentang Lengang menyelinap/ di antara bayang-bayang/ ketiak daun// […] Sesuatu yang asing/ mengintai/ di antara kuning pepohonan// (“Siang di Pekarangan”). Tentang ngigau, patung-patung kodok, laba-laba di sudut kamar, sanggah kepala rusa, bulan dan kucing di bubungan dan suasana malam yang tak biasa:
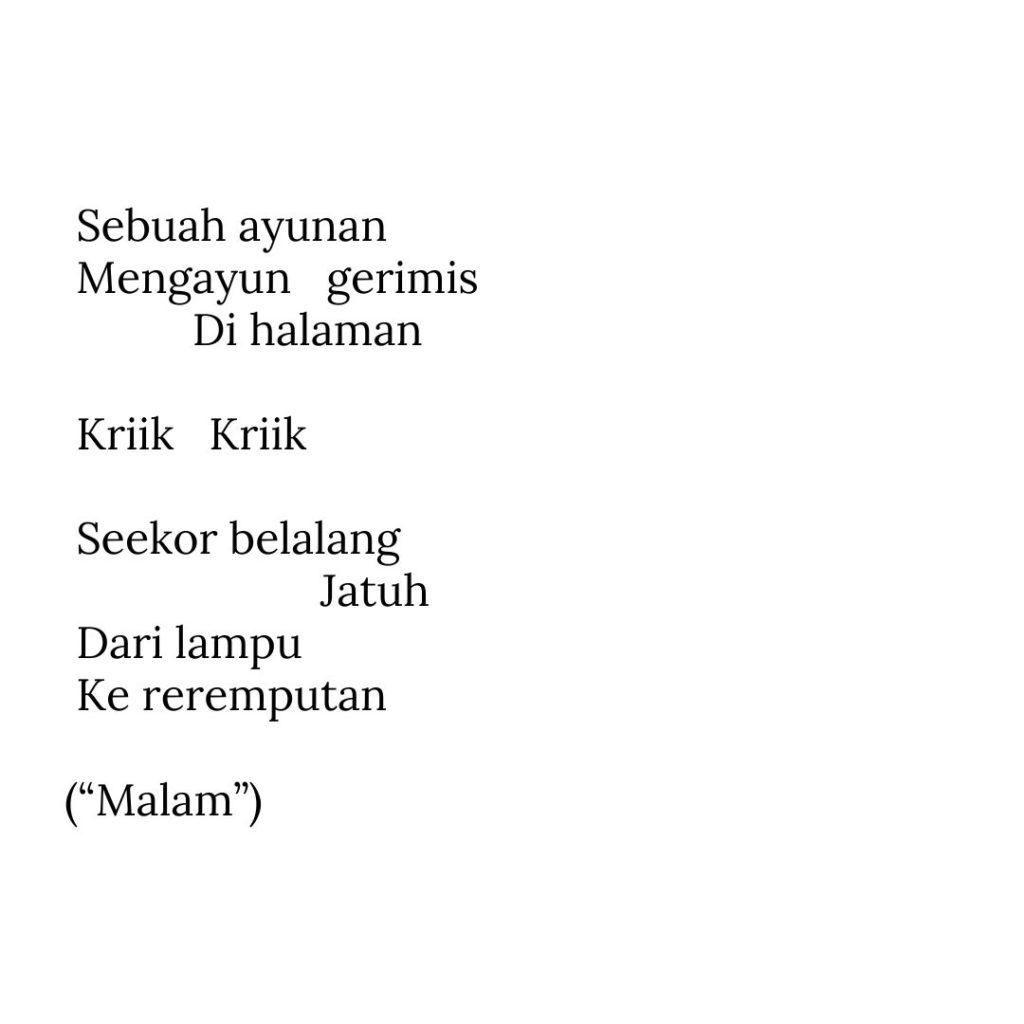
Namun sajak imajis itu tak sepenuhnya personal, sebab dalam sejumlah sajak dapat terbaca unsur sosial yang disampaikannya meskipun tetap dalam nuansa imajis yang lebih mencekam. Misalnya saja tentang sajak “Musium” yang menyoal “sejarah manusia” ini:
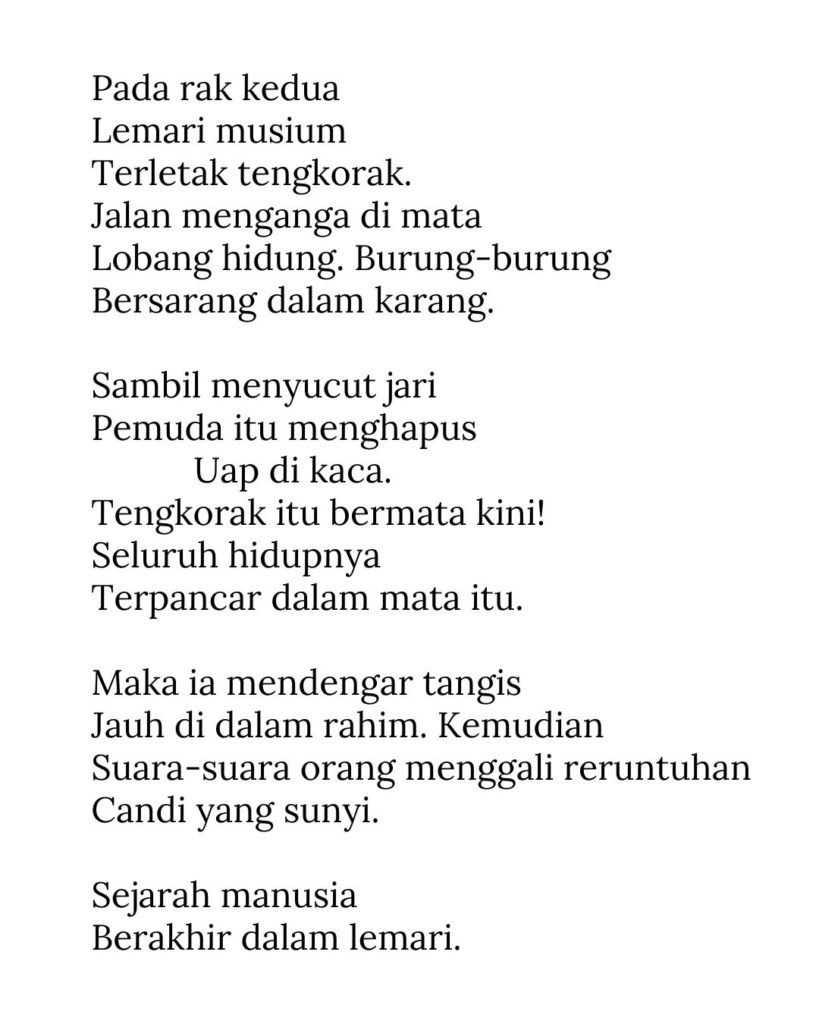
Atau yang paling populer dalam periode ini adalah puisi “Selamat Jalan I Gusti Nyoman Lempad”, sebuah sajak ode yang sudah sangat jelas isinya. Akan tetapi toh cara Frans menyampaikan selamat jalan atas wafatnya pelukis generasi pertama Pitamaha itu jelas tidak biasa. Suasana imajis dengan materi unik dan ganjil—batu paras yang ditatah dengan kapak; desa dengan sumber air panas dan menjangan-menjangan berkumpul di sana; angin yang berobah perangainya; langit yang jatuh melekat seperti kaki-kaki gurita, ayunan lengkung cahaya, topeng-topeng untuk berangkat—semua berkelindan di antara bait-bait sakit dan pilu. Apalagi jika sajak ini dibacakan oleh Mbak MAS Ruscita Dewi dengan setengah menembang, sungguh, suasana terasa menggigilkan tulang:
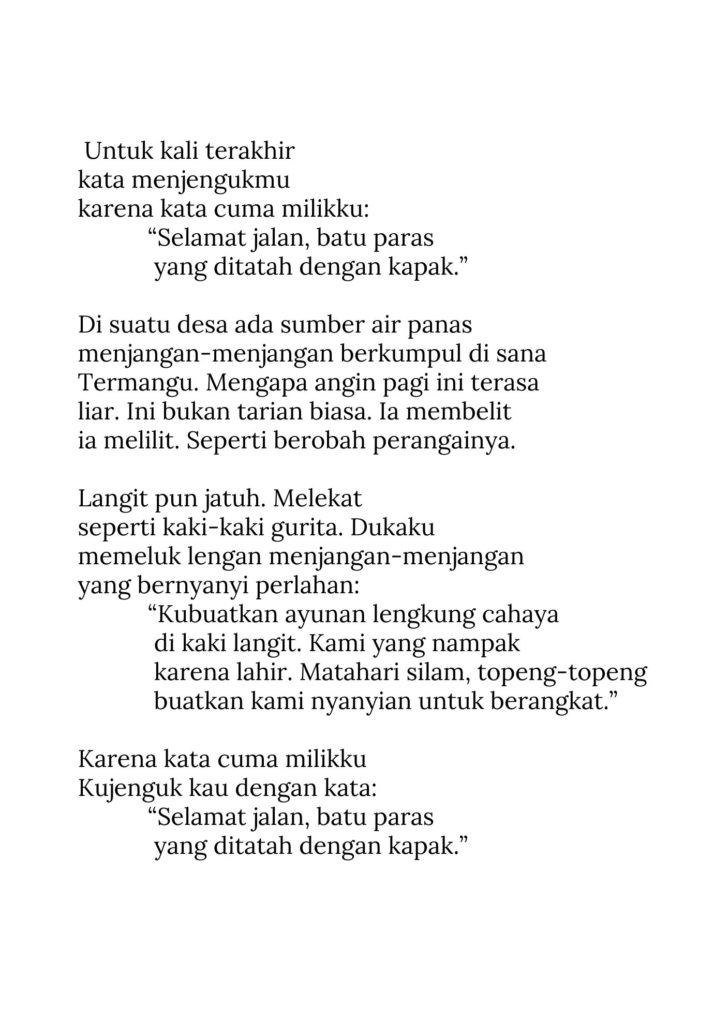
Bait pembuka yang suwung ia ulangi kembali sebagai penutup, bukan saja sebagai penguat pesan, pola ini, sebagaimana banyak ia terapkan di sejumlah sajaknya yang lain, juga mendekatkan pada pola mantra yang merepetisi sebagian dan atau mengulang bagian yang lebih besar, sehingga suasana imajis makin meresap.
Sajak “Selamat Jalan I Gusti Nyoman Lempad”, bersama sajak Umbu Landu Paranggi “Ni Reneng” (1984), menurut saya termasuk salah dua sajak ode terbaik yang pernah ditulis di Indonesia.
Sementara sajak “Si Nyoman Gila” menampilkan ironi pariwisata Bali pada masa awal kejayaannya, yang hampir seusia dengan sajak “Sajak Pulau Bali” (1977) Rendra. Namun jika Rendra mengkritisi pariwisata Bali melalui sajak pamflet, Frans Nadjira menampilkan sosok Nyoman—dengan lentera pagi hari/ menelusuri pasar-pasar—sehingga ia dianggap gila di tengah kegilaan pada dunia turistik. Padahal dalam dunia turistik itu “Dewa telah mati” dan orang-orang hanya melakukan ritual chak chak dalam hampa seperti Sita yang menari tanpa taksu dan meletakkan sajen di atas TV. Dan Hanoman melompat dari dahan/ ke dahan tersedu dari pantai ke pantai/ mencari Rama yang tewas tertembak Mannix. Dunia yang chaos dan kwalik itu, di mata seorang turis yang mereguk tuak dari sepotong bambu tampak sebagai pesona dunia timur yang tiada duanya.
Begitulah sejak awal kita bisa melihat posisi personalitas kepenyairan Frans, tetap bersipongang di antara sejumlah persoalan sosial yang menumupuk di ufuk mata. Pilihan ekspresi yang unik dan orisinal, ibaratnya tidak membuatnya kehilangan “silau cahaya luar”, tapi juga tidak “memadamkan cahaya lilin di kamar.”
Dalam kumpulan Jadikan Sajak, menurut Arif B. Prasetyo, ruang kesadaran penyair sebagai makhluk individual bertumpang-tindih dengan ruang kesadaran penyair sebagai makhluk sosial. Visi puitik Frans bergerak menjelajahi problem umat manusia yang kelam dan memprihatinkan seperti diskriminasi rasial dan tragedi perang. Ini pertanda Frans sebagai “penyair soliter” mulai mengemansipasikan dirinya jadi “penyair solider” (2007: 12).
Memang, dalam kumpulan inilah kita bertemu sajak “Sungai Mississippi” yang salah satu barisnya berbunyi: “Minum, ini anggur dari cairan otak orang Indian!” Namun dalam ungkapan yang lugas itu, ia juga memberi pertanyaan jika bukan pernyataan hikmat seperti ini: Mengapa bumi tak rata/ agar matahari dapat membagi cahayanya? Ini setara dengan ungkapan “Bumi panas tapi tak cukup untuk menetaskan sebutir telur dalam “Sajak Kampuchea”, atau “Bosnia, satu hal yang pasti adalah cahaya/ Maka yang mungkin hanyalah berlari seperti cahaya” dalam “Sajak untuk Sejuta Lobang Peluru”.
Dalam situasi chaos, seperti perang dan pengusiran, ungkapan reflektif semacam itu kadang justru terasa lebih menyentak ketimbang ungkapan lugas karena kelugasan sudah diambil-alih oleh warta-berita atau opini publik; meski kelugasan seorang penyair seperti Frans tetap saja bernilai puitik. Bahkan, dalam situasi getir pun ia masih bisa menyelipkan semacam parodi modernitas sebagaimana terlihat dalam bait pembuka “Sungai Mississippi”:
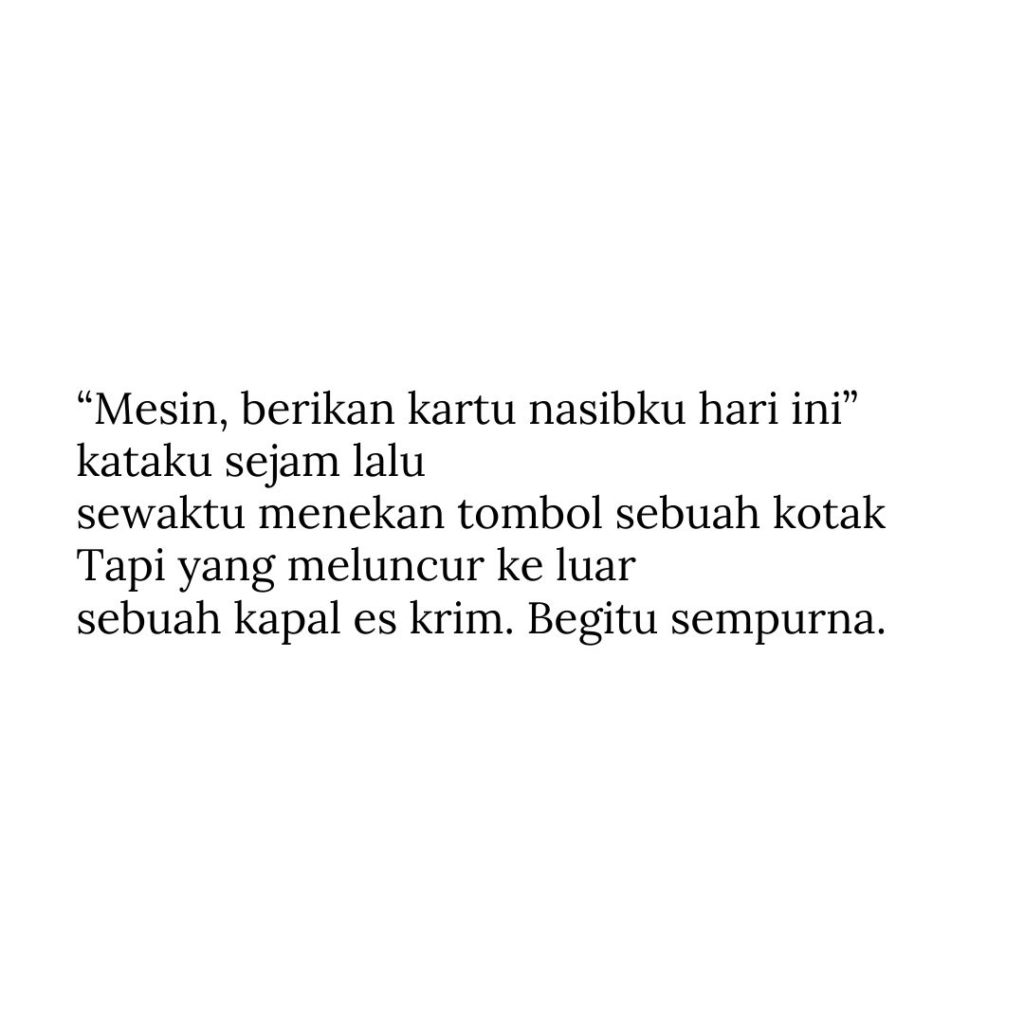
Sajak “Barnett Newman, Siapa yang Takut pada Warna?” tak kalah luas menampung kehidupan sosial Kota Iowa. Tentang bunyi tembakan di sebuah taman dan orang-orang berkerumun memandang ke dalam luka menganga. Tak seorang pun mengenal si mati yang tertembak. Tentang perempuan kurus melintasi kaca buram penuh grafitti liar dan suaminya seorang veteran perang Vietnam yang pernah dikepung musuh dan kini ia pun dikepung lapar. Seolah mengkonfirmasi posisinya yang tak gentar menulis “warna kusam” kehidupan Amerika yang kadung dianggap gemerlap, ia ajak pelukis Barnettt Newman, bercakap. Pelukis ekspresionis yang lazim memajang kanvas dengan warna-warna jantang itu, seakan menantang Frans untuk berkata-kata dengan lantang pula (yang analog dengan warna-warna Newman).
Namun lihatlah, ia tidak sepenuhnya meneriakkan kata-kata telanjang, melainkan sembari mengacungkan selubung majas menjadi semacam tirai tipis untuk memberi aksentuasi khas pada bahasa protes dan gugatan. Ia memang berkata lantang nyaris mengulang bunyi tulisan di tembok kusam Subway,”Setiap orang ada harganya.” Namun ia cepat menyadari bahwa ungkapan itu dengan sekali sentakan bisa melar seperti permen karet alih-alih klise. Maka ungkapan dan kesadaran pada bait pertama itu segera ia sambut dengan ungkapan khas hasil amatan personal: Tapi tak ada yang ingin pergi. Di atas/ terlalu banyak angin. Dingin sekali// Segala sesuatu menuju/ ke satu titik rahasia/Tak ada yang hilang. New York, bilang/ pada anak marah yang lenyap di kabut/ musim dingin;”
Begitulah seterusnya, dalam sajak-sajak solidaritas yang lebih membuka selubung sajak, Frans selalu memberi bagian sisi dirinya yang tersembunyi dalam selubung kata-kata puitik. Itulah yang dapat kita rasakan dalam “Sajak Kampuchea” yang merupakan solidaritasnya kepada manusia perahu dari Kamboja, sajak “Ya, Allah Mereka Berperang” dan “Sajak untuk Sejuta Lobang Peluru” yang ia tulis atas penderitaan bangsa Bosnia menghadapi genosida oleh Serbia, dan seterusnya.
Jejak Jendela
Artinya, dalam situasi bagaimana pun, sajak imajis yang menjadi kekuatan awalnya masih kuat bercokol. Dari situ ia mengeksplorasi pengalaman-pengalaman personal secara unik dan ganjil, tapi plot naratif tersamar memberinya ruang untuk bercerita atau menceritakan sesuatu secara solider. Itu berarti pula mentransfer situasi komunal ke sebuah alur, mungkin ibarat jalan di pegunungan yang kadang samar kadang terang, dan tak jarang alur itu sampai ke laut dengan ombak dan gelombangnya yang garang.
Lihat bagaimana misalnya, dalam sajak “The Ginseng” ia menceritakan siklus hidup sepasang pengantin dari malam pertama, kelahiran anak-anak hingga tiba masa tua di mana anak-anak pun menyusul jadi pengantin. Pengalaman ini tentu sangat personal bagi masing-masing orang, akan tetapi pasti ada pengalaman bersama yang mengikatnya jadi bermakna universal: Kutanggalkan tulang igaku/ jadi pinggul menggeliat/ di depanku/ Ruang remang/ Pikiran-pikiran iseng:/ Akan kuterkam ia/ karena merangsangku/ Akan kuremuk ia/ karena tingkahnya//.
Dalam bait ini sangat terasa pengalaman personal lengkap dengan pikiran-pikiran isengnya yang niscaya berbeda dengan malam pertama pengantin lain. Termasuk bagaimana ia membayangkan “sang tulang iga” berdiri dekat bufet mulus seperti bayi, dan pikirannya melayang bagaimana ibunya melahirkannya? Akan tetapi, ketika tiba pada bait selanjutnya, ia memanggul pengalaman universal: Kuraba igaku./ Terbayang saat yang menakutkan:/ Masa tua/ Anak-anak sudah kawin/Duduk di satu taman rumah sakit/ memandangi burung-burung kuning/ mandi pasir setiap senja/ sebelum tidur/ Awan nampak jauh/ menunggu saat jatuh/ ke dalam hujan. Apalagi ketika ia dengan sadar menutup sajak ini dengan mengulangi satu bait filosofis yang sudah disebut pada bait keempat:
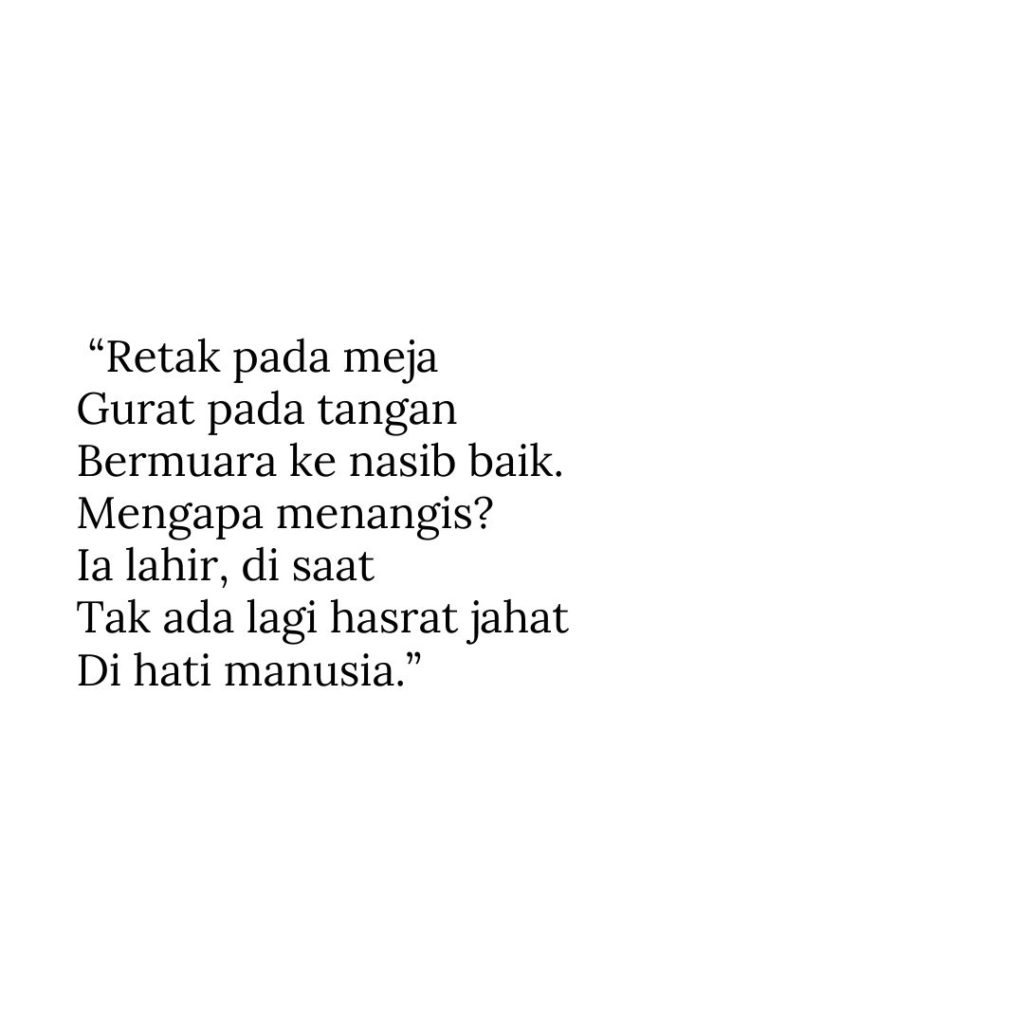
“Sajak Bonsai Memandang Pagi”, “Pohon Kesayangan Burung-Burung Terbakar”, “Gerhana”, “P.B.”, “M.E.”, pun sajak relegius yang amat reflektif seperti “Sajak Malam Natal” dan “Sajak Cinta Malam Paskah”, semua itu seolah menjemput kekuatan awalnya dari kumpulan Jendela. Termasuk sajak “Sepeda Anak-Anak di Halaman”, menghadirkan ingatan dominan pada “halaman” dan “pekarangan” sebagai ruang bermain yang imajinatif—kadang saya amsal lahir dari bayangan perihnya mengingat anak lelaki satu-satunya yang mendahuluinya dalam masa-masa sulit dulu; karena itu selalu lekang.
Dan seperti ia katakan dengan jelas di baris pembuka sajak berjudul sama “Jendela”: Geser sedikit tirai itu/ agar cahaya matahari dapat langsung/ masuk ke dalam kamarku/”. Ia lalu mengulangi pada baris penutup,”Karena itu tolong geser sedikit/ tirai itu biar ia masuk.” Atau untuk lebih jelasnya, saya kutipkan sajak tersebut selengkapnya:
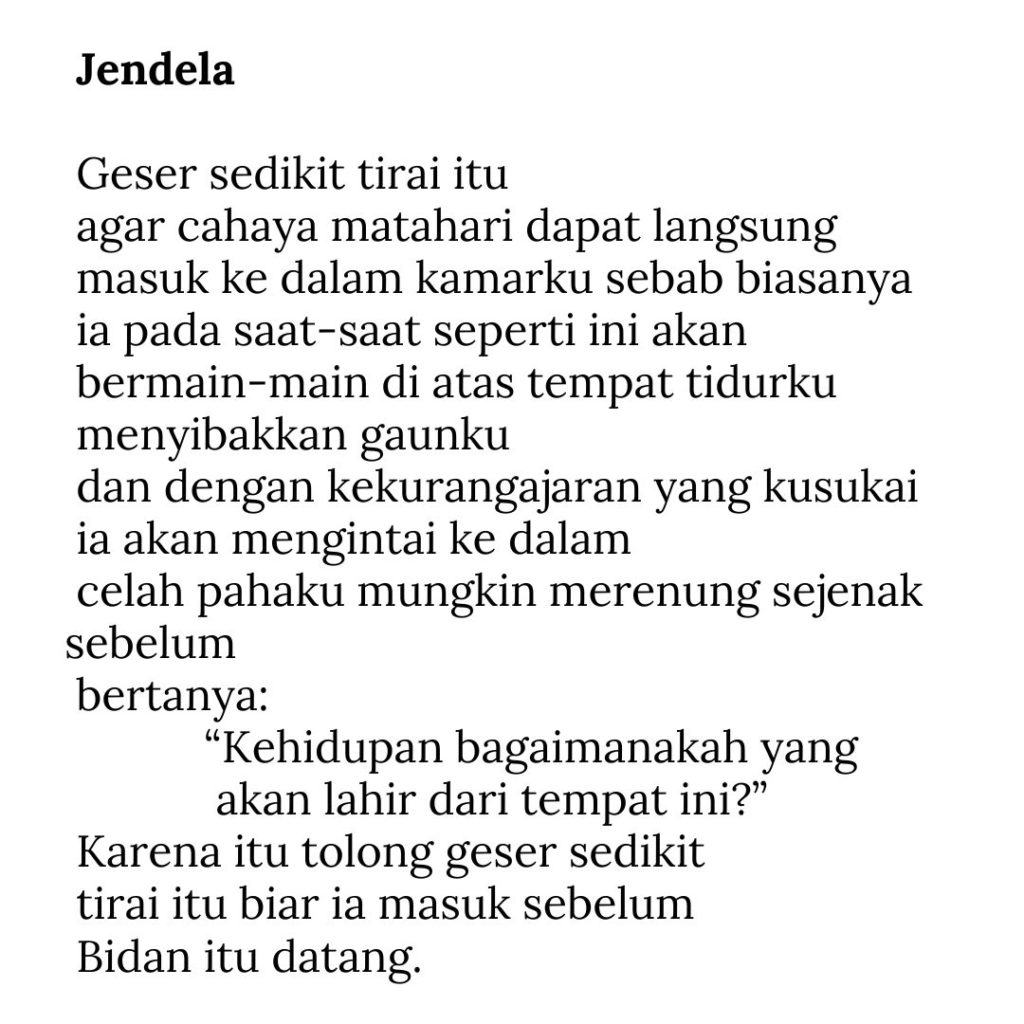
Jelaslah Frans Nadjira secara sadar hanya ingin menggeser sedikit tirai di kamar kreatifitasnya, namun dengan begitu cahaya matahari sebagai sumber kehidupan tetap dapat masuk leluasa dan memberinya sensasi penciptaan yang unik dan ganjil (“dengan kekurangajaran yang kusukai”). Sehingga jika penciptaan puisi dianalogikan sebagai ibu yang melahirkan, maka kita tak akan pernah tahu wujud apakah yang akan dilahirkan itu (“kehidupan bagaimanakah yang akan lahir dari tempat ini?”, pertanyaan dengan jawaban yang sama tak akan diketahui baik oleh si ibu yang melahirkan maupun oleh kehidupan yang datang menjenguk). Satu-satunya jawaban adalah menunggu “Bidan itu datang” yang akan membantu persalinan, yang bisa bermakna juru selamat bagi pergulatan dalam kamar penciptaan.
Saya kira ini juga selaras dengan proses penciptaan Frans Nadjira dalam melukis. Ia menyebut proses melukisnya dengan istilah “psikografi”, yakni mencipta dari satu titik spontan di kanvas, lalu melalui tarian kuas yang tak henti titik itu makin melebar dan meluas hingga memenuhi bidang kanvas. Saat itulah ia seolah tersadar bahwa jendela visualnya penuh dengan aneka warna, sapuan kabut dan cahaya, objek-objek renik yang multifaset, dan sesekali terlihat wajah perempuan, ikan, bulan dan bunga-bunga. Surealis, imajis.

Raudal, Aslan A. Abidin dan Om Frans di Taman Budaya Yogyakarta / Dok. Raudal
Kita bisa menyibak selubung warna dan objek-objek ganjil itu, yang nanti akan terhubung juga dengan situasi sekitar, misalnya dengan merujuk judul-judul lukisannya yang tak kalah puitis seperti “Puisi Minggu Cerah di Taman”, “Dari Cahaya untuk Ganggang”, “Seandainya Sawah adalah Ladang Peristirahatan bagi Bulan”, “Kehidupan Baru di Kebun Senja”, “Perjalanan Menuju Kebun Batin Penuh Cahaya”, atau “Berkat Duka Kami maka Bangsa Ini Berdaulat” dan seterusnya.
Ini padan dengan judul sajak-sajaknya yang unik, semisal “Pohon yang Tinggi Dekat dengan Bulan”, “Sajak Kamar Luka Bakar”, “Malam Pengantin Mabuk”, “Sajak Bonsai Memandang Pagi”, “Pohon Kesayangan Burung-Burung Terbakar” dan seterusnya.
Judul bagi Frans tak bisa dipenggal dari batang tubuh karya, karena ibarat kepala pada judul sudah tercantum ciri dan identitas. Judul menjadi semacam bingkai dalam melukis dan seperti peraman kata dalam sajak, sehingga meski ia melukis dengan teknik spontan, ia sebenarnya sudah punya pegangan. Sama seperti menulis sajak. Meski kerap ia menulis sajak dengan panggilan tiba-tiba, katakanlah dalam suatu moment puitik, tapi sejumlah bibit kata yang telah ia kantongi dalam batin menjadi stimulan dan titik cahaya yang bisa menyebar seluas-luasnya. Maka tak heran, sejumlah judul membuatnya tampak obsesif sehingga bisa ia gunakan untuk judul puisi dan cerpen sekaligus, atau judul puisi dan judul lukisan, dan tak tertutup kemungkinan judul yang sama digunakan untuk judul puisi, cerpen dan lukisan.
“Pohon Kesayangan Burung-Burung Terbakar” misalnya, selain sebagai judul puisi dalam kumpulan Jadikan Sajak, juga jadi judul sebuah lukisannya. Begitu pula “Sepeda Anak-Anak di Halaman” yang sama-sama menjadi judul puisi dalam kumpulan Jadikan Sajak dan judul cerpen dalam kumpulan Bercakap-cakap di Bawah Guguran Daun-Daun. “Makam di Kebun Anggur” menjadi judul cerpen dalam kumpulan Pohon Kunang-Kunang dan judul puisi dalam kumpulan Jadikan Sajak.
Demikianlah, pergeseran perlahan Frans Nadjira dari Jendela ke Jadikan Sajak (dan kemudian keduanya disatukan dalam Springs of Fire Springs of Tears) memunggah masalah-masalah sosial di luar “halaman” dan “pekarangan”. Dalam dua buku puisi berikutnya, Curriculum Vitae (2007) dan Panggilan Warna dan Kata-Kata (2010), porsi sajak-sajak sosialnya semakin banyak dan sikap solidernya kian tampak, di mana kita akan dengan mudah bertemu dengan sajak tentang demonstrasi mahasiswa, Timor-Timur, lumpur bencana dan nyanyian Tanah Air yang sumbang.
Begitu pun dalam kumpulan cerpen Pohon Kunang-Kunang (2010) yang penuh dengan cerita orang-orang kecil yang timbul-tenggelam dalam kesulitan hidup. Ia juga menerbitkan novel Keluarga Lara (2015) yang dari judulnya saja tercermin pahitnya hidup pada masa konflik Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.
Hal ini seiring dengan jawabannya ketika Arif B. Prasetyo mengajukan pertanyaan: Apa kabar puisi Anda? Dan dijawabnya: Setelah kumpulan sajak Jendela, saya mencoba sesuatu yang lain. Sewaktu di Amerika, saya melihat ada yang tidak beres. Di tempat-tempat yang namanya berbahasa Indian—seperti Ohio, Iowa—tidak ada orang indian. Akhirnya ketika pulang ke tanah air, saya katakan, puisi harus ada isinya. Karena kalau hanya bermain dengan metafora, puisi akan kehilangan makna. Tapi jangan sampai unsur estetiknya ditinggalkan.
Saya harap dapat memperluas jelajah setelah sajak “Sungai Mississippi”. Menyapa mereka yang terserak di bawah kolong jembatan, yang mengais-ngais tempat sampah, yang ditumpuk seperti pisang busuk di kantor polisi sebelum digunduli. Biar sajak memuliakan mereka, cahaya manusia itu. [….]
Saya kira kalau melihat kondisi bangsa kita sekarang, tidak ada salahnya menulis puisi seperti W.S. rendra atau Wiji Thukul. […] Terlalu banyak hal yang tidak bisa kita tolerir lagi sebagai penyair. Kini penyair harus mengambil pertanggungjawaban sebagai suatu bangsa, di mana semua sandiwara ini dipentaskan di depannya. […] (2007: 9).
Demikianlah, maka Frans Nadjira, dalam “Pidato Seorang Mahasiswa di Makam Pahlawan” dengan fasih berucap: Puasa kesabaranku usai sudah./ Sampai ke batas. Di depan pintu-pintu bisu/ Berjuta mata menatap Berjuta mulut meratap/ Tangan menggenggam tangan mengeras di udara./ Negeri ini sedang garing/ Sebuah singgasana/ Menggigil di dahi orang-orang miskin.”
Selamat Ulang Tahun ke-81, Om Frans, Ikan Besar yang berenang di kedalaman![T]
BACA artikel TATLITERAT yang lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA










![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)
![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)

















