DALAM PERGAULAN, adakalanya kita bertemu dengan orang yang memancarkan aura berbeda lantaran dirinya berada dalam dua dimensi; masa kini dan masa lalu. Bagaimana ia eksis dalam dua dimensi itu, sangat tergantung pada minat atau profesi yang dijalaninya. Kita mungkin akan terbayang sosok sejarawan yang bertungkus-lumus mengkaji masa lalu meski hidup di zaman kini; ahli purbakala yang menggali dan menggosok barang-barang kuno-purba demi kilau masa sekarang. Bisa pula para filolog yang berdialog dengan masa lampau dengan teks dan konteks bahasa arkais. Serta sederet profesi lain yang menempatkan penyandang profesi itu ulang-alik dalam waktu siklis.
Selain itu ada pula sosok yang tidak secara langsung terkait dengan profesi yang menuntutnya menjalani rutinitas kantor atau peneliti, namun bisa memosisikan diri dalam aura dua dimensi itu. Tentu saja ini tak harus diartikan harfiah, melainkan menunjukkan minat seseorang tersebut kepada masa lalu, sebesar minatnya kepada masa kini atau masa depan. Sekalipun profesi resminya tidak menuntut demikian, kecuali dorongan hasrat, minat dan mungkin juga keasyikkan. Meski bukan berarti pula semua tanpa alasan, bahkan mau tak mau juga mengait kepada suatu jalan yang dipilih atau ditempuhnya, katakanlah jalan kepenyairan (jika ini masih dianggap ambigu untuk disebut sebagai profesi).
Sosok seperti point terakhir inilah yang saya temukan pada diri IDK Raka Kusuma, penyair kelahiran Klungkung, 21 November 1957 dan berpulang 5 Agustus baru lalu. Kesan itu saya dapatkan terutama memang saat bertemu langsung dengannya, namun kadang muncul saat mengingat dan membaca karya-karyanya. Kita akan menemukan tapak tilas ke masa silam melalui percakapan-percakapannya yang intim, atau melalui puisi-puisinya yang sublim. Alam, sekala-niskala, para penatah lontar, aksara kuno, kampung-kampung tua, ritual, upacara, puri dan pura, semua fasih diucapkan dan dituliskannya, membawa minat kita untuk masuk ke sana atau sekadar mendengarnya.
Saya misalnya masih ingat bagaimana bersemangatnya Bang Raka bercerita tentang kampung Nyuling yang menyimpan kekayaan aksara di kitab-kitab daun lontar. Kampung itu terletak di sebuah lembah tak jauh dari belakang puri Karangasem. Sejarahnya memang terhubung dengan Puri Karangasem, di mana raja yang kekuasaannya dulu mencakup Pulau Lombok itu membawa orang-orang Sasak ke ibukota kerajaan untuk berbagai pekerjaan. Mereka ditampung di kampung lembah yang dialiri sebatang sungai kecil jernih berbatu, sehingga tampak cocok dengan jiwa sebagian mereka yang ahli menata aksara.
Ke sanalah saya pernah diajak bersama Putu Fajar Arcana ketika yang bersangkutan baru magang sebagai wartawan Kompas. Bang Raka langsung membawa kami ke sebuah rumah yang letaknya agak tinggi di atas dinding lembah seberang sungai, menunjukkan ia sudah mengenali dengan baik rumah penata akasara yang ia tuju. Saya lupa namanya, tapi benar, di rumahnya yang sederhana ternyata begitu banyak koleksi tatahan lontar. Dan sembari melihat koleksi tersebut, saya ingat bagaimana akrabnya Bang Raka bercakap dengan tuan rumah perihal koleksinya yang menunjukkan bahwa sang tamu pun cukup menguasai sejumlah hal dari dunia per-lontar-an.
Dari Nyuling ia mengajak kami keliling ke Budakeling dan Saren Jawa, itu kampung-kampung muslim di Karangasem yang punya sejarah panjang dan eksis berinteraksi hingga kini. Bang Raka juga bisa menceritakan sejarah kedua kampung itu, sebagaimana ia bisa menceritakan kampung-kampung lain yang ia rekomendasikan untuk dikunjungi apabila saya—barangkali juga teman-teman lain—berkunjung ke Karangasem.
Suatu kali saya menginap di rumahnya—sebuah kompleks BTN di pinggiran kota Amlapura—dan ia menunjukkan banyak kliping dan dokumentasi penting tentang sastra Indonesia dan sastra Bali (keduanya memang diminati dan dilakoninya). Termasuk puisi-puisi Bung Umbu yang sebelumnya belum pernah saya lihat. Ia secara khusus memperlihatkan kepada saya sejilid kliping tulisan Emha Ainun Nadjib di surat kabar, dan untuk itu ia berkata yakin,“Adik pasti juga bisa menulis seperti ini…”
Tanpa bermaksud menganggapnya mudah, jelas itu motivasi yang sengaja disampaikan dengan terlebih dulu membuat momentum kecil; membuka dan mendiskusikan kliping, dan ketika suasana merasuk, saat itulah ia masuk. Mungkin sekali dengan cara itu ia menginginkan gema pesannya akan lebih hidup. Dan bagi saya memang, itu pesan yang tak pernah padam.
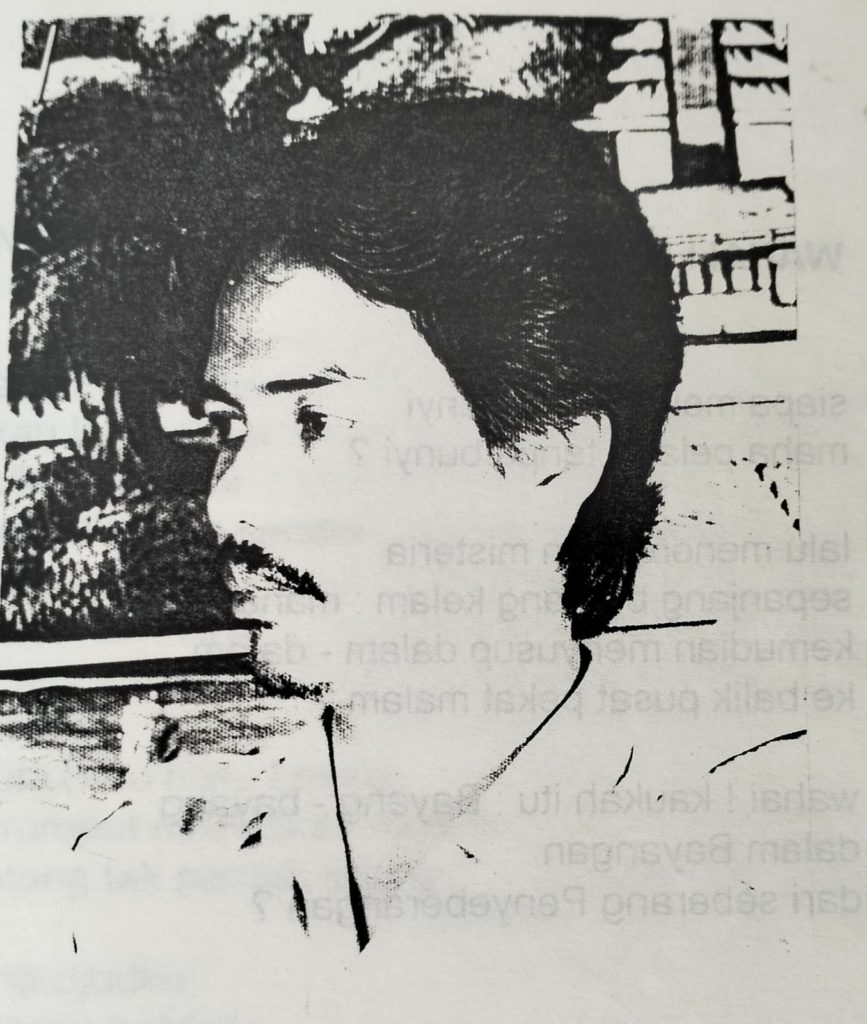
IDK Raka Kusuma | Foto: Dok. Raudal
Kali lain, saya dan rombongan dari Denpasar yang sedang mengajak seorang kawan dari Papua keliling Bali, mampir di rumahnya. Selain saya dan kawan dari Papua tersebut, ada penyair Nuryana Asmaudi, Subagio dan Riki Dhamparan Putra (mudah-mudahan saya tak salah ingat). Ia menawari kami menginap di rumahnya. Meski rumahnya tidak besar, tapi ia selalu terbuka menerima tamu, termasuk numpang nginap. Umbu pun sering memilih menginap di sana jika sedang “turba” ke ujung timur pulau Dewata
Tengah malam, ia mengajak kami ke luar, mula-mula menjemput I Wayan Arthawa, kawan sparring-partner-nya, lalu bersama-sama kami pergi ke Tulamben. Di sana kami bukan hanya menyaksikan laut pantai Tulamben yang ia lengkapi dengan cerita tenggelamnya kapal Amerika diterpedo kapal selam Jepang tahun 1942, juga melihat batu-batuan bekas lahar Gunung Agung dan pohonan lontar yang tumbuh berbaris jauh ke ketinggian. Suasana itu terasa menyergap, menyergap.
Bang Raka seperti instruktur yang sedang mengisi workshop, dan kami tanpa sadar dibawanya ke luar kelas untuk menggosok-gosok kepekaan seraya menyerahkan diri pada alam yang terkembang luas. Segurat bulan jelang purnama kebetulan mengambang di langit dan menerangi apa yang kami lihat. Meski samar tapi segala sesuatu cukup jelas, seperti kami masuki watas waktu yang telah dilalui dan akan dijelang.
Ia lalu mengajak kami singgah ke tempat yang tak sepopuler Tulamben atau kampung-kampung tua Karangasem, sebuah pantai lain, kalau tak salah namanya Pantai Pura Batu Belah. Pantai itu mungkin tak punya masa lalu segemilang tempat lain yang ia ceritakan, namun dengan memberinya konteks, dalam hal ini konteks kepenyairan, kami pun kembali terbakar. “Kak Umbu suka datang malam-malam ke pantai itu, seperti kita sekarang,” katanya (Beda dengan kebanyakan kawan di Bali yang memanggil Umbu dengan “Bung”, ia memanggilnya “Kakak”; dan kepada kami yang muda-muda ia memanggil “Adik”).
“Di pantai itu, Dik, bulan dapat dijangkau, itu diucapkan Kak Umbu.”
Bagai sumbu terpercik minyak, korek api Bang Raka tinggal dicetuskan. Maka begitulah, sesampai di tempat itu, hal pertama yang kami perhatikan bukanlah fisik atau lokasinya (yang sebenarnya biasa saja), tapi konteks ceritanya. Boleh jadi kami tersugesti, tapi itulah yang membawa kami setidaknya pada saat itu seolah berada dalam waktu dua dimensi—hal yang dilakoninya sehari-hari.
Kira-kira dalam situasi seperti itulah tampaknya Riki Dhamparan Putra berhasil menulis sajak “Tulamben” dan “Jalan ke Tulamben”. Boleh jadi itu tak semata dipicu oleh pengalaman bersama Bang Raka, tapi saya yakin jejak jalan bersama “Umbu kedua” itu tak lenyap begitu saja saat ia menggubah bait “Tulamben” seperti ini:
Ke perbukitan bisu
Kita mencari teguh janji waktu
Seteguh Gunung Agung
Sesunyi batu-batu yang melepaskan seribu masa silam
Dari pintu matanya yang murung
Laut akan tetap asin
Hamparan kaktus dan ilalang
Akan tumbuh kelak
Sebagai hujan yang mengairi sungai-sungai
Di mana cinta mengalir
Dan kata-lata dipanen seperti nyala bunga
Atau Nuryana Asmaudi yang menulis “Cerita dari Tulamben”: …serasa waktu berdetak, bisik pelatuk/membangun sarang di dahan kering/kau sudah ada tapi belum tahu apa-apa/usia hijau dipanggang api/dibakar lahar sepanjang hari.”
Saya sendiri menulis puisi “Aksara Gaib”, “Nyuling” dan “Calon Arang”—dua di antaranya saya persembahkan kepada Bang Raka, jelas terpantik oleh suasana yang diciptakannya itu sekaligus ingatan pada sosoknya secara keseluruhan.
Ia juga tak pelit berbagi buku dan kliping. Selalu, setiap kali berkunjung ke tempatnya ada saja oleh-oleh berupa buku, dan tak kalah penting fotokopian arsip-arsip lama. Bukunya bukan saja dari khazanah Hindu yang menjadi pegangannya (ia guru agama Hindu di sekolah), juga agama lain. Dari khazanah Islam ada buku-buku Rumi, Iqbal atau Syed Hussein Nasr. (Minatnya pada agama memberi corak pada puisinya, karena itu konon Abdul Hadi WM pernah menggelarinya “penyair sufi dari Bali” untuk puisi-puisinya yang dimuat Berita Buana).
Penghasilannya sebagai guru SD, merangkap penjaga perpustakaan, mungkin tidak besar, tapi ia rutin berbelanja buku sejak dulu, hingga memasuki era online seperti sekarang. Ketika ia aktif di dunia medsos (sebelum sakit), hampir setiap ada buku puisi atau prosa yang terbit dan promo di fb, ia akan pesan, tak peduli itu penulis lama atau baru. Begitu pula jika ada karya kita dimuat di surat kabar tapi ia kesulitan mendapatkannya, ia akan meminta dikirimi soft-copinya via WA.
Lewat cara itu ia tak ketinggalan informasi terbaru dan tak kehilangan jejak peta sastra terkini. Saya kira ini lanjutan dari masa sebelum era medsos, ketika ia menghapal dengan baik kutipan puisi kita yang ia anggap bagus, dan menyatakan,”Toop!” Hal sama dilakukan era SMS, di mana ia berbagi info lomba atau sayembara atau bertanya tentang karya terbaru si anu.
Dalam cerita sejumlah kawan, seperti pengalaman Made Sujaya, Bang Raka juga menempuh cara jemput bola sebagaimana lazim dilakukan Bung Umbu Landu Paranggi. Ia pernah mendatangi Sujaya untuk menyampaikan informasi lomba dan memotivasi. Belum lagi kesuntukan dan kesediaannya meluangkan waktu mengelola sanggar sastra yang ia dirikan, Sanggar Kata, atau sanggar-sanggar yang ia dorong keberadaannya. Ia mengasuh dan menerbitkan majalah berbahasa Bali, Buratwangi, atau menjadi kontributor/koresponden media seperti Wiyatamandala (Denpasar), Jurnal Kolong (Magelang) dan Minggu Pagi (Yogya).
Atas hal-hal tersebutlah, saya menganggap Bang Raka ibarat “Umbu Kedua”, sebagaimana saya singgung selintas. Tanpa bermaksud menganggap yang satu lebih tinggi daripada yang lain, jelas Bang Raka terinspirasi sosok dan pola Umbu dalam menggambleng santri-santri puisi. Ia sendiri, dalam beberapa kesempatan, baik langsung maupun tersirat, mengakui hal itu. Salah satu dorongannya saya duga, karena pada sosok Pangeran Sumba itulah ia menemukan dimensi waktu yang juga meruang dalam dirinya. Mungkin sekali ia memosisikan Bung Umbu seperti sang kawi dalam jagad Bali masa silam, sebagaimana Ida Pedanda Ngurah yang punya kebiasaan mengunjungi desa-desa dari ujung timur ke ujung barat pulau Bali. Mungkin. Yang jelas, ia merawat spirit tersebut hingga abad milenial.
Karena itu tak heran, ketika Bung Umbu wafat, ketika banyak kawan seperti hilang bahasa—setidaknya saya yang belum bisa menulis satu sajak pun—Bang Rakalah satu-satunya penyair yang siap menciptakan puisi mengiringi kepergian itu. Bukan hanya dalam satu-dua puisi, tapi satu buku, Pukul Nol Tiga Lima-Lima (2022). Buku ini berisi 66 judul sajak, umumnya berpola rubayat, dan itu digubahnya dalam kondisi sudah mulai sakit.

Buku yang memuat puisi-puisi IDK Raka Kusuma | Foto: Raudal
Inisiatif menggubah satu nama dalam banyak sajak atau bahkan satu buku puisi tentu bukan hal baru, sebagaimana misalnya dilakukan penyair Suriah, Nizar Qabbani atas anak dan istrinya. Begitu pula Syahril Latif yang pernah menulis satu buku puisi tipis tentang obituari Nurhayati, istrinya, Ziarah (1981). Sebutlah apa yang dilakukannya bagian dari tradisi, atau melanjutkan tradisi itu, tapi Bang Raka berhasil menulis lebih banyak sajak ode.
Tidak mudah menciptakan sajak untuk subjek yang tak berjarak, karena ia telah menyatu menjadi pengalaman sehingga lebih nyaman dirasakan ketimbang dituliskan. Kecuali kalau secara emosional kita lebih “stabil”, dan sanggup menjinakkan kata dengan bijak, sebagaimana berhasil dilakukan Bang Raka. Ia menulis dalam posisi sangat dekat, seperti dapat dilihat dari judul bukunya yang detail mencatat apa yang terjadi pada pukul 03.55. Dan ia mungkin harus membuka barang-barang memorial seperti dalam puisi ini:
DUA SURAT MENDIANG
surat pertama mendiang
ditulis pada kertas empat persegi panjang
diakhiri lukisan kuda berlari kencang
di atas sabana luas dikitar ilalang menjulang
“imajinasi kuda liar tak kasat mata
lapar senantiasa. sembarangan menangkap
seketika tiada
imajinasi kuda liar tak terlihat mata
dahaga senantiasa. tangkap dengan tali laso jiwa”
surat kedua akhirnya datang
setelah membalas berulang-ulang
“ada padang luas nun di pedalaman hati
Lepaskan di sana. rumput, mata air, muncul abadi”
Puisi-puisi Bang Raka akrab dengan kata-kata arkais namun tidak terasa lebam, alih-alih tambah nyaring jika bukan kontemplatif. Kata atau istilah lawasan tersebut muncul silih-berganti: bunga padma, sukma, purnama, bau cendana, bumbung tuak, gamelan, sungai suci, mantra keramat, jampi sakti, genta, dan aksara. Tentu semua itu ia olah dalam ungkapan, metafora atau prafrase yang sebagian terasa kekinian, namun sebagian lagi justru semakin jauh ke masa silam. Maka kita akan bersua larik atau bait yang sayup-sayup datang dari masa silam, atau menjauh ke masa silam, namun tak padam oleh geriap bahasa ungkap puisi kini.
Bisa ambil secara acak ungkapannya yang menarik dari sejumlah baris atau bait puisinya dalam Kesaksian Burung Sukma (kumpulan sajak berempat terbitan Dermaga Seni Buleleng, 1996. Selain Raka, ada I Ketut Suwidja, Gde Artawan dan I Wayan Arthawa):
Kaukah itu: Bayang-bayang/dalam Bayangan/dari seberang Penyeberangan? (“Wahai! Kaukah Itu”)
Dalam sinar matahari/masih kau lukis candi/penuh ukiran petani/bersawah di badan sendiri/masih kanvasmu/langit selembar, biru (“Klungkung”)
Menari ayun bunga di udara/padamu kutunjukkan bukan keriangan tubuh/menyongsong bayangan bianglala berlumpur/aku dibentuk dari bayangan hujan renta (“Kepada Pratiwi”)
Kampung halamanmu di balik matahari/jauh sudah kau tempuh jalan kembali (“Anak Cahaya”)
Siapa mengusik kami kutuk/jadi bulan mabuk/diguyur tuak dari mana-mana (“Pesta Purnama”)
Sekendi aksara ini untuk dunia/untukku sekendi bunga (“Kepada Ni Reneng”)
Kutipan baris atau bait di atas niscaya menunjukkan posisi IDK Raka Kusuma dalam apa yang saya sebut di awal: berdiam dalam dua dimensi waktu. Akibatnya memang, sejumlah sajaknya bagi sebagian pembaca sekarang terasa berjarak, sekuat apa pun ia mencoba menyegarkan bahasa ungkap. Karena soalnya bukan sebatas bahasa ungkap, melainkan juga lokus atau jagad yang ia angkat, di mana kebanyakan kita mungkin kurang akrab atau enggan mengakrabinya. Juga bukan perkara sajaknya tampak sederhana atau bersahaja, melainkan bagaimana kesederhanaan itu didayagunakan membangun suasana kontemplatif sesuai latar. Simak misalnya sajak berikut:
TOPENG KAYU
kau pilih di dinding bertapa
agar tarianmu purnama nanti
menggetar angkasa
menggetar bumi?
tarianmu purnama nanti
masih air menjelma api
api menjelma bunga padma
merah menyala
bergetar tak henti?
dalam diammu masih mantra
kau rapal? mantra menari
di kalanganmu bau cendana
dikitar nyala wangi
topeng kayu
terpejam matamu kini
kerilingmu purnama nanti
masihkah menggetar ruang dan waktu?
(1995)
Keakraban Raka Kusuma dengan “aksara” dan “tembang-tembang” Bali masa lalu, tidak membuat puisinya tertinggal dalam belantara dunia arkais, tapi sebaliknya, mengada di masa kini dengan mengaktualisasi peristiwa dan nilai-nilainya. Dunia itu tetap jernih, seperti aliran sebatang sungai di lembah Nyuling, atau seperti daun-daun lontar yang melambai di bekas jalan lahar Tulamben. Setiap menyaksikannya, pikiran kita akan terhantar ke suatu masa gemilang, masa di mana mata air jadi sumber pertitaan dan daunan lontar tempat menggurat aksara. Hal-hal yang membuat kita kini ada, berada di suatu masa yang lain, jauh dari moyang tapi toh tersambung siklus waktu, seperti ruh atau roh, hubungan kita tak putus.
Kesadaran itu agaknya membuat Raka Kusuma memilih menjaga, menjulangkan dan menyalakan “aksara-akasra” lampau itu di sepanjang jalan hidupnya. Itulah jalan kepenyairan, yang kerap digambarkan menyimpan tragiknya sendiri. Raka mungkin menyebutnya “tuhan mengutuk/ deras diriku luruh /agar tahu/ keriangan sukmamu (dalam puisi Kepada Pratiwi).” Subagio Sastrowardoyo menggambarkan tragik itu dalam “Mata Penyair” dan Rendra menceritakannya dalam sajak panjang “Khotbah”.
Dalam sebuah sajak yang dipersembahkan kepada I Wayan Arthawa, sejawatnya yang telah lebih dulu pergi, Bang Raka seperti berjanji—dan sahabatnya itu saksi—untuk menerima secara sadar “kutukan deras” itu, karena soalnya ia “sudra” yang terpilih. Kita tampilkan di bawah, sebagai penutup obituari kecil ini, tapi tidak menutup kenang-kenangan dengan segala hormat kita kepadanya:
DI DESA BUDAKELING
Buat Arthawa
sepanjang jalan
aksara-aksara menjulang
menghadang berseru
raja aksara
wajah menyala-nyala
kami api tapi padam
beri aku sukmamu!
Dewata
aku raja aksara?
bukankah aku sudra
lahir dari debu
di bawah reruntuhan waktu?
aksara-aksara makin menjulang
ke arahku berjuluran
berseru makin keras
Dewata
bukankah aku sudra?
(1995)
[][][]
- BACA artikel TATLITERAT yang lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA










![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)
![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)

















