ibuku
tanah sepanjang pesisir bali
tanah yang memeram
perih luka sayat sembilu
di detak jantungku
muara sengketa
yang tak berakhir
Sudah sejak lama para penyair Bali menyuarakan kritik sosial atas pencaplokan tanah-tanah Bali oleh para pemodal. Sajak-sajak penyair Bali era tahun 1990-an didominasi oleh keresahan mengenai ludesnya tanah-tanah Bali, terutama oleh masifnya perkembangan industri pariwisata. Keterdesakan dan keterasingan masyarakat Bali karena hak atas tanah yang makin lenyap disuarakan oleh sebagian besar penyair Bali pada saat itu[1].
Para penyair Bali yang menulis puisi tentang raibnya tanah-tanah milik orang Bali ke tangan para investor antara lain Putu Fajar Arcana, Nyoman Wirata, Alit S. Rini, Wayan Arthawa, Sthiraprana Duarsa, Hartanto, Oka Rusmini, termasuk GM Sukawidana. Namun, di antara para penyair itu, tampaknya GM Sukawidana yang paling konsisten mengusung tema keresahan atas masa depan tanah dan pesisir Bali.
Hingga lebih dari tiga dasa warsa kemudian, penyair kelahiran Denpasar, 16 Juli 1960 ini masih berteriak mengenai persoalan yang sama. Ini bisa dipahami karena persoalan alih fungsi dan alih kepemilikan tanah di Bali terus berlanjut hingga kini, bahkan makin menghebat. Kecemasan tentang makin meluasnya tanah Bali yang dikuasai para kapitalis amat sering mengemuka di tengah-tengah masyarakat, menghiasi wacana di media massa maupun media sosial. Dalam sajak “Sajak Tanah Ibu” yang dikutip di awal pengantar ini, GM Sukawidana melukiskannya sebagai “muara sengketa yang tak berakhir”.
“Sajak Tanah Ibu” merupakan sajak paling pendek di antara 44 sajak dalam buku Air Mata (Tanah) Bali, buku terbaru karya GM Sukawidana. Namun, sajak ringkas itu merepresentasikan sajak-sajak lain yang umumnya panjang. Seperti buku-buku puisi karya GM Sukawidana sebelumnya, Air Mata (Tanah) Bali masih menyuarakan kecemasan dan keresahan atas tanah dan pesisir Bali. Judul buku ini, meskipun tidak diambil dari salah satu judul sajak dalam buku, menyiratkan suara-suara yang diusung oleh sajak-sajak di dalamnya.
GM Sukawidana sepertinya bersetia menyuarakan keprihatinannya atas masa depan tanah dan pesisir Bali. Sajak-sajaknya selalu hadir merespons dinamika tanah kelahirannya tiap kali mengemuka kasus-kasus konflik tanah dan pesisir. Dalam kasus-kasus mutakhir, seperti proyek reklamasi Teluk Benoa dan petani Selasih di Gianyar, GM Sukawidana tak ketinggalan berteriak, bahkan ketika yang lain sepertinya sudah lelah berteriak lalu memilih diam. Petikan bait terakhir sajak “Upacara Bersampan di Teluk Benoa” berikut ini menunjukkan bagaimana GM Sukawidana tak hanya resah karena pencaplokan tanah Bali terus berulang, tapi juga suara-suara protes atas hal itu makin sayup-sayup saja.
saat itu nanti
anak cucuku tak tahu
di mana pesisir untuk melasti saat nyepi
saat piodalan agung di pura-pura
di mana tanah leluhur yang memeram darah dagingnya!
akankah kau berdiam diri menyaksikan itu semua?
Kegundahan yang sama juga diungkapkannya saat merespons kasus tanah petani Selasih. Baca sajak petikan sajak “Pada Ibuku Tanah Selasih” berikut ini.
terkutuklah kau
jika membiarkan orang-orang hitam
berjubah kekuasaan
dengan pongah
merampas dan menggusur ibuku
dari tanah moyangnya
hanya berbekal silsilah masa lalu
dan kata warisan
Dalam sajak-sajaknya GM Sukawidana jelas menunjuk gemerlap industri pariwisata sebagai antagonis atas sengketa tanah dan pesisir yang tak kunjung berakhir di tanah Bali. Di satu sisi, pariwisata mungkin dipandang membawa kemajuan pesat bagi perekonomian Bali. Namun, bagi GM Sukawidana kemajuan pesat yang dibawa pariwisata menyisakan rasa keterasingan di rumah sendiri seperti suasana yang dibangun dalam sajak “Denpasar Malam-malam” dan “Pulang ke Ubud”.
Dampak paling serius dari pariwisata tentu saja direnggutnya tanah dan pesisir Bali. Entah berapa luka dan air mata yang harus ditumpahkan untuk melayani kepentingan pariwisata. Dalam “Sajak Tanah Selasih”, GM Sukawidana menggugat apa yang didengung-dengungkan sebagai kemajuan pariwisata karena menyisakan air mata dan jerit pilu rakyat yang kehilangan tanah leluhurnya.
apalah artinya pariwisata
selain pesta pora
daging busuk para cukong
leleh anggur air mata jelata
dengan nada nyanyian jerit pilu
yang kehilangan jejak tanah moyangnya
Melalui sajak-sajaknya, GM Sukawidana seolah hendak menegaskan dirinya tak akan berhenti berteriak ketika “pemerkosaan” terhadap tanah-tanah Bali terus terjadi. Bahkan, bila sudah tak ada lagi yang mau bersuara. Dia sepertinya masih yakin pada kekuatan puisi sebagai wahana mengungkapkan protes-protesnya atas kerakusan pada cukong-cukong tanah Bali. Bagi GM Sukawidana, puisi juga harus ambil bagian sehingga puisi tetap punya tempat, tetap akan dicatat.
Mengapa GM Sukawidana begitu keras berteriak mengenai pencaplokan tanah dan pesisir Bali? Dalam peluncuran buku Upacara Terakhir di Jatijagat Kampung Puisi, 14 Maret 2020, penyair yang pernah bergiat di Sanggar Minum Kopi (SMK) ini mengungkapkan alasannya selalu menulis tentang tanah pesisir dalam sajak-sajaknya. Terlebih lagi pesisir Serangan dan Teluk Benoa. Menurutnya, pesisir merupakan masa kecilnya.
“Serangan dan Teluk Benoa adalah masa kecil saya sampai saat ini. Saya banyak bergaul dengan orang-orang Serangan dan Teluk Benoa. Wilayah pencarian saya juga di sekitar Teluk Benoa. Bahkan di masa lau saya punya sampan untuk memancing di sana. Jadi akrab sekali,” kata GM Sukawidana.
Namun, pandangan dunia orang Bali tentang tanah dan pesisirlah tampaknya yang berpengaruh pada sajak-sajak GM Sukawidana. Sebagaimana pandangan Lucien Goldmann, pencetus pendekatan strukturalisme genetik dalam kajian sastra, pengarang merepresentasikan subjek kolektif sebagai hasil dialektika dengan latar belakang sosial historis yang melingkupinya. Pandangan dunia pengarang bukanlah bersifat personal, tetapi merepresentasikan pandangan kelompok sosialnya.
Sebagai orang Bali, GM Sukawidana sepertinya menyadari betapa vitalnya fungsi tanah dan pesisir dalam kebudayaan Bali. Cendekiawan Bali, almarhum I Gusti Ngurah Bagus menyebut ada empat fungsi pokok tanah, yaitu (1) berhubungan dengan agama, (2) pemukiman orang, desa, banjar, (3) berhubungan dengan kekerabatan/keluarga, (4) sumber mata pencaharian. Keempat fungsi itu tentu saja saling berkaitan satu sama lain[2].
Suara keras GM Sukawidana merefleksikan cara pandang manusia Bali melihat tanah dan pesisir. Bagi manusia Bali, tanah dan pesisir pertama-tama bukanlah sebagai aset ekonomi, tetapi justru aset budaya sekaligus identitas. Selain manusia, tanah dan pesisir dalam tradisi Bali merupakan penyangga penting kebudayan Bali. Di atas tanah-tanah itulah kebudayaan Bali yang unik dan otentik itu hadir dan bertumbuh. GM Sukawidana menyimbolkannya sebagai upacara. Ketika tanah tak lagi dikuasai orang Bali, di mana upacara-upacara
Di Bali, tanah dan pesisir tak hanya menjadi tempat berlangsungnya berbagai ritual, tapi juga diupacarai dengan siklus waktu tertentu. Karena itu, dalam tradisi Bali, tanah dan pesisir terutama berfungsi secara sosial-kultural. Koyaknya tanah Bali berarti koyaknya kebudayaan Bali. Koyaknya kebudayaan Bali, berarti koyaknya manusia Bali.
GM Sukawidana memang memilih mengkontraskan nafsu kuasa pemodal atas tanah Bali dengan simbol-simbol kultural Bali. Karena itu, selain diksi tanah moyang dan tanah pesisir, pembaca menemukan banyak diksi lokal Bali, khususnya berbagai upacara dan tradisi khas Bali. Inilah tampaknya yang disebut penyair Tan Lioe Ie saat bedah buku Upacara Terakhir sebagai romantisisme kultural. Yoki, panggilan akrab Tan Lioe Ie, mengajak merenungkan kembali apakah benar generasi kini yang direpresentasikan GM Sukawidana dalam sajak-sajaknya sebagai Made Teruna dan Nyoman Bajang memang ingin kembali atau mempertahankan yang sudah ada. “Di sinilah kita perlu melakukan autokritik, tanpa mengatakan karya itu gagal secara estetik,” kata Yoki.
Dalam realitas objektif, orang Bali memang kerap menggunakan simbol-simbol kultural dalam melawan dahsyatnya kerakusan kaum kapitalisme yang memberangus tanah dan pesisir mereka. Di tengah akutnya persengkokolan antara pengusaha dan penguasa dan alat-alat negara bisa dikendalikan kuasa modal, rakyat memang tak punya pilihan lain kecuali kembali pada jati dirinya, yaitu tradisi dan keyakinan. Dua hal itu menjadi modal kultural yang dapat digunakan sebagai satu-satunya senjata. Walau terkadang modal kultural ini juga bisa dimanipulasi dan pada akhirnya dibuat bertekuk lutut di hadapan modal uang. GM Sukawidana tampaknya merepresentasikan kecenderungan umum orang Bali dalam berhadapan dengan kuasa modal dengan cara kembali menengok modal kulturalnya.
Bagi GM Sukawidana, tanah dan pesisir merupakan warisan leluhur atau nenek moyang yang harus dijaga untuk diwariskan kembali kepada generasi selanjutnya. Mungkin karena itu, GM Sukawidana memunculkan tokoh imajiner I Made Teruna dan Ni Nyoman Bajang sebagai representasi generasi muda Bali. Melalui kedua tokoh rekaan itulah, GM Sukawidana membangun narasi dalam sajak-sajaknya, menumpahkan kegelisahan dan kecemasan atas koyaknya tanah dan pesisir Bali. Kegelisahan dan kecemasan itu disampaikan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang menutup bait sajak-sajaknya seperti pada sajak “Upacara Terakhir” berikut ini.
duh made teruna! duh ni nyoman bajang!
akankah kau menyerahkan begitu saja
apa yang masih tersisa dari sisa yang telah dirampas?
(4)
di wajah tuaku
tergurat kegetiran hidup anak cucu
tanpa tanah moyangnya
Bait penutup semacam ini jamak ditemukan dalam sajak-sajak GM Sukawidana yang lain dan tampaknya menjadi kecenderungan gaya ungkapnya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi menjadi semacam isyarat yang sarat bagi generasi muda Bali.
(: maka tanyaku sekarang kepadamu
hanya sebatas tanya
yang tak berjawab
Pada akhirnya, ketika perlawanan sudah mencapai puncaknya dan kapitalisme yang dihadapi bukan makin lemah, justru makin kuat, GM Sukawidana seperti lazimnya orang Bali memilih jalan menyerahkannya kepada semesta. Penyair sepertinya percaya bahwa di atas kuasa manusia, begitu pun kuasa pemodal dan penguasa, masih ada kuasa semesta yang salah satunya ditunjukkan melalui apa yang disebut manusia sebagai bencana alam. Simak saja sajak “Sajak Ibu Bumi” yang ditulis pada tahun 2020.
berguncanglah
apa dan bagaimana maumu
saatnya
dengan segala beban dan luka
ibu bumi
menyembuhkan dirinya
dengan cara sendiri
tanpa campur tangan
mereka yang melukai
dan membebani
aku
senantiasa menerima
dengan ikhlas
Sajak ini merepresentasikan pandangan hidup orang Bali tentang keseimbangan alam dan manusia. Eksploitasi alam secara berlebihan yang dilakukan manusia akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Pada akhirnya, alam akan memiliki cara sendiri untuk mengembalikan ketidakseimbangan itu sebagai cara alam menyembuhkan dirinya. Pada titik itu, manusia hanya bisa pasrah, ikhlas. Seperti larik sajak Chairil Anwar, “ridla menerima segala tiba”.
Jika demikian, apakah itu berarti suara-suara keras dan pertanyaan-pertanyaan tajam itu hanya kesia-siaan? Tentu tidak sesederhana itu. GM Sukawidana justru sedang menebarkan kesadaran bahwa jika sengketa tanah pesisir takkan pernah berakhir, perlawanan pun tak boleh berakhir. Suara-suara harus terus didengungkan, pertanyaan-pertanyaan tajam mesti tiada henti dihujamkan.
Pergeseran Gaya Ucap
Sajak-sajak dalam Air Mata (Tanah) Bali merupakan pemuatan kembali sejumlah sajak dalam buku-buku sebelumnya. Dua sajak diambil dari Upacara Tengah Hari (1993), 16 sajak dari Upacara Senja Upacara Tanah Moyang (2000), 16 sajak dari Upacara Terakhir (2019), dan 10 sajak dari buku kumpulan puisi terakhirnya, Lukisan Kabut (2021). Karena itu, sajak-sajak dalam Air Mata (Tanah) Bali dapat dipandang sebagai sajak-sajak terbaik dalam masa kepenyairan GM Sukawidana pada rentang waktu 1990—2021. Setidak-tidaknya menurut penilaian penyairnya jika sajak-sajak dalam buku ini dipilih sendiri oleh penyairnya atau menurut kurator jika pemilihannya dilakukan oleh kurator.
Lantas, adakah sajak-sajak dalam buku ini merupakan sajak-sajak puncak seorang GM Sukawidana? Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena hingga kini penyair yang lebih senang menyebut diri sebagai “gelandangan” ini masih terus menulis sajak. Dengan kerja kepenyairan yang belum berakhir, bahkan boleh jadi makin produktif, GM Sukawidana yang tahun 2021 menerima penghargaan Bali Jani Nugraha dari Gubernur Bali masih memiliki kemungkinan-kemungkinan yang amat terbuka.
Namun, sebagai buku yang menghimpun sajak-sajak terpilih sepanjang rentang kepenyairan penyairnya, tentu pertanyaan yang menggoda pembaca, sejauh mana perubahan telah terjadi, misalnya dalam hal tematik maupun gaya ucap. Pada hakikatnya, sajak-sajak karya seorang penyair pada rentang waktu yang panjang mencerminkan pencarian dan pencapaian estetika sang penyair. Sebelum sang penyair berhenti menulis, proses pencarian itu juga tidak pernah berhenti, bahkan setelah menghasilkan karya yang dipandang masterpiece sekalipun.
Pada karya-karya GM Sukawidana, pembaca tampaknya menemukan kesetiaan penyairnya menggali tema-tema seputar upacara, tanah, dan pesisir dalam konteks kebudayaan Bali yang khas sekaligus kompleks. Meminjam istilah almarhum Umbu Landu Paranggi, tiga tema itulah yang menjadi ladang garapan yang tiada henti digali-gali, digaru-garu GM Sukawidana. Dalam sajak-sajaknya, pembaca menemukan kesetiaan dan kesuntukan penyairnya menghadirkan diksi upacara, pakembar, tanah Bali, pesisir, sampan, bakau, peladang, peladang garam, dan lainnya.
Karena tema upacara, tanah, dan pesisir juga digarap penyair lain, sajak-sajak GM Sukawidana terasa tak istimewa secara tematik. Namun, intensitas penggarapan dalam rentang waktu yang panjang tak pelak memberikan identitas pada kepenyairan seorang GM Sukawidana. Siapa pun yang hendak menelusuri atau mengkaji suara-suara kecemasan atas masa depan tanah dan pesisir Bali tidak akan mungkin mengabaikan sajak-sajak GM Sukawidana, alih-alih menempatkannya sebagai sajak-sajak di garda terdepan.
Perubahan yang penting dicatat dalam sajak-sajak GM Sukawidana tampaknya pada gaya ucapnya. Pada periode tahun 1990-an, penggunaan diksi lokal yang berasal dari bahasa Bali begitu kental. Aspek ini pula yang dipandang sebagai salah satu ciri menonjol sajak-sajak GM Sukawidana[3]. Namun, dalam sajak-sajak terbaru, diksi-diksi lokal itu terlihat makin berkurang.
Dalam kata pengantar buku Lukisan Kabut, GM Sukawidana secara terbuka mengakui pergeseran gaya ucapnya itu. Menurut GM Sukawidana, pergeseran itu “mungkin terjadi sebagai bentuk kesadaran bahwa puisi tidak semata karena ‘permainan’ kata-kata atau ‘akrobatik’ kata-kata”. Selain itu, GM Sukawidana memang memiliki harapan agar sajak-sajaknya “dapat dinikmati dan dirasakan tanpa harus membebani pembaca dengan istilah atau makna kata tertentu yang bisa menimbulkan kesulitan dalam memahami puisi itu”.
Pengakuan GM Sukawidana ini mencerminkan kesadaran atas kehadiran pembaca. Sang penyair tampaknya menyadari betapa pun puisi sebagai ekspresi personal yang estetis, pada akhirnya juga memiliki fungsi komunikatif dengan pembaca. Karya itu pun akan hidup sepanjang waktu berkat pemaknaan pembaca. Sebagaimana diungkapkan Roland Barthes, pengarang telah mati dalam pengertian daya hidup suatu karya sastra tidak lagi bergantung pada pengarang (penyair) tetapi justru pada pembaca. Walaupun latar belakang pengarang akan dihadirkan kembali dalam proses pemaknaan oleh pembaca, pada akhirnya pembaca yang memegang kendali atas makna karya itu.
Sampai di sini, GM Sukawidana patut diakui mencapai kematangannya. Sebagai penyair, dia telah mebebaskan diri dari ego kreatifnya. Dia mempertimbangkan pembaca dengan membuka jalan menjadi lebih lapang untuk memaknai karya-karyanya.
Selain itu, pergeseran gaya ucap sajak-sajak GM Sukawidana dari aspek diksi juga dapat dimaknai sebagai kematangan penyairnya dalam mengolah bahasa. Pada penyair dengan latar belakang sebagai penutur lebih dari satu bahasa, kedwibahasaan bahkan multibahasa, memang menjadi salah satu potensi. Akan tetapi jika dalam suatu sajak banyak bertaburan diksi lokal atau asing, tentu akan berdampak pada terjadinya rumpang dalam pemaknaan, terutama pada pembaca yang tidak memiliki latar belakang kultural yang sama. Misalnya, sajak-sajak berdiksi lokal Bali di hadapan pembaca yang bukan berlatar belakang budaya Bali seperti pada kasus sajak-sajak GM Sukawidana. Pemaknaan pembaca setidak-tidaknya terjeda, walaupun terkadang makna menjadi tidak penting lagi karena pembaca terbius dengan kemampuan penyairnya membangun “orkestrasi kata” seperti hasil pembacaan Hartanto Yudo Prasetyo atas sajak-sajak GM Sukawidana dalam buku Upacara Terakhir (2019).
Pada akhirnya, tantangan penyair tiada lain menemukan bahasa. Sajak-sajak GM Sukawidana menunjukkan pergulatan dengan bahasa yang dilakukan penyairnya secara intens. Hingga akhirnya kita menikmati sajak-sajaknya, bukan saja sebagai “kata-kata terbaik dalam susunan terbaik” sebagaimana dinyatakan Sapardi Djoko Damono, tetapi tampaknya juga pengalaman puitik terbaik dari penyairnya. [T]
[1] Artikel I Nyoman Darma Putra yang berjudul “Sajak Protes Penyair Bali 1990-an” dalam buku Proses & Protes Budaya Persembahan untuk Ngurah Bagus (1998: 143—165)
[2] idem
[3] Baca pengantar Ketut Syahruwardi Abbas dalam buku Upacara Tengah Hari (1993), I Nyoman Darma Putra dalam Upacara Senja Upacara Tanah Moyang (2000), maupun Hartanto Yudo Prasetyo dalam Upacara Terakhir (2019).
- Catatan: Artikel ini adalah catatan pengantar Buku “Air Mata (Tanah)Bali, Sajak-Sajak Gm. Sukawidana 1990-2021” terbitan Pustaka Ekspresi (2023)



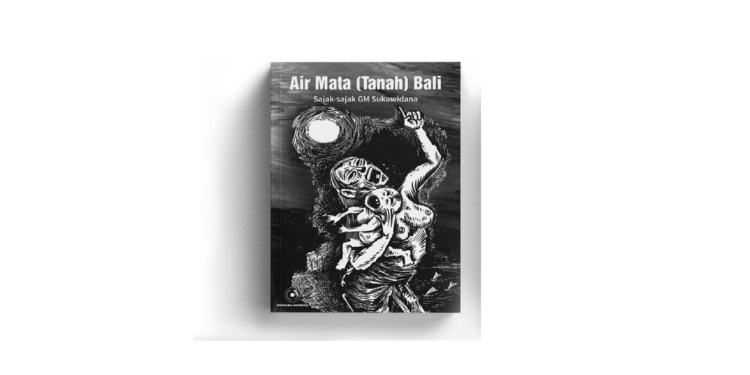







![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)
![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)

















