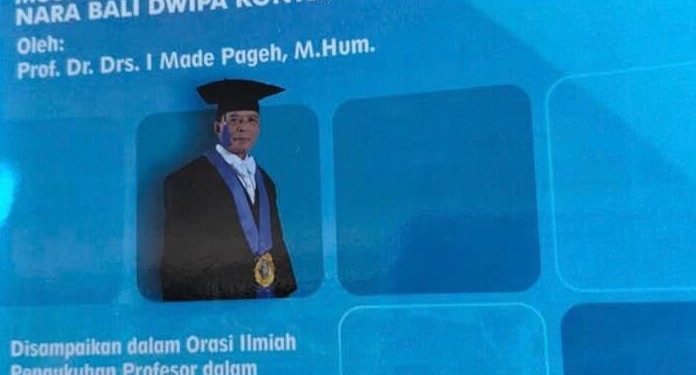“Pak Made”, begitulah cara saya menyapa Bapak I Made Pageh. Akan tetapi, mungkin sapaan itu akan segera kehilangan makna, sebab saat tulisan ini dibuat, ia sudah dikukuhkan sebagai guru besar per tanggal 18 Januari 2023 melalui sidang pengukuhan Guru Besar bertempat di Gedung Auditorium Universitas Pendidikan Ganesha.
Oleh sebab itu, idealnya harus disapa “Prof Made” ; sapaan yang menurut saya wajar disandangnya meski tampak agak berjarak. Namun, saya percaya, ia pribadi adalah orang yang membumi dan tidak begitu silau dengan capaian gelar akademik. Saya merasa lebih nyaman menyapanya “Pak Made” ; lebih hangat, lebih dekat, selayaknya hubungan anak dan ayah.
Bagi saya, Pak Made lebih dari sekedar sosok dosen atau teman sejawat di kampus. Pak Made adalah ayah ideologis yang sangat menginspirasi, baik saat saya menjadi mahasiswa maupun kini ketika sudah menjadi kolegialnya di kampus.
Dialah, bersama almarhum Pak Gusti Made Aryana, sering bercerita tentang ketokohan intelektual Bulak Sumur seperti Pak Sartono dan Pak Kunto ; dua akademisi UGM yang sering dianggap sebagai “Begawan Sejarah” Indonesia. Rasa penasaran dan keinginan untuk bertemu dengan kedua tokoh itu mendorong saya untuk melanjutkan studi master ilmu sejarah di UGM tahun 2012.
Sebelum sampai pada uraian kritik, saya ingin menyampaikan tiga hal.
Pertama, saya telah berdiskusi dengan Pak Made berkaitan dengan kemungkinan memberi komentar metodologis terhadap karyanya di platform ini. Hanya saja, tidak akan panjang lebar.
Kedua, beberapa bulan sebelum pidato pengukuhan guru besar itu dibuat, saya telah membaca versi asli (utuh) tulisan ini. Tepatnya pada tanggal 23 september 2022, saat saya diminta oleh Pak Made mengerjakan mind mapping sebuah uraian panjang yang belakangan menjadi topik dari pidato pengukuhan guru besarnya. Rencananya, mind mapping itu akan dipresentasikan kepada student exchange dari Jepang dan Filipina di Gedung Rektorat Undiksha Lantai III.
Ketiga, tulisan ini adalah wujud dari artikulasi percakapan keilmuwan antara saya dengan Pak Made. Dalam hal ini, kami lebih sering berseberangan alih-alih sepaham. Bagi saya, pertengkaran pikiran dan saling mengkomentari keilmuwan masing-masing akan menghindarkan pada keadaan yang saya sebut sebagai “obesitas intelektual”.
Menurut saya, perdebatan kami murni disebabkan keyakinan terhadap disiplin keilmuwan. Saya pribadi masih bersikap idealis terhadap keilmuan sejarah. Di sisi lain, Pak Made, saya pikir telah berubah haluan semenjak didaulat sebagai doktor pada Jurusan Kajian Budaya di Universitas Udayana pada tahun 2016. Perdebatan-perdebatan kecil kami terutama di ruang dosen maupun ruang perkuliahan dipicu oleh sindiran-sindiran saya terhadap sikap mendua tokoh kajian budaya yang teorinya sering menjadi framework artikel Pak Made, termasuk dalam pidato pengukuhan guru besar yang akan saya kritisi berikut ini.
Saya meminjam konsep banalitas dari Hannah Arendt. Ia merupakan salah satu pemikir New School of Social Research, Chicago Amerika dan sekaligus volunter yang mengajukan diri sebagai reporter atas pengadilan terhadap mantan tentara NAZI, Adolf Eichmann yang melarikan diri ke Argentina dan ditemukan oleh intel Israel.
Arendt meliput sidang Eichmann mulai dari 11 April 1961 sampai 14 Agustus 1961. Wawancara Arendt itu dipublikasi pada 1963 dengan judul Eichmann in Jerusalam, A Report on the Banality of Evil. Hannah mendefinisikan banalitas sebagai yakni suatu situasi, dimana kejahatan tidak lagi dirasa sebagai kejahatan, tetapi sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang wajar. Argumen ini didapatkan dari pengamatannya terhadap orang-orang Jerman biasa, yang tidak memiliki pikiran jahat, namun mampu berpartisipasi aktif di dalam suatu tindak kejahatan brutal.
Dengan bermodal gagasan Hannah Arendt, didukung oleh definisi serupa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, banalitas teori yang saya maksud sebagai otokritik adalah kegagalan metodologis terhadap sense of self (rasa kedirian) teoritik yang dipakai Pak Made dalam menganalisis tulisannya. Kegagalan itu disebabkan oleh ketidakmampuan teori untuk “bersuara”. Akibatnya, teori tidak (belum) menemukan eksistensi (makna)-nya. Selanjutnya, kritik teori ini akan berpusat pada bagian metodologi.
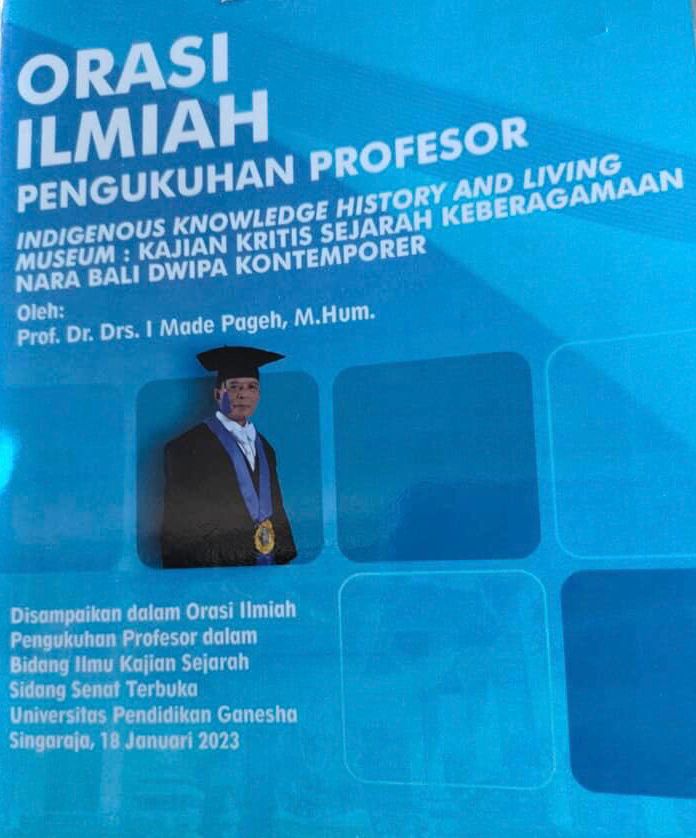
Orasi Ilmiah Pak Made di Gedung Auditorium Undiksha | Sumber : Dokumentasi Pribadi, Januari 2023
Di bagian metodologi penulisan pidato pengukuhan guru besar itu, saya akan menguraikan dua masalah pokok. Pertama, saya tidak menemukan satu upaya sistematik dari penulis dalam memperlakukan teori-teori itu sesuai kapabilitasnya. Pak Made sangat meyakinkan dan percaya diri ketika menyebut tokoh post kolonial seperti Homi Babha, tokoh teori wacana Michel Foucault, sosiolog Prancis Piere Bordieu hingga pengkaji sastra seperti Roland Barthes.
Hanya saja, dia tidak menjelaskan lebih dalam bagaimana teori itu digunakan sebagai matra untuk membedah gejala kebudayaan yang dikaji. Saya menganalogikan teks dalam wujud teori itu sebagaimana yang disampaikan oleh Derrida sebagai “keterpasungan logosentrisme”. Teori-teori yang dicomot itu secara tekstual bersuara tetapi (terdengar) lirih, atau jangan-jangan memang sengaja di(ter)bungkam dalam (kon)teks yang sedang dibicarakan demi kebutuhan legitimasi akademis penulis.
“Pak Kunto”, begitulah ia disapa, merupakaan dosen Pak Made saat berkuliah di UGM tahun 98; namanya disebut bersama dengan Pak Sartono di bagian ucapan terimakasih. Pak Kunto Almarhum mungkin saja mencak-mencak di alam kubur saat membaca uraian metodologis pengukuhan guru besarnya itu. Saya jadi haqul yakin kalau Pak Kunto akan melabelinya “etalase teori”. Sebab memang terlalu banyak teori, sehingga yang cenderung muncul adalah selebrasi dibanding esensi.
Sebagai sebuah epistem, kritik “etalase teori” pernah Pak Kunto juga sampaikan ketika berseberangan pemikiran dengan Pak Sartono di tahun 1980-an. Pak Sartono saat itu baru menyelesaikan studi doktoralnya di Leiden. Ia dibimbing oleh salah satu indonesianis terkenal, Pak Werttheim. Magnus opumnya yang terkenal dan segera menjadi bacaan wajib sarjana humaniora Indonesia berjudul “Pemberontakan Petani Banten 1888” yang terbit tahun 1984.
Pak Sartono pribadi adalah pengikut madzab Annales Prancis dengan dua tokohnya yang terkenal March Bloch dan Lucien Febre. Akan tetapi, di dalam biografinya, Pak Sartono menyebut dirinya sebagai pengikut total history Fernand Braudel.
Menurut Pak Sartono, teori sosial akan membantu menjelaskan dimensi sinkronik ; meluas dalam ruang. Di sisi lain, teori sosial akan mendongkrak populisme ilmu sejarah di mimbar akademik yang posisinya mulai redup dan goyah seiring dengan semakin majunya metodologi yang berhasil dikembangkan oleh ilmuwan sosial. Gagasan Pak Sartono belakangan disebut dengan “multidimentional aproach”, atau pendekatan multidimensional.
Berbeda dengan Pak Sartono, Pak Kunto menolak diktum teori ke dalam ilmu sejarah. Menurutnya, terlalu bergantung kepada teori justru menyebabkan abrasi terhadap ciri khas sejarah. Di dalam bukunya yang berjudul “Penjelasan Sejarah (historical explanation)” terbit tahun 2008 disebutkan bahwa teori itu bersifat general dan mencari hukum-hukum universial.
Oleh sebab itu, teori sosial khususnya berkarakter nomotetik alih-alih ideografik. Lebih lanjut, Pak Kunto mengutip pemikiran Kant, bahwa einmalig dan verstehen kesejarahan akan mengalami disorientasi. Pak Kunto menyampaikan alternatif pemikiran, yang kemudian disempurnakan oleh muridnya, Pak Bambang Purwanto dalam pidato pengukuhan Guru Besar berjudul “Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?”, tahun 2004 bahwa untuk menjelaskan sejarah, tidak perlu bergantung dengan teori, sejarawan bisa menggunakan teknik “the power of chronology” dan eksplanasi atau penjelasan sejarah.
Kedua, teori post, entahkah post kolonial dan post struktural yang dicantumkan sebagai desain “kritis” di dalam tulisan itu secara tekstual bertugas melakukan proses kritik yang berakhir dengan dekonstruksi. Istilah ini berlawanan dengan konstruksi dan bertujuan untuk melakukan pembongkaran (penelanjangan) terhadap normativitas (kon)tekstual. Jadi, tujuan akhir dari penggunaan teori post adalah kritik terhadap kanonisasi dan logosentrisme.
Oleh sebab itu, gambaran dekonstruksi yang diidealkan berusaha menghindari penunggalan terhadap kebenaran. Tidak ada kesimpulan, serba arbitrer yang tujuannya memberi ruang bagi pikiran lain untuk memberi tafsir-tafsir baru.
Gagasan apa dari tulisan Pak Made yang perlu dicurigai sebagai kanotik, sehingga yang hadir bukan sebuah ruang yang mendorong lahirnya demokrasi berpikir seperti yang diharapkan tokoh post yang ia comot teorinya, melainkan narasi yang normatif, monolitik dan absolut? Jawabannya adalah “indigenous knowlegde”, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna “pengetahuan yang asli”.
Lalu mengapa indigenous knowlegde merupakan upaya kanotik? Para ilmuwan post mengharamkan usaha menemukan keaslian. Mereka beranggapan tidak ada yang asli. Segala hal adalah hasil dari bentukan atau konstruksi sosial.
Samuel Huntington di dalam kata pengantar bukunya yang berjudul “The Clash of Civilisation” yang diterbitkan pada tahun 1983 menyebut bahwa tidak ada kebudayaan yang berdiri sendiri, semua terhubung ke dalam satu pola yang disebut interaksi global. Inilah alasan mengapa piramid Mesir memiliki kemiripan dengan piramid Sumeria, piramid Nusantara, serta piramid Aztec dan Maya di Amerika yang jaraknya ribuan mill. Artinya di masa lalu, kemungkinan besar bangsa-bangsa itu telah melakukan interaksi perdagangan global yang kemudian mengarah kepada interaksi intelektual.
Jika yang “asli” itu tidak ada, hanya utopia yang dikerjakan secara sia-sia, lalu apakah yang dimaksudkan Pak Made dengan indigenous? Saya kira, ada satu pikiran alternatif untuk menjelaskan keaslian yakni “khas”. Istilah ini bisa jadi alternatif untuk mengurai jejalin rumit pengetahuan yang datang dari luar, lalu berkolaborasi dengan pengetahuan lokal dan membentuk apa yang Pak Made sebut dengan “bekisarisasi” ; pelokalan gagasan salah satu tokoh post kolonial, Homi Babha dalam karyanya yang berjudul “The Location of Culture”.
Pak Made tidak menyebut Franz Fanon dalam karyanya yang berjudul White Mask and the Black Skin untuk mengurai lebih jauh konsep bekisarisasi.
Menurut saya, Fanon setara dengan Rudolf Mrazek yang menulis “Engineers of Happy Land”. Fanon adalah penerjemah terbaik dari gagasan Babha yang faktual untuk beberapa kasus negara terjajah di Afrika, sehingga teoritisasi yang dikembangkan Babha nampak hidup. Di sisi lain, karya Mrazek di atas adalah narasi teknis berkaitan dengan telaah mendalam seorang indonesianis sekaligus marxis kanan kawakan, Ben Anderson yang menulis “imagine communities”. Mrazek menjelaskan secara lebih teknis tentang gagasan Ben bahwa nasionalisme Indonesia pertama-tama dibentuk oleh perkembangan kapitalisme cetak.
Gagasan Mrazek dan Fanon bisa dipakai membedah konsep bekisarisasi yang dipelajari di bangku kuliah sebagai “akulturasi”. Akulturasi mengandaikan dua unsur yang egaliter, kemudian mengadakan pertemuan yang kompromistis. hibridasi menjelaskan satu unsur inferios dan unsur lainnya superior. Agar inferior tidak musnah, inferior melalui strateginya berusaha mengadopsi si superior, meramunya dan menjadikannya “khas”.
Meski nampak ada adopsi, dan kemungkinan si superior menganggap unsur mereka telah diadopsi oleh si inferior, unsur si superior itu tidak benar-benar menubuh/embodied, hanya menempel/embedded, karena sikap mentalnya masih tetap si inferior. Kesimpulannya, si inferior sedang bersembunyi atau menyembunyikan dirinya dalam balutan adopsi unsur superior melalui kecerdasan dan lambang-lambang tertentu.
Jika hibridasi itu digambarkan dengan contoh di atas, lalu hubungannya dengan asimilasi semu? Asimilasi dalam kontesk kolonialisme Barat berkesuaisan dengan pola unsur di dalam gagasan hibrid. Bedanya, si inferior di dalam fenomena asimilasi melihat si superior sebagai tolok ukur, role model, dan secara sadar dan taqlid menjadikan dirinya identik dengan si superior.
Dalam proses sosial itu, si inferior akan melakukan imitasi dan identifikasi unsur superior sekaligus. Tujuan mereka menjadi identik dengan si superior dipengaruhi oleh hasrat untuk mendapatkan perlakuan (previlege) yang sama dengan si superior. Dengan kata lain, si inferior melakukan copy paste si superior ke dalam dirinya untuk tujuan-tujuan tertentu.
Saya menduga Pak Pageh sedang memperlihatkan sikap ambivalen, atau mendua. Beliau sebenarnya sadar bahwa konsep “asli” lebih cocok disandingkan dengan normativitas pendidikan. Sebaliknya sangat problematis bila disandingkan dengan teori post. Dalam beberapa diskusi kecil kami tentang “asli”, Pak Made selalu meminjam analisis Jean Baudrillard tentang simulakra. Ia bahkan menggunakan teori itu untuk memperkuat argumentasi disertasinya tentang “Balisering” di mana salah satu kesimpulannya, tidak ada yang asli, termasuk kebudayaan Bali yang digembar gemborkan sebagai “adi luhung” itu. Kebudayaan Bali,sebagaimana Baudrillard adalah hasil dari simulakra, copian dari copian. [T]