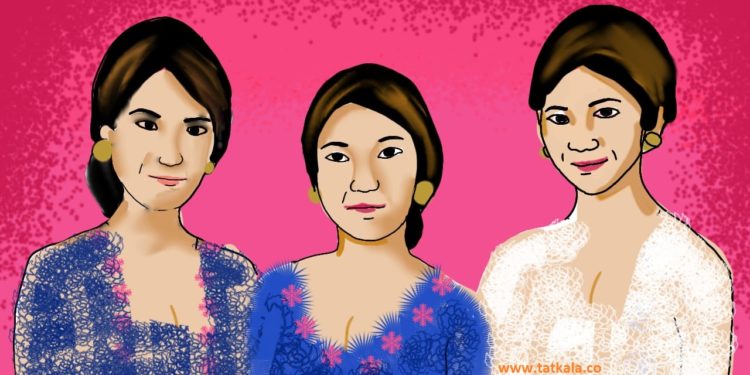Bali begitu banyak memproleh label dengan rlatar belakang representasi keindahan pulaunya, seperti Bali Pulau Seribu Pura, Pulau Surga, Pulau Dewata dan Pulau Banten. Ini membuktikan Bali memang menjadi tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan asing maupun domestik.
Di balik citra pulau Bali yang memiliki keeksotisan alam, adat istiadat, dan budaya, tradisi, dan agama, terselip kesenjangan-kesenjangan yang masih perlu menjadi bahan renungan dan pemikiran, terutama menyangkut persoalan-persoalan kaum-kaum hawa atau perempuam.
Tulisan ini bukan sekadar melihat wajah perempuan Bali secara sekilas dalam ranah sosial di Bali. Namun bisa dianggap sebagai bahan pemikiran untuk meluruskan konstruksi-kontruksi yang dibangun oleh budaya partriaki, di mana budaya patriaki masih tertanam dengan kuat di mata publik.
Bicara soal perempuan, terdapat sejumlah hal ini yang paradoks dengan pandangan Agama Hindu sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya secara dominan oleh masyarakat Bali. Dalam ajaran itu, perempuan sangat dimuliakan, dianggap sebagai sakti (memiliki kekuatan mistis) bagi laki-laki.
Perempuan dalam Hindu dipuja sebagai Dewi. Sebagaimana diceritakan dalam Purana-Purana Hindu, kekuatan tiga Dewa (Tri Murti) selalu dikaitkan dengan pasangan (sakti). Dewa Brahma saktinya Dewi Saraswati, tugasnya sebagai pencipta alam semesta. Dewa Wisnu saktinya Dewi Sri tugasnya sebagai pemelihara alam semsesta. Dan, Dewa Siwa saktinya Dewi Durga tugasnya sebagai pelebur isi alam semseta (Rahmawati, 2016:58-59).
Pada dasarnya budaya patriaki di Bali sangat kental, sehingga tentu sangat sulit untuk dihilangkan. Namun sebaiknya memang ada upaya-upaya untuk meminimalkan pelbagai stigma yang dibangun untuk menyudutkan peran perempuan.
Clifford Geertz dalam bukunya Negara Teater (2017) melukiskan bagaimana perempuan menjadi korban budaya patriarki pada zaman kerajaan di Bali. Ketika seorang raja meninggal, lalu diadakan acara kremasi, yakni pembakaran mayat, para selir turut andil dalam acara. Mereka, para selir itu dengan rasa tulus ikhlas menceburkan dirinya ke dalam kubangan api besar untuk mengiringi kepergian raja.
Laki-laki dan perempuan semesetinya perannya/kedudukannya dipandang sama hanya saja mereka dibedakan dari jenis kelamin (perempuan melahirkan—menyusui) (Beilhraz, 2016:18).
Berkaca dari keindahan Bali yang begitu luar biasa, tentu persoalan-persoalan yang tertuju pada perempuan Bali sebaiknya dicarikan solusi yang baik agar keindahan Bali makin sempurna.
Sejumlah persoalan perempuan Bali di tengah budaya patriarki yang perlu dipikirkan, antara lain:
Eksploitasi Seksualitas
Setiap insan yang hidup di muka bumi ini perlu adanya generasi untuk meneruskan aktivitas-aktivitas yang sudah dijalankan oleh pendahulunya. Begitu juga pada masyarakat di Bali. Warga yang sudah menikah akan menanti kehadiran buah hati.
Keturunan ini akan memberikan suasana yang berbeda, apalagi latar belakang Bali kental akan adanya aktivitas ngayah, menyamabraya, dan sejensinya. Keturunan dipercaya akan membuat sebuah keluarga bisa meneruskan tradisi ngayah dan menyamabraya.
Kehadiran anak sangat begitu dinanti-nanti sebagai generasi penerus keluarga, sehingga mampu menjaga keturunan dan sebagai pewaris di ranah keluarga itu sendiri. Apalagi, melihat kenyataan Bali kental akan nuansa gotong royong perlu adanya kehadiran anak laki-laki sebagai tonggak utama untuk meneruskan semangat itu.
Banyak keluarga di Bali kesulitan memproleh keturunan laki-laki. Di zaman modern ini banyak juga orang tua menerima dengan lapang dada jika mereka tak memiliki keturunan laki-laki. Mereka mencari solusi untuk keadaan seperti itu, bukan menjadikan penyesalan yang berlarut-larut.
Namun, banyak juga orang tua begitu ngotot menginginkan anak laki-laki. Jika demikian halnya maka perempuan sering terkena imbasnya . Misalnya dalam satu keluarga punya anak tiga orang dan ketiga-tiganya perempuan, maka paling rasional yang bisa dilakukan ialah memproduksi keturunan lagi agar mereka mendapatkan keturuan laki-laki.
Meski misalnya sang istri tidak menolak, tapi “ide” untuk melahirkan anak hingga memperoleh keturunan laki-laki bisa membuat perempuan dari segi fisik maupun fsikis merasa dieksploitasi.
Solusi terhadap masalah keturunan laki-laki sudah mendapatkan respon sosial dan solusi melalui sistem perkawinan nyentana, di mana laki-laki setelah menikah si laki-laki tinggal dan menjadi pewaris di rumah keluarga perempuan. Namun, masalahnya bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak menganut sistem perkawinan nyentana?
Ada juga solusi lain, misalnya sistem perkawinan mapanak bareng, di mana yang laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban pada dua keluarga, baik di keluarga perempuan maupun di keluarga laki-laki. Namun solusi ini tampaknya belum populer.
Stereotif Ilmu Leak
Masyarakat Bali tidak asing lagi dengan wacana-wacana tentang ajaran ilmu leak atau ilmu hitam. Ilmu semacam ini dipercya dipelajari untuk menyakiti orang per orangan yang timbul dari rasa iri hati, dengki, dan sejenisnya. Paham semacam ini sudah muncul dalam cerita-cerita lontar calonarang.
Calonarang tidak lain ialah seorang janda yang tinggal di Desa Dirah memiliki seorang putri cantik bernama Ratna Manggali. Si Calonarang ini dengan ilmu hitam yang dimilikinya digunakan untuk menyakiti penduduk di wilayahnya.
Stereotif masyarakat mengenai ilmu leak ini, bahwa ilmu itu hanya dipelajari oleh perempuan, sehingga perempuan seolah-olah memiliki citra buruk di masyarakat Bali.
Timbul beberapa konsepsi dimata publik seperti “Da nyen melali-melali kema apalagi misi ngidih ajeng-ajengan, dadong e to nak bise ngeleak”. Artinya jangan main-main kesana apalagi minta makanan, nenek itu punya ilmu hitam (leak).
Hal ini sebaiknya secara terus-menerus diluruskan. Karena bicara soal ilmu, termasuk ilmu hitam, bisa dipelajari dan diterapkan oleh siapa saja, kaum laki-laki maupun perempuan.
Paruman
Bali yang kental akan nuansa ritual kegamaan tidak bisa dilepaskan dengan adanya prosesi paruman. Sejatinya aktivitas ritual kegamaan dengan paruman memiliki hubungan yang komplementer yakni saling berhubungan antara sesama warga. Hubungan komplementer ini timbul sebagaimana ketika melaksanakan ritual kegamaan terlebih dahulu dilakukan sebuah prosesi paruman.
Paruman ini berfungsi sebagai media masyarakat untuk membahas apa saja yang diperlukan ketika melaksanakan ritual keagamaan, membahasa biaya yang akan dikeluarkan, dan sejenisnya. Lebih-lebih paruman berfungsi sebagai tempat mediasi untuk menyelesaikan suatu perkara di masyarakat ataupun perihal dalam pembuatan awig-awig.
Pendek kata, prosesi paruman ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Padahal secara substansi, perempuan juga memilki peran dan andil besar dalam ritual dan kegiatan kemasyarakatan. Peran itupun tidak boleh dikesampingkan begitu saja.
Apa perempuan selalu ditempatkan di posisi kedua setelah laki-laki? Apa memang harus laki-laki yang harus memegang kendali di ranah publik?
Bahwasannya dalam ranah publik keberadaan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya unsur tumpang tindih apalagi ini berkaitan dengan keberlangsungan harmonisasi bermasyarakat dalam lingkup paruman yang di dalamnya banyak membahas persoalan-persoalan publik.
Jadi, pelibatan perempuan di dalam paruman itu sebaiknya ada. Apalagi ketika paruman berkaitan dengan persoalan-persoalan banten dan hal-hal lainyang biasanya tugas semacam itu diserahkan pada kaum perempuan.
Bukankah jika perempuan diajak rapat lebih awal, maka pekerjaan akan bisa direncanakan dengan lebih lancar? [T]
Referensi
Beilharz, Peter. (2016). Teori-Teori Sosial. (Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Geertz, Clifford. (2017). Negara Teater. (Pertama). Yogyakarta: Basa Basi
Rahmawati, N.N. (2016). “Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)”. Komunitas Studi Kultur Indonesia. Volume 1, Nomor 1, 58-64.
[][][][][]