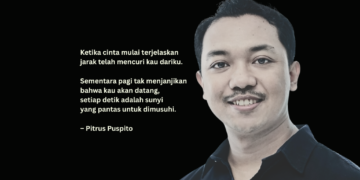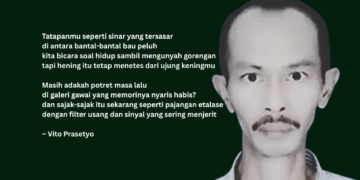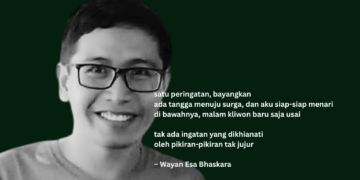Monolog dan Kekasih Satu Tahun Lalu
– Cerpen Eva Lailatur Riska
_____
Cempaka. Denpasar, Desember 2017
Kita berkenalan setelah hujan yang tergesa-gesa itu reda—ingatkah kau? “Dalam perjalanan menuju istana atas awan,” bualmu. Khidmat aku mendengarkan segala yang meluncur dari mulut tipismu, yang berhamburan bagai bintang-bintang sehingga penuh semangat, aku mencoba mengingatnya dengan sangat hati-hati, karena ingatan adalah rumah: tempat yang tepat untuk pulang menuju kenangan.
Ah, bagaimana bisa aku sebentar saja tak mengingatmu? Tentu saja aku tak akan pernah melupakan orang aneh yang membuatku jatuh cinta; yang hampir saja menikahiku. Aku sudah bicara banyak pada ibu perihal sesuatu yang akhir-akhir ini, membuatku tak bisa lelap. Ibu sudah menduganya, dan Ibu langsung setuju. Inilah kali pertamaku berterus terang kepadanya tentang sebuah perasaan. Aku dapat merasakan aura bahagia yang menguar dari ibu waktu itu.
***
Huru-hara kota memang sering memberi kejutan: menciptakan kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya—termasuk perkenalanku denganmu. Ketika itu, harusnya aku berterimakasih kepada hujan. Karena hujan, kau berteduh di rumah kopi ibuku. Sejak pertemuan pagi itu, aku menjadi wanita yang tidak sabaran. Bangun pagi-pagi—bahkan kepagian—berangkat menemani ibu ke rumah kopi. Terus terang, Kekasih, aku mulai merasakan beratnya rindu.
Kau memiliki banyak sekali cerita seperti juru dongeng yang benar-benar diutus untuk menghiburku; menjadi sahabatku entah sampai kapan. Pernah pula kau menceritakan seorang gadis yang senang memunguti sisa hujan, seorang pemuda yang mencintai gerimis, dan banyak lagi cerita fiksi lainnya. Herannya, aku percaya saja dengan cerita yang kau ujarkan, meski kalau dipikir-pikir, sungguh tidak masuk nalar.
Aku mulai jelas mengenali intonasi, artikulasi bunyi, serta suramu yang sedikit berat—dan tentu saja berat untuk sekadar aku ingat-ingat. Pengucapan huruf “r”-mu yang serupa huruf “l”, membuatku semakin gemas; selain suaramu, diam-diam aku telah bersahabat baik dengan aroma parfum yang kau semprotkan ke bagian tubuhmu sebelum menemuiku, Kekasih. Aroma kayu gaharu. Aroma yang terus terpilin dalam hidungku. Rasanya, aku ingin mengihrup aroma itu dalam-dalam agar tersimpan rapi dalam ingatanku.
Aku meraba kembali lorong hatiku yang kini sudah kosong – sudah berapa lama? Aku tidak menghitungnya secara pasti, kekasih. Mungkin kau tahu seberapa lama itu.
“Kau sangat menyukai gerimis,” kataku malu-malu kala itu, saat gerimis masih saja mericis sejak fajar.
“Selalu ada alasan kuat bagi seseorang untuk menyukai sesuatu,” jawabmu. “Sama seperti aku menyukai cerita-cerita tentang hujan dan gerimis yang telah banyak kuceritakan kepadamu, Cempaka.”
“Kenangan.” Balasku hati-hati.
“Bisa saja.” Kau menjawab dengan nada yang terdengar hampir putus asa.
Aku diam cukup lama dan memikirkan, “Apa itu kenangan?” dan “apakah aku mempunyai kenangan yang benar-benar berharga?” Aku telah medapat jawaban itu. Aku memiliki kenangan! Bahkan kenangan yang sangat manis: kenangan tentangmu, kekasih, dan hujan dengan serpihan gerimis.
“Dulu, aku pernah mempunyai pendengar setia sepertimu, Cempaka. Aku selalu menceritakan apa pun tentang hujan kepadanya. Ia sangat girang, seakan hujan benar-benar turun walaupun cuaca sedang terik-teriknya. Kami berjanji akan berjalan berpegangan tangan, dan tiba-tiba gerimis berjatuhan di kepala kami. Ya, aku berjanji.” Jelasmu dengan suara sesak.
“Apa kau menangis?” Aku yang tersentuh dengan suaramu, lebih berhati-hati menanyakan itu.
“Bukan.,” kau mengelak.
“Namun aku yakin kau sedang bersedih.”
“Baiklah. Aku menangis. Namun, menangis tak selalu berarti sedih, ‘kan?”
Aku senang mendengar jawaban itu. Senang dan penasaran.
***
Akhir-akhir ini, hujan lebih sering turun membungkus kota Denpasar. Kota terasa lebih manis dan romantis. Aku lebih sering menghangatkan badan dengan secangkir coklat panas buatan ibu dan buku yang belum selesai kubaca sejak tiga hari lalu. Seharian suntuk, aku hanya duduk mendengarkan musik di sofa dekat tangga; tepat di sebelah meja bar. Pikiranku mengawang; terbayang aroma kayu gaharu yang selalu melekati tubuhmu, tapi ada yang lain lagi: harum kopi Kintamani. Kopi tanpa gula yang selalu kau pesan, Kekasih. Walaupun banyak menu baru, tapi kau sangat setia dengan kopi kesukaanmu itu.
Ibu mengerti keadaan hatiku yang sudah lama tidak baik-baik saja, bahkan bahagianya yang dulu terbawa ceritaku kini turut larut dengan situasi baru hatiku.
“Kelana,” gumamku dalam hati. Nama yang kau perkenalkan padaku, Kekasih; tepat saat hujan yang tergesa-gesa itu reda dan menyisakan gerimis satu-dua. Namun, waktu berlari jauh. Begitu cepat tanpa bisa kucegah barang sedetik pun. Waktu yang kini hanya meninggalkan air mata pada lesung pipiku.
***
Kelana. Jepara, Maret 2018.
Sesungguhnya aku tidak menyukai hujan. Hujan membuat benda-benda menjadi basah dan orang-orang menjadi repot. Dan satu lagi; hujan telah merenggut orang-orang yang aku cintai: bapak, ibu, dan Adel. Tepat satu tahun yang lalu, hujan mengikis rumah kami yang berada di bibir sungai. Aku beruntung, keluar pagi-pagi dan berteduh di rumah kopi milik ibu Cempaka karena dihadang hujan. Tapi ayah, ibu, dan Adel melakukan pekerjaan rumahnya masing-masing. Hujan reda. Aku pulang. Namun tak kudapati rumah. Hanya sungai keruh dan sisa bangunan yang sungguh tak dapat kukenali.
Satu lagi, hujan menjauhkanku dari Cempaka. Ya, aku juga kehilangan Cempaka, sebelum aku sempat memberinya apa-apa, selain cerita hujan yang entah ia kenang atau tidak. O, Cempaka, wanita yang manis! Wanita berambut gelombang sebahu. Setiap aku menemuinya, ia sering mengenakan baju rajut abu-abu berlengan panjang. Seolah Cempaka adalah langit yang sedang muram. Langit yang mendung di hadapanku. Namun senyum serekah matahari itu selalu terbit dan terbenam, dan selalu berhasil menguasai kesepianku.
O, Cempaka! Gadis manis yang tak bosan-bosannya mendengar ceritaku. Cerita tentang hujan yang baginya adalah hadiah terindah. Cerita yang selalu hadir setelah aku berada dalam hidupannya. Kini, aku ditemani penyesalan, dan penyesalan adalah kecerobohan seorang laki-laki yang tak dapat berbuat apa-apa, sedangkan rindu adalah ganjaran bagiku: lelaki yang telah menyakiti Cempaka. [T]
_____

Mencincang Pesan
Puisi Santi Dewi
Seorang dicincang pesanan
Dua telur di dapur
Hiruk pikuk keluar kulkas
Bawang dikocok, garam melintas
Bumbu diputar wajan dan nampan
Rempah bebutiran masuk jadi kenyal
Ketika mulut menyendok hakau
Green tea berubah kacang hijau
Di depan,
Hitam dedaunan hiasi tembok gedung
Lumut mencicip jendela murung
Sepi rumah tingkat
Sementara di sepanjang jalan tersisih
Ia jumput tisu bekas, sumpit-sumpit kambang
Juga bebijian kekosongan
Sepi,
Menuang pekat di permukaan
Men Brayut, 12 Desember 2020.