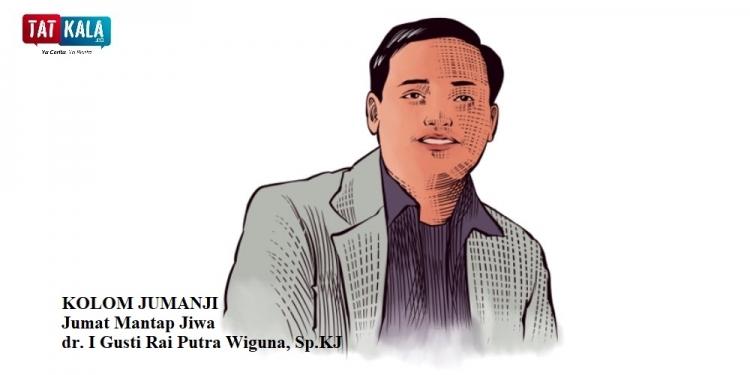Beberapa hari terakhir di Bali masyarakat ditunjukkan fenomena-fenomena kekerasan dan agresivitas yang terjadi, dengan aksi dan reaksi yang beragam. Dari sejak demonstrasi yang mengarah pada kekerasan beberapa pekan lalu dan belum pernah terjadi di Bali sebelumnya.
Aksi demonstrasi tersebut disertai aksi pelemparan yang dibalas tindakan tegas aparat pengamanan sebagai respon atas apa yang dilakukan pendemo. Hal itu ditunjukkan secara langsung di video-video atau gambar-gambar di media sosial.
Sebelumnya, banyak juga kita baca tentang kriminalitas yang terjadi beberapa bulan terakhir di masa pandemi yang lebih sering terjadi bila dibandingkan masa sebelum pandemi. Keadaan terkini, beberapa hari yang lalu ada tindakan pemukulan terhadap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali yang dipicu oleh kontroversi ujaran-ujaran yang menurut sejumlah masyarakat Bali adalah penghinaan dan kebencian.
Dan terjadilah respon seperti kita saksikan dalam video yang banyak tersebar di media massa, dengan tanggapan beragam. Ada yang mengecam secara halus, ada juga yang mengecam dengan cara yang cukup keras, dengan kata-kata berupa kebencian. Ada juga yang cukup unik, justru merayakan kekerasan itu sebagai hal yang lucu.
Saya tentu tidak akan mengupas bagaimana latar belakang hal tersebut secara sosial karena tidak mempunyai kompetensi di bidang ilmu sosial. Tetapi, saya ingin mengupasnya dari sudut kesehatan mental karena latar belakang saya adalah profesional di bidang kesehatan mental.
Sebenarnya apa yang terjadi dalam otak kita ketika ada perilaku agresif atau violence (kekerasan)? Sebenarnya ada dua regulasi yang terjadi di dalam otak kita yang mempengaruhi tindakan agresif atau kekerasan. Yang pertama adalah mekanisme top down atau sesuatu yang mengatur otak kita untuk bisa menenteramkan atau mencegah terjadinya kekerasan.
Bagian otak yang bertanggung jawab terhadap top down dan agresivitas adalah bagian frontal, utamanya korteks orbito frontal. Di sini kita menggunakan kemampuan dalam hal merencanakan, mengatur respon kita terhadap suatu emosi primer,misalnya sedih, lelah, capek, frustrasi, kesal dan sebagainya.
Ada juga zat-zat kimia yang berpengaruh pada regulasi ini, misalnya serotonin dan dopamine. Pada serotonin yang rendah pada otak kita, atau peningkatan dopamine pada bagian otak ini akan membuat seseorang mudah marah, melakukan kekerasan, dan tidak ada kendali pada emosinya.
Mekanisme kedua dalam otak kita yang bertangggung jawab terhadap terjadinya agresivitas adalah mekanisme drive up atau sesuatu yang menyebabkan dan menimbulkan terjadinya kekerasan yaitu bagian otak di limbik sistem, utamanya adalah amigdala dan insula.
Bagian otak ini berpengaruh dalam hal ambang frustrasi, kecemasan dan sebagainya. Ketika bagian ini terlalu sensitif, yang berhubungan dengan kadar zat kimia Gamma Amino Butiric Acid (GABBA) yang rendah maka maka akan terjadi luapan emosi dan rasa frustasi yang tidak tertahankan.
Jadi sebenarnya rasa marah dan kekerasan bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi, tetapi ada kaitannya dengan keadaan-keadaaan keseimbangan zat kimia di dalam otak. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya perubahan di dalam otak kita? Beberapa hal terkait dengan hal itu misalnya paparan berita kekerasan.
Semakin sering seseorang terpapar; membaca, melihat, atau menonton suatu kekerasan di masyarakat, apalagi dibiarkan, artinya yang melakukan hal tersebut tidak mendapat konsekuensi, misalnya para pejabat yang melakukan kekerasan namun perkaranya tidak dimasukkan dalam proses hukum entah karena berbagai sebab.
Hal lainnya, tayangan-tayangan kekerasan di televisi; perusakan, pemukulan apalagi tayangan itu dilakukan secara berulang tanpa penjelasan yang tepat dari berbagai bidang, itu justru akan memberikan perubahan di dalam otak kita menjadi lebih agresif. Selain paparan informasi dan tayangan, ujaran-ujaran kebencian terutama di media sosial itu juga akan memberikan learning theory kepada otak kita, bahwa hal-hal itu adalah sah untuk dilakukan.
Kemudian ada juga tipikal-tipikal sesuatu hal yang menciptakan kekerasan dalam masyarakat yaitu ucapan-ucapan yang menyinggung suatu kepercayaan atau sesuatu yang sangat diyakini masyarakat. Menyinggung harga diri adalah hal yang sangat mudah memicu terjadinya kekerasan.
Makin sempitnya ruang-ruang dialog yang matang sebagai orang dewasa dimana dialog bukan hanya menjadi tontonan ataupun menambah pencitraan tetapi memang untuk saling bisa memahami. Ketika ruang-ruang seperti ini makin berkurang, tentu saja akan juga memicu terjadinya kekerasan. Penting sekali bagaimana ruang dialog bukan hanya sebuah action, sebuah pencitraan, sebuah pembenaran, ataupun sebuah klarifikasi dari ucapan-ucapan yang bertentangan satu sama lain.
Ketika ruang dialog hanya menjadi panggung sandiwara, itu juga akan menciptakan suasana psikologi masyarakat makin agresif. Juga, riwayat kekerasan yang terjadi di masa lalu pada seseorang atau sebuah komunitas masyarakat juga sangat berpengaruh.
Dalam konteks Bali, tentu kita masih ingat kekerasan terjadi secara masif di tahun 1965-1966 ketika konflik antar warga, pemberantasan orang-orang yang dituduh berafiliasi dengan Partai Komunitas Indonesia (PKI) yang berujung pada pembunuhan massal tanpa proses peradilan dan hukum sangat membekas di ingatan masyarakat Bali.
Selain itu, kekerasan juga bisa dipicu oleh kondisi-kondisi gangguan kejiwaan, misalnya pengaruh narkotika dan psikotropika pada otak kita. Penyalahgunaan narkoba juga sangat mempengaruhi ambang frustasi dan kendali terhadap agresivitas kita.
Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas adalah stres yang terjadi di masyarakat apakah karena masalah ekonomi, masalah sosial terutama himpitan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kerentanan menjadi agresif dan mudah marah.
Termasuk juga gangguan-gangguan kesehatan mental lainnya, misalnya psikotik dan depresi ataupun kekerasan yang terjadi pada masa remaja. Kondisi-kondisi seperti Conduct Disorder, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif yang tidak tertangani itu juga bisa memicu terjadinya kecenderungan melakukan kekerasan di usia remaja. Misalnya pada korban bullying dulu pernah mengalami kekerasan maka kemungkinan juga melakukan kekerasan di usia dewasa akan makin meningkat.
Marilah kita mulai dari diri sendiri, di masyarakat kita lebih banyak menguatkan diri kita, bukan dengan mengeluarkan istilah-istilah kebencian bagi sekelompok golongan lain yang kita anggap bertentangan dengan kepentingan kita. Istilah-istilah “dauh tukad”, “dangin tukad” untuk menyitir kelompok masyarakat yang kita tidak sukai itupun perlu dipahami secara bawah sadar juga bisa menanamkan kebencian di dalam pikiran kita.
Marilah kita menjadikan momen ini sebagai suatu kesempatan untuk mawas diri, menilai dan memperbaiki diri kita bahkan sebelum kerusakan itu terjadi. Apabila ada anggota keluarga kita yang secara konstan sering agresif, marah bahkan tanpa pemicu yang jelas ada baiknya segera berkonsultasi ke profesional kesehatan mental seperti psikiater.
Mudah-mudahan tulisan ini bisa menjadi cermin bagi kita untuk memperbaiki diri dan senantiasa menjadi mantap jiwa sampai semua keadaan di masa pandemi ini bisa pulih seperti sediakala. Salam mantap jiwa.