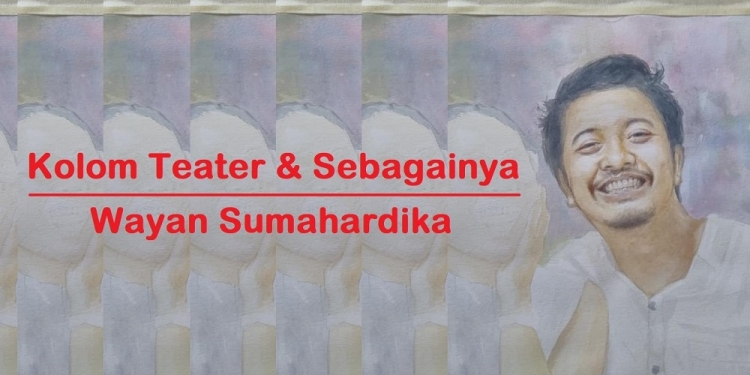Beberapa waktu lalu, sempat beredar video parodi tentang virus corona. Diperlihatkan seorang pria yang tengah mencuci tangan di sebuah toilet umum. Ia cuci bersih tangannya, mulai dari kuku, sela jari, punggung dan telapak tangan. Sebersih-bersihnya. Pada tangan yang dikucek itu saya bayangkan takkan ada satupun virus yang bakal bercokol. Tak ada tangan penuh virus yang menyentuh wajah. Tak ada virus masuk ke dalam tubuh. Tak ada corona.
Masalah kemudian terjadi ketika pria itu hendak mematikan keran air yang dirasa mungkin saja ada virus tengah menempel disana. Maka ia bersihkan juga keran air dengan sabun. Lalu kembali ia cuci bersih tangannya. Saat sampai di muka pintu, gagang pintupun dicurigai tak bersih. Lagi ia bersihkan gagang pintu dengan sabun. Tiba-tiba sabunpun tak lepas dari kecurigaan. Dicucinya juga sabun itu dengan sabun lain. Kecurigaan terus berlanjut sampai pria itu depresi terhadap benda-benda di sekitarnya. Bahkan untuk depresi sekalipun untuk menggeletakan dirinya di lantai toilet, ia mesti beranjak dulu sebentar, sekadar membersihkan lantai dengan sabun.
Demikian video ini menyimpan ironi tentang corona. Di sisi lain mampu membuat kita tersenyum barang sedikit di tengah rasa takut akan wabah yang mengancam. Menyaksikan video, membuat saya pribadi berpikir, mungkin pada masa-masa corona inilah manusia benar-benar diberi kesempatan untuk kian mengetatkan kesadaran terhadap tubuh. Yang sehari-hari biasa kita gerakan sesuka hati dengan penuh kesadaran atau kita biarkan refleks bergerak begitu saja sebagai sebuah keniscayaan (luar kesadaran).
Pemahaman akan kesadaran tubuh dan keniscayaan tubuh merupakan wujud tubuh primordial manusia yang dibawa dan dihayati sejak awal kelahiran. Pemahaman tubuh, yang notabene belum diinterpretasi dengan berbagai macam ilmu semacam kedokteran, agama, sosial, dan lain-lain. Pemahaman yang lahir dari pengalaman empiris sehari-hari. Namun karena rutinitas sehari-hari yang kita jalani pula, seringkali kesadaran dan keniscayaan akan tubuh jadi kian terbengkalai.
Lebih jauh, video parodi ini menyiratkan pemahaman akan kesadaran dan keniscayaan tubuh yang berdampak pada orientasi kita memandang tubuh. Manusia dikatakan berada pada dua kutub ketegangan tubuh, antara pandangan bahwa manusia memiliki tubuh dengan manusia adalah tubuh itu sendiri. Pandangan tentang manusia memiliki tubuh dapat dirasakan ketika ia sadar atas kontrol terhadap tubuh. Ada kehendak yang dibangun dengan kesadaran penuh atas berbagai gerak tubuh yang dilakukan.
Sementara pada pandangan tentang manusia adalah tubuh itu sendiri, tak ada kehendak. Yang ada hanya keniscayaan. Saatnya bernafas ya bernafas saja. Tanpa memperhitungkan kapan baiknya menarik nafas, kapan menahan, kapan menghembuskan. Saatnya berjalan ya berjalan saja, tanpa menyoal kaki manakah yang bergerak lebih dahulu. Pun demikian dengan saatnya membuka keran air, membuka pintu, duduk, dan tergeletak sebagaimana adegan yang hadir pada video, ya lakukan saja. Tanpa harus berpikir berapa banyak kuman dan viruskah yang menempel disana. Adakah corona tengah berdiam di sekitarnya?
Dalam pemahaman tentang manusia adalah tubuh itu sendiri, secara tidak langsung menjadikan manusia mampu berkoneksi dengan alam sekitar. Karena tubuh, kita mampu bersetubuh dengan hal-hal di luar tubuh. Bersetubuh dengan pasangan misalnya, merupakan hubungan yang dibangun lewat persentuhan antartubuh. Bahkan karena tubuh jugalah, kita bisa bersetubuh dengan motor, mobil dan sebangsanya. Acapkali mengendarai, tubuh kita seakan menyatu dengan kendaraan. Begitupun dengan dengan lantai yang kita pijak atau gagang pintu yang kita buka setiap hari. Tanpa disadari, semua menjadi bagian tubuh sendiri. Maka tubuh dalam konteks ini bisa dikatakan sebagai sebab manusia mendunia. Jika tak ada tubuh, tentu kita tak akan ada di dunia, bukan?
Saking pentingnya keberadaan tubuh, menjadikan manusia takut kehilangan tubuh. Takut jika terjadi sesuatu dengan tubuh. Maka diciptakanlah rumah untuk melindungi diri dari gejala buruk cuaca, serangan binatang liar, dan hal-hal sekitar yang dirasa membahayakan tubuh. Saat takut badan terluka, aurat terbuka, kita jahit kain jadi pakaian. Saat takut kaki lecet, kita rancang sandal dan sepatu. Kita bentangkan jalan, trotoar dan rambu lalu lintas untuk menjaga tubuh dari kecelakaan. Kita bangun gedung besar dan tinggi, untuk menjaga diri saat bekerja. Dan seterusnya. Dan seterusnya.
Semua dibuat agar hilang takut manusia pada segala sekitar yang dapat melukai tubuh. Ironisnya, corona sebagai virus berukuran mikro, justru masuk lewat lubang-lubang kecil manusia yang tak terlindungi. Bagaimanakah mesti menutup lubang-lubang kecil ini? Sedang lubanglah yang berperan sebagai keluar masuk udara dalam tubuh. Ruang keluar masuk kehidupan. Ruang alam memberi daya hidup pada tubuh. Ruang tubuh memberi daya hidup pada alam. Bagaimana mesti menutup lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, lubang mulut, lubang kulit, dan segala macam lubang lainnya pada tubuh kita? Bahkan lubang ketakutan yang lekat di ceruk hati terdalam manusia, dengan cara apa bisa ditutupi?
Suatu kali dalam perjalanan ke Tegalalang Gianyar, karena ada kerja yang harus diselesaikan, jalanan menjadi sesuatu yang menakutkan. Berapa banyak debu yang lintas, berapa virus bertebaran? Diantara tourist-tourist yang melintas menaiki sepeda motor, tubuh dibuat waspada. Menjaga jarak dengan mereka. Bagaimana jika sewaktu-waktu tourist-tourist itu bersin dan batuk-batuk? Bagaimana jika bersin dan ludah batuk paling kecil dari sisa-sisa terkecilnya tak sengaja menempel di tangan? Tangan menyentuh hidung yang gatal karena debu, mengucek mata, menyentuh tubuh, menyentuh sekitar.
Sebab menyentuh dan tak tersentuh, hari ini jadi persoalan yang dilematis. Karena corona, kita jadi sadar dengan segala yang bersentuhan dengan tubuh. Bahkan tempat-tempat yang jarang tersentuh tubuhpun jadi tutup karena corona. Di facebook, tempat-tempat seperti Gedong Kertiya dan Museum Denpasar diberitakan tutup oleh pemerintah. Seolah-olah setiap harinya banyak tubuh yang lalu lalang berkunjung ke sana. Banyak bersin dan ludah menempel di dalamnya. Padahal tanpa pengumuman itupun, jangan-jangan sejak semula jarang ada orang yang singgah ke sana. Berbanding terbalik dengan tempat-tempat wisata lainnya di Bali, yang biasanya ramai pengunjung, namun jarang diberitakan telah ditutup. Apakah sudah benar-benar ditutup? Atau malah tetap terbuka dan sengaja ditutupi keterbukaanya?
Jika ingin menyebut satu tempat lagi yang terhindar dari corona, barangkali salah satu yang aman adalah panggung teater. Panggung tempat para aktor bermain. Yang senantiasa dibersihkan oleh tim produksi, yang berjarak dengan tempat duduk para penonton. Di panggung inilah, pandangan terhadap kesadaran dan keniscayaan tubuh sering diotak-atik jadi bahan eksplorasi pertunjukan. Namun tampaknya, dari sekian pertunjukan yang pernah saya tonton, jarang ada tubuh yang mengeksplorasi bersin dan batuk-batuk. Jikapun ada, bersin dan batuk hanya jadi stereotipe yang biasa digunakan untuk menunjukan adegan sakit atau tokoh yang lanjut usia.
Apakah saya yang kelewatan menonton pentas semacam ini? Atau bersin dan batuk memang bukan hal yang menarik untuk digali kemungkinannya dalam konteks kesadaran dan keniscayaan tubuh? Ah, Corona.. Gara-gara kau, segalanya jadi tampak begitu berjarak. Antara aku, tubuhku, dan dunia sekitar. Bahkan bersin dan batukpun kini jadi tampak begitu dramatis. Ingin sekali rasanya membuat pentas dimana para aktornya bersin-bersin dan batuk-batuk sepanjang pertunjukan. Tentu tak sekarang, Nanti. Jika tiba saatnya corona enyah dari dunia ini. [T]
Denpasar, 2020