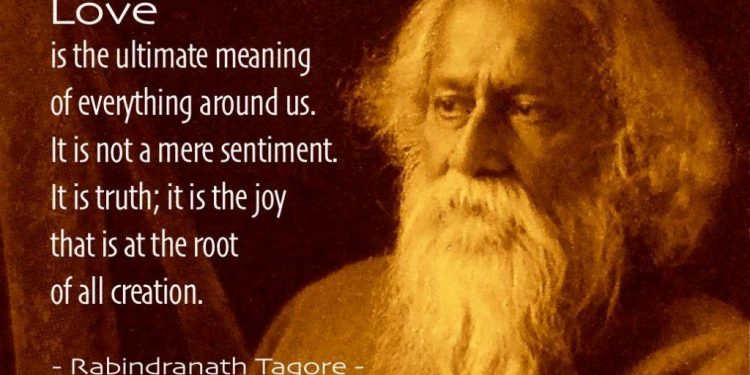RABINDRANATH dan Suniti mencatat beberapa hal yang ditemukan dalam perjalanan ke Bali ini. Rabindranath menyajikan catatan tersebut dalam bentuk surat-surat yang ditulisnya dalam perjalanan tersebut; sementara Suniti mencatat layaknya peneliti dan menyajikannya dalam bentuk paper.
Dalam surat Tagore terungkap bagaimana para raja dan pendeta Bali yang ditemui menjadi lebih sadar akan jalinan budaya Bali dengan tanah India, dan mereka yang ditemui sangat antusias serta ingin memperbaharui hubungan budaya Bali dengan India.
Rabindranath mencatat bahwa kebudayaan Bali dilihatnya sebagai kelanjutan dan kelangsungan dari ‘zaman Purana’. “Cerita-cerita dan kemeriahan upacara yang disebutkan dalam Purana di sini menemukan harmoni mereka masyarakat, sifat yang telah terwujud dalam berbagai produktitas seni dan ritual”. [Surat ditulis di Karang Asem tanggal 30 Agustus 1927].
Lebih lanjut ia membandingkan Ngaben dengan Sraddha:
“Pada festival (ngaben) yang kita saksikan padahari pertama kedatangan kami, pakaian, ornamen atau perlengkapan lainnya tidak memiliki kemiripan dengan kita, atau bahkan tidak mirip dengan semangat upacara pemakaman yang kita kenal sebagai Sraddha, tetapi, terlepas dari perbedaan dalam detail dari hal-hal India, bagaimana pun, ada kesamaan sikap.
Para Brahmana dengan duduk berjejer tinggi-tinggi, membunyikan genta mereka dan bermantra sesuai dengan teks yang rumusannya telah ditentukan, setiap penyimpangan akan bisa membatalkan seluruh acara. Para Brahmana, ternyata, tidak mengenakan benang suci (sacred thread).
Melalui penyelidikan kita belajar bahwa mereka tahu nama Gayatri, tetapi telah kehilangan kata-kata yang tepat dari mantra tersebut, beberapa dari mereka bisa mengulangi hanya potongan-potongan itu…
Sepertinya, pasti ada waktu ketika mereka telah diinisiasi secara utuh ke dalam Hinduisme, dengan para dewa dan dewi, dengan sopan santun dan adat istiadat, ritual dan upacara, Purana dan sastra suci. Kemudian mereka kehilangan kontak dengan asal-muasalnya, dan ketika Hindu terhalang bentang laut-pelayaran, tenggelam dalam jarak, terhadang oleh perbatasannya sendiri, lupa sama sekali bahwa ia telah memperoleh wilayah besar di luar tembok-temboknya sendiri.”[Surat ditulis di Karang Asem tanggal 31 Agustus 1927]
Dari diskusi di Puri Gianyar, Rabindranath mengetahui bahwa para pandita di Bali melaksanakan ritual Tantra dan tidak mengetahui mantra Gayatri. Para pedanda atau purohita ingin belajar mantra Gayatri dan Suniti Kumar Chatterjee melaksanakan tugas mengajari para padanda tersebut.
Rabindranath berjanji akan mengirim ahli Sanskrit secara khusus yang nantinya bisa memenuhi keinginan kalangan pendeta untuk ini. Janji ini nampaknya dipenuhi Tagore, pada tahun 1928, seorang ahli Sanskrit dan pakar Indologi terbaik, Prof Sylvain Levi, yang sebelumnya menjadi pengajar tamu di Santiniketan, datang ke Bali dan melakukan riset yang lebih mendalam terhadap Surya Sewana dan berbagai teks Sansekerta yang ada di lontar-lontar Bali dan melakukan interview mendalam ke para padanda (pandita) di Bali.
Tentang diskusinya di Puri Gianyar, Tagore mencatat:
“Aku datang ke istana Raja Gianjar. Suniti menjadi perhatian pusat dari sebuah pertemuan yang antusias (yang diikuti) oleh para pandita sebelum makan siang. Setelah kami makan tuan rumah kami meminta saya untuk membacakan beberapa ayat Sansekerta, dan saya mengulangi sesuai aturan berbagai jenis guru-lagu. Ketika Suniti menyebut nama salah satu dari mereka-Sárdûla-vikrîdita-Raja mengulangi nama itu untuk menunjukkan bahwa ia mengenalnya.
Mendengar bahwa nama Sansekerta diucapkan olehnya cukup mengejutkan saya. Raja kemudian melanjutkan menyebut nama guru-lagu lainnya, Sikharinî, Srakdhará, Malini, Vasanta-tilaka, dan menambahkan beberapa nama yang saya belum pernah dengar dalam karya bahasa Sansekerta…
Dia mengatakan semua nama tersebut mengunakan bahasa mereka, namun ia tidak mengetahui Mandákrántá atau Anustubha. Demi menyaksikan jejak-jejak retak dari budaya Hindu membuat saya merasa seolah-olah beberapa kota besar lama telah hancur akibat gempa dan terkubur di bawah tanah, di mana generasi berikutnya telah membangun rumah-rumah sendiri dan membuat lantai di atasnya, sedangkan bekas peninggalannya masih tampak di tempatnya, dan keduaanya lalu dikombinasikan dalam membentuk pemukiman manusia baru”.[Surat ditulis di Gianyar tanggal 31 Agustus 1927].
Di Puri Gianyar Rabindranath juga berbincang-bincang dengan Dr. R. Goris tentang keberadaan Ramayana dan Mahabarata di Bali dan Jawa. Dalam pandangan Rabindranath, Ngaben di Bali mungkin gabungan unsur tradisi upacara pemakaman China yang digabungkan dengan tradisi Hindu India, sebuah kompromi antar adua ritus berbeda (China dan India?):
“Anda mungkin telah belajar dari surat saya ke orang lain bahwa kami pertama kali datang untuk melihat festival pemakaman besar. Itu sangat mirip dengan tradisi Cina yang melengkapi upacara pemakaman mereka dengan dekorasi berlimpah, musik dan demonstrasi lainnya. Hanya mantra-mantra yang terucap yang memiliki kemiripan dengan cara Hindu. Mereka telah mengambil tradisi kremasi dari Hindu, namun, tampaknya tidak sepenuh hati.
Pemeluk Hindu berpikir tentang jiwa yang melampaui dan berbeda dari tubuh, dan seterusnya, setelah kematian, mereka ingin mencapai kebebasan dari segala keterikatan yang terakhir dengan mereduksinya menjadi abu. Di sini mereka sering menjaga mayat tanpa dikremasi selama bertahun-tahun. Ide dari menjaga mayat itu sama seperti apa yang mendasari kebiasaan penguburan. Mereka tampaknya telah berusaha untuk membuat kompromi antara dua ritus berbeda”. [Surat ditulis di Gianyar tanggal 31 Agustus 1927].
Dua surat yang ditulisnya di Munduk (sebuah desa di Buleleng) adalah surat-surat terakhirnya dari Bali. Ia kembali mengulas upacara Ngaben:
“Ini adalah hari terakhir kami di Bali. Saya telah mengungsi di dak-bungalow di bukit Mundak… Selama seluruh perjalanan kami, pulau itu dalam pergolakan upacara pemakaman besar (ngaben)
… Sulit untuk mengambil semua aspek-aspek yang menyusun jalannya ngaben secara keseluruhan. Hal yang terutama menarik bagi saya adalah iringan para pendukung prosesi. Dari setiap penjuru perempatan dan dari jarak yang jauh para perempuan membawa sesaji penghormatan di atas kepala mereka, satu demi satu, dalam prosesi yang panjang.
Ada sebuah miniatur festival, diiringi musik gamelan, di setiap tempat dari mana prosesi tersebut dimulai. Masyarakat pulau ini turut serta mengambil bagian mereka dalam upacara dengan cara mereka sendiri…” [Surat ditulis di Munduk, tanggal 8 September 1927]
Surat
Surat Tagore yang ditulisnya di Munduk, Buleleng,mengabarkan bahwa Sunitikumar diundang untuk membacakan dari Veda untuk upacara ngaben di Ubud. “Upacara ini sedang dilakukan oleh Raja Ubud. Ketika ia mendengar bahwa Suniti adalah Brahmana, berpengalaman dalam shastra, ia mengirim pesan kepadanya, karena upacara pemakaman tersebut, lengkap dalam semua rinciannya, tidak akan pernah terulang di negeri ini, ia akan merasa spesial dan kehormatan jika Suniti mengenakan Brahmin pakaian, membakar dupa, dan menutup ritus dengan mantram-mantra dari Kathopanishad.
Berabad-abad yang lalu ada sebuah hari ketika pertama kali upacara pemakaman dilakukan di Bali dengan iringan teks Weda. Sekarang, mungkin, sama bergema mantra khidmat di dalamnya untuk terakhir kalinya …”
Tagore juga mengungkap biaya ngaben di Ubud cukup tinggi:
“Mereka memberitahu saya bahwa biaya upacara mencapai Rs. 50.000 jika disetarakan dengan uang kita. Tampaknya bagi mereka ini jumlah besar untuk dibelanjakan, meskipun itu tidak akan dihitung begitu berlebihan oleh umat Hindu yang kaya di negara kita…
Perbedaan nyata, bagaimana pun, adalah bahwa di sini obyek utama adalah untuk membuat tampilan (display) sementara di India adalah untuk mendapatkan pahala. Di negara kita sebagian besar pengeluaran terdiri dari hadiah yang dibuat untuk menjamin kesejahteraan jiwa yang berangkat, –di sini adalah dalam dekorasi yang menjadi abu bersama tubuh”.
Renungan mendalam kita tentang tradisi dan agama Bali yang disebutkan oleh Tagore sebagai ‘agam’, penting disimak disini:
“Orang-orang Hindu Bali menyebutnya mereka adalah Agama, dan upacara pemakaman (ngaben) adalah salah satu festival yang paling penting. Pasalnya, mereka percaya, bahwa jiwa dapat kembali dari wilayah kabut kembali ke bumi, hanya jika ritual ini sepatutnya dilakukan, setelah mencapai pembebasan dalam tempat tinggal Siwa, setelah dimurnikan melalui kelahiran berturut-turut”.
Ketika Tagore berkunjung, kata Hindu atau istilah Hindu belum begitu dikenal oleh masyarakat kebanyakan. Masyarakat Bali umumnya menyebut keyakinan dan ritual yang dijalankannya adalah Agama Bali. Dan istilah Hindu di masa kunjungan Tagore belum menjadi ‘payung’ atau ‘istilah generik’ yang memayungi keyakinan dan religi Bali.
Kata ‘agama’dalam bahasa Indonesia sekarang dengan kata ‘agama’ dalam bahasa Bali konteks tahun 1927 sangat berbeda maknanya. Agama dalam bahasa Indonesia sejajar maknanya dengan kata religion dalam bahasa Inggeris. Sedangkan dalam bahasa Bali konteks masa sebelum kemerdekaan dan para penekun lontar-lontar, kata agama berarti kepercayaan yang bersumber atau berpedoman pada kitab-kitab yang masuk genre atau kodefikasi naskah Agama – diantaranya: Lontar Siwagama, lontar Budhagama, Sundarigama, serta berbagai lontar tutur dan tattwa, dan seterusnya.
Standarisasi keyakinan dan ajaran di Bali dalam wadah atau istilah Hindu terjadi setelah kemerdekaan, tepatnya di tahun 1950-an, dalam rangka perjuangan meraih pengakuan agar Agama yang dipeluk oleh masyarakat Bali diterima sebagai agama resmi yang diakui negara. Apa yang disaksikan Tagore dalam kunjungannya adalah masyarakat Bali yang menganut lontar-lontar jenis Agama yang belum distandarisasi dalam sebutan Hindu sebagaimana nantinya terjadi semenjak tahun 1950-an dan sekarang. (T)
- Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di Bali Post, 8 September 2013