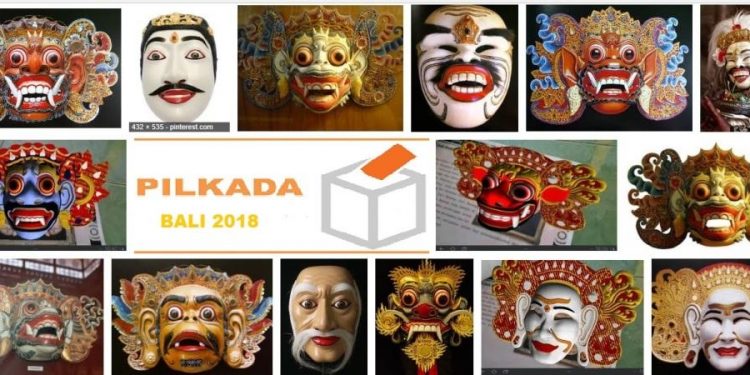EUFORIA pemilukada serentak tahun 2017 resmi berakhir. Sisa endapan perseteruan, bahkan percikan kebencian tidak dapat ditunggu agar selesai, tapi harus diselesaikan.
Khusus di DKI Jakarta, selamat, mereka memiliki gubernur baru. Bukan lagi orang yang katanya arogan dan kasar. Sekitar 58% dari mereka yang ber-KTP DKI Jakarta, menurut hasil hitung cepat, memutuskan memilih sosok yang terlihat lebih santun. Masalah kinerja, nanti saja dilihat setelah resmi dilantik oleh Cahyo Kumolo.
Prihal pilkada DKI Jakarta menyita perhatian banyak orang beberapa bulan terakhir, itu juga fakta. Sebagian besar pembicaraan di dunia maya selalu ditujukan ke sana. Mulai ketika masih ada Agus, hingga hanya tersisa Anies dan Ahok. Tidak bisa dipungkiri banyak emosi terkuras, banyak konflik tercipta.
Ahok, seorang kristen, seolah menjadi bulan-bulanan di sana. Video yang diunggah Buni Yani nyatanya sukses, tepat sasaran. Memainkan isu agama yang memang sedari dulu sudah menjadi isu paling sensitif di negeri Pancasila ini.
Fakta unik lainnya, menurut hasil survei, kepuasan publik kepada Ahok tidak pernah menyentuh angka di bawah 70%. Namun, nyatanya menurut versi hasil hitung cepat, dia hanya dipilih 42% orang di DKI Jakarta (hasil hitung pagi 19-4-2017). Kemana sisanya? Menguap.
Jika berbicara hitung-hitungan rasional, rumusnya pasti begini: “kalau anda puas, anda akan memilihnya”. Itu hukum alam. Namun, sayangnya DKI Jakarta lebih dari sekadar perkara rasional. Ada unsur emosi yang dimainkan. Ada isu sektarian yang dihembuskan. Lalu, ada isu primordial radikal yang dikembangkan. Mulai agama hingga etnis. Yang sejujurnya bagiku itu bagian yang kurang relevan dalam konteks sebuah negara demokrasi ber-Pancasila.
Emosi itu manusiawi. Namun, apabila ditempatkan bukan pada tempat yang seharusnya, maka akan menjadi duri. Mungkin semua orang setuju, bahwa ketika sebuah keputusan diambil berdasarkan emosi, maka yang lahir adalah keputusan emosional. Bukan keputusan rasional. Silakan dimaknai sendiri, bagaimana jika emosi dimainkan ketika pemilukada. Dengan asumsi bahwa pemilukada adalah ajang pengambilan keputusan.
Yang jadi masalah kemudian adalah kekhawatiran bahwa emosi itu menular. Bahwa isu sektarian ini akan menyebar. Lalu, fanatisme primordial ini jadi merambat. Kemungkinan itu terbuka lebar, karena sekali lagi, sebagian manusia Indonesia masih memahami Pancasila sebatas pada pelajaran PPKn yang diajarkan Bapak/Ibu guru ketika SD. Hasilnya, Garuda tinggal burung perkutut, Pancasila tinggal kode buntut, kata Virgiawan Listanto. Lalu kataku, Bhinneka Tunggal Ika tinggal semboyan yang kalut.
Pilgub Bali
Sekarang aku ingin lebih khusus tentang Bali. Sebentar lagi, 2018, Bali akan menggelar pengambilan keputusan mengganti gubernur dan wakilnya. Kenapa mengganti? Ya, karena sudah dua periode, dan konstitusi tidak mengizinkan mereka untuk berkontestasi lagi. Kecuali kalau mau, tukar posisi antara gubernur dan wakilnya.
Jangan berpikir Bali tidak bisa dipermainkan oleh isu-isu macam tadi, seperti isu sektarian semacam agama. Kendati warga Bali mayoritas Hindu, nyatanya ada turunan di bawahnya yang saat ini masih bersegmen. Nama segmen itu antara lain kasta/wangsa, atau juga soroh atau klan.
Kasta/wangsa memiliki kadar sensitivitas yang mirip dengan isu agama atau entis yang bermain di DKI Jakarta tempo hari. Yang juga akan laku menjadi barang jualan kampanye politik. Buktinya, beberapa hari lalu aku membaca artikel dengan judul “Pilgub Bali 2018: Hasil Penelitian UI, Masyarakat Bali Ingin Top Leader Triwangsa”. Ilmiah? Iya, sepertinya. Karena membawa label Universitas Indonesia. Logis? Sama sekali tidak, bagiku.
Aku punya keyakinan bahwa tulisan itu memiliki niat untuk memperjelas segmen dalam kehidupan masyarakat Bali yang senyatanya segmen itu memang sudah ada. Tulisan itu mencoba menggiring opini bahwa yang diinginkan masyarakat untuk memimpin Bali adalah tokoh wangsa Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Jangan lupa, di Bali juga ada wangsa Sudra.
Tulisan itu sepertinya mencoba menggiring opini bahwa yang layak memimpin Bali hanya tokoh dari kalangan Triwangsa. Kalau mau dilihat secara frontal, bagiku, tulisan itu punya unsur memecah belah. Ingin mengadopsi taktik politik di DKI Jakarta, lalu dibawa ke Bali. Agar menguntungkan golongan tertentu, dan merugikan yang lain. Padahal, faktanya pemilukada bukan sekadar perkara wangsa.
Bagaimana sebaiknya orang Bali bersikap?
Gubernur bukan prihal wangsa. Pemimpin itu perkara kualitas. Ketika ada di antara mereka yang kaum Sudra memiliki kualitas lebih baik, apa mesti dipaksakan agar gubernur berasal dari wangsa Brahmana, Ksatria, dan Waisya? Apa layak menitipkan pemerintahan kepada seseorang hanya dengan pertimbangan wangsa dan mengesampingkan kualitas? Bukankah Bali bagian dari Indonesia yang mengakui Pancasila? Yang menjamin hak seluruh warganya untuk memilih dan dipilih.
Sederhananya, siapa yang berkualitas, itu yang dipilih. Biarlah prihal wangsa berada pada domain yang berbeda. Meskipun, sampai sekarang pemaknaan wangsa nyatanya masih banyak yang keliru.
Domain Wangsa dan Politik
Dalam pandanganku, ketika domain wangsa dicampuradukkan dengan domain politik sebagaimana pencampuran agama dan politik di DKI Jakarta, ya nasibnya akan 11-12 seperti di DKI Jakarta. Mungkin akan ada isu sing maan setra bagi mereka yang memilih berbeda. Akan semakin menegaskan otokritik masyarakat Bali bahwa arit mangan itu ke tengah. Akan ramai konflik bahkan ada yang mepuik dengan pisaga selat tembok. Lalu, yang tertinggal hanya teriakkan Ajeg Bali yang bermakna Ajeng Bali dan mempertegas bahwa politik devide at impera Belanda nyatanya masih lestari hingga saat ini.
Memisahkan kedua domain itu memang bukan perkara mudah, namun bukan sesuatu yang mustahil. Sederhana, kalau menyatakan diri percaya Tuhan, linier dengan itu seharusnya manusia menghargai perbedaan. Karena nyatanya mereka yang berbeda juga diciptakan oleh Tuhan. Selanjutnya, ketika sudah merasa bahwa kita semua berasal dari Tuhan, maka selayaknya memiliki kewajiban dan hak yang sama. Kewajiban sebagaimana dharma agama dan dharma negara, serta hak, yang dalam konteks tulisan ini, untuk menjadi pemimpin pemerintahan tanpa batasan wangsa. Karena, sepemahamanku, Tuhan tidak menciptakan wangsa, melainkan menciptakan warna yang bersifat fungsional dan tidak herediter.
Terakhir, biarlah perkara wangsa menjadi bagian dari tradisi. Dalam konteks politik dan pemerintahan, mari lebih mengedepankan nalar yang rasional daripada fanatisme primordial yang radikal. Bali patut belajar dari DKI Jakarta jika ingin menjadi Bali yang tetap ajeg dan menjadi Bali yang tetap dimiliki oleh seluruh orang Bali. (T)