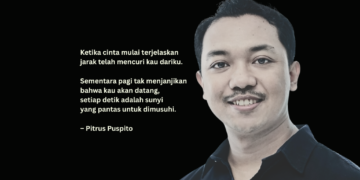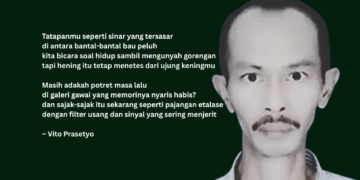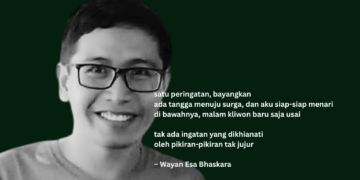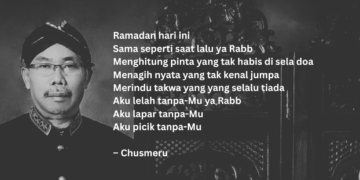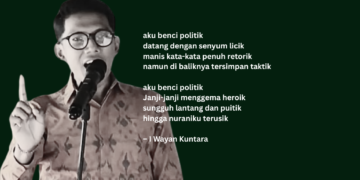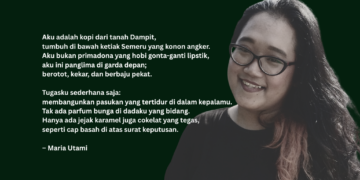BUNGA KECOMBRANG
(1 )
Pada kelopak mudaku kau temukan rasa
yang enggan pergi
dari tiap ujung papila
Kau terbakar rasa larut dalam liur
kuntum kuntumku membuat dadamu lebih lapang dari tubuh pelangi
seperti tubuh ombak yang buncah
leleh dalam peram dan pejam
kau melenguh diantara peluh
melepas cadas legenda
dalam uap uapku
(2)
Tiga siung bawang merah dan sejumput terasi garam
kau padu aku dalam sebuah tempat
seperti seekor burung yang membuat sarang
kau hias dengan dongeng cabe rawit
kau melayari daerah daerah keramat
semakin jauh tak kenal mata angin
hanya kecombrang yang hujan
di langit lidahmu
(3)
Kini kau telanjang menghembus renjana
menghidu kuyup sebilah pedang dari masa lalu
bagimu aku tempat meledakkan setumpuk pahit
yang lama berakar di sekat tenggorokan
tubuhku ruah dalam liur hangat
ke batas sunyi kau hantar aku
dan kau
menjelma kupu-kupu
(Tegaljaya, Juli 2016)
UMUR KELAHIRAN
Aku lupa
kita pernah lahir dari rahim yang sama
Aku lupa
kita pernah melewati jalan yang sama di tanah tua
Semuanya aku lupa sebab,
kita tak lagi memahami duka sebagai kekuatan
kita hanya menakar suka duka dengan emosi
nilai kebersamaan pun tak berdaya apalagi umur kelahiran
Semua berlalu bersama hembusan nafas terakhir di malam kelam
Jarak tak nampak memetakan aura kematian
Sejak detik itu
sajak sajak duka mengabut di matamu
bibirmu kelu mengeja luka
kenangan menggenang pilu di serabut jantungmu
Aku hanya dapat mengulum sunyi diam diam
menikahi kata-kata yang beterbangan dan tercecer di jalanan
kita selalu memulai babak hari dengan secangkir teh panas
dari asapnya kau melompat tajam
menghujaniku dengan pertanyaan getir dan satir
bibirku mengunyah tanya lumat menjadi debu purba
yang mengisi pori pori kita
Aku termangu antara umur kelahiran dan umur jiwaku
menjadikan puisi sebagai mempelai
sedang kau mencongkel tawa dari tubuh pagi
kita tercerabut dan terhempas ke matra yang lain
berjarak
tak berdaya mengingat setiap tetes air susu ibu yang pernah kita sesap
yang tersisa hanya jalan di depan kita,
yang tak pernah kita tahu ujungnya
(Kerobokan, 1 Februari 2015)
MALAM PURNAMA
Ini hari mengenang malam itu
Mengenang ratusan purnama
yang berbaris di hitam belacan
menari dalam kaldu santan
meruahkan liur kita yang pecah dalam derit malam
Ibu memintal tubuh ikan
mencelupkannya dalam lautan tepung
menjelma bayang masa lalu
Ibu berkata pada dirinya,
“Bayang bulan biarlah jadi tanah,
dan kecambah rindu membuang sendu.”
Ini hari mengenang malam itu
Kita duduk di tikar pandan
Ibu menyuguhkan sajak warna-warni
tercelup kuah gurih gurau
dalam uapnya semayam urat akarmu
Uap teh jahe berkeliaran di dada kita
yang jadi lebih lapang karena wanginya
Kuteguk perlahan
Larik-larik puisi terbit dari udara malam yang kau tiriskan
“Ini malam apa?” tanyaku
“Kubangan kenangan?” tanyaku lagi
Kau mengaliskan senyum di dahiku
Aku tak paham
Yang ku tahu, hanya menguliti angka-angka di wajah purnama
Yang ku tahu, inilah purnama paling purna dalam darahku
(Tuban, April 2016)
JARAK
Mimpi tak henti melingkari kita
Dalam derai abu-abu atau
bayang bayang sepi
Keluh kesah tak usai mengitari kita
menumbuhkan benih-benih jarak tak nampak
Bahkan sujud kita berjarak diantara dua cat
menari di sudut-sudut kamar dan
menulis serangkaian kata-kata di tembikar
yang setiap hari kita elus
Suatu saat ia akan bercerita tentang hari ini
Saat tawa lahir dari sentuhan luka
atau tumbak yang mengumpan cemburu
Hujan tak mampu menyapu gigil ranting tubuh kita
selimut-selimut kering di ranjang tawar
air muka tak cukup menyingkap bebatu yang kita sandung
segaris sabit cuaca tlah menciptakan lembaran beku
di serambi jantung
Aku masih ingat, ketika pelangi menjadi warna mata
kita menjelma bunga dan kumbang
Kini ketika berlembar-lembar pagi tlah berlari
akar-akar ranting menahan batang tubuh
rambut rambut api meletupkan jarak
aku terhempas ke pintu sunyi
memiliki atau dimiliki
memerangkap indraku
ke sebuah labirin sepi seperti seseduh kopi
uapnya sepi tiada kata
hanya jarak
dan aku tak mampu menyeberang
ke kedalaman lautmu
tak mampu menerobos rerimbunan belantaramu
hingga
lapuk dalam pembaringan puisi
(Tegaljaya, September 2015)
KITA
Aku menemu malam di tubuhmu
menghitung pekat porimu dan tertegun menatap beku kelopak dadamu
yang membangun gigil di langit lidahku
Kasur dingin kuyup dalam bayang kemarau
sepotong ekor cicak
mencari tempat sembunyi
mencoba menghalau cemas dari ceruk yang lebih pekat dari sekadar gelap
Kita tak lebih tinggi dari awan
hanya butiran debu di eraman takdir
Kita tak lebih rendah dari lembah
hanya bebuih bir yang luruh di tenggorokan
Kita sering terjebak suara jalanan yang kerap singgah di rongga kepala
ketombe-ketombe liar menari diantara uban yang mengeriap tawar
meriutkan dada yang membusung tinggi
Tlah kita singgahi dalam tahun pertama
kala bulan setengah purnama menjarah usia
mencuri seperempat nafas
mengapa kita merasa asing?
Tak perlukah kita merasa senasib?
Lihatlah !
dalam puisi-puisi cintamu, birahi sembunyi di kaki kata-kata
dalam luapan ludahku kata-kata mabuk meremas-remas doa
tubuh kita tak berdosa
tak bernoktah
hanya kadang takut akan kemungkinan lain di luar isi kepala
sama seperti ekor cicak yang baru putus dan sembunyi
di sela-sela mimpi
(Tuban, Mei 2016)