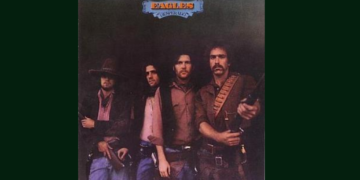After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.
(Setelah keheningan, musiklah yang mampu mengekspresikan apa yang nyaris tak terungkapkan.)
—Aldous Huxley
Dalam dunia musik klasik di tanah air nama Ananda Sukarlan telah melegenda. Buktinya? Di era digital ini, gampang mencari bukti. Ketiklah namanya di Google. Jika muncul “Daftar Komponis Indonesia,” silakan klik. Akan muncul nama-nama komponis besar, salah satunya nama Ananda Sukarlan. Nama-nama lain merujuk para musisi sohor di Indonesia, di antaranya: Wage Rudolf Supratman, Ismail Marzuki, Gesang Martohartono, dan Amir Pasaribu.
Bagaimana dengan pemberitaan di media utama? Jangan keluar dari Google. Ketiklah “kompas ananda sukarlan” atau “tempo ananda sukarlan”. Maka akan muncul puluhan artikel yang mengulas profil Ananda Sukarlan, dan menyajikan berbagai berita tentang konsernya di dalam maupun di luar negeri. Konser di dalam negeri terkait dengan peristiwa penting seperti memperingati hari kemerdekaan atau hari pendidikan nasional; sedangkan konser di luar negeri terutama bertujuan meningkatkan hubungan diplomatik via musik sebagai pembawa misi kebudayaan dan perdamaian.
Anda ingin tahu karya-karya Ananda Sukarlan? Masuklah ke YouTube lewat nama yang sama. Akan muncul “ananda sukarlan” + penjelasan, di antaranya: rapsodia nusantara, piano, rayuan pulau kelapa, dalam doaku, passacaglia, dan daydream. Ini baru sebagian kecil dari karyanya. Secara keseluruhan, ada ratusan karya Ananda Sukarlan di YouTube. Komponis ini adalah sumber kreasi yang tak pernah kering.
Mungkin pembaca bertanya-tanya. Jika saya awam tentang dunia musik, apa tujuannya menulis esai ini? Ada cerita singkat. Saya belum pernah bertemu Ananda, dan baru berkenalan lalu berkawan lewat cyber space. Sebagai pencinta puisi, atau penyair pinggiran, saya beruntung. Puisi saya “Di Halaman Indonesia”, dalam buku antologi tunggal dengan judul yang sama (Kadarisman 2023), mendapatkan apresiasi Ananda. Pada awal Juli, puisi itu digubah jadi tembang puitik. Partiturnya dikirim kepada saya. Pada tanggal 17 Agustus 2024, bersama karya lima penyair lain (Emi Suy, Hilmi Faiq, Sihar Ramses Simatupang, Shantined, dan dan Budhi Setyawan) yang telah digubah ulang, seluruh tembang puitik tersebut dipentaskan sebagai konser refleksi kemerdekaan.
Apakah tembang puitik? Ini istilah baru, terjemahan dari art song—a short piece, typically for solo voice with piano accompaniment, of serious artistic intent (komposisi pendek, lazimnya dinyanyikan secara solo dengan iringan piano, yang digubah dengan tujuan serius). Di ranah ini, Ananda Sukarlan layak disebut sebagai penerus art song atau tembang puitik, yang di era 1980an pernah dirintis, antara lain, oleh Mochtar Embut dan F. X. Sutopo. Namun ada perbedaan yang mencolok. Mochtar Embut hanya menggubah ulang beberapa puisi W. S. Rendra menjadi tembang puitik. Sebaliknya, selama tiga puluh tahun terakhir Ananda telah menggubah ratusan tembang puitik. Menurut info di Wikipedia, komponis tembang puitik di kawasan Asia hanya tiga orang: Ananda Sukarlan dari Indonesia, Nicanor Abelardo dari Filipina, dan Byambasuren Sharav dari Mongolia.
Dalam konteks ini, Ananda meminta saya menulis tentang tembang puitik. Semula saya menolak, karena saya buta huruf tentang musik. Namun saya terus diberi dorongan dan dukungan. Jika diperlukan deskripsi tentang musik, Ananda akan memberikan pemaparan. Jadi, esai ini adalah hasil kolaborasi. Saya memaparkan aspek puitika dan bagaimana puisi dengan berbagai mood digubah ulang menjadi tembang puitik; dan Ananda menjelaskan proses dan hasil gubah-ulang tersebut.
Tembang Puitik sebagai Penerjemahan Intra- dan Inter-semiotik
Bahasawan kelahiran Rusia, Roman Jakobson (1896-1982), karena politik represif di negaranya, berpindah ke Eropa dan akhirnya menetap dan wafat di Amerika Serikat. Salah satu karyanya yang monumental adalah “Linguistics and Poetics” (Jakobson 1960). Dalam konteks pembahasan tembang puitik, ada makalah kecil yang relevan “On Linguistic Aspects of Translation” (Jakobson 1959 [1992]).
Bagaimana teori Jakobson menjelaskan kegiatan kreatif Ananda? Marilah kita tengok “rapsodia nusantara” sebagai contoh penerjemahan intrasemiotik, atau gubah-ulang dalam satu sistem tanda yang sama, yaitu dunia musik. Secara semi-matematis, tafsir-artistik itu dapat dilambangkan sebagai berikut: x → X, di mana panah → berarti ‘menjadi’, dan x (musik lokal) maupun X (musik klasik) adalah representasi dunia musik. Perhatikanlah, ketika x menjadi X, ada dua implikasi penting. Pertama, Ananda mampu mengapresiasi nada dan irama musik lokal yang dipilihnya. Kedua, musik lokal itu ditafsir atau digubah ulang dan dipromosikan ke ranah internasional. Hasilnya, musisi nasional ataupun internasional, yang tertarik pada hasil gubahan ini, dapat membawakannya dalam konser yang ia pentaskan.
Sebagai pianis-komponis kaliber dunia, Ananda adalah garuda yang terbang tinggi, berpandangan tajam, dan berwawasan amat luas. Cabang seni lukis pun tak luput dari perhatiannya. Lukisan-lukisan terkenal—misalnya “Bacchus and Ariadne” karya Titian, atau beberapa lukisan Vincent Van Gogh mengenai musim semi—juga menjadi inspirasinya untuk menggubah lagu klasik. Komposisi yang terinspirasi oleh lukisan ini merupakan contoh dari penerjemahan intersemiotik, atau gubah-ulang dari suatu cabang seni ke cabang seni lain yang berbeda. Formula matematisnya sebagai berikut: P → X, di mana panah → berarti ‘menjadi’, dan P adalah representasi seni lukis sedangkan X representasi seni musik.
Kembali ke tembang puitik. Ini juga masuk kategori penerjemahan intersemiotik, dengan formula serupa: Q → X, di mana panah → berarti ‘menjadi’, dan Q adalah representasi seni kata atau puisi sedangkan X representasi seni musik. Secara umum, Ananda telah menggubah ratusan komposisi musik klasik yang terinspirasi oleh puisi-puisi dalam tiga bahasa: Indonesia, Inggris, dan Spanyol. Ini menunjukkan adanya bakat seni yang luar biasa.
Maksudnya? Tidak semua penutur bahasa Indonesia mampu mengapresiasi puisi dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa asing. Diperlukan ketajaman rasa bahasa, yang lazimnya merupakan bakat alam. Jelasnya, selain memiliki talenta yang dahsyat di bidang musik, Ananda juga memiliki bakat seni yang amat komprehensif, meliputi seni lukis dan puisi.
Tidak main-main. Dalam hal puisi, ia mampu mengapresiasi puisi dalam tiga bahasa. Pembaca yang telah merasakan betapa sulitnya menguasai bahasa asing (sebagai alat komunikasi) bisa membayangkan beratnya memasuki puitika dari bahasa tersebut. Ananda, sang maestro musik klasik, mampu menaklukkan puitika bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, lalu menyerap dan menggubahnya menjadi komposisi musik klasik. Sungguh seniman yang super-langka. Bagian berikut adalah elaborasi dari tembang puitik.
Tembang Puitik, Bunga Rampai tak Tepermanai
Mengulang ulasan di depan, tembang puitik adalah komposisi musik klasik yang terinspirasi oleh puitika dalam sebuah bahasa. Bagi Ananda, puitika itu bisa berasal dari bahasa Ibu (bahasa Indonesia) maupun bahasa asing (bahasa Inggris dan Spanyol). Bagian ini seperti merpati terbang, yang membentangkan dan mengepakkan kedua sayapnya. Sayap kiri adalah puitika, bagian saya; dan sayap kanan adalah proses gubah-ulang (yang menghasilkan tembang puitik), bagian Ananda. Mohon diingat pula, tembang puitik masuk kategori penerjemahan intersemiotik. Ruh puisi digubah ulang menjadi lagu klasik.
Dalam penerjemahan interlingual, hasil terjemahan yang baik berwujud the closest natural equivalent (Nida 1969), atau padanan alamiah terdekat. Di dunia puisi, contoh terkenal adalah “Huesca”, yang diterjemahkan oleh Chairil Anwar dengan judul yang sama. Terjemahan ini saya bahas dalam esai saya “On Poetry Translation”, dan saya kategorikan sebagai subtle translation, terjemahan yang subtil atau canggih (Kadarisman 2011). Hasilnya bukan hanya memukau pembaca, tapi terjemahan itu diterima sebagai karya sastra yang merupakan bagian dari sastra Indonesia.
Dalam sastra Inggris, ada pula adaptasi atau saduran terkenal. Puisi aslinya dalam bahasa Parsi, tidak disertakan—mungkin dengan asumsi bahwa pembaca di Barat tidak memahami versi asli tersebut. Hasil saduran itu berupa antologi The Rubaiyat of Omar Khayam (yang berisi 75 kwatrin), karya Edward FitzGerald (1809-1883), penyair Inggris abad 19. Begitu intensif kerja FitzGerald dalam melakukan adaptasi, sehingga ia menghasilkan lima versi saduran. Yang dimuat dalam edisi Dover 1990 adalah saduran versi pertama dan versi kelima. Proses adaptasi ini dipuji oleh Editor Dover sebagai “creating what was essentially a new work of English poetry” (menggubah karya yang sepenuhnya baru dalam puitika bahasa Inggris).
Apa maksud merujuk “Huesca” sebagai terjemahan yang hebat dan mengulas The Rubaiyat of Omar Khayam sebagai hasil saduran yang impresif? Saya berasumsi bahwa dalam melakukan penerjemahan intersemiotik, dari puisi (dalam tiga bahasa) menjadi tembang puitik, Ananda melakukan hal yang sama. Ruh puisi terpilih itu akan tetap hidup dengan nyala serupa dalam tembang puitik. Maka kolaborasi saya dan Ananda akan sepenuhnya terbaca pada bagian ini.
Demi menghemat ruang, saya kemukakan tiga catatan. Pertama, dari ratusan puisi yang telah digubah menjadi tembang puitik, saya hanya memilih tiga puisi. Dua puisi bahasa Indonesia, yang melantunkan kerinduan dan mengibarkan kepahlawanan; dan satu puisi bahasa Inggris, yang bersimpati berat terhadap kemanusiaan. Kedua, kita akan mencermati bagaimana tiga puisi dengan tema dan mood yang berbeda itu lahir kembali sebagai tembang puitik. Lebih jelasnya, apakah tiga getar-puitis itu muncul dengan nuansa estetik serupa dalam tembang puitik? Ketiga dan terakhir, tiga puisi yang dipilih ini dimaksudkan sebagai sampel. Meskipun secara kuantitatif jumlah ini amat kecil, setidaknya akan bisa dilihat bahwa penerjemahan intersemiotik itu mirip dengan penerjemahan interlingual. Ada upaya maksimal dari Ananda Sukarlan sebagai komponis unggul untuk memelihara ruh ketiga puisi tersebut dalam tembang puitik.
Puitika Sunyi: Rindu kepada Ibu
Puisi sering lahir sebagai ekspresi cinta dan rindu. Dalam makna sempit, cinta adalah amorous love, kasih berbalut birahi. Dalam arti luas, cinta meliputi rasa kasih kepada alam, sesama manusia, dan Tuhan. Yang sedang rindu pasti mengalami rasa sunyi. Ada ungkapan bijak oleh Arthur Schopenhauer (1788-1860) tentang sunyi dan kesendirian: To live alone is the fate of all great souls. In solitude the mind gains strength and learns to lean upon itself. (Hidup sendirian merupakan nasib dari jiwa besar. Dalam kesendirian, akal-pikiran mendapatkan kekuatan dan belajar bersandar pada dirinya sendiri.)
Untuk kepenyairan di Indonesia masa kini, saya merujuk Emi Suy sebagai “penyair sunyi”. Begitu intensif ia memasuki dan menggeluti kesunyian, sehingga secara eksplisit kata “sunyi” muncul pada tiga judul antologi puisi tunggalnya: Alarm Sunyi (2017), Ayat Sunyi (2018), dan Api Sunyi (2020). Bagi saya, Emi Suy adalah “the Emily Dickinson of Indonesia”. Emily Dickinson (1830-1886 ), penyair sunyi Amerika Serikat abad 19, begitu akrab dengan kesendirian dan kehampaan. Ia sering larut mencumbu kesunyian, dan bahkan kematian, misalnya lewat puisi-puisinya yang terkenal: “I’m nobody”, “Because I could not stop for death”, dan “I felt a funeral in my brain”.
Dalam kaitannya dengan kreasi musik klasik Ananda Sukarlan, ada tiga puisi lepas karya Emi Suy, plus dua puluh sembilan puisi dalam antologinya I’m Not for Sale (akan terbit 2025), yang telah digubah ulang menjadi tembang puitik. Hanya satu puisi lepas yang saya pilih dan saya bahas, “Kukusan”.
KUKUSAN
Di kukusan bambu, menghitam
dibakar bara dan doa, begitu tenang
ibu menanak usia kami, hingga matang.
Di malam mendidih, di siang perih
Ibu pelan-pelan menua, bagai kukusan
menampung segala, ringkih dan perkasa
sesekali meneguk
air matanya
sendiri
2021
Puisi ini terbit dalam antologi yang berjudul panjang Ibu Menanak Nasi hingga Matang Usia Kami (2022). Lihatlah, judul ini sebagian besar muncul sebagai baris ketiga dari bait pertama. Apa artinya? Puisi “Kukusan” merupakan bingkai bagi buku antologi ini. Posisi puisi ini sentral; ia menjadi titik pusat, dan puisi-puisi lainnya secara maknawi berkisar dan berputar mengelilinginya. Interpretasi selanjutnya? Bagi Emi Suy, “Kukusan” adalah metafora untuk ibu, yang menghitam dan pelan-pelan menua. Perjuangannya membesarkan putra-putrinya bagaikan waktu yang dipanggang, namun tiada henti melantunkan doa. Sepanjang usia, dengan melewatkan siang (yang) perih dan malam (yang) mendidih, ibu tetap hadir sebagai perempuan yang tangguh: menampung segala, (yang) ringkih dan perkasa. Bila terhimpit kesulitan hidup, tidak ada keluh-kesah. Ibu hanya meneguk / air / matanya sendiri.
Terbacakah nostalgia dalam puisi ini? Jelas sekali, pada diri penyair ada bara nostalgia dan api rindu yang tersembunyi. Di era digital ini, kukusan sebagai sign (‘tanda bahasa’ dalam paradigma Saussure) juga merasa kesepian. Di masyarakat kota, kukusan susah mencari referent, atau benda yang dirujuknya. Jadi, bagaimana? Judul “kukusan” menyiratkan makna tersembunyi. Dulu di desa, ketika aku masih kanak-kanak, ibu menanak nasi secara tradisional. Kini aku teringat pada tungku dengan nyala kayu bakar, dandang beserta kukusan, dan dapur yang aromanya tak terlupakan. Lebih dari itu, aku kangen pada ibu. Wanita perkasa dengan pandangan teduh penuh kasih. Ibu adalah pohon cinta, sungai rindu, dan cermin bening yang menyimpan masa kecilku yang bahagia.
Nah, bagaimanakah puisi yang lembut, sendu, dan romantis ini digubah ulang menjadi tembang puitik? Simaklah seorang peserta kompetisi Ananda Sukarlan Award, Felicia Sunaryo https://youtu.be/MjPX9nBNf48?si=EH1WLZlYUoiLGBon. Warna musik klasik terdengar dominan; dan ruh puitika dari sajak “Kukusan” tetap terjaga. Tidak diragukan, proses penerjemahan intersemiotik berhasil dengan baik.
Heroisme: Suara Pejuang dari Negeri Abadi
Berpindah dari romantisme ke heroisme, apa yang terasa? Seperti melepas rembulan tua merenungi bayangannya di bengawan, lalu menumpang perahu yang bergulat dengan badai di laut lepas. Dalam karier kepenyairannya yang pendek, hanya delapan tahun, Chairil Anwar (1922-1949) berhasil menulis sajak-sajak kepahlawanan yang mendebarkan. Seperti didokumentasikan dengan baik oleh Pamusuk Eneste (1986) dalam buku Chairil Anwar: Aku Ini Binatang Jalang, di antara karya-karya heroik itu adalah “Diponegoro” (1943), “Persetujuan dengan Bung Karno” (1948), dan “Krawang-Bekasi” (1948). Para peminat sastra di Indonesia lazimnya tahu bahwa puisi terakhir ini merupakan saduran dari “The Young Dead Soldiers Do Not Speak” (1940), karya Archibald MacLeish (1892-1982).
Tentang dua sajak ini, ada kemiripan yang layak dicatat. “The Young Dead Soldiers”, yang terbit delapan tahun lebih awal, disadur oleh Chairil Anwar menjadi “Krawang-Bekasi”. Sajak pertama terinspirasi oleh gugurnya tentara Amerika pada Perang Dunia II; dan sajak kedua terinspirasi oleh gugurnya para pejuang di wilayah Karawang-Bekasi menjelang 1945, tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lewat dua puisi kepahlawanan ini, kedua penyair menyuarakan gairah perjuangan prajurit yang telah gugur, agar pengorbanan mereka tak dilupakan. Hanya puisi Chairil Anwar yang saya kutip sebagian dan saya bahas secara singkat, karena puisi inilah yang telah digubah menjadi tembang puitik oleh Ananda Sukarlan.
KRAWANG-BEKASI
Kami yang kini terbaring antara Krawang-Bekasi
Tidak bisa teriak “Merdeka” dan angkat senjata lagi
……………
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu
Kenang, kenanglah kami
……………
Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan
Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan,
kemenangan dan harapan
Atau tidak untuk apa-apa
……………
Kenang, kenanglah kami
Teruskan, teruskanlah jiwa kami
Menjaga Bung Karno
Menjaga Bung Hatta
Menjaga Bung Sjahrir
Kami sekarang mayat
Berilah kami arti
Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian
……………
Puisi ini, yang menyuarakan semangat perjuangan para prajurit yang telah gugur, sungguh menggetarkan dan dibangun dengan retorika yang cantik dan heroik. Dari makam yang terserak di wilayah Karawang-Bekasi, tulang-tulang yang diliputi debu itu berbicara dalam hening di malam sepi kepada manusia Indonesia yang masih hidup. Kalianlah yang tentukan nilai pengorbanan kami. Kalianlah yang harus meneruskan semangat kami, merawat kemerdekaan dan menjaga para pemimpin negeri ini. Kalian harus terus bergerak ke depan, berjaga … di garis batas pernyataan dan impian. Dalam puisi ini, api perjuangan para pahlawan terus menyala. Tak heran, “Krawang-Bekasi” selalu terpilih untuk dideklamasikan setiap bulan Agustus, ketika kita merayakan proklamasi kemerdekaan.
Simaklah, setelah menjadi tembang puitik di tangan pianis Ananda Sukarlan, api kepahlawanan puisi ini terus membara menghangatkan jiwa, lewat suara tenor Nikodemus Lukas (dikenal sebagai Nick Lucas di dunia pop) bersama Svaditra Choir https://www.youtube.com/watch?v=O7jlyK9vOwM. Derap perjuangan seolah terdengar lewat nada-nada yang mendebarkan; dan suasana hening, khidmat, dan melankolis juga terbangun dengan baik, yang menyarankan hadirnya suara para pahlawan yang mati muda. Ada upaya sungguh-sungguh untuk memelihara mood serta greget dan semangat juang dalam tembang puitik ini.
Humanisme: Merengkuh yang Menderita dan Terpinggirkan
Seniman berjiwa besar bukan hanya mampu mengungkapkan perasaan yang bersifat pribadi, tapi juga sensitif terhadap derita orang lain dan mampu menuangkannya dalam karya seni yang digelutinya. “Jika engkau merasa sakit, berarti engkau hidup. Tapi jika kau rasakan penderitaan orang lain, berarti engkau manusia,” kata novelis Leo Tolstoy (1828-1910). Untuk puitika humanis, saya memilih sajak “I Sit and Look out”, karya Walt Whitman (1819-1892), yang terkenal sebagai “bard of democracy” atau penyair-pengumandang demokrasi.
I SIT AND LOOK OUT
I SIT and look out upon all the sorrows of the world, and upon all
oppression and shame;
I hear secret convulsive sobs from young men, at anguish with
themselves, remorseful after deeds done;
I see, in low life, the mother misused by her children, dying,
neglected, gaunt, desperate;
……………
I observe the slights and degradations cast by arrogant persons upon
laborers, the poor, and upon negroes, and the like;
All these—All the meanness and agony without end, I sitting, look
out upon,
See, hear, and am silent.
“Aku Duduk dan Mengamati”. Apakah yang diamati penyair? Penderitaan dunia, penindasan, dan tindak-memalukan; tangis orang-orang muda yang menyesali perbuatan nista; ibu yang disia-siakan anaknya, kurus-kering, sekarat, diabaikan, putus asa; tindak meremehkan dan merendahkan oleh manusia-manusia arogan terhadap para pekerja, orang miskin, budak berkulit hitam … Semua ini—semua tindak-keji dan siksa-derita tanpa ujung, kusaksikan dan kurenungkan. Aku lihat, aku dengar semuanya, dan aku hanya bisa terdiam, bungkam.
Penyair bungkam, tak berdaya. Maka ratap-tangis, hati yang nyeri, dan beban penderitaan manusia karena penindasan dan kekejaman menjadi semakin dalam mengiris. Puisi Whitman ini adalah gambaran luka Amerika abad 19. Namun, di pojok-pojok lain dunia ini, pada abad yang sama atau berbeda, penderitaan manusia tak pernah berhenti. Penderitaan karena nasib atau penindasan terus merajam hati penyair, dan melahirkan puisi luka atau sajak air mata. “The Cry of the Children”, karya Elizabeth B. Browning (1806-1861), adalah puisi nyeri, yang berisi kritik pedas terhadap eksploitasi buruh anak-anak selama Revolusi Industri di Inggris. “To the Poor”, terjemahan dari Aux Pauvres, karya Victor Hugo (18021885), adalah puisi protes terhadap pemerasan tenaga kerja miskin di komunitas urban di Perancis. Dan “To Our Land”, terjemahan dari Libilādinā, karya penyair Palestina Mahmoud Darwisy (1941-2008), adalah elegi, puisi ratapan atas kesaksian menghilangnya negeri Palestina, tanah air yang menyusut amat cepat (dalam waktu delapan dasawarsa) dan nyaris lenyap dari geografi Timur Tengah.
Indonesia pun menyimak sajak-sajak serupa. “Doa Orang Lapar” dan “Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta” karya W. S. Rendra, “Penangkapan Sukra” karya Goenawan Mohamad, “Negeri Amplop” dan “Negeri Haha Hihi” karya Gus Mus (panggilan akrab dari K. H. Ahmad Mustofa Bisri), “Sajak Suara” dan “Bunga dan Tembok” karya Wiji Thukul, dan “Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia” karya Taufiq Ismail—semua ini hanya sebagian kecil dari puisi-puisi protes, baik berupa sindiran halus maupun bentakan keras, yang menggugat ketidakadilan di Indonesia. Apakah sajak-sajak protes ini didengar oleh penguasa? Tak mudah menjawab pertanyaan ini. Karena kata “penguasa” mencakup ratusan pemimpin. Sebagian kecil mereka mau mendengar suara akar rumput, termasuk puisi protes. Tetapi sebagian besar tak mengenal puisi—bahasa yang berbelit-belit, plus nurani yang hampir atau telah mati.
Kembali ke puisi Whitman “Sit and Look out”, bagaimanakah sajak humanis ini digubah ulang oleh Ananda Sukarlan menjadi tembang puitik? Simak soprano Alice Cahya Putri di menit ke-7 video ini https://youtu.be/8wRD3nhEs4U?si=ttwPK1yLI2hG6V8b. Empati terhadap orang-orang lemah yang terhimpit, terhempas, dan tertindas mewarnai nada dan irama penampilan Alice. Ketika ia melantunkan baris terakhir See, hear, and am silent, ada jeda panjang. Makna “aku bungkam”—tak tahu dan tak mampu harus berbuat apa—tampil secara visual dan auditif.
Penutup, Sejumlah Catatan
Kini, marilah kita simak dengan cermat. Apakah ruh puitika dari sajak “Kukusan”, “Krawang-Bekasi”, dan “I Sit and Look out” hadir dengan napas estetik serupa ketika lahir kembali sebagai tembang puitik? Jawaban singkatnya: YA. Jawaban terperinci telah diberikan lewat tiga tautan YouTube sebagai hasil kolaborasi dengan Ananda Sukarlan. Ini berkat dokumentasi elektronik yang tertata rapi. Dari ratusan tembang puitik yang telah digubahnya, Ananda menempel (pada esai ini) tiga tautan video di YouTube itu dalam waktu kurang dari setengah jam. Karakteristik masing-masing tembang puitik tersebut, secara berurutan, telah disampaikan secara ringkas. Tiga tembang puitik ini adalah sampel, yang secara kuantitatif amat kecil namun secara kualitatif amat bermakna. Maksudnya? Dengan menyimak keberhasilan penerjemahan semiotik pada tiga tembang puitik tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh, setidaknya sebagian besar, tembang puitik yang digubah oleh Ananda Sukarlan merupakan karya seni unggulan.
Selanjutnya adalah apresiasi. Lewat esai kecil ini, saya menyampaikan penghargaan tinggi terhadap Ananda Sukarlan, sang pianis-komponis musik klasik. Para penyair di Indonesia, yang puisi-puisinya telah digubah ulang menjadi tembang puitik, mendapatkan keuntungan ganda. Pertama, puisi yang dipilih oleh Ananda Sukarlan jelas puisi berbobot; ia memiliki aesthetic power yang menggerakkan ruh kreativitas dalam diri sang komponis. Kedua, setelah puisi tersebut lahir kembali menjadi tembang puitik, daya jangkau seninya meluas—bukan hanya terbatas di ranah sastra, tapi juga menjangkau ranah musik klasik. Tambahan lagi, partitur tembang puitik tersebut bersifat universal dan permanen. Ingat, verba volant, scripta manen. (Kata-kata terbang, tulisan tetap ada.) Berdasarkan partitur tersebut, tembang puitik itu bisa dipentaskan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja.
Di bagian awal tulisan ini telah disebutkan bahwa Ananda Sukarlan adalah komponis langka. Ia salah satu dari tiga komponis tembang puitik di Asia; dan saat ini ia adalah satu-satunya di Indonesia. Yang lebih mengagumkan adalah kreativitasnya. Dalam durasi sekitar tiga puluh tahun, ia telah mencipta lebih dari 500 tembang puitik. Dan napas kreativitasnya terus mengalir deras. Telah disinggung sekilas bahwa 30 puisi dalam antologi I’m Not for Sale karya Emi Suy telah digubah ulang jadi tembang puitik. Bulan Oktober 2025 nanti, gubahan ini akan dipentaskan sebagai opera. Pementasan tembang puitik beraroma sejarah ini adalah contoh konkret hasil kolaborasi penyair dan komponis.
Saling menginspirasi antar-ranah seni gampang dimengerti. Yang indah selalu memancar dan mungkin saja terbit kembali sebagai keindahan baru. Puisi bisa jadi inspirasi bagi komponis, pelukis, atau koreografer. Pada gilirannya, sebuah lagu atau komposisi musik bisa jadi inspirasi bagi pelukis, cerpenis, atau desainer. Menghormati Ananda Sukarlan, saya ingin mengutip bait kedua dari puisi “Di Beranda ini Angin tak Kedengaran Lagi”, karya Goenawan Mohamad.
Di piano bernyanyi baris dari Rubaiyat
Di luar detik dan kereta telah berangkat
Sebelum bait pertama. Sebelum selesai kata
Sebelum hari tahu ke mana lagi akan tiba
Rubaiyat, himpunan puisi empat baris dari Persia abad 12 itu, berdenting pada tuts piano. Ada yang telah berangkat, dan ada yang terlambat—puisi yang tak selesai. Tapi esok pagi akan terbit matahari. Akan terbit tembang puitik dari jemari rindu Ananda Sukarlan, karena cahaya di dadamu, cahaya semarak yang melahirkan sekuntum sajak. [T]
Malang, 3 Desember 2024