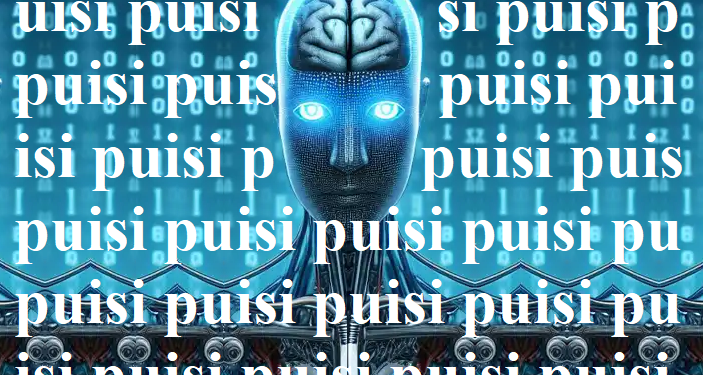DI dunia luas, puisi adalah ruang paling aman untuk sembunyi. Di dalamnya dinding-dinding terbuat dari sunyi, di luar hiruk pikuk kehidupan yang bising dan gaduh tengah dipentaskan. Saya melihat dan mendengarnya sendiri seperti seorang pengamat, tapi tentu saja bukan Tuhan.
Sebagai seorang perempuan penikmat puisi, saya menganggap bahwa berbicara melalui puisi adalah cara agar saya bisa menjahit luka sendiri, seperti yang pernah ditulis begawan penyair Umbu Landu Paranggi dalam sajaknya: //dengan mata pena kugali-gali seluruh diriku/dengan helai-helai kertas kututup nganga luka-lukaku/kupancing udara di dalam dengan angin tangkapanku/begitulah, kutulis nyawaMu senyawa-nyawaku// (“Upacara XXII”, 1978).
Dengan menulis puisi saya menciptakan waktu dari jam yang rusak, saya membuat “alarm sunyi” agar hati selalu terjaga, saya menjahit keadaan yang robek, serta perasaan yang bolong, saya menambal lubang-lubang kecewa dan terkatuplah semua.
Menulis puisi bagi saya adalah juga sebuah upaya memuliakan kehidupan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, mengatasi rasa tidak baik-baik saja seorang manusia yang daif dan rawan, demi menjaga kewarasan serta keseimbangan dalam hidup agar tidak mudah terpuruk dan ingin mengakhiri hidup, seperti kata penyair Subagio Sastrowardoyo: sajak ini melupakan aku kepada pisau dan tali/sajak ini melupakan kepada bunuh diri//.
Maka, puisi adalah anugerah yang amat besar bagi hidup kita. Hidup puisi dan kita manusia berhati. Puisi yang selalu memuliakan kehidupan kita yang fana ini, dan menjadikannya tetap abadi, setidaknya dalam kata-kata.
Puisi adalah milik semua orang, tidak dibatasi usia dan tanpa aturan atau tetek bengek lainnya untuk memasuki gerbangnya. Puisi senantiasa terbuka untuk mata kita berjalan menyusuri keindahan lanskap maknanya, dengan menghayati imaji-imaji sampai ke dalam lubuk rahasianya. Sedangkan menulis puisi adalah salah satu upaya kita memeluk diri sendiri dan memeluk orang lain dengan cinta yang murni.
Kata-kata yang dilahirkan oleh cinta di dalam puisi dapat mendekap dan menyentuh ruang batin orang-orang yang membaca serta mendengarkannya. Kekuatan kata-kata itu bisa menggerakkan jiwa mereka untuk sampai kepada makna khasnya masing-masing, dan membuat manusia mudah untuk menerima, bahkan takdir yang paling getir.
Ruang Batin itu Bernama Puisi
Puisi sebagai ruang sunyi tidak mungkin dihayati oleh mesin, dan puisi sebagai tempat bersembunyi si “aku lirik” tidak mungkin digantikan oleh “aku algoritma”, sebab algoritma tidak punya ke-aku-an, tidak punya kehendak. Puisi sebagai ruang sunyi, yaitu ruang yang sarat dengan perenungan dan permenungan, mustahil menjadi sarang hampa tanpa perenungan dan permenungan. Sebab robot tidak mungkin memiliki perasaan untuk melakukan kedua hal tersebut. Pendek kata, puisi adalah “ruang batin” bukan “ruang mesin”.
Puisi sebagai cermin, sebagai mozaik, sebagai instrumen, sebagai music, sebagai puzzle, sebagai alarm, sebagai embun, sebagai alam raya, sebagai sari pati kehidupan, sebagai jembatan, sebagai jalan sunyi, sebagai arus deras sungai yang menghayutkan, tidak mungkin hidup dalam “alam mesin” yang hanya dihuni oleh angka-angka dan kalkulasi tanpa penghayatan, hanya memori yang berputar-putar dalam pola yang telah ditentukan. Puisi akan tetap hidup di alam murni tanpa manipulasi, puisi akan tetap ditangkap oleh hati bukan segumpal kabel.
Puisi sebagai apa yang kita pikirkan, tidak mungkin dimengerti oleh mesin yang hanya dilatih untuk menghitung. Pikiran kita yang dipenuhi kenangan, tidak bisa ditiru oleh mesin yang tidak memiliki kesadaran.
Mesin adalah proyeksi pikiran matematis tanpa subjek dan kehendak, ia tidak punya kimia seperti manusia, yang bisa merasakan sedih dan suka secara mendalam dan kompleks. Apa yang disebut AI, bisa diumpakan seperti jam dinding yang tidak pernah akan menyimpan satu pun kenangan tentang temu dan perpisahan, bahkan dalam sehari pun tidak, apa yang terjadi di dalam tubuh manusia tidak akan benar-benar terjadi pada tubuh mesin yang paling canggih sekalipun.
Puisi: Seni yang Tak Bisa Beku
Puisi adalah bentuk seni berbahasa yang telah ada selama berabad-abad. Sebagai contoh; di Yunani, para filsuf lebih dulu mempelajari puisi Homeros (penyair yang mengarang Illiad dan Odyssey, karya puisi epik yang menjadi fondasi sastra Yunani kuno), sebelum beranjak ke filsafat dan sains. Bahasa terus berkembang dari sejak puisi pertama ada; mantra, pantun, nyanyian sampai sekarang ketika puisi hendak disaingi oleh teknologi. Penyair sebenarnya (tukang puisi) terus mengembangkan bahasa di dalam puisi, sedangkan “penyair sebagai mesin” hanya mengulang-ulang apa yang usang, kemudian menyusun-nyusunnya ke dalam bentuk yang bukan cuma mudah retak, tetapi yang tidak pernah berbentuk; seperti pecahan kaca dan gelas yang hendak disatukan jadi satu. Itu artinya AI tidak bisa melakukan penciptaan bahasa seperti manusia, dan tanpa manusia AI hanyalah seonggok perangkat yang tidak kreatif dan tidak akan pernah produktif.
Puisi membuat bahasa manusia menjadi kaya, sedangkan mesin tampaknya hanya membuat bahasa manusia menjadi semakin miskin, contohnya; kita saat menggunakan internet akan bertemu dengan istilah-istilah yang sama, teknis, kaku dan beku. Puisi mencairkan suasana kebekuan itu, membuat keberagaman kembali tumbuh, membuat manusia menjadi utuh, puisi menolak keseragaman juga ketercerai-beraian.
Bahwa puisi begitu penting dalam kehidupan ini, jelas telah tercatat dalam sejarah bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sebelum adanya teknologi canggih seperti sekarang, puisi seperti pantun sudah digunakan rakyat Melayu sebagai alat perlawan terhadap kekuasan raja yang lalim. Bahkan, di Aceh dulu, Hikayat Perang Sabil yang ditulis dalam bentuk syair, telah membuat penjajah kolonial Belanda kelabakan hingga harus melarang kitab syair tersebut beredar dan dibacakan di majlis-majlis perkumpulan, sebabnya setiap orang yang membaca dan mendengar syair tersebut dibacakan, besoknya pasti ada ditemukan orang Belanda yang terkapar karena tertusuk keris atau bambu runcing.
Meski dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda, syair itu sudah telanjur dihafal di luar kepala oleh rakyat Aceh, dan dituturkan dari lisan ke lisan. Dengan begitu, puisi terbukti dapat meningkatkan kesadaran tentang arti “merdeka” dan “kemerdekaan”.
Puisi mampu meningkatkan empati serta pengertian kita terhadap sesama makhluk, bukan hanya kepada manusia, tetapi binatang, tumbuhan, juga benda-benda diam. Puisi memiliki kekuatan untuk menyentuh kepekaan hati dan pikiran kita, mempunyai kekuatan sebagai media untuk mengekspresikan diri dengan cara yang unik, bisa membuat katarsis, bahkan revolusi.
Saya teringat Seno Gumira Ajidarma pernah mengatakan, “Setiap kali ada orang Indonesia menulis puisi, kita harus bersyukur, karena kalau toh ia tidak berhasil menyelamatkan jiwa orang lain, setidaknya ia telah menyelamatkan jiwanya sendiri. Puisi memang tidak bisa menunda kematian manusia yang sampai kepada akhir hidupnya, tapi puisi jelas menunda kematian jiwa dalam diri manusia yang masih hidup.”
Puisi, Saya & Sunyi yang Nyaring Sekali
Bahwa sejatinya puisi juga sebagai penjaga peradaban dan harus masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan yang beragam. Puisi adalah penggugah batin untuk semua lapisan masyarakat. Puisi dapat dibacakan di depan anak-anak pemulung yang hidup di antara timbunan sampah, anak-anak nelayan miskin di pesisir, bisa dibacakan di pinggir jalan ngamen untuk penggalangan dana sosial, di festival sastra nasional maupun internasional, di coffee shop dan cafe-cafe, di alun-alun berbaur dengan masyarakat, di gedung-gedung kantor pemerintah yang megah, di gedung-gedung kesenian dan kebudayaan yang berkelas, di depan hadirin rapat para petinggi bisnis dan pemerintahan, di hotel berbintang yang elit, bahkan di ballroom dengan konser piano klasik yang ekslusif.
Puisi telah masuk ke dalam ruang publik, puisi tidak hanya ditulis di buku catatan harian dan dibacakan kepada diri sendiri sebelum terlelap dan bermimpi. Puisi telah dicoba dengan berbagai cara, menjelma ke dalam aneka media dan wahana, melalui medium-medium tanpa kata, melalui mesin dan algoritma. Puisi bukan sekedar menjadi hasil dari kebudayaan, tetapi telah menjadi budaya, khususnya marak di perkotaan, di desa mungkin segelintir ada.
Ya, puisi milik semua kalangan dari seluruh lapisan masyarakat, maka sampaikanlah kepada semua orang di sekeliling kita, bahwa puisi milik segala yang ada dan bagi tiada. Puisi berhasil menggugah rasa kemanusiaan kita, karena puisi adalah potret sekaligus lukisan kehidupan. Puisi adalah kristalisasi pemikiran, perenungan, permenungan dan olah rasa. Puisi adalah tempat yang indah untuk tersesat di “Jalan Sunyi” yang akan selalu mempesona, seperti yang ditulis penyair Pelopor Angkatan 45, Chairil Anwar; “Nasib adalah kesunyian masing-masing.”
Seseorang pernah bertanya kepada saya kenapa saya suka sekali pada sunyi. Saya hanya tersenyum waktu itu, tersenyum sunyi. Bagi saya, sunyi itu inti, di mana kita berasal dan kembali. Dalam sunyi, saya merasa segalanya menjadi terbuka; jalan, pesan, dan tujuan. Sunyi adalah kunci untuk membuka pintu sejati makna.
antara sunyi & puisi
mana lebih bunyi
sepi atau sunyi?
dari sunyi ke sunyi
segala nyaring sekali
memuncak hening
segala merdu
segala rindu
di dasar kalbu
terbuat dari suara
dalam kepala bergema
perasaan berloncat
— berlarian ngejar makna
bagai jari jemari
di antara tuts-tuts piano
berdenting lagu
dalam alun musik klasik
Saya masih ‘berasyik-masyuk’ dengan sunyi. Saya masih menyukai “sunyi” sebagai sumber ide penciptaan puisi. Puisi-puisi saya hampir semua sibuk melulu “ngurusin” perkara (ke)sunyi(an), dengan menggali-gali berbagai kemungkinan bentuk dan makna sunyi yang terkandung di dalamnya.
Makna sunyi itu menjadi lebih mewah dan menyala bagi perempuan pada umumnya, khususnya di Indonesia. Untuk mengalami dan merasakan esensi sunyi, tentu tiap orang berbeda-beda. Sebagian perempuan mungkin memaknai sunyi sebagai upaya untuk bisa menziarahi labirin dirinya yang rahasia. Sebagian perempuan lainnya, terlebih yang berstatus istri, ibu, atau – sekaligus – buruh, mau tak mau harus jungkir balik menebus waktu, menembus partisi-partisi kesunyian demi menjaga bangunan kehormatan diri dan keluarga tetap kokoh.
Dengan segenap kekuatan berusaha menjadi wonder woman di saat dihadapkan pada situasi-situasi kerja yang tak mudah, kemudian mengurus rumah dan keluarga. Namun, sekuat-sekuatnya perempuan ada kalanya berada dalam titik puncak penat dan lelah; fisik maupun psikis. Saya pribadi merasa sunyi sebagai hal yang mutlak diperlukan setiap orang, terlebih bagi diri saya sendiri, yang memang sengaja menyesatkan diri di “Jalan Sunyi”. Dalam lingkungan hidup sehari-hari yang bising dan asing, bisa menemukan dan merasakan kesunyian adalah sesuatu yang mewah bagi saya.
Tanpa sunyi, kita tak punya ruang-waktu untuk bercermin, kita tak punya ruang-waktu untuk mengenal diri sendiri. Kita kehilangan ruang-waktu untuk mendengarkan dan merasakan aliran napas sendiri. Kita dari hari ke hari semakin jauh dari diri kita sendiri, semakin merasa asing, seperti kata penyair besar WS Rendra dalam sajaknya yang berjudul “Seonggok Jagung di Kamar”: /ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata:/“Di sini aku merasa asing dan sepi!”//.Dengan demikian, “Ayat Sunyi” ini merupakan ruang waktu tersendiri, di mana saya bisa menemukan kesunyian, barangkali juga pembaca yang tidak pernah saya kenal.
Kesunyian pada sebuah tempat, ternyata tidak hanya sebagai gateway atau pintu gerbang yang dicari-cari banyak orang untuk melarikan diri dari rutinitas, tapi juga mampu membuat otak jadi lebih sehat. Di dunia yang penuh dengan keriuhan dan kebisingan, tawaran tempat yang sunyi, segar dan asri, seketika menjadi sebuah manifestasi wisata yang sangat menarik.
Menulis puisi sunyi di tempat sunyi dalam situasi dan kondisi sunyi adalah hal terindah yang pernah saya lakukan. Selain mengobati diri saya sendiri, setidaknya kelak menjadi ‘jejak’: raga boleh tiada, usia boleh usai, namun puisi tak pernah mati dan selesai.
Itulah puisi yang lahir dari kedalaman rasa dan kalbu manusia. Menurut saya, puisi lahir karena manusia punya rasa, kalbu, kedalaman batin, respon kepada lingkungan, dan bukan puisi kalau hanya merespon dirinya sendiri, seperti “puisi mesin” yang sedang ramai akhir-akhir ini.
“Puisi Mesin” yang Belum Sampai Batas “Mungkin”
Saat ini aplikasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin marak, bahkan sudah tersedia fitur untuk berbagai bidang dalam kehidupan, termasuk dunia kesenian, yang paling terkenal di masyarakat awam adalah ChatGPT. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang mampu membuat puisi atau poem generator memberikan tantangan kepada dunia perpuisian serta kepenyairan, mulai dari tantangan teknis, sampai kepada hal yang fundamental, yaitu tantangan filosofis dan etika. Inilah yang harus dijawab bersama.
Pakar teknologi digital, Riri Satria, mengatakan bahwa kita tidak lagi pada porsi menahan lajunya perkembangan teknologi, melainkan menyikapi perkembangan teknologi dengan arif dan bijaksana, dan tentu saja dengan pemikiran dan catatan kritis, termasuk dalam dunia perpuisian dan kepenyairan.
Nah, pertanyaan mendasarnya adalah; apakah “puisi mesin” yang dibuat oleh algoritma kecerdasan buatan itu adalah puisi? Atau hanya kemungkinan puisi yang masih belum sampai batas “mungkin”? Secara struktur bangunan boleh dikatakan sebagai mirip puisi, namun secara lebih mendalam ke lapis-lapisnya; olah rasa, olah pikiran tidak ada, jelas itu bukan termasuk ke dalam puisi yang dipahami selama berabad-abad lewat sejarah sastra. Mengapa? Sebab, puisi yang dihasilkan oleh AI adalah text yang disusun dengan menggunakan algoritma yang sangat matematis tanpa melibatkan olah rasa sama sekali. Padahal, untuk memilih diksi tidak mungkin mengabaikan apa yang disebut “rasa” itu, karena di sinilah letak estetika puisi.
Saya sendiri sudah menggunakan aplikasi AI untuk melakukan eksperimen membuat puisi, salah satunya ChatGPT. Saya memasukkan kata kunci lewat prompt ChatGPT, dan dalam hitungan detik, jadilah sebuah puisi. Namun, puisi yang dihasilkan oleh AI itu garing (dangkal), saya mengumpakannya seperti robot. Hasil buatan teknologi mesin dengan pemrograman digital yang sangat matematis. Ia mungkin dibuat mirip seperti manusia, misalnya, seorang perempuan cantik. Ia bisa melakukan pekerjaan manusia yang diperintahkan melalui program-program yang terpola.
Namun, robot tidak punya hati untuk merasakan, tidak punya pikiran walaupun nampak cerdas, mungkin ingatan robot bekerja lebih baik dari kebanyakan kita, tetapi tetap tidak sekompleks ingatan manusia, sebab robot tidak hidup di dalam keseharian dan tidak mengantisipasi kehidupan, sedangkan manusia bergulat setiap detik dengan kehidupannya. Robot hanya bekerja dibawah kendali sensor. Begitu pun dengan puisi yang dihasilkan oleh AI (kecerdasan buatan), puisi itu akan garing, tidak ada rasa dan tidak ada ruhnya sama sekali.
Maraknya penggunaan AI ke dalam berbagai bidang, dikhawatirkan akan bisa menggantikan profesi-profesi yang kini dijalankan oleh manusia, istilahnya robotisasi. Untuk itu, para penulis (termasuk penyair) harus pandai meningkatkan kapasitas diri agar tidak tergantikan AI. Penyair harus menjadi referensi untuk AI, bukan sebaliknya, di mana AI jadi referensi untuk penyair. Tapi sebenarnya jika kita melihat cara kerja AI, mereka hanya menggunakan bahan-bahan yang ada, dan itu artinya membuat karya baru pun hanya dari bahan-bahan yang ada. Penyair sangat mungkin bekerja lebih kompleks daripada robot, sebab tak ada yang sekompleks rasa, bukan?
Memang para penyair harus meningkatkan kapasitas diri atau meng-upgrade diri seiring perkembangan zaman. Kita harus semakin terampil. Jika AI bisa menciptakan puisi, maka dalam proses peciptaannya tidak sama seperti proses kreativitas atau perenungan batin manusia yang mendalam. Ini yang tidak bisa ditiru oleh AI. Kita tidak boleh tergilas zaman dan kenyataan, bahwa zaman semakin canggih, iya, tetapi kita tidak boleh tersisih. Bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut untuk berkarya lebih dahsyat, sehingga karya manusia tidak tergantikan.
Kembali kepada pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini, apakah sebuah “puisi” yang dihasilkan oleh AI itu sebuah puisi? Atau hanya kemungkinan yang belum sampai batas “mungkin”? Saya kira, jawaban kedua adalah kenyataannya.
Jika kita melihat kepada definisi puisi, maka menjadi jelas bahwa puisi itu lahir dari olah rasa dan kedalaman batin manusia, bukan dari perhitungan angka, memilih diksi yang kuat tidak mungkin dilakukan oleh pertimbangan matematika, tetapi oleh pertimbangan rasa yang dalam. Maka, saya pribadi dengan tegas mengatakan bahwa hasil AI itu bukanlah puisi. Itu hanyalah teks yang menyerupai puisi, namun tidak akan pernah memiliki ruh sebagai puisi.
Jika teknologi sudah mampu membuat humanoid atau robot yang menyerupai manusia, maka tetap saja itu bukanlah manusia, melainkan sesuatu yang menyerupai manusia, namun tidak memiliki apa yang esensial ada pada manusia, terutama kalbu.
Demikian pula dengan puisi. Saya tetap berpegang teguh pada prinsip, bahwa puisi itu memiliki ruh yang dihasilkan oleh olah rasa dan kontemplasi kedalaman batin manusia, bukan oleh kalkulasi matematis dari rumus algoritma.
Jakarta, Januari 2024