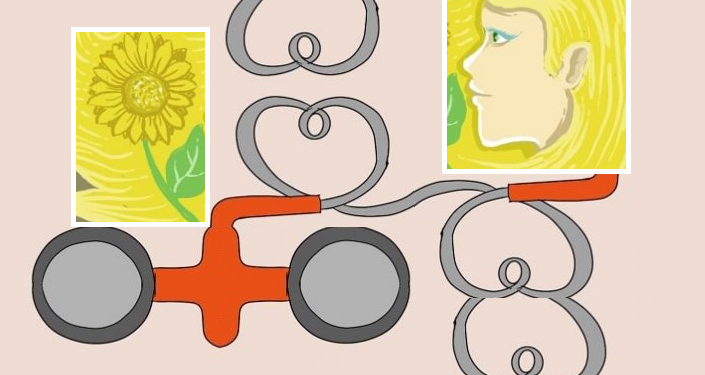Deru motor mengacaukan pikiranku. Kuas yang tadinya ingin kuusapkan pada sketsa berbentuk bunga, malah menyapu zona langit. Aku berdecak. Kesal setengah mati pada pemilik motor tua yang tinggal bersebarangan denganku. Tubuhku bangkit untuk melihat sosok dengan motor tua itu. Dari jendela kamar, dapat kulihat laki-laki berusia 70 tahunan memasuki rumahnya. Aku tahu betul suara motor itu. Motor tua berwarna biru langit, dengan suara yang bising, mengingatkanku pada seseorang yang menuntutku untuk menghabiskan waktu memikirkannya.
Sekitar lima tahun yang lalu, saat itu, seorang lelaki mengantarkan sup jamur buatan ibunya. “Hai. Ibuku memasak sup jamur cukup banyak hari ini, kami tidak bisa menghabiskannya berdua saja. Jadi, tolong diterima,” katanya sembari mengulurkan tangan yang memegang satu mangkuk besar berisi sup.
Aku menerimanya tanpa ragu.
“Oh, iya. Perkenalkan, namaku Akiro. Aku tinggal bersama ibuku di seberang rumahmu. Salam kenal,” sambungnya.
Aku melirik sebentar ke arah bangunan yang sebelumnya tidak berpenghuni. Rumah itu membuatku takut saat malam hari karena tak ada cahaya yang muncul dari dalamnya. Persis seperti bangunan yang ada di film horor.
“Aku pamit dulu, permisi.”
Akiro berbalik dan bergegas pulang. Padahal aku belum menyebutkan namaku, Akiro juga tidak bertanya. Ya sudah., mungkin lain kali kami bisa berkenalan dengan benar.
Keesokan harinya, aku mendengar suara motor tua yang tak asing di telingaku. Suara itu semakin lama semakin kencang. Saat itu, aku sedang tergesa mengaitkan tali sepatuku di samping pagar rumah. Tatkala aku mendongak, kudapati Akiro menggunakan seragam yang sama denganku.
“Ternyata kita satu sekolah. Kau mau berangkat bersamaku?” ujar Akiro.
Aku mengamatinya yang menaiki motor tua dengan kepulan asap dari knalpot.
“Tidak usah. Aku berangkat sendiri saja,” tolakku halus.
“Ah, tidak apa-apa. Jangan sungkan.”
Tepat setelah itu, ibu berteriak dari dalam rumah agar aku menerima tawaran Akiro. Alasannya biar tidak lelah jalan kaki. Canggung rasanya kalau harus berdua saja dengan orang yang belum lama dikenal. Alhasil dengan sedikit paksaan dari ibu, aku membonceng di belakang Akiro.
“Aku belum tahu namamu,” kata Akiro.
“Apa?!” teriakku di sela-sela keramaian jalan raya. Sebenarnya tidak perlu berteriak kalau motor Akiro bukanlah motor tua dengan suara bising. Wajar saja bila kami harus menaikkan suara beberapa oktaf agar terdengar satu sama lain.
“Kubilang, aku belum tahu namamu!”
“Oh, aku Yasena. Panggil Sena saja!”
Hari-hari berikutnya, Akiro selalu menghampiriku untuk berangkat ke sekolah bersama. Menaiki motor tua dengan tingkat kebisingan yang teramat sangat. Butuh waktu lama untukku bisa beradaptasi dengan itu. Setiap berangkat atau pulang sekolah, aku selalu menggerutu dalam hati. Suara motor Akiro sangat nyaring, membuat kami mencolok di area jalan raya. Kadang seseorang mengumpati kami karena asap motor Akiro yang memenuhi jalanan. Mengapa Akiro bisa punya motor seperti ini? Gemas rasanya, ingin kukatakan pada Akiro untuk mengganti mesin atau sekedar knalpotnya saja. Namun, kuberi saran pun sepertinya percuma.
“Motor ini milik penghuni lama. Kata ibu, tidak apa-apa dipakai,” ujar Akiro saat kami tengah berhenti di sebuah halte bus.
Siang itu, hujan turun sangat deras. Jadi, karena kami tidak membawa mantel, kami harus berteduh agar tidak kehujanan. Akiro memberiku jaket yang dikenakannya. Aku sempat menolak, tapi dia memaksa.
“Pakai saja. Aku tidak mau kau sakit. Nanti aku yang dimarahi ibumu.”
Begitu banyak kisah yang tidak dapat dituliskan atau bahkan diungkapkan dengan kata. Di atas motor, Akiro akan bercerita banyak hal. Mengenai dirinya yang disukai oleh banyak teman perempuannya, mengenai dirinya yang tidak suka makanan pedas, tidak suka buah pepaya, dan lain-lain. Cerita itu, disampaikan Akiro dengan setengah berteriak tentunya. Mengobrol ala kami sangatlah berbeda, bukan?
Hingga suatu hari sepulang sekolah, Akiro mengatakan suatu hal yang membuatku terpukul.
“Sena, setelah lulus nanti, aku akan pindah. Kau tahu sendiri kampung halamanku adalah Jepang, kan? Kurasa, aku akan kembali kesana. Sudah bertahun-tahun aku dan ibu berkelana di Indonesia.”
Aku memilih untuk pura-pura tuli, pura-pura bisu, dan pura-pura buta. Bahkan jika boleh aku ingin pura-pura mati. Selama itu, tatkala aku hanya bisa melihat punggung Akiro yang bercerita banyak hal di atas motor, aku menyadari sesuatu. Aku tidak ingin kehilangan Akiro.
“Apakah kita masih bisa bertemu lagi?” tanyaku pada Akiro.
“Masih. Biarkan takdir yang bekerja.”
Di atas motor tua itu, aku merasakan getir perpisahan dengan Akiro. Kukira aku dan Akiro akan selamanya berada di sini. Bersama-sama dalam waktu yang lama, membuatku benar-benar terikat dengannya. Seharusnya aku tahu, Akiro tidak pernah main-main dengan ucapannya. Namun aku bodoh dengan menganggap itu sebagai lelucon. Terang saja, setelah acara kelulusan itu, rumah seberang sana tidak berpenghuni lagi.
Ketika hari telah berganti, tak kudapati Akiro dengan motor tuanya di depan rumahku. Payah sekali Akiro tidak meninggalkan nomor telepon, alamat surel, atau apa pun yang bisa menjadi media untuk kami berkomunikasi. Bahkan dia tidak mengatakan kota mana yang menjadi persinggahannya di Jepang. Mengingat itu, aku merutuki diri sendiri. Mengapa aku tidak pernah bertanya pada Akiro? Aku hanya membiarkan dirinya bercerita sambil berteriak di atas motor tanpa kutahu bagaimana raut wajahnya saat itu.
Beribu penyesalan menguasai diriku. Semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hingga pada suatu pagi aku mendengar suara motor tua itu kembali, aku bergegas melihat ke depan rumah. Mana tahu Akiro datang kemari. Tapi naas, yang kulihat hanya seorang pria tua—yang bernama kakek Mahmud—dengan motor itu. Rupanya rumah seberang telah ditempati oleh orang lain.
Setiap hari aku harus mendengarkan suara motor tua yang dikendarai oleh kakek Mahmud. Kalau aku beruntung, aku bisa melihatnya berboncengan dengan istrinya. Benar-benar mengingatkanku pada Akiro. Bagaimana kabarnya? Saat ini tengah bekerja atau melanjutkan pendidikan?
Semua hal tentang Akiro begitu saja terlintas dalam benakku. Berjatuhan layaknya air yang turun saat musim penghujan. Bersama itu, aku memiliki keinginan untuk menyusul Akiro. Setelah aku meraih gelar sarjana, aku akan mencari Akiro dengan dalih melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Keinginan itu bertumbuh seiring dengan deru motor tua yang kudengar setiap harinya.
Madiun, 2 Juli 2022
_____