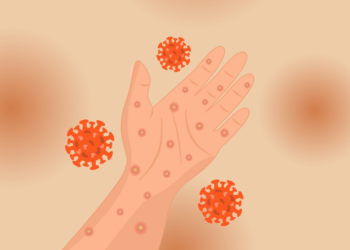Adikku Nohan tak pernah berhenti mematuk-matukkan jemarinya ke layar ponsel. Bocah empat belas tahun itu sesekali menggoyang-goyangkan ponsel putihnya, lalu memiring-miringkannya. Dia pergi ke halaman, menjulurkan lengannya sambil menggenggam ponsel, berlagak seolah sedang mengintip sesuatu yang menyelinap di balik tanaman pagar.
Itu adalah hari ketiga setelah dia mulai kerasukan jin ponsel. Dia berceloteh sendirian dengan ponselnya, lalu marah-marah. Sudah ratusan kali aku mendengar suara ting tong,—atau jenis suara apalah namanya—keluar dari ponsel itu, dan tatkala itu terdengar, Nohan akan menelantarkan makan siangnya.
“Ibu berjanji. Sekali lagi kau menyisakan makan siangmu, kami akan mengirimmu ke Zimbabwe!” omel ibu suatu hari saat ia memergoki bekas gigitan bocah kelas 9 itu di separuh potongan kentang di piring makannya, terselip di antara tumpukan nasi.
Namun aku yakin walaupun dia dikirim ke Afrika, Nohan akan terbiasa hidup bersama hewan-hewan liar karena setiap hari kerjanya hanya mengendap-endap, menodongkan ponselnya ke arah pohon cemara, membuntuti mobil tetangga, menaiki tembok rumah dan mengejutkan kucing Bu Monez yang sedang bermalas-malasan di singgasana sofa-nya.
“Untuk naik level, aku harus menemukannya di tempat lain!” celetuk adikku. “Chloromon adalah monster langka berbintang lima!”
Aku menghela napas dan melenguh bagaikan seekor kuda nil yang bosan. “Anggap saja aku seekor monster dan tangkap aku dengan ponselmu. Aku monster bintang sepuluh.”
“Kak, ini seru!” Nohan mengalihkan pembicaraan.
“Semua orang tidak suka dengan tingkahmu yang seperti orang gila,” letupku. “Tak bisakah kau hidup normal dan menghabiskan sisa kentangmu?”
Nohan memiringkan telinganya dan mengangkat alisnya. “Hidup normal tanpa game GPS?” baliknya. “Bukankah jauh lebih tidak normal bahwa ada manusia di abad 21 yang sibuk dengan buku-buku tetapi tidak tahu yang namanya GPS?”
Dia menyindirku. Aku tahu. Suatu hari aku bertanya apa itu GPS kepadanya. Aku jurusan antropologi, jadi aku lebih hapal daftar nama prasasti daripada teknologi.
Dan setelah pertengkaran kami yang singkat itu, aku tidak pernah lagi melihat Nohan. Saat itu Rabu sore. Dia menyambar sepeda motornya sepulang sekolah dan pergi tanpa pamitan. Ayah meneleponnya berkali-kali namun tak pernah diangkat. Kami semua sudah bisa memastikan bahwa dia sedang menangkap monster-monster nyentrik di jalanan dan mengurungnya dalam ponsel. Jadi, saluran telepon sedang sibuk karena dipenuhi raungan monster-monster ganas.
“Jika dia pulang nanti, ponselnya akan kukunci dalam brankas selama-lamanya!” ayahku geram. Tadi siang ia menerima telepon dari sekolah bahwa game berbasis GPS dilarang di lingkungan sekolah sehingga orang tua wajib mengingatkan anak-anak mereka. Betapa tidak, sudah banyak kecelakaan dan musibah yang terjadi karena orang-orang sibuk menangkap monster yang bersembunyi di berbagai pelosok kota. Menurut berbagai komentar, monster-monster virtual itu bisa menyeberang jalan, mengintip dari rak baju, bergelayutan di pepohonan, bahkan berenang di air.
Sumpah. Aku tak pernah melihat satu pun batang hidung monster itu di mana pun dengan mataku sendiri.
“Ibu akan memanggang ponsel itu besok,” ibu berseru dari balik pintu. “Nohan sudah keterlaluan.”
Kemarin sepulang kerja, aku melihat seorang lelaki berjalan di pematang sawah sambil menodongkan ponselnya. Dia menginjak-injak beberapa rumpun padi lalu tiba-tiba berteriak kegirangan. Monster itu telah tertangkap dan masuk ke ponselnya.
Teman-teman di kantor menawariku untuk mencoba bergabung dalam tim pencari monster. Mereka membentuk tim pemburu dan berbagi hasil buruan,—begitulah. Well, jika aku diundang untuk sekadar mencicipi sepotong kue pia cokelat buatan Pak Robert di rumahnya, aku pasti akan membawa kaleng untuk membungkus hingga sepuluh potong, tetapi hari itu Pak Robert malah menawariku menjadi wakil ketua tim pemburu monster yang mencari buruan virtual di mana pun, termasuk ke tempat-tempat ekstrem seperti atap gedung, pangkalan militer dan Area 52.
“Game-nya seru banget lho, Rohan!” Pak Robert mulai lagi,—belum sebulan sejak ia berkata kepadaku, “Kue pia cokelat buatanku enak banget lho, Rohan!”
Jadi dengan kata lain, aku akan menjadi seperti Nohan. Bedanya, aku punya pangkat sebagai asisten ketua pemburu, sedangkan Nohan berstatus pemburu ilegal.
Sebuah mimpi buruk. Untung beberapa hari setelahnya kepala kantor memasang pengumuman yang mempensiunkan semua pemburu monster di kantorku dengan sedikit rasa hormat dan prihatin. Sungguh bijak.
Malam tiba. Ibu tak bisa menyentuh sebutir nasi pun, dan ayah termenung di kursi kerjanya sambil memutar-mutar ponselnya. Sudah puluhan kali ayah mencoba menghubungi Nohan, dan aku yakin tekanan darahnya mulai naik. Dia harus menenangkan diri.
Aku berpikir untuk mencarinya dan bertandang ke rumah-rumah pemburu monster lainnya yang seumuran dengannya. Namun mereka terlalu banyak dan dia bisa ada di mana saja,—termasuk di hutan belantara.
Tatkala aku mencoba bicara untuk menenangkan ayah, seseorang berseru dari arah depan rumah.
Bibi Yonita. Wanita setengah gemuk itu menyeret kakinya yang tembam ke pintu rumah kami. Ia berkata histeris dengan wajah belepotan bahwa anaknya, Rheyya, belum menunjukkan tanda-tanda pulang.
“Dia tidak pulang dari siang tadi,” bibi Yonita memasang wajah cemas bukan kepalang. “Aku takut seekor monster telah menyergapnya. Dia berpesan pada suamiku bahwa dia pergi berburu monster siang tadi. Aku samasekali tak habis pikir apa makhluk-makhluk itu benar-benar sedang menyerang kota dan memangsa anak-anak?”
Ibuku melotot menahan tawa. Gaya bicara Bibi Yonita memang tak pernah kelihatan serius. Jika seandainya dapurnya terbakar dan dia minta tolong, tak akan ada yang percaya. Semua orang bakal menganggapnya sedang melucu.
Tetapi kami semua tahu bahwa kekhawatiran kami sangat-sangat beralasan. Rheyya, Nohan, dan mungkin anak-anak lain sebayanya belum pulang hingga saat itu.
Kami memutuskan menelepon polisi pada pukul 10 malam karena hingga saat itu tak ada balasan apa pun dari Nohan atau Rheyya. Polisi datang beberapa belas menit kemudian. Dua orang polisi menyambangi rumah kami dan menanyakan identitas dan meminta foto Nohan. Bibi Yonita memberikan keterangan yang sama tentang hilangnya Rheyya.
Aku mendengar suara ting-tong dari saku salah seorang polisi. Suara ting-tong yang persis sama dengan punya Nohan. Lalu konsentrasiku buyar lagi.
Nohan tak kembali hingga pagi. Ibu tidak masuk kantor dan menangis tanpa henti. Ayah menelepon sekolah dan menanyakan apakah Nohan sudah tiba di sekolah.
Jawabannya belum. Malah, pihak sekolah melaporkan ada sampai seratus anak yang tidak masuk hari itu dan dinyatakan hilang oleh orang tua mereka.
“Gawat,” ayah menutup telepon sambil bermuram durja. “Dunia kiamat. Anak yang hilang terlalu banyak.”
Aku masuk kantor agak terlambat karena harus menenangkan ibu agar tidak berpikir konyol bahwa lusinan monster sedang menginvasi kota dan memanggang anak bungsunya untuk sarapan.
Di kantor, aku melihat kepala kantor mondar-mandir di resepsionis dengan wajah merah padam.
“Maaf saya terlambat, Pak,” sambutku.
Kepala kantor bergegas mendekatiku, mencekal lenganku dan menatapku dengan wajah ngeri. “Saya pikir kau juga bolos, Rohan!” bentaknya lirih. “Ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak ada yang masuk kantor hari ini. Semuanya lenyap tak berbekas.”
Aku menghela napas dengan sangat berat sambil memandang sekeliling. Semuanya sepi. Tidak ada Pak Robert, tidak ada pegawai yang berjaga di resepsionis, dan tidak ada orang-orang berlalu-lalang. Aku menyambar sebuah remote televisi di meja tamu dan menyalakan televisi.
Seluruh dunia sedang gempar. Ribuan orang menghilang tanpa bekas setelah memainkan game monster virtual itu. Polisi tidak dapat menemukan jejak apa pun mengenai siapa penculik ribuan orang itu dan apa motif mereka.
Setelah mengusulkan agar kantor benar-benar ditutup walaupun tanpa arahan dari pemerintah, saya dan kepala kantor bergegas pulang untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari serbuan monster-monster yang tak kasat mata tetapi berkeliaran. Tampaknya serbuan itu benar-benar nyata. Buktinya, orang-orang dewasa juga turut hilang. Kepala kantor punya tiga anak, dan ia tak mau terlambat menyelamatkan mereka. Ia mengatakan kepadaku bahwa ia akan meremukkan ponsel-ponsel itu dengan sepatunya sebelum anak-anaknya lenyap disantap monster-monster.
Ayah meneleponku di jalan. Ia berkata bahwa aku harus segera berbalik arah dan menemuinya di tempat praktik Tuan Hualachi, seorang paranormal terkenal di kota kami.
“Mengapa harus ke paranormal?!” desisku. “Ini tidak ada sangkut pautnya,—“
Sambungan terputus. Itu pertanda bahwa ayah tak mau kompromi.
***
Di kediaman paranormal itu, aku beringsut di antara kerumunan orang-orang yang antri untuk mengkonsultasikan masalah yang sama,—anggota keluarga mereka menghilang tanpa jejak. Ada sekitar lima puluh orang dari keluarga-keluarga yang berbeda-beda dan dari kota-kota yang berjauhan menunggu giliran untuk menanyakan di mana lokasi sanak kerabat mereka yang menghilang. Tatkala aku tiba di baris terdepan, beberapa orang malah baru saja datang dan mengantri di barisan paling belakang.
Sambil menunggu antrian, aku memperhatikan gerak-gerik paranormal itu dan apa petunjuknya kepada orang-orang yang mendapat giliran lebih dulu.
“Aku adalah arwah Onyx!” paranormal itu mulai kerasukan dan meliuk-liuk seperti ular. Dia kelihatan begitu menghayati gerak-geriknya. Begitu natural. Begitu nyata dan mistis.
Aku sedikit terpana.
Kemudian, pada giliran berikutnya, arwah bernama Poison Ivy merasuki paranormal itu, lalu berturut-turut arwah bernama Lalamon, Ogress, Golemn, dan Shell yang membuat tubuh Tuan Hualachi menggeliat-geliat bebas tanpa derajat kewarasan. Semua orang menjadi semakin ketakutan saat paranormal itu menunjukkan gerak-gerik yang berbeda-beda saat arwah-arwah yang berbeda merasukinya. Kadang ia menjilat-jilat tangannya seperti kucing, mengepak-ngepakkan lengannya seperti merpati, dan beringkrak-jingkrak seperti kera.
Walau bagaimana pun, semua nama arwah itu kedengaran asing. Aku berpikir tampaknya mereka bukan arwah-arwah lokal. Tidak ada kuntilanak centil, wewe gombel berjerawat, atau leak bali berjanggut. Aku sempat khawatir jangan-jangan Nohan benar-benar telah diculik arwah luar negeri dan dibawa ke Zimbabwe.
“Sekarang giliran kita,” bisik ayah. Aku menarik napas. Kami maju ke depan si paranormal. Paranormal itu berpakaian hitam legam, memegang sebuah cermin, dan konon dari cermin itu dia bisa melihat di mana orang yang hilang berada. Sebuah pedupaan dengan asap berbau menyan yang menyengat menjejal hidungku. Paranormal itu membubuhi cerminnya dengan bunga-bunga, mencelupkannya ke dalam air yang telah dikomat-kamitkan, lalu merajangnya di atas bara kemenyan.
“Ting-tong!”
Suara yang tidak asing. Telingakuku langsung jadi tajam. Suara itu keluar dari ponsel milik si paranormal. Lelaki setengah tua dengan janggut tanggung itu menghentikan ritualnya, menaruh cermin ajaibnya, dan memeriksa ponselnya.
Aku mengamati setiap mikrosekon gerakannya, seperti sebuah kamera HD perekam film.
“Hm…,” gumamnya sambil mengangguk-anggukkan kepala sambil menatap tajam ke arah ponselnya. “Sore ini aku harus memeriksa hutan di belakang rumah.”
Beberapa saat kemudian, badan paranormal itu tiba-tiba gemetar. Matanya kelayapan dan tangannya mencakar-cakar tikar tempatnya duduk. Ibuku sampai ketakutan dibuatnya.
“Dia sedang trance,” bisik ayah ke telinga kananku.
Aku memutar mata dengan bosan. Mengapa semua paranormal harus melakukan gerak-gerik stereotype seperti itu sejak zaman dahulu kala?
Kemudian paranormal itu kembali terdiam. Kali itu matanya menatap lurus ke depan. Gigi-gigi bagian atasnya terlihat menyembul dari mulutnya. Ia tampak seperti kelinci. Aku menduga bahwa yang merasukinya adalah sejenis arwah kelinci hutan, armadilo, cerpelai atau bajing yang tahu di mana adikku dan ribuan orang lainnya tersesat.
“Namaku Pikacho!” pekik paranormal itu tiba-tiba, masih dalam keadaan trance. Suaranya berubah jadi melengking tinggi seperti decit tikus. “Apa yang kalian ingin tanyakan?”
Aku membuka mulutku. Terbelalak. Pikacho?
“A… anu—,” ayah gelagapan. “Anak kami hilang dari kemarin.”
Paranormal yang kerasukan makhluk bernama Pikacho itu mengendus-endus layaknya marmut. Sejurus kemudian, ia berkata, “Anakmu diculik oleh Taugemon. Dia sangat tangguh.”
“Apa yang bisa kami lakukan?” ayah mendesak.
Aku mencubit lengan ayah. “Yah,”desisku curiga. “Ini sinting.“
“Diam kamu!” ayah memotong kata-kataku dengan sangar. “Nanti proses trance-nya terganggu!”
Lalu arwah Pikacho memberikan petunjuk bahwa ayah harus mempersembahkan beberapa buah pir manis dan beberapa batang white chocolate untuk santapan arwah-arwah itu agar tenang dan mau mengembalikan orang-orang yang hilang.
Aku menepuk kepalaku. Apabila bapak kepala kantor saat itu ada di sana, aku pasti langsung menariknya keluar dan mengajaknya makan white chocholate dan buah pir sungguhandi warung nongkrong bersama ketiga anaknya.
Dengan semakin kuat, aku menggoyang-goyang badan ayah. Beliau sudah terlampau khusuk mendengarkan celoteh arwah Pikacho.
Detik berikutnya, aku bangkit sambil mengingat-ingat. Semua nama arwah itu pernah kudengar sebelumnya. Otakku langsung berputar, namun satu-satunya tempat yang bisa kuingat di mana semua arwah itu pernah muncul adalah di televisi, kala aku kanak-kanak.
Aku yakin, besok paranormal itu juga akan lenyap menyusul mereka yang sudah menghilang, menjadi korban arwah Pikacho.
Dan masalah Nohan—ah, mungkin aku hanya perlu datang ke game center terdekat, tempat semua monster itu berkumpul dan memakan korban mereka satu per satu. Hanya saja aku perlu bergegas agar mereka tak keburu memakan otak adikku Nohan hingga tak tersisa.
Mangupura, 28 Juli 2016.