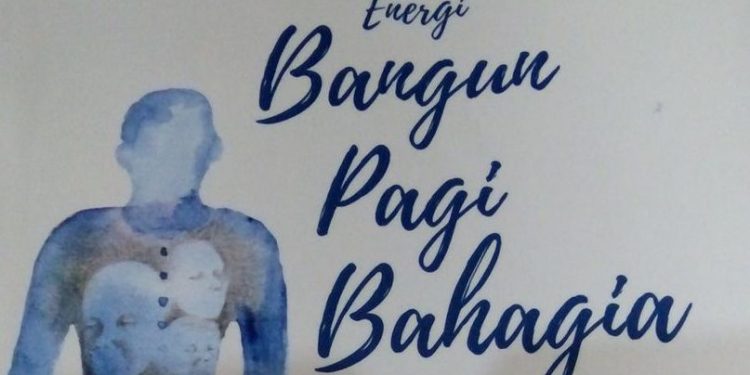#Judul buku: Energi Bangun Pagi Bahagia #Penulis: Andy Sri Wahyudi #Penerbit: Garudhawaca Yogyakarta #Tahun Terbit: Juni 2016
TERUS terang, membaca puisi-puisi Andy Sri Wahyudi di dalam bukunya Energi Bangun Pagi Bahagia saya tidak menemukan kebahagiaan apa pun. Bahkan, boleh dikatakan saya justru kehabisan energi ketika membacanya. Melelahkan. Padahal, menurut Andy sendiri “tugas pemimpin adalah membuat rakyatnya bangun pagi bahagia”. Saya sebagai salah satu rakyatnya merasa tidak bahagia. Jika batasan “bahagia” adalah terbebas dari segala yang menyusahkan, (maka) ke-57 puisi dalam antologi itu malah benar-benar menyusahkan saya.
Betapa tidak, sampai pagi tadi kening saya ini mengkerut memikirkan apa sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penyair kelahiran Yogyakarta itu. Ketika kening saya mengkerut itu artinya saya tengah berpikir keras dan ketika seseorang sedang berpikir keras sesungguhnya ia sedang jauh dari dunia ke(bahagia)an. Tugas saya berikutnya adalah memikirkan apa kira-kira yang menyebabkan puisi-puisi Andy kebanyakan menguras energi saat saya membacanya? Setelah dibaca dengan saksama, berikut akan saya tawarkan beberapa alternatif penyebabnya.
Pertama, keutuhan/kesatupaduan (unity) puisi-puisinya longgar. Kelonggaran ini memungkinkan timbulnya puisi-puisi absurd. Absurditas itu disebabkan oleh ketiadaan batas lagi antara yang nyata dengan yang imajiner, manusia dengan hewan dan tumbuhan, benda-benda alam dengan benda-benda kebudayaan. Ruang-ruang kosong dalam puisi-puisi tersebut terlalu lebar bahkan banyak. Jika puisi terlalu lebar memberi ruang-ruang kosong baik antarkata, antarlarik, antarbait, kemungkinan keutuhan puisi tidak akan terjaga.
Keutuhan itu menyangkut hubungan yang erat dan logis antarberbagai unsur yang ditampilkan, khususnya peristiwa-peristiwa dan keseluruhan pengalaman kehidupan yang hendak dikomunikasikan. Keutuhan juga semacam benang merah yang menghubungkan bebagai aspek cerita sehingga seluruhnya dirasakan sebagai satu kesatuan yang utuh dan padu.
berapa jarak kesepian dari hidupmu?
puntung-puntung kretek menggambar sejarah di setiap malam
dongeng-dongeng menggenang di secangkir kopi.
malam ini ada yang lupa
pada kekasih yang manja
ke mana hati ini berlari?
….
(Titik-titik Air)
Televisi tak pernah mengajariku merasakan cinta
Burung-burung dan serangga hanya mengajariku berbisik
Aku menertawai rindu yang mulai menari-nari di rubuhku
Rindu adalah antagonis yang manis
….
(Berani Patah Hati)
Secara sintagmatik, hubungan antarkata dalam puisi di atas boleh dikatakan padu. Namun, secara paradigmatik, hubungan antarlarik pada kedua puisi di atas tidaklah utuh, bahkan tidak padu. Inilah yang saya maksud ruang-ruang kosong itu terlampau longgar. Hubungan antara jarak kesepian dengan puntung kretek dengan dongeng-dongeng sangatlah lebar. Pun berlaku sama pada hubungan televisi-cinta dengan burung-berbisik dengan rindu-tubuh dengan rindu-manis.
Puisi-puisi semacam ini benar-benar mengingatkan saya kepada puisi-puisinya Afrizal Malna. Jika Chairil Anwar menggali kata hingga akarnya untuk membangun makna, Sutardji Calzoum Bachri membebaskan kata dari makna, (maka) Afrizal menganggap kata tidak penting dalam proses penciptaan makna, yang penting adalah relasinya dalam struktur (Gaus, 2014). Kutipan ini akan membela kelemahan atas kelonggaran kepaduan puisi-puisi di atas. Itu berarti kita akan memperoleh makna puisinya manakala kita mampu menembus relasi-relasinya dalam strukturnya yang serba berjarak itu.
Yang dapat membahagiakan ketika orang membaca puisi adalah hanya satu hal yakni saat mampu melakukan penghayatan yang intens terhadapnya. Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh Riffatere puisi selalu menyatakan sesuatu secara tidak langsung, mengatakan sesuatu dengan maksud yang lain. Di sinilah letak susahnya pembaca. Jalan satu-satunya agar mampu menangkap maksud sebuah puisi adalah dengan melakukan pembacaan berlapis.
Ini memang pekerjaan yang berat. Pembacaan heuristik menghasilkan arti sajak berdasarkan konvensi bahasa belum sampai kepada makna puisi. Dengan kata lain, pembacaan itu baru sebatas pembacaan harfiah (denotatif) atau kebanyakan menyebutnya makna di dalam kamus. Pembacaan semacam ini bisa dicontohkan sebagai berikut.
Energi
sri, jika hidup hanya diam dan sudah tak terkatakan
jangan hiraukan suara mesin atau suara Tuhan
guncanglah!
Bagi saya, pertanyaan pemandu dalam pembacaan heuristik adalah “apakah itu…?”. Dengan demikian kita bisa bertanya “apakah itu sri?”, “apakah itu jika?”. “apakah itu hidup?”, dan seterusnya. Intinya adalah mencari arti dari masing-masing kata yang ada di dalam puisi. Pembacaan hermeneutik merupakan pembacaan berdasarkan konvensi sastra.
Artinya, sebuah sajak diinterpretasikan melalui pemahaman kata dari makna konotatif dan ketidakberlangsungan ekspresi yang sengaja dilakukan oleh penyair. Pembacaan hermeneutik ini membuat puisi dapat dipahami maknanya secara keseluruhan. Dengan demikian, selain “apakah itu…?” akan diperlukan pertanyaan pemandu tambahan dalam memahami seluruh konstruksi kata dalam puisi yaitu “mengapa…?”. Kita kemudian bisa mempertanyakan “mengapa sri?”, “mengapa hidup?”, mengapa guncanglah?, dan seterusnya.
Kedua, puisi-puisi Andy tidak mementingkan metafora (idiom/ungkapan). Padahal, puisi-puisinya memperlihatkan prinsip bahwa apa saja bisa masuk ke dalam puisi. Kata-kata tidak diseleksi secara ketat. Kata-kata yang sebelumnya tidak mengandung muatan puitis kini menjadi bebas bertebaran dalam puisi seperti kue tart, cumi goreng, jajanan pasar, televisi, sekolah, ekonomi, buah tomat, sapu lidi, kemoceng, dll. Bahkan, masih ada ungkapan yang terbaca klise seperti ufuk timur, fajar menyingsing, menggunung, lembaran hidup, dll.
Ketidakketatan itulah yang mungkin menjadi penyebab metafora pada puisi-puisi itu lemah.Tradisi puisi pada zaman Chairil ditandai dengan penjagaan ritmis puisi dengan persajakan yang terpelihara ketat, dengan asonansi dan aliterasi yang terjaga, serta dengan simbol-simbol bunyi yang dibangun dengan konsisten. Dengan irama-irama semacam itu, puisi-puisi sezaman Chairil mampu membangun suasana; liris.
Kebanyakan puisi-puisi Andy menggunakan “tanya” di dalamnya. Sudah tentu, jenis kalimat tanya yang dipakai adalah tanya yang retorik. Artinya penyair tidak sedang butuh jawaban berupa informasi, penjelasan, klarifikasi, atau konfirmasi atas apa yang disampaikan dalam puisi-puisinya.
di manakah jam dinding?
apakah ini diam?
apakah sudah makan cumi goreng atau ikan bakar hari ini?
siapakah yang membunuh rindu?
kamu di mana?
apakah kita sudah tersenyum untuk semua anak manusia, untuk hutan, untuk musim panen dan televisi?
di manakah ibu swasti bersekolah?
apakah padipadi bisa tertawa seperti aku ibu?
Segala bentuk tanya semacam itu mengimplikasikan bahwa puisi-puisi tersebut tidak hanya sedang mendeskripsikan sesuatu tetapi juga berusaha membangun dialog-dialog pemikiran/perenungan. Memang, puisi Andy bukan hanya sebagai puisi-puisi yang kontemplatif, melainkan juga puisi komunikatif. Salah satu kontemplasi yang dimaksud diwakili oleh puisi yang berjudul “?” sebagai berikut.
?
Bu guru, mohon terangkan bagaimana sejarah perasaan
manusia itu?
Bila puisi kontemplatif menyangkut hubungan antara subjek-objek, dalam puisi komunikatif yang terbangun adalah hubungan antara subjek-subjek. Kedua hubungan itu dibangun dalam puisi, saling mengisi. Namun, di sisi lain ada kemungkinan disebut puisi-puisi ini disebut sebagai puisi empirik yang kontemplatif. Alam empirik memegang peranan penting dalam puisi-puisi Andy. Rata-rata berbicara sekitar alam sekitar; lingkungan alam, yang mampu ditangkap secara indrawi.
Berbagai hal yang ada di alam, terutama benda-benda menjadi detail penting dalam puisi-puisinya. Konsisten memasukkan benda-benda ke dalam puisinya tanpa harus mempertimbangkan bunyi estetikanya. Kata-kata benda dengan leluasa masuk tanpa beban bunyi yang dapat menimbulkan rima dalam larik atau antarlariknya. Jika boleh dikatakan puisi-puisi yang ditulis tidak terlalu memainkan bunyi-bunyi bahasa. Ini dimungkinkan oleh penangkapan penyair terhadap fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya apa adanya.
Jika asas estetika penyair tahun 70-an yaitu kata adalah representasi dari dunia pengalaman bukan dunia gagasan atau dunia sistem yang serba abstrak, homogen, monoton, suci, dipakai sebagai dasa dalam menentukan kualitas puisi-puisi dalam antologi itu pasti akan gagal. Dunia pengalaman merupakan dunia yang konkret, heterogen, variatif, unik. Seberapa jauh kata-kata yang digunakan dalam puisi dapat membawa kita ke dalam dunia pengalaman, dan sudah tentu tidak hanya berusaha memahaminya tetapi juga mengalaminya.
Jika menggunakan perspektif 70-an sebuah puisi yang baik harus memenuhi kesatuan imaji. Jika dalam puisi tidak ada kesatuan imaji maka akan mengganggu proses penyampaian maksud kepada pembaca. Inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan puisi-puisi gelap. Puisi-puisi Andy lebih banyak bergerak dalam dunia pengalaman. Mengajak kita untuk ikut serta dalam segala cerita (yang sekalipun alurnya masih terbata-bata) yang dibangun dalam puisinya. Sekalipun kadang-kadang menggugat di tengah-tengah pencariannya yang serba merenung, serba diam, serba sunyi, serba setia, dan serba rahasia.
Andy tampaknya tidak terlalu banyak bermain di wilayah bentuk (tipografi). Sekalipun mencoba menemukan ‘sesuatu’ di kutub puisi-puisi pendeknya. Tipografi puisinya lagi-lagi (mungkin) kena gesekan Afrizalian, yang lebih condong ke dalam bentuk naratif. Yang menarik adalah, puisi-puisi di halaman pertama hampir semua kata menggunakan huruf kecil.
Lalu, puisi-puisi berikutnya diawali dengan huruf kapital pada setiap lariknya. Saya lebih condong ke “huruf kecil” itu. Jika saja Andy konsisten menulis semua puisi-puisinya (kecuali judul) dengan mengggunakan huruf kecil, bisa jadi ini adalah tawaran yang menarik (khas) pada puisi-puisinya.
Memandang Jauh I
: Mando Sariano
langit adalah mata hati yang mencintai gunung dan desau angin
di sana kekasih matahari sore sedang duduk bersimpuh,
ia membaca debur ombak yang selalu berbisik lirih:
kita adalah dunia yang terbuat dari bahasa yang sunyi
untuk membuat gelombang yang menjadi.
Bandingkan dengan:
Regenerasi
Catatan untuk Tunes
Ingatan lahir dari benturan kata-kata
Hari ini adalah doa dari masyarakat masa lalu
Dunia adalah api yang dinyalakan bayi-bayi manusia
Dari kepala ke kepala. Dan kita adalah anak-anak api.
Api dunia.
Masa kematangan puisi-puisi Andy sesungguhnya ada pada puisi yang berjudul “Memandang Jauh I” dan “Memandang Jauh II”. Sekalipun kedua puisi ini pendek tetapi kesatuan emosi dan kepadatan maknanya sangat terjaga. Hanya saja, yang paling mengganggu adalah keterangan waktu penulisan puisi tersebut tidak logis. “Memandang I” seharusnya adalah hipogram dari “Memandang Jauh II” tetapi pada kenyataannya puisi kedua lebih dahulu tercipta dibandingkan dengan puisi pertama. Gejala semacam itu tentu menyalahi konsep hipogram karena judul puisi kedua sebagai teks mengeksplisitkan sebagai respons puisi pertama sebagai teks pertama.
Sementara itu, puisi yang belum menemukan “apa-apa” adalah pada puisi “Aku Menggugat kepada Lupa”. Puisi ini memang harus digugat lebih lanjut. Andy mungkin benar-benar sedang “lupa” saat menulis puisi ini. Satu-satunya puisi yang paling panjang tetapi emosinya benar-benar liar, meletup tanpa ada kontrol yang ketat, hanya sebagai etalase satuan linguistik; pajangan kata-kata semata.
Bahwa puisi-puisi Andy memang sedang berusaha membebaskan diri dari tekanan makna kata-kata. Maka wajahlah jika Aprizal dalam pengantarnya menyatakan “puisi yang cenderung membebaskan diri dari teritori makna”. Pembebasannya dilakukan dengan menghilangkan batas-batas antara fiksi dan kenyataan. Semua yang ada dalam jangkauan matanya berhak untuk ikut ambil bagian dalam puisinya. Segala macam formalitas bahasa berusaha untuk dilupakan, bahkan ditiadakan sama sekali.
Hanya saja, dalam menarasikan segala sesuatu yang ada itu terlalu longgar sehingga memungkinkan yang diinginkan ikut terlibat dalam puisinya memiliki imajinasi ke mana-mana. Tak ada jalinan yang mampu mengikatnya. Memang, beginilah kodrat puisi-puisi bergaya posmodern itu. (T)