ADA satu mantera modern yang nyaris diucapkan serentak di lorong-lorong kantor atau di grup WhatsApp keluarga: “Anak Gen Z ini lho… lemah, nggak bisa kerja, dikit-dikit ngelawan, baperan, dituding boros gara-gara kopi susu kekinian, hobi healing padahal dompet tipis!” Cap ini melekat, dibumbui dengan kekesalan atau mungkin sekadar keheranan dari generasi-generasi sebelumnya yang (katanya) lebih tangguh, lebih loyal, dan lebih… “normal”.
Sungguh mudah melabeli. Seperti mencetak stempel pada selembar kertas yang masih kosong. Generasi Z, sang template baru dalam dunia kerja, seolah datang dengan instruksi manual yang berbeda, membingungkan para pengguna lama. Mereka dibilang tidak tahan banting. Cepat berontak saat ditekan. Air mata mudah tumpah karena kritik. Gaji bulanan habis entah ke mana, tapi kalau diajak lembur, jawabnya: “Maaf, saya butuh healing.”
Eits…Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita ramai-ramai menghakimi sambil menyeruput kopi (yang mungkin juga kekinian), mari kita berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam. Bukankah Gen Z ini produk dari rahim Baby Boomers dan didikan Millennials? Jika mereka dianggap gagal, bukankah ada andil dari generasi pendahulunya dalam membentuk mereka? Menyalahkan Gen Z sepenuhnya terasa seperti mencuci tangan dari tanggung jawab kolektif.
Lebih penting lagi, daripada sekadar adu kuat argumen dengan contoh “ponakan saya rajin kok” atau “karyawan Gen Z saya malas banget”, mari kita lihat gambaran besarnya. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa Gen Z adalah salah satu generasi paling rentan secara mental. Disebutkan bahwa pada tahun 2023, tingkat depresi mereka sebesar 2%, bersaing tipis dengan kelompok usia lansia di atas 75 tahun.
Wow. Apakah ini hanya karena TikTok dan FOMO (Fear of Missing Out)? Mungkin sebagian. Akses informasi tanpa batas dan tekanan eksistensi di dunia maya memang punya andil. Dunia digital menawarkan pelarian sekaligus penjara; “halu” bisa jadi mekanisme pertahanan dari realitas yang keras.
Namun, menyalahkan internet dan media sosial saja terlalu menyederhanakan masalah. Mari kita perkenalkan tersangka utama yang seringkali luput dari perhatian ketika membahas keluhan generasi muda yaitu kapitalisme dalam bentuknya yang paling ganas.
Sistem ini, dirancang untuk terus tumbuh, seringkali dengan mengorbankan kesejahteraan pekerjanya. Gen Z memasuki dunia kerja di era ketika pekerjaan stabil nan aman adalah sebuah kemewahan. Model outsourcing merajalela, kontrak kerja jangka pendek tanpa jenjang karier yang jelas menjadi norma.
Rasa aman? Itu barang langka. Loyalitas perusahaan? Bagaimana bisa loyal jika perusahaan tidak menawarkan jaminan masa depan? Alih-alih cepat melawan, mungkin Gen Z lebih cepat sadar bahwa loyalitas buta pada sistem yang eksploitatif adalah tindakan bunuh diri pelan-pelan. Mereka tahu boundaries, batas mana yang tidak boleh dilewati demi menjaga kewarasan. Apakah itu salah?
Lalu, mari bicara soal “boros” dan “healing“. Kapitalisme tidak hanya menghisap tenaga, tapi juga kewarasan. Ia menciptakan kekosongan makna yang kemudian coba kita isi dengan konsumsi. Kita didorong untuk percaya bahwa kebahagiaan bisa dibeli—gadget terbaru, pakaian trendi, liburan instagrammable, dan ya, kopi susu seharga makan siang.
Ketika jiwa terasa hampa dan lelah oleh tekanan kerja serta ketidakpastian hidup, membeli barang atau scroll media sosial berjam-jam menjadi pelarian termudah. Kita berusaha menghibur diri sampai mati, terjebak dalam siklus pencarian kesenangan instan yang tak pernah benar-benar memuaskan. Bukannya bahagia, kita malah makin terperosok dalam keputusasaan. Healing menjadi kebutuhan, bukan sekadar gaya hidup, sebagai respons terhadap sistem yang membuat kita sakit.
Sekarang, tambahkan faktor ekonomi makro. Harga rumah melambung gila-gilaan. Generasi sebelumnya mungkin masih bisa mencicil rumah dengan gaji standar, tapi bagi Gen Z, mimpi punya rumah sendiri terasa seperti fantasi. Gaji cenderung stagnan, tidak sebanding dengan inflasi dan biaya hidup yang terus meroket. Suku bunga pinjaman? Jangan ditanya, tinggi banget!
Bagaimana generasi muda tidak pesimis jika fondasi dasar kehidupan yang layak—pekerjaan aman dan rumah terjangkau—tampak begitu jauh dari jangkauan, bahkan meski sudah mati-matian menabung dan menahan diri dari godaan kopi susu? Tanpa privilese atau bantuan, mimpi hidup sejahtera dan bebas depresi itu seperti menunggu hujan di musim kemarau.
Jadi, ketika asyik melabeli dan menertawakan, atau bahkan “membela” mereka dengan kisah sukses satu-dua orang, bukankah lebih produktif jika kita mulai berpikir bersama? Bagaimana caranya memperbaiki sistem yang membuat satu generasi merasa begitu tertekan, begitu tidak aman, dan begitu pesimistis tentang masa depan? Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi, akses ke kesehatan mental yang lebih mudah, dan kesempatan ekonomi yang lebih adil?
Mungkin PR-nya bukan “membetulkan” Gen Z agar sesuai dengan standar generasi sebelumnya, tapi “membetulkan” dunia yang kita tinggali bersama ini, agar semua generasi, termasuk Gen Z, punya kesempatan yang layak untuk sejahtera dan tidak perlu healing melulu karena kelelahan batin. [T]
Penulis: Komang Puja Savitri
Editor: Adnyana Ole
Penulis adalah mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi STAHN Mpu Kuturan Singaraja yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tatkala.co.
- BACA JUGA:









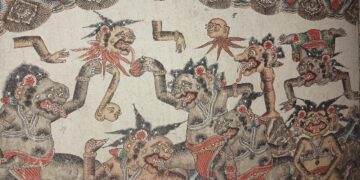













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)










