Menjernihkan ‘Bias Citra’ Antara Dewi Danu, Jaya Pangus, dan Putri Cina[i]
Kisah cinta antara Dewi Danu, Jaya Pangus, dan seorang putri Cina bernama Kang Cing Wie terlanjur mengalir deras ke dalam berbagai telaga kreativitas. Di dunia sastra, wacana itu melahirkan sejumlah karya sastra geguritan. Sementara itu, dalam lanskap seni pertunjukan, menitis beragam pergelaran seni seperti arja[ii], prembon kolaborasi[iii], sendratari[iv], fragmentari[v], dan yang lainnya. Tak ketinggalan, dalam bidang seni rupa juga muncul sejumlah patung dan relief sebagai diorama kisah cinta sang Raja Bali dengan puteri raja dari Negeri Cina[vi].
Motif di balik kelahiran berbagai kreativitas ini menarik ditelusuri. Munculnya beragam karya sastra geguritan barangkali disebabkan karena wacana Dewi Danu, Jaya Pangus, dan Kang Cing Wie diduga memberikan jawaban awal eksistensi barong landung yang banyak disungsung di Bali. Wujud ikonografis figur perempuan yang kerap disebut Jero Luh dengan mata sipit dan paras wajah berwarna putih identik dengan perempuan yang berasal dari Negeri Cina.[vii] Namun demikian, sesungguhnya sangat sulit membayangkan wajah Jaya Pangus dengan perwujudan transgresif seperti itu: berkulit hitam, mata sipit, dengan gigi yang melengkung ke depan serupa raksasa.
Pada saat yang bersamaan, kisah cinta dari etnis berbeda ini pasti menjadi garapan yang dapat dimainkan untuk menyentuh perasaan dan menyampaikan berbagai pesan keberagaman dalam seni pertunjukan. Senada dengan hal itu, tujuan untuk menarik wisatawan Cina untuk datang ke Bali juga menjadi pemantik dibuatnya patung serta relief di sejumlah objek wisata.
Berbagai tujuan untuk mengekspolari kisah hubungan antara Dewi Danu, Jaya Pangus, dan Kang Cing Wie sejauh ditujukan untuk kepentingan pihak luar, tentu tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi, bias citra Dewi Danu yang dinarasikan memiliki khusus dengan Jaya Pangus dan Kang Cing Wie, potensial menggores luka bagi masyarakat yang menempatkan beliau sebagai dewata pujaannya. Dalam konteks lain, wacana ini juga dapat berakibat pada kaburnya entitas dan identitas Raja Jayapangus sebagai salah satu tokoh sejarah Bali yang benar-benar sempat memerintah di Bali pada masa silam. Beliau bahkan disebut sebagai raja yang mengamalkan nilai-nilai kebajikan karena paling banyak menurunkan kebijakan untuk menjaga stabilitas pemerintahannya. Yang lebih fatal sesungguhnya adalah hubungan etnis Bali dan Cina yang direpresentasikan dalam kisah ini. Hubungan cinta segitiga di antara ketiga figur tersebut sejatinya tidak berakhir dengan happy ending ‘kebahagiaan’, tetapi sebaliknya. Sebab, Kang Cing Wie yang berasal dari Cina dinarasikan dibakar oleh Dewi Danu menggunakan kekuatan mata ketigaNya.
Berangkat dari situasi tersebut, wacana pembanding tampaknya diperlukan untuk mengantisipasi dua mata pisau dari bergulirnya diskursus ini. Satu bahan tekstual yang ditawarkan dalam tulisan ini berusaha memberikan kemungkinan hulu wacana tentang kisah di antara Dewi Danu, Jaya Pangus, dan Kang Cing Wie. Sumber ini tentu bukan satu-satunya, tetapi hanya salah satunya. Kita menunggu sumber-sumber lain yang lebih otoritatif dan mampu memberikan nyala kebenaran lebih terang.
Lontar Ngatep Barong
Disimpan di Unit Lontar Universitas Udayana. Lontar Ngatep Barong terdiri atas sejumlah teks seperti Kakawin Manuk Dadali, Kidung Kadiri Pangalang[viii], Upakaraning Pamelas Tapel (Ngatep Barong), Pangentas Sarwa Meng, Purana Ring Bali[ix], Pamancangah Ida Padanda Made Sidemen (Babad Brahmana Mas). Penulisnya sendiri diduga sesuai dengan uraian teks terakhir, yaitu Ida Padanda Made Sidemen. Hal ini juga didasarkan pada bukti internal teks yang menyebutkan secara rinci silsilah keleluhuran beliau, termasuk kekaryaannya di bidang seni sastra dan seni rupa. Dalam salah satu teks itu, khususnya bagian Purana Ring Bali menyelip narasi antara Dewi Danu, Jaya Pangus, dan Putri Cina.
Kisahnya dimulai dari uraian tentang seorang tokoh bernama Śri Māyādanawa yang tinggal di wilayah Balingkang. Ia adalah putra dari Dewī Danu. Ketika remaja, ia diberikan anugerah berupa pengetahuan tentang rājanīti agar bisa menaklukkan kerajaan lain di Pulau Bali oleh ibundanya (aji tungkulaning jagat). Maka pada saat ia dewasa, seluruh kerajaan lain di Pulau Bali, baik yang berada di sisi timur, selatan, maupun barat diserangnya. Karena kesaktian itu, raja lain berhasil ditaklukkan melalui perang. Sebagian lagi menyerah kalah.
Setelah dinobatkan menjadi raja yang berkuasa penuh atas wilayah Bali, Śri Māyādanawa diperintahkan oleh Dewi Danu untuk menikah. Beliau menyuruh agar putranya melamar seorang putri dari Kerajaan Cina yang saat itu diperintah oleh Raja Onte. Menanggapi perintah ini, Śri Māyadānawa tidak menolak. Dengan menghaturkan sangu pernikahan dalam jumlah yang banyak, Raja Onte memberikan restu kepada putrinya untuk menikah dengan Sang Raja Bali. Melalui jalur udara, Māyadānawa membawa istrinya pulang menuju Balingkang. Patih Kala Wong yang diberi tugas untuk menggelar upacara ini sukses mengadakan pernikahan Śri Māyadānawa dan putri Cina dengan suasana yang meriah.
Ketika mengatur pemerintahan di Kerajaan Bali bersama permaisurinya, Śri Māyadānawa ternyata tidak mengizinkan para pendeta menggelar upacara persembahan kepada Hyang Widhi. Mulai dari hulu pegunungan Bali hingga ke desa-desa, seluruh ritual dibatalkan. Ia menghapuskan tatanan masyarakat yang terbagi dalam empat lapisan wangsa yang dikenal dengan sebutan catur waṛṇa. Akibat kebijakan ini, kondisi alam Bali menjadi labil. Musibah dan wabah pun tak pernah jeda. Semua tanaman mati karena kekeringan, sedangkan air yang mengalir tak lagi menyuburkan. Hal ini semua diakibatkan oleh perintah Śri Māyadānawa yang melarang para pendeta dan masyarakat untuk melakukan upacara.
Menyadari situasi ini, permaisurinya yang berasal dari Cina memohon kepada Śri Māyadānawa untuk memotong taringnya. Sebab, Raja Bali itu memiliki taring yang menyerupai gandarwa. Menanggapi hal ini, Śri Māyadānawa menerima permintaan istrinya. Ia juga berpesan kepada seluruh masyarakat di Kerajaan Bali agar melakukan potong gigi sebelum menikah[x].
Selang beberapa waktu ketika keduanya memutar jantra pemerintahan, istri Śri Māyadānawa tiba-tiba jatuh sakit. Hal ini disebabkan oleh perilakunya yang masih mengutamakan ajaran agamanya sendiri (apan kasowanganing gama kottamanira). Dalam situasi itu, Śri Māyadānawa bermaksud memohon anugerah dari para dewata yang berstana di Tohlangkir. Namun sayang, setelah beberapa hari memohon kesembuhan, para dewata yang berstana di gunung itu tidak berkenan memberikan berkah.
Mendapatkan perlakuan seperti ini, ia semakin membenci dunia. Śri Māyadānawa kembali melarang warga masyarakat untuk menghaturkan pemujaan kepada para dewata di seluruh tempat pemujaan. Ia bahkan memerintahkan warga masyarakat untuk memuja dirinya. Ia juga mengklaim dirinya sebagai dewa yang harus dipuja oleh umat manusia di dunia.
Sikap Raja Bali yang seperti itu semakin menutup ruang untuk mendapatkan anugerah para dewata. Usaha Śri Māyadānawa untuk menyembuhkan istrinya pun tak kunjung berbuah. Sang Putri Cina akhirnya sekarat. Jelang kematiannya, anak Raja Onte itu memberi pesan kepada suaminya agar jenazahnya dibakar. Abunya ditempatkan di dalam sebuah kelapa gading, lengkap dengan rajah ongkara. Di atasnya ditusukkan kayu dedap dan dipayungi dengan kelopak pinang, serta dibungkus dengan kain putih, serta hiasan berbagai jenis bunga. Semuanya kemudian dilarung di laut dengan harapan agar arwahnya bisa kembali lagi ke tempat ayah dan ibunya samula, yaitu Cina (makadon saŋ pitara mulihéŋ yayah bibi muwah).
Setelah pesan ini disampaikan, Sang Putri Cina akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Śri Māyadānawa pun memenuhi seluruh permintaan istrinya. Cinta antara raja Bali dan putri Cina kandas.
Keadaan ini menyebabkan Sang Raja Bali semakin frustasi. Untuk mengobati rasa kehilangannya, ia lalu memutuskan untuk meninggalkan Kerajaan Balingkang. Walaupun tak lagi tinggal di istananya, Śri Māyadānawa ternyata masih tetap menyuruh masyarakat Bali untuk menghaturkan pemujaan saban tahun kepadanya. Hal inilah yang menyebabkan keadaan Pulau Bali menjadi semakin kacau. Sampai pada akhirnya, Dewa Indra akhirnya turun ke Bali untuk menghentikan langkah Śri Māyadanawa. Walaupun melalui suatu perang yang dahsyat, seperti yang dapat diduga oleh pembaca, kemenangan tentu ada di pihak Dewa Indra.
Kekalahan Śri Māyadanawa mengakhiri era pemerintahan yang berpusat di Balingkang. Setelah itu, sejak rentang tahun 804 sampai 836 Śaka Kerajaan Bali diperintah oleh Śri Mahāraja Sanjaya yang bertahta di Mataram-Jawa. Beliau sendiri tidak menunjuk raja di Bali karena diperintah langsung dari Jawa. Oleh sebab itulah prasasti-prasasti di Bali menggunakan bahasa Bali Kuno.
Sejak tahun 837 sampai 855 Śaka, Kerajaan Bali diperintah oleh Śri Mahāraja Ugraśena (putra dari Raja Sanjaya). Selanjutnya, tahta kerajaan dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama (Ta)Bhanendra Warmadewa dengan istrinya yang bergelar Śri Subhādrika Warmadewa pada tahun 870 Śaka. Setelah itu, tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya yang bernama Śri Mahārāja Cāndra Bhaya Singha Warmmadewa. Setelah sang raja wafat, putranya yang bernama Śrī Mahārāja Janasadhu Warmadewa menggantikannya menjadi raja bersama istrinya yang bernama Śri Wijaya Mahadéwi pada tahun 897 Śaka. Karena sang raja wafat, pemerintahan digantikan oleh istrinya, yaitu Śri Wijaya Mahadéwi dan menerbitkan prasasti pada tahun 905 Śaka.
Selanjutnya, Kerajaan Bali diperintah oleh keturunan Śrī Mahārāja Janasadhu Warmadewa yang bernama Śri Udayana Warmadewa. Raja Bali ini menikahi misannya bernama Śri Guņapriyā Dharmapatni yang memerintah dari tahun 916-938 Śaka. Salah satu anak dari Udayana yang bernama Erlangga dijadikan raja di Jawa, sedangkan adiknya yang bernama Śri Aji Anak Wungsu menjabat sebagai raja di Bali pada tahun 994 Śaka. Setelah sekian lama menjabat sebagai Raja Bali, ketika beliau wafat abunya kemudian distanakan di Pura Gunung Kawi, Tampaksiring. Sementara itu, abu ayahnya yakni Udayana distanakan di Bhanuweka di dekat Desa Batuan, Gianyar dan ibunya yaitu Gunapriyadharmapatni distanakan di Bukit Dharma, dekat Desa Buruan Gianyar. Putra Anak Wungsu bernama Sri Wira Kesari lalu melanjutkan kekuasaan dengan kerajaan yang berlokasi di Dalem Puri. Namun demikian, pemerintahan beliau tidak lama, penggantinya adalah putranya yang bernama Śri Jaya Kasunu.
Pengganti Śri Jaya Kasunu adalah putranya yang bernama Śri Jaya Pangus dengan istrinya yang bernama Śri Intuja Ketana pada tahun 1103 Śaka. Setelah Śri Jaya Pangus bertahta, raja yang berkuasa di Bali adalah Bhațara Guru Śri Adi Kunti Kétana pada tahun 1126 Śaka. Setelah itu, tahta kerajaan dipegang oleh Bhațara Śri Mahā Guru pada tahun 1246 Śaka [xi]. Penerus tampuk kekuasaan setelah Śri Mahāguru adalah putranya yang kembar bernama Śri Maśula Maśuli[xii]. Beliau kemudian menurunkan seorang putra yang bernama Śri Tataklapa. Meski raja ini terkenal sangat tampan, tapi beliau lebih memiliki menikahi seorang perempuan dari wangsa jaba sehingga memunculkan keturunan yang salah rupa.
Demikianlah cerita masa lalu raja-raja yang pernah berkuasa di Bali. Meskipun samar-samar, keturunan Sri Tataklapa yang salah rupa itulah yang kemudian memerintah di Kerajaan Bali. Figur yang disebutkan terakhir sangat identik dengan Sri Astaśura Ratnabhumi Banten. Beliaulah Raja Bali yang ditaklukkan oleh Gajah Mada. Setelah kemenangan diperoleh, Kerajaan Majapahit menempatkan Dalem Ketut Kresna Kapakisan sebagai Raja Bali.
Kritik Naskah dan Teks
Naskah lontar Ngatep Barong yang dikoleksi di Unit Lontar Universitas Udayana memang salinan yang relatif baru. Salinan itu diselesaikan tanggal 19 Desember tahun 1962. Meskipun naskahnya baru, teks yang dinarasikan di dalamnya pasti lebih kuno. Apalagi, penulisnya diyakini sebagai figur pengarang besar Bali, yaitu Ida Padanda Made Sidemen.
Ida Padanda Made Sidemen tampaknya berusaha merekonstruksi masa lalu Bali dari dua sumber dalam teks Purana Ring Bali, yang sifatnya simbolis mitologis dan tulis yang berasal dari prasasti-prasasti. Oleh sebab itu, boleh jadi penempatan figur Māyadānawa sebelum deretan raja yang pernah menerbitkan prasasti merupakan tokoh alegoris yang menjadi batas cakrawala pengetahuan penulis. Barangkali beliau tahu bahwa masyarakat Bali memiliki ikatan yang kuat dengan Negeri Cina, tetapi bukti penyangga untuk memastikan hubungan itu belum sempurna sehingga diciptakanlah kisah Mayādanawa.
Di sisi lain, dengan menggunakan sumber informasi dari prasasti Bali, beliau berusaha menyusun bentang raja-raja yang pernah bertahta di Bali. Raja itu dimulai dari Ugrasena hingga datangnya Sri Kresna Kapakisan sebagai utusan Majapahit yang berkuasa di Bali. Uraian tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Bali menurut sumber ini tentu memiliki peluang sangat menganga untuk dikritisi oleh para penekun epigrafi. Sebab, uraian raja yang berkuasa di Bali di atas tidak semuanya ditemukan prasastinya. Raja-raja itu di antaranya adalah Sri Aji Jaya Kasunu, Masula Masuli, Sri Tataklapa, dan yang lainnya.
Meskipun demikian, ada data-data berharga yang dapat dijadikan sebagai benih pembuktian lebih lanjut melalui data ini. Hal itu misalnya alasan di balik kekosongan nama raja dalam prasasti Bali Kuno, hubungan kekerabatan antarraja, termasuk pula tempat khusus para raja Bali dicandikan yang masih bisa dikunjungi hingga saat ini.
Secara tekstual, uraian karya sastra ini sangat mirip dengan pustaka Usana Bali. Pustaka Usana Bali memang berhubungan dengan kronik cerita raja-raja yang berkuasa di Bali pada masa Bali Kuno, sedangkan teks Usana Jawa berhubungan dengan narasi ekspansi Kerajaan Majapahit ke Bali. Di tengah-tengah intertekstualitas itu, jauh sebelum kedatangan Majapahit ke Bali, ternyata ada kisah yang menjadi memori kolektif masyarakat Bali, yaitu salampah laku Dewi Danu, Śri Mayādanawa, dan seorang putri dari Negeri Cina. Seting lokasi kerajaannya sendiri berada di kawasan pegunungan Bali, yaitu Balingkang.
Menjernihkan Bias
Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dugaan bahwa teks Purana Ring Bali adalah representasi dari hulu endapan ingatan masyarakat Bali tentang hubungan Raja Bali dengan Putri Cina, ada sejumlah hal yang perlu digarisbawahi.
Pertama, teks secara benderang menyebutkan ada kerajaan yang berpusat di wilayah pegunungan Bali, yaitu Balingkang dengan rajanya yang bergelar Śri Māyadanāwa (kari saŋ maya dānawa, hana riŋ bāliŋkaŋ, iŋayapiŋ détya dānawa). Kedua, figur Dewi Danu adalah dewata yang merupakan ibu dari Śri Māyadānawa[xiii]. Hubungan biologis-simbolis serupa juga diwacanakan dalam teks lain seperti Kakawin Usana Bali Mayantaka karya Dang Hyang Nirartha dan Geguritan Rajendra Prasad karya Tjokorde Gde Ngoerah. Ini artinya, hubungan Dewi Danu dengan Śri Māyadānawa merupakan ingatan bersama. Ketiga, meskipun teks di atas memuat seorang putri Cina yang merupakan anak dari Raja Onte, teks tidak menyatakan hubungan putri tersebut dengan Jaya Pangus, tetapi Māyadānawa. Teks juga tidak menyebutkan nama tokoh Kang Cing Wie yang menikah dengan Raja Jaya Pangus yang kala itu bertahta sebagai Raja Bali. Jaya Pangus sendiri disebutkan berkuasa di era belakangan dengan tahun yang pasti, yaitu pada tahun 1103 Śaka.
Dari uraian tersebut, kita melihat kemungkinan adanya ‘patahan’ dalam proses transmisi teks yang mengisahkan tentang Dewi Danu, Putri Cina, dan Jaya Pangus. Teks tulis seperti Purana Ring Bali mungkin hanya bisa diakses oleh sejumlah kalangan sehingga ketika dituturkan terjadi bias hubungan antartokohnya. Apalagi hal tersebut dikukuhkan dengan beragam seni pertunjukan. Maka, figur Dewi Danu yang semula diwacanakan sebagai ibunda dari Śri Māyadanāwa dalam dinamikanya dikisahkan menjadi memiliki hubungan istimewa dengan Jaya Pangus. Sementara itu, putri Cina yang menjadi istri dari Śri Māyadanawa juga diceritakan menikah dengan Jaya Pangus. Padahal, Jaya Pangus sendiri berdasarkan teks Purana Ring Bali berkuasa pada era yang berbeda.
Apabila dicermati lebih mendalam, teks Purana Ring Bali di atas sesungguhnya tak kalah dramatik dengan kisah Jaya Pangus dan Kang Cing Wie yang kini beredar luas di masyarakat. Bukti tekstual ini dapat dikembangkan menjadi beragam kreativitas dengan tema hubungan Bali dengan Cina. Melalui kesaksian teks ini pula kita belajar dari Śri Māyadānawa yang pernah menikahi Putri Cina dengan salaksa tantangan dalam memutar jantra pemerintahan karena kebijakannya dalam hal upacara. Di sisi lain, kita juga bisa menempatkan Jaya Pangus sebagai raja Bali yang memang berkiprah dalam matra sejarah. Yang terpenting, kita memberikan altar pemuliaan kepada Dewi Danu sebagai shakti yang dalam banyak teks dinarasikan sebagai ‘Ibu’ pengasuh untuk seluruh tata kelola air di Bali. [T]
[i] Tulisan ini terinspirasi dari dialog antara Guru Sugi Lanus dan Jero Panyarikan Duuran Batur (IK Eriadi Ariana) di salah satu postingan Museum Nasional yang menyelenggarakan pameran hubungan budaya Cina dan Indonesia. Tulisan ini mendukung dugaan barunya narasi kisah antara Jaya Pangus dan Kang Cing Wie yang ditulis dalam komentar postingan tersebut dengan menyodorkan satu bukti tekstual dari lontar Ngatep Barong diduga ditulis oleh Ida Padanda Made Sidemen yang lebih tua. Penulis sempat mentransliterasi lontar tersebut atas permintaan Ratu Aji IBG Agastia.
[ii] Drama tari Arja Barong Landung sempat dipentaskan Tari Rare Kumara, Desa Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Hari Rabu,Tanggal, 29 Juni 2016 di Kalangan Angsoka, Taman Budaya Art Center Provinsi Bali. Dokumentasinya bisa diakses di channel Youtube Imago Bali.
[iii] Prembon Kolaborasi dengan tajuk Dalem Balingkang pernah ditayangkan di Bali TV. Videonya dapat diakses di channel Program Bali TV.
[iv] Sendratari Dalem Balingkang pernah dipentaskan oleh Sekaa Truna Truni Banjar Negara Batuan, Gianyar. Videonya dapat diakses di channel Indria Ningsih.
[v] Fragmentari dengan judul ini pernah dipentaskan dalam acara Balingkang Kintamani Festival tahun 2019.
[vi] https://balitribune.co.id/content/goa-jepang-dihiasi-relief-kisah-percintaan-jaya-pangus-dengan-puteri-kang-cing-wie
[vii] Pertautan antara barong landung dengan tokoh Jero Gede Nusa tampaknya lebih kuat dibandingkan dengan kisah ini. Hal ini perlu diteliti dan dipastikan lagi.
[viii] Judul ini hanya sementara saja. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk identifikasi judul yang lebih tepat.
[ix] Judul ini juga tidak disebutkan secara eksplisit di dalam teks, pemberian judul ini hanya didasarkan atas kutipan puraņa riŋ bāli pinih riin, tan wantĕn inucap, lwir pasengan raja-raja (34r-34v).
[x] ana bașamané śri dānawarāja, sawoŋiŋ bāli rāja, kinon apapar untu stri kakuŋ, yan tan maŋkana, tan winéh alakirabi.
[xi] Hubungan antara raja yang bergelar Bhațara Guru Śri Adi Kunti Kétana dan Bhațara Śri Mahā Guru dengan raja sebelum serta setelahnya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam teks.
[xii] Tak disebutkan tahun spesifik masa beliau bertahta.
[xiii] śri māya dānawa, sāmpun kreta locitta, katĕkan jajaka sira, masi ibu nira bathari danu (31v)
Penulis: Putu Eka Guna Yasa
Editor: Adnyana Ole
- BACA artikel lain dari penulisPUTU EKA GUNA YASA









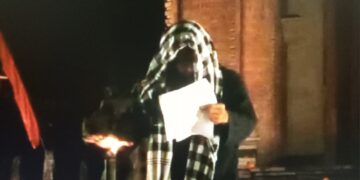













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)










