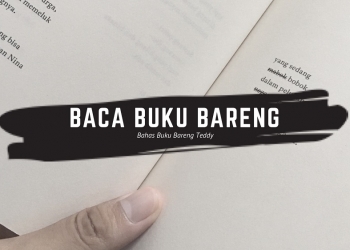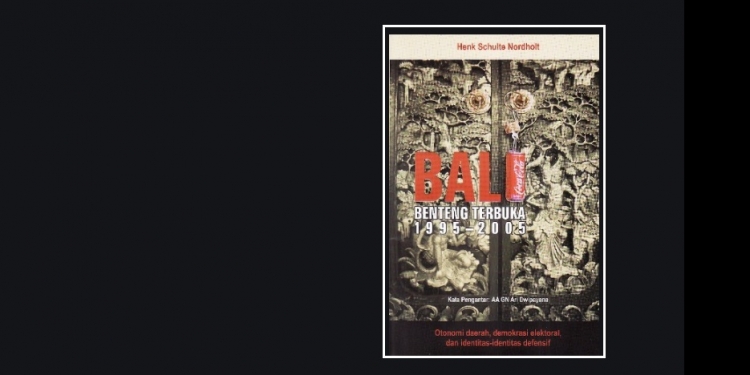Malam itu langkah kaki menuntun saya sampai ke area Ksirarnawa, Art Centre. Tentu bukan tanpa alasan saya bisa sampai disini. Kala itu pemerintah melalui Dinas Kebudayaan menyelenggarakan festival budaya bertajuk “Festival Bali Jani”. Menariknya, festival ini juga mengundang beberapa penggerak literasi memamerkan berbagai buku-buku yang bisa dibawa pulang oleh pembeli.
Pustaka Larasan adalah salah satu penerbit beken yang ikut dalam festival ini. Disinilah saya bertemu dengan buku karya Henk Schulte Nordholt yang dengan ciamik diterjemahkan oleh Arif B. Prasetyo. Buku yang sudah saya dapat lebih kurang 2 tahun lalu, baru saja selesai saya baca. Kali ini saya mencoba membahas buku ini secara sederhana dan tidak meninggalkan substansi yang ingin dibawa oleh penulis.
Menarik Hati Sejak Pandangan Pertama
Sebagai pembaca yang mengutamakan tampilan sampul suatu buku, saya langsung dibuat jatuh cinta oleh sampul buku “Bali Benteng Terbuka 1995-2005” karya Henk Schulte Nordholt. Kombinasi warna cream, putih, hitam, dan merah mendominasi sampul buku yang diterbitkan kali pertama oleh Pustaka Larasan pada Juni 2010 ini. Berlatar belakang pintu khas Bali lengkap dengan ukiran, tungkai pintu beserta gembok yang tidak terkunci. Menariknya huruf ‘I’ pada kata Bali diganti dengan gambar kaleng softdrink yang merajai pasar tak terkecuali Bali.
Menjadi menarik bagi pembaca untuk menerka-menerka maksud dari sampul buku yang buat saya cukup satire. Bali sebagai pulau yang identik dengan budayanya sudah mulai bergeser ke industri pariwisata urban sejak masa kolonial, masyarakatnya mulai menunjukkan keseriusannya terhadap industri ini, terlihat dari berbagai infrastruktur mulai dibangun guna menunjang destinasi wisata. Rakyatnya pun ‘banting setir’ ke dunia pariwisata. Dalam waktu bersamaan, masyarakat Bali juga dituntut mempertahankan tradisi, budaya warisan leluhur yang mulai dirongrong oleh sosok jahat bernama Globalisasi. Rasa-rasanya konflik itu yang ingin disampaikan oleh penulis melalui sampul yang sangat berkarakter ini. Sampul ini menurut saya sangat pantas diganjar penghargaan sebagai sampul buku terbaik.
Buku setebal xxx + 120 halaman ini terdiri dari delapan bab yang semuanya membahas soal Bali medio 1995 – 2005. Yah, sesuai dengan judulnya yang juga menunjukkan Batasan masalah yang diambil oleh penulis. Adapun delapan bab yang dibahas dalam buku ini yakni, Mencari kestabilan (Bab I), Gejolak dan perubahan (Bab II), Kasta dan desa (Bab III), Bentuk-bentuk kekerasan (Bab IV), Negara partai yang tidak stabil (Bab V), Ajeg Bali (Bab VI), Pemilu (Bab VII), dan Melampau Ajeg Bali (Bab VIII).
Bali Mencari Jati Diri
Pasca runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto tahun 1998, berbagai kebijakan baru mulai dibuat dan diterapkan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi dan Otonomi Daerah salah satunya. Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 benar-benar menjanjikan adanya otonomi lebih besar, sekaligus perpecahan dan kesimpangsiuran administratif. Perubahan begitu terasa hingga akar rumput (grassroot), dalam hal ini mulai terbukanya hubungan antara ranah dinas dan adat. Apalagi pada tahun 2001 oleh Pemerintah Provinsi Bali dikeluarkan Perda No.3 Tahun 2001 tentang peran desa adat.
Peraturan ini memberikan wewenang penuh kepada desa pakraman menjalankan urusan internalnya, dan menjadikan dewan desa sebagai otoritas tertinggi. Desa pakraman mendapat perhatian begitu besar mengingat desa pakraman dianggap sebagai pusat kebudayaan sehingga pemerintah mulai mengucurkan dana ke desa pakraman dengan nominal yang tidak sedikit. Namun, hal ini meninggalkan satu permasalahan yang menyangkut hubungan antara aturan adat dan hukum nasional. Karena aturan adat tersubordinasi di bawah hukum nasional yang tentu saja dapat merongrong otonomi yang dimiliki desa pakraman. Tetapi hal baik yang dapat dipetik dari berbagai aturan anyar ini adalah desa pakraman mulai menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat setelah ditekan pada masa orde baru yang mengatasnamakan pembangunan nasional.
Gonjang-Ganjing Bali
Reformasi benar-benar mendatangkan perubahan besar-besaran kepada pulau kecil yang nantinya menjadi tolok ukur pariwisata Indonesia ini. Terbukanya kembali keran demokrasi oleh B.J. Habibie (Presiden RI ke-3) benar-benar disambut antusias oleh masyarakat. Hasil Pemilu 1999 juga tak kalah mengejutkan. Partai besutan Megawati Soekarno Putri berhasil tampil menjadi pemenang, di Bali sendiri PDI-P berhasil mendulang suara sebesar 79,5% dan berhasil menjungkalkan dominasi Golkar yang mulanya pada Pemilu 1997 mendulang suara 93,5% menjadi hanya 10,5% (hal. 20).
Kekalahan Megawati dalam pemilihan Presiden RI ke-4 menyulut kerusuhan besar di Bali. Bali sebagai “Rumah Banteng” tidak terima atas kekalahan ini, penulis juga menyebutkan hal tersebut menunjukkan sentimen anti-Jawa dan anti-Muslim. (Mungkin) kerusuhan besar yang terjadi di sebagian besar daerah Bali ini menjadi kerusuhan terbesar yang terjadi di Bali pasca Reformasi. Hal ini mengingat kerusuhan sampai merusak berbagai fasilitas dan Gedung pelayanan publik. Beberapa kediaman kepala daerah yang berlatar belakang Golkar pun tak luput dari serangan. Menariknya, penulis menunjukkan bahwa ada mobilitas orang-orang tak dikenal yang berhasil memainkan peran utama dalam kerusuhan. Hem, bahkan sejak dulu aksi-aksi sudah disusupi ya.
Pemilihan kepala daerah pasca reformasi yang dimulai sejak tahun 2000 juga menandakan krisis di tengah partai pemenang, PDI-P di Bali. Berbagai kekalahan menimpa partai berlambangkan banteng moncong putih ini. Pada tahun 2000 terpilihnya Winasa di Jembrana berhasil menjungkalkan jago banteng di kabupaten itu. Begitu juga dengan pemilihan selanjutnya, mulai dari Buleleng, Karangasem, hingga Badung lepas dari kuasa PDI-P. Hal ini dikarenakan konsolidasi internal yang kurang, hubungan yang kurang harmonis antara pusat dan daerah, serta konflik internal yang terjadi antar sesama kader sehingga membuka peluang bagi tokoh-tokoh independent melaju menjadi orang nomor satu di daerahnya masing-masing. Puncaknya adalah kekalahan Megawati Soekarno Putri dalam perebutan kursi Presiden pada Pemilu Tahun 2004. Meski mendulang suara yang dominan di Bali, nampaknya hal tersebut tak membantu sang Ketua Umum untuk menduduki kembali kursi Presiden RI.
Kalau membaca buku ini dan mencocokkan dengan referensi bacaan lain, saya rasa kekalahan Megawati dalam Pemilu Tahun 2004 dikarenakan kepercayaan diri yang begitu tinggi. Hal serupa pun terjadi pada pemilihan presiden tahun 1999 saat presiden masih ditentukan dalam siding MPR RI. Kepercayaan diri terlihat dari minimnya kunjungan sang Ketua Umum ke Bali, begitu pula dengan absennya pada perhelatan Pesta Kesenian Bali saat itu. Padahal jadwal pembukaannya sudah disesuaikan dengan jadwal sang presiden, namun tetap saja ia tak hadir.
Menyambut Wacana Ajeg Bali Beserta Turunannya
Istilah Ajeg Bali kali pertama dipublikasikan oleh harian Bali Post pada 16 Agustus 2003, tepat pada peringatan ulang tahun ke -55 tahun. Wacana Ajeg Bali dijadikan kata kunci dalam rencana induk baru yang menghormati keseimbangan atau istilah Bali-nya Tri Hita Karana. Ajeg Bali juga menjadi semboyan yang mengisyaratkan kebutuhan akan suatu pertahanan diri, social budaya. Namun hingga detik ini pun, tak jelas wacana konkret soal Ajeg Bali ini.
Dalam hal ini Ajeg Bali seakan mengajak masyarakat Bali untuk Bersatu, melindungi diri sendiri, sanak saudara, tradisi dan budaya dari ancaman luar. Secara tidak langsung masyarakat Bali diajak untuk mencari “musuh bersama” guna Bersatu melindungi apa yang dimiliki Bali. Terjadinya Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 semakin membuat wacana Ajeg Bali. Wacana Ajeg Bali menjadi induk dari berbagai kekerasan. Salah satunya adalah massifnya aksi swiping yang dilakukan oleh polisi berbasis desa adat (pecalang). Pasca Bom Bali I, Pemerintah Kota Denpasar langsung menerapkan kebijakan izin tinggal bagi pendatang. Tak tanggung-tanggung, pembuatan izin tersebut dipungut biaya hingga Rp400.000.
Pendek kata, ancaman disodorkan oleh dekadensi barat dan intrusi Islam. Artinya ancaman tersebut berasal dari luar Bali, dan wacana Ajeg Bali menjadi narasi penangkal yang cukup efektif. Mengingat wacana Ajeg Bali berhasil menghegemoni ruang-ruang percakapan masyarakat di Bali. Sentimen terhadap dua hal tersebut juga masih bisa kita lihat hingga sekarang.
Namun sayangnya masyarakat Bali tak menyadari bahwa ancaman yang paling berbahaya malah datang dari dalam diri. Masyarakat yang abai terhadap tradisi, gagal melanjutkan informasi-informasi penting terkait sejarah keasalmulaannya, lalai dengan berbagai kebudayaan yang harusnya ia lanjutkan adalah segelintir permasalahan yang kini kita hadapi bersama. Melihat pemuda-pemudi Bali yang masih menaruh perhatian lebih terhadap warisan leluhur dianggap “kuno”. Apakah itu yang kita mau? Bukankah musuh yang paling sulit dikalahkan adalah diri sendiri? Bahkan salah satu petinju terkenal pernah mengatakan bahwa cara bertahan terbaik adalah dengan cara menyerang.
Bagi saya, buku ini mengajak saya untuk mendalami berbagai persoalan yang terjadi di Bali pada medio waktu 1995-2005 yang permasalahannya masih bisa saya rasakan hingga kini. Setelah mendalami, tentu mencari solusi bersama agar Bali terlepas dari bayang-bayang kehancuran. Ohh, iya bagi saya sendiri sudah tidak zamannya lagi menyalahkan pihak luar atas kemunduran yang terjadi saat ini di Bali. Kalau bagi kalian bagaimana? [T]
_____
BACA ULASAN BUKU LAIN DARI TEDDY