ADA kisah pilu pada pertengahan Oktober 2023 lalu. Gadis (23) penyandang disabilitas rungu wicara diperkosa oleh kerabatnya sendiri yang berumur 55 tahun sampai hamil. Pelaku melakukan perbuatan biadap itu sebanyak 3 kali di rumah si gadis. Akibatnya, si korban hamil dan merasa depresi.
Pada tahun dan di daerah yang sama, kekerasan seksual kembali terjadi. Kini lebih memilukan, sebab korbannya anak-anak. Kasus ini mulai menguar saat terdapat indikasi penyakit kelamin yang dialami korban. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan awal dengan sejumlah saksi, korban diduga disetubuhi sebanyak 5 kali di salah satu desa dan dua terduga pelaku lainnya melakukan persetubuhan dan pencabulan di dua tempat dan kejadian yang berbeda.
Mei 2024, kejadian serupa kembali terjadi. Gadis tujuh tahun diperkosa oleh tetangganya sendiri—yang sudah berumur setengah abad. Sedangkan dua tahun sebelumnya, gadis 15 tahun dirudapaksa ayahnya sendiri. Tak berhenti di situ, kasus semacamnya—kekerasan maupun pelecehan seksual—terus saja terjadi meski para penjahat itu sudah mendekam di penjara. Ada saja korban baru, ada saja predator baru. Dan semua kasus di atas, ironisnya, terjadi di Kabupaten Buleleng, Bali.
Sudah jamak diberitakan, memang, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Buleleng telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Data Sentra Mahatmiya Bali menunjukkan, sepanjang tahun 2024 hingga Januari 2025, tercatat 30 kasus kekerasan seksual dengan lima kasus di antaranya terjadi pada bulan Januari saja. Sedangkan di Tabanan tercatat 3 kasus; Badung 2 kasus; Denpasar 15 kasus; Gianyar 9 kasus; Bangli 6 kasus; Klungkung 2 kasus; Jembrana 8 kasus; dan Karangasem 8 kasus. Sungguh menakutkan.
Menurut para ahli yang berseliweran di internet, kondisi tingginya angka kekerasan pun pelecehan seksual terhadap anak maupun perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pengetahuan atau pendidikan seks bagi anak usia sekolah, lingkungan yang rawan terhadap gangguan atau pelecehan secara seksual—bahkan di lingkungan keluarga sendiri dan di lembaga pendidikan (sekolah dan kampus), dan lain sebagainya.
Namun, terlepas dari faktor-faktor tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum harus serius dalam melakukan pencegahan terjadinya kasus baru dan memproses para pelaku pelecahan dan kekerasan seksual seberat-beratnya. Perlindungan terhadap korban juga harus menjadi prioritas. Dukungan itu termasuk kesiapan LPSK RI dalam memberikan perlindungan kepada korban sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam perspektif hak asasi, kekerasan maupun pelecehan seksual merupakan kasus yang masuk sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Sedangkan khusus aturan tentang anak dalam instrumen HAM dibahas sebanyak 13 pasal di dalam pasal 53-66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Kekerasan seksual sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Pada Pasal 76 C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Urgensi Rumah Aman?
Meski demikian, hingga saat ini, terkait perlindungan korban dan saksi, belum ada tempat aman atau semacam itu di Buleleng. Belum ada rumah aman, atau rumah perlindungan (safe house) yang memadai untuk menangani korban kekerasan dan pelecehan, sehingga panti asuhan menjadi solusi sementara tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Keputusan untuk menempatkan korban di panti asuhan jelas bukan solusi yang paling baik—walaupun panti asuhan dianggap sebagai tempat yang aman dan jauh dari lingkungan yang mungkin mengingatkan korban pada kejadian traumatis.
Namun, keputusan ini memunculkan kekhawatiran baru. Potensi diskriminasi, perisakan (bullying), atau malah pelecehan dan kekerasan seksual kembali, di lingkungan panti asuhan menjadi momok yang menghantui para penyintas, keluarga mereka, hingga para pendamping rehabilitasi. Situasi ini menjadi alasan mendesak bagi Pemerintah Buleleng untuk segera memiliki rumah aman sebagai solusi utama di samping solusi-solusi pencegahan lainnya.
Rumah aman yang dimaksud tidak hanya sekadar sebagai tempat perlindungan fisik, lebih dari itu, pula jaminan pemulihan trauma (psikologis) dan hal-hal yang dapat mendukung keberlangsungan hidup penyintas pelecehan atau kekerasan seksual atau KDRT, perisakan, dll. Pemerintah—dan kita semua—harus berkomitmen dalam melindungi warga yang paling rentan.
Secara legalitas, dasar hukum untuk menyediakan rumah aman sudah jelas. Pasal 5 ayat (1) huruf K Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara yang aman. Namun, tanpa realisasi nyata, seperti bidang-bidang lain, undang-undang ini hanya menjadi formalitas di atas kertas, tanpa memberi dampak signifikan terhadap apa pun.
Pada 20 November 2024, saat debat Pilkada Bali 2024 dan kampanye di Buleleng, pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster menjadi harapan bagi masyarakat. Ia berjanji untuk membangun rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual (RPPA) di seluruh kabupaten di Bali.
Menurut Koster, keberadaan RPPA di seluruh Bali sangat penting untuk memberikan layanan terpadu bagi korban kekerasan maupun pelecehan seksual, mulai dari pendampingan hukum, psikologis, hingga rehabilitasi. “Dengan adanya rumah perlindungan ini, kita dapat memberikan rasa aman dan memutus rantai kekerasan,” ujarnya saat berkampanye di Buleleng bersama Gen Z, tahun lalu, sebagaimana dikutip dari Bali Express (18/11/2024).
Seperti janji Koster, rumah perlindungan akan dilengkapi fasilitas ruang konseling, layanan kesehatan, dan tempat penampungan sementara. Selain itu, tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum akan disiagakan untuk memberikan layanan maksimal. Di sela-sela mengumbar janjinya, ia mengimbau masyarakat untuk lebih aktif melaporkan jika mengetahui adanya tindak kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan dan anak.
(Masyarakat harus lebih aktif melapor. Itu dapat membantu pemerintah dan aparat hukum dalam menanggulanginya. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak orang yang enggan melaporkan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual—dengan berbagai alasan—yang terjadi, sebagaimana cerita Made Adnyana Ole kepada Yahya Umar dalam siniar “Kekerasan Seksual Anak dan Janji Rumah Aman Koster-Giri” dalam Podcast Lolohin Malu di kanal YouTube tatkala dotco)
Di Buleleng pernah ada rencana pembangunan rumah aman. Tetapi sampai sekarang tidak pernah terwujud dengan berbagai alasan klise. Dan di lain pihak, kepada Bali Express, saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna pernah ingin patungan dengan Kepala Dinas Sosial untuk membangun rumah aman. Tapi itu juga tidak terjadi.
“Rumah aman sepertinya belum dianggap penting. Secara politis tidak menguntungkan,” ujar Yahya Umar dalam siniar di Youtube tatkala dotco. “Itu persoalannya. Membangun rumah aman dianggap tidak dapat menarik suara konstituen,” Made Adnyana Ole menimpali.
Tetapi, apakah rumah aman adalah solusi terbaik? Mungkin saja tidak. Mengingat, awal Juli 2020, sebagaimana disampaikan Muhamad Heychael dalam esainya, “Kekerasan Seksual dalam Dua Scroll: Liputan Pemerkosaan Anak di Rumah Aman”, justru pemerkosaan dilakukan oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur terhadap anak perempuan berinisial NF.
Kita tahu P2TP2A adalah lembaga yang berfungsi sebagai rumah aman bagi mereka yang mengalami pemerkosaan. Namun, ironisnya, kala dalam lindungan lembaga—yang dianggap dapat menjamin keamanan korban—tersebut NF malah kembali diperkosa. Miris.
Sampai di sini, sebelum mendirikan atau membangun rumah aman, orang-orang yang akan bertugas di dalamnya harus melalui proses yang ketat. Lantas, proses rekrutmen atau track record seperti apa yang semestinya menjadi kriteria penilaian rekrutmen? Patut dipikirkan dan dirumuskan lebih lanjut.
Dan ucapan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Theresia Iswarini yang meminta memikirkan aspek gender dalam perekrutan pegawai rumah aman dan menilai sebaiknya pegawai laki-laki tidak diberi tugas yang bersentuhan langsung dengan penyintas atau sebagai pengambilan keputusan bisa menjadi pertimbangan penting.
Berhenti Victim Blaming
Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak berpotensi memberikan trauma jangka panjang bagi penyintas. Belum lagi stigma negatif yang justru kerap salah sasaran. Selama ini korban malah lebih sering mendapat stigma negatif daripada pelaku. Banyak orang belum bisa melihat atau menilai dari perspektif korban pelecehan dan kekerasan seksual dan tak sedikit cenderung menghakimi korban daripada pelaku.
Coba lihat kejadian bulan Mei 2023 lalu, ketika seorang karyawati perusahaan kosmetik berinisial AD melaporkan HK, manajer perusahaan tempatnya bekerja, ke Mapolres Metro Bekasi atas ajakan staycation sebagai syarat agar kontrak kerjanya diperpanjang. Kejadian ini viral di media sosial.
Tetapi sayang, alih-alih fokus pada pelecehan seksual yang dialaminya, AD malah banyak menuai komentar victim blaming dari warganet. Sebagian netizen malah tertuju pada penampilan AD. Dari penerawangan konyol atas raut wajah, bentuk tubuh, dan pakaian AS, warganet menganggap AD sebagai “pemain” atau “pro player”. AD malah dianggap sebagai perempuan yang pantas dilecehkan. Hal ini sering menjebak banyak orang pada mitos bahwa pemerkosaan adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh perempuan.
Mengutip Muhamad Heychael (2020), dalam panduan berjudul Moving toward prevention: A guide for reframing sexual violence yang dibuat oleh Berkeley Media Studies Group dan National Sexual Violence Resource Center (NSVRC), ada tiga mitos mengenai pemerkosaan yang kerap digambarkan oleh media. Pertama, pemerkosaan sebagai peristiwa tunggal yang tidak berhubungan dengan permasalahan struktural seperti ketimpangan relasi gender dan kuasa antara pelaku dan penyintas. Kedua, pemerkosaan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu yang terlampau jahat atau bad apple. Terakhir, pelaziman pemerkosaan sebagai masalah yang tak mungkin atau terlalu besar untuk diselesaikan.
Victim blaming bukan respons baru terhadap kekerasan seksual. Dalam reaksi terhadap kekerasan seksual, banyak orang biasanya menyalahkan korban yang utamanya perempuan karena menggunakan pakaian tertentu atau melakukan sesuatu yang dianggap mengundang kekerasan seksual. Studi menunjukan bahwa laki-laki lebih sering melakukan victim blaming dibandingkan perempuan (Grubb, 2012).
Lebih lanjut, dalam esai “Victim Blaming dan Imaji tentang Perfect Victim”, Bhenageerushtia menyampaikan teori atribusi defensif menjelaskan bahwa mengatributkan penyebab peristiwa negatif pada perilaku atau tindakan korban memungkinkan orang-orang melepas tanggung jawab atasnya. Bagi perempuan yang menyalahkan korban perempuan, victim blaming membuat mereka merasa tidak lebih rentan dari korban (Pinciotti dan Orcutt, 2019). Sementara itu, bagi laki-laki, yang lebih sering melakukan victim blaming dibanding perempuan, victim blaming memungkinkan mereka menangkis bahwa kelompok gendernya bertanggung jawab atas kasus-kasus kekerasan seksual.
Coba kita lihat dalam konteks unggahan berita pelecehan atau kekerasan seksual di Buleleng. Pada 4 Januari lalu, Tribun Bali mengunggah link berita berjudul “Aksi Begal Alat Vital di Buleleng Viral, Ciri-Ciri Pelaku Terungkap” di Facebook. Ada satu komentar yang aneh di sana. Begini komentarnya, “Kan dia cuma meniru dan melestarikan budaya leluhur Nusantara” dengan tiga emot tertawa. Terlepas apakah ia bercanda atau apa tapi komentar seperti inilah yang sebaiknya dihentikan.
Lebih dulu, Desember 2024, Tribun Bali juga mengunggah link berita dengan judul “NEKAT Hamili Murid Lantas Dipecat! Polisi Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Oknum PPPK di Buleleng” di Facebook. Dua warganet kemudian berkomentar. Pertama, “Kalo udh SMP hamil berarti mereka melakukan suka sama suka, lebih baik di nikahkan saja demi status anak di kandungan, kasian anak yg di perut nanti lahir GK ada bapak,,dan sedih nya lagi nanti jika ank trsebut beranjak dewasa anak malu di buli jika di panggil anak haram,”. Kedua, “Klk dihamili langsung suruh nikahin”. Ini jelas dua komentar yang asal-asalan. Menikahkan penyintas dengan pelaku jelas bukan solusi yang tepat. Apalagi pelaku sudah memiliki istri.
Pada 2023, beredar video CCTV seorang mahasiswi Stikes Buleleng yang dilecehkan dan hendak diperkosa oleh dosennya sendiri. Video tersebut viral dan menuai banyak tanggapan, termasuk komentar victim blaming. Beberapa komentar tersebut sebagai berikut:
“Dia yg ngundang masuk kamar, dia yg melapor di lecehkan, klo gitu mending pasang tarip aja berapa sejam.”
“Ehhhmm, ttp aja mahasiswa salah. Kesel, knp masih ttp jadi korban saja. Intinya klu ga dikasi peluang dan kesempatan oleh mahasiswanya, tdk mungkin terjadi pelecehan. Pintar2 wanita membawa diri jika tidak ingin dilecehkan. Knp harus memberikan alamat sih ke dosen, tengah malam, mana masuk kamar kos pula. Prnh menjadi mahasiswa, ga prnh sampai terjadi sprti itu, karena kita bisa menempatkan diri.”
“Ya ngapain mempersilakan cwo datang ke kosan?”
“Sudah terbiasa kalo gini2 mah dan tak banyak yg di umbar aja.”
“Cewek juga kynya gampangan.”
Victim blaming dan pemakluman terhadap kekerasan seksual hanya akan mendorong kekerasan seksual itu sendiri. Pun, semakin banyak perempuan yang bakal enggan mengungkapkan kekerasan seksual yang dialami karena berpikir mereka tidak cukup terlihat sebagai korban. Jadi, alih-alih berkomentar yang menyalahkan penyintas atau komentar seksis, menertawakan, berasumsi, atau komentar apa pun yang tak relevan pada kasusnya, kita mesti mendukung korban sampai kebenarannya terungkap. Dukungan tersebut akan mendorong suara-suara korban pelecehan seksual dan saksi untuk melapor. [T]
Reporter/Penulis: Jaswanto
Editor: Adnyana Ole








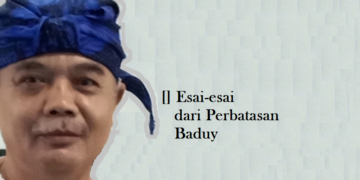














![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)










