Dharma Pawayangan merupakan pustaka khusus yang isinya memuat petunjuk yang membimbing para dalang dalam melaksanakan dharma kewajibannya sebagai dalang. Pustaka Dharma Pawayangan merupakan rambu-rambu yang mengikat dalang untuk tidak menyimpang dari dharma yang dilakoninya. Spiritual (jnyana hening) yang menjadi dasar dan tuntunan dalam segala laku (tri kaya parisudha) sehingga senantiasa berada dalam kesadaran sunya (dedeg pageh tan obah, landuh) (Sugriwa, 1963: 21; Hooykass, 1973: 17; Rota, 1992: 3). Teks Dharma Pawayangan tidak hanya merupakan tuntunan bagi para dalang dalam mempelajari ketrampilan ngwayang, akan tetapi mencakup ketrampilan dalam menghayati dan melaksanakan unsur-unsur metafisik dari pertunjukan wayang.
I Gusti Bagus Sugriwa (1963); I wayan Kawen (1976); I Ketut Rinda (1976); dan Ida Bagus Sarga (1976) menyebutkan bahwa penguasaan isi teks Dharma Pawayangan dan penggunaannya sebagai tuntunan dalam melaksanakan pagelaran wayang, merupakan keharusan bagi setiap dalang. Sehingga diharapkan dengan mempelahari isi naskah tersebut disadari atau tidak akan meningkatakan pengetahuan dan ketrampilan dalang sebagai seniman. Sugriwa (1963: 21 dalam Wicaksana, 2018: xix) dengan tegas menyatakan bahwa Dharma Pawayangan sebagai ajaran suci bagi para dalang yang statusnya digolongkan sebagai sulinggih. Tidak sedikit sebenarnya keterampilan dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin menjadi dalang. Disamping harus terampil memainkan wayang, terampil menabuh gamelan, menguasai berbagai jenis kakawin (tembang), menguasai bahasa Kawi dan bahasa Bali secara baik, memiliki pengetahuan umum yang luas.
Dalam teks Dharma Pawayangan memuat spiritual, dimensi agama, susastra, dan estetika susastra weda yang memuat tentang dunia ide/gagasan dunia dewani mengandung keindahan spiritual menuju pada Tuhan. Dalang dengan segala kesadarannya (pradhana) dituntun oleh Yang Maha Kuasa (Sanghyang Iswara Dewaning ringgit) menyuarakan intisari Weda dalam alur dramatic lakon-lakon wayang di balik kelir, dan wayang dengan segala aparatusnya sebagai prakerti yakni unsur ketidaksadaran.
Dalang memuja Sang Hyang Tigajnyana, Sanghyang Gurureka, Sang Hyang Saraswati, Sang Hyang Kawiswara sebagai ilham penuntun dari Tuhan (Sang Hyang Suksma). Konsep teo- estetikanya adalah; Gurureka adalah penjaga pemikiran (idep), mengilhami alur cerita dalam pertunjukan wayang, Saraswati sebagai asala mula bentuk verbal, terutama teks tertulis (sabda wayang), dan Kawiswara memberdayakan kekuatan vokal swara (bayu) untuk menghidupkan cerita dan bahasa pertunjukan wayang.

I Gusti Putu Sudarta (penulis) sedang membaca lontar dharma pawayangan | Foto: Dok. pribadi
Dharma Pawayangan secara garis besarnya digolongkan menjadi 10 bagian (Hooykaas seperti dikutip Rota (1992: 29-31). Berikut uraian singkat dengan merujuk bait teks Dharma Pewayangan yang disarikan dari Disertasi yang berjudul “Implementasi Estetika Hindu Dharma Pawayangan Oleh Dalang Wayang Kulit Di Bali” Oleh I Dewa Ketut Wicaksana, Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018.
1. Bagian Pendahuluan
Bagian ini mengangdung hal-hal yang bersifat metafisik seperti: (a) merupakan kewajiban setiap dalang agar mempelajari dan melaksanakan isi Lontar Dharma Pawayanga; (b) sang amangku (dapat) bertindak sebagai bumi, butha, dan dewa (“…..mawak gumi, mawak butha, mawak dewa); (c) hendaknya sang mangku dalang maklum akan adanya yang disebut dalang caturlokapala (4 macam dalang) seperti; dalang samirana, dalang anteban, dalang sampurna, dan dalang jaruman; (d) tempat para tokoh wayang dalam badan manusia, seperti wayang kiri (pengiwa) bertempat di hati, dan wayang kanan (panengen) bertempat di nyali; (e) demikian juga panakawan (pendasar/panasar) Delem, Sangut, Merdah, Tualen dalam tubuh.
(a) Merupakan kewajiban setiap dalang agar mempelajari dan melaksanakan teks Dharma Pawayangan, antara lain:
1) “…..Om awignamastu namos sidham. Niha Tutur Purwa Wacana ngaranya, dharma pawayangan, wenang ingangge de sang amangku dalang, ring wong tumaki-taki mangwayang, Sudha maka utamaning dalang….”
Terjemahannya: Ya Tuhan semoga hamba tidak ada halangan dan selalu dalam lindunganMu. Ini adalah tutur purwa wacana (sastra tatwa awal yang utama) yang disebut dharma pawayangan, harus diketahui dan digunakan oleh sang mangku dalang, ketika mulai belajar ‘ngewayang’, kesucian merupakan keutamaan sang dalang.
2) “…Kawruhakna kang dalang, ring sariraning suksma, kang dalang ring pantaraning papusuh, gagadingnya, rupanya endah, swaranya sakawuwus-wuwus, tutur jati ngaranya, suksma, triwikrama tingkahing suksma, ndi ya ta lwirnya…”
Terjemahannya: Ketahuilah oleh sang dalang, dalam diri seorang dalang di ujung jantung pusatnya, beragam wujud yang indah, suaranya bergetar, membahana memenuhi ruang, hakekat diri sejati yang bersifat sangat halus dan rahasia, bertransformasi melampaui lapisan-lapisan kesadaran, diantaranya adalah….
6) “…Mwang sang ngamong sang mangku dalang, tiga lwiran ing Hyang Suksma, Sanghyang Gurureka ring idep, Sanghyang Saraswati ring canteling lidah, Sanghyang Kawiswara ring wayaning sabda…”
Terjemahannya: juga yang melindungi sang dalang adalah Tuhan dalam tiga murti manifestasi yaitu Sanghyang Gurureka ada dalam benih pikiran, Sanghyang Saraswati berada pada cantelin lidah, Sanghyang Kawiswara pada sumber suara yang bertransformasi dalam berbagai rupa.
(b) Sang Amangku Dalang (bisa) bersifat dan bertindak sebagai bhumi, bhuta, dan dewa.
5) “…Sang mangku dalang mawak gumi, mawak butha, mawak dewa, dalang ngaranya waneh, karana dadi Siwa, karana dadi Parama Siwa, karananya dadi Sada Siwa, karana dadi Hyang Achintya, mapan Sanghyan Acintya panunggalan ring bhuwana kabeh, wenang umilihaken lungguhnya, mangkana sangkanya ngaran dalang, sira ta wenang mangwasaken kata, prayatnakna de sang amangku dalang den apened, matemu ring papusuh, metu sabdanya, Mahadewa witning sabda, Wisnu pukuhing sabda, Brahma madyaning sabda, Iswara tungtungning sabda, Bhatara Guru mulaning sabda, ya sangkaning mulih ring kuwungning ati, ri witning ati ngaranya, ya ta dadi Hyang Ening, ya dadi Hyang Amerta, ya dadi pati, ya dadi urip, metu aksara roro, Am, Ah, ya dadi sor luhur, akasa lawan pertiwi kalinganya, ala kalawan ayu, dewa lan buta…”
Terjemahannya: Sang mangku dalang menjadi wujud bumi, berwujud bhuta, berwujud dewa, begitulah dalang, karenanya bisa menjadi Siwa, Paramasiwa, menjadi Sadasiwa, Sanghyang Acintya menyatu dengan alam semesta, bisa berada dimana saja, itulah yang disebut dalang. Beliau menguasai cerita peristiwa semesta alam. Hendaknya diperhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh, semuanya bertemu dan menyatu di jantung menjadi suara (sabda). Mahadewa merupakan awal dari suara, Wisnu merupakan pangkal suara, Brahma merupakan tengah suara, sedangkan Iswara merupakan ujungnya (akhir) suara, Bhatara Guru mula (penyebab) suara, itu yang menyebabkan pulang di lingkaran dalam hati, asal mulanya hati namanya. Itu yang menyebabkan beliau mewujud menjadi Sanghyang Hening dan juga menjadi Sanghyang Amerta. Menjadi mati dan hidup, menjadi dua aksara Ang, Ah (purusa-pradana), yang menyebabkan ada atas-bawah, langit dan tanah, karenanya ada buruk dan baik, dewa dan bhuta.
(c) Tempat para tokoh wayang dalam badan manusia, seperti wayang kiri (pangiwa) bertempat di Hati, dan wayang kanan (panengen) bertempat di nyali:
3) “…Punang wayang pangiwa mulih ring ati, wayang panengen mulih ring nyali, Krepa Swatama Salya mulih ring tengen, kakayonan mulih ring tengah pupusuh, mawa carita wayang….”
Terjemahannya: Wayang yang di kiri kembali ke hati, wayang yang kanan kembali ke empedu, Krepa Swatama Salya kembali di kanan, kayonan kembali dalam jantung, menjadi cerita wayang.
(d) Demikian juga pandasar/panasar (panakawan): Delem bertempat di jantung (pupusuh), twalen di hati, Mredah bertempat di ginjal, dan Sangut di nyali.
4) “…Malih kang pandasar, Delem magenah ri pagantunganing papusuh, Twalen magenah ri pagantunganing ati, Mredah magenah ri pagantunganing babuwahan, Sangut magenah ri pagantunganing nyali….”
Terjemahannya: Lagi tentang panakawan, Delem bertempat di jantung, Twalen bertempat di pagantunganing hati, Mredah bertemat di pegantunganing ginjal, Sangut bertempat di pagantunganing empedu.
2. Bagian yang menggambarkan perbuatan (laku, tikas) dan mantra-mantra yang dianggap penting bagi sang dalang, antara lain:
(a) Apa yang mesti dilakukan ketika pergi ngewayang dan keluar dari pintu gerbang pekarangan (pamesuan); (b) apa yang diperbuat atau dilakukan pada waktu sampai di rumah orang yang menanggap wayang; (c) mantra untuk pasepan (dupa); (d) mantra pada waktu nebah keropak ping tiga (mengetuk gedog/kotak wayang tiga kali); (e) mantra pada waktu mengambil wayang; (f) mantra pada waktu akan memainkan Kekayonan; (g) hal-hal yang harus dilakukan pada waktu mulai duduk ngwayang, dan mantra yang diucapkan, seperti meningktakan volume suara gedog/kotak, cepala, dan dalang (pangembak swaraning kropak, cepala mwang swaraning amuwus; (h) mantra pada waktu membuat pengeger (menarik perhatian penonton), seperti, pengalup swara (suara besar dan panjang), pangraksa jiwa (jiwa sang dalang menjadi aman), pangurip wayang (wayang terasa hidup), nyimpen wayang (menyimpan wayang), penyimpenan pandasar (menyimpan wayang punakawan), serta bagian yang menggambarkan perbuatan dan mantra-mantra yang dianggap penting bagi sang dalang.
(a) Apa yang mesti dilakukan ketika pergi ngewayang dan keluar dari pintu gerbang pekarangan (pamesuan).
“…Mwah yan sira lunga mangwayang, yan sira lumaku, mandeg sira ring pameswanira, tatabana uswasanira, yan adres kiwa, suku kiwa tindakang rumuhun, yan adres tengen, suku tengen tindakang rumuhun, yan sama adresnya, mancogan laris lumaku…”
Terjemahannya: Jika dalang pergi ngewayang, saat kamu berjalan, berhenti sejenak di depan pintu gerbang pekarangan, Tarik dan hembuskan nafas, rasakan kalau deras hidung kiri, kaki kiri melangkah duluan, kalau deras hidung kanan, kaki kanan melangkah duluan, kalau keduanya sama deras meloncat lalu berjalan.
Untuk bagian selanjutnya pada bagian dua ini tidak diuraikan lagi karena bagian pendahuluan ini menarik dibahas dengan harapan dapat memahami dengan lebih jelas apa yang dimaksud dalam teks bertolak dari beberapa penekanan yang penulis anggap penting untuk didiskusikan.
Kalau menyimak bagian pendahuluan dari Lontar Dharma Pawayangan yang menguraikan tentang dharmaning dalang, disiplin, kewajiban, dan siapa sesungguhnya sang dalang, akan didapati phrase kata-kata petunjuk, yang sesungguhnya mengacu kepada kesucian, panunggalan alam semesta, penyatuan kepada dewa yang dipuja, dan kesadaran yang berada pada tingkat pencerahan supra (jnyana hening).
Sudha maka utamaning dalang yang menyatakan bahwa dalang harus senantiasa berada dalam kesucian lahir bathin. Kesucian tetap terjaga dengan menjalankan sadhana atau disiplin sehingga pikiran tidak lagi memerintah dengan segala keinginannya yang tidak pernah habis. Pikiran menjadi berada dalam keadaan dedeg landuh (jnyana hening).
Rupanya endah, swaranya sakawuwus-wuwus, tutur jati ngaranya, suksma, triwikrama tingkahing suksma, ketika dalang melampau dimensi ruang dan waktu, dalang dalam posisi di dalam Padma hredaya berwujud beragam rupa, suara membahana memenuhi dan melampaui segala pemaknaan rupa, hakekat diri sejati yang bersifat sangat halus dan rahasia, bertransformasi melampaui lapisan-lapisan kesadaran.
Hyang Suksma, Sanghyang Gurureka ring idep, Sanghyang Saraswati ring canteling lidah, Sanghyang Kawiswara ring wayaning sabda…”
Seorang dalang selalu berada dalam keheningan yang terjaga, berada dalam kesadaran budhi (bodhi citta) yang telah melampaui lapisan-lapisan kesadaran rendah (citta, manah, ahamkara). Kama (obsesi, nafsu keinginan) tidak lagi menguasai pikiran karena pikiran itu sendiri telah terlampaui. Keheningan adalah Hyang Suksma, ketika berada dalam keheningan berada dalam kesadaran ilahi yang tidak bisa dijelaskan. Dalam terangnya budhi akan senantiasa bisa menghadirkan ilham (Sanghyang Gurureka, idep), mendapatkan pengetahuan pencerahan (Sanghyang saraswati, sabda), dan menumbuhkan kreativitas penciptaan (Sanghyang Kawiswara, bayu). (duk manahe tan memanah, ring budine tan mabudhi, ring tawange tan manawang, ditu ida jenek linggih, ditu ida rumaga jati, sangkan arang anak tahu, wireh Ida tanpa rupa,twara tepuk yan tan purun ngutang rasa).
Sang mangku dalang mawak gumi, mawak butha, mawak dewa.
Sang mangku dalang menguasai semua sifat-sifat alam dan kekuatan-kekuatan alam sehingga menjadi sakti, namun tidak terikat dan melampaui sifat-sifat itu.
Dalang ngaranya waneh, karana dadi Siwa, karana dadi Parama Siwa, karananya dadi Sada Siwa, oleh karenanya sang mangku dalang senantiasa berada dalam kesadaran Siwa.
Karana dadi Hyang Acintya, mapan Sanghyang Acintya panunggalan ring bhuwana kabeh,
Manunggal dengan keberadaan, senantiasa selaras dengan alam semesta, keberadaan dan ketiadaan menyatu, berpikir, pikiran, dan yang dipikirkan telah lebur, itulah Hyang Acintya, Sanghyang Acintya.
Wenang umilihaken lungguhnya, mangkana sangkanya ngaran dalang, sira ta wenang mangwasaken kata, sang mangku dalang mengetahui dan menguasai berbagai cerita tentang alam semesta, peristiwa dan berbagai konflik dan fenomena kehidupan, dan solusi pembebasan dari peristiwa itu, sehingga mampu menuturkan kisah dan peristiwa dengan indah dan mencerahkan.
Prayatnakna de sang amangku dalang den apened, matemu ring papusuh, metu sabdanya, Mahadewa witning sabda, Wisnu pukuhing sabda, Brahma madyaning sabda, Iswara tungtungning sabda, Bhatara Guru mulaning sabda, ya sangkaning mulih ring kuwungning ati, ri witning ati ngaranya, ya ta dadi Hyang Ening, ya dadi Hyang Amerta, ya dadi pati, ya dadi urip, metu aksara roro, Am, Ah, ya dadi sor luhur, akasa lawan pertiwi kalinganya, ala kalawan ayu, dewa lan buta…” Sang mangku dalang senantiasa harus tetap waspada, selalu berada dalam keadaan jaga, dalam kesadaran padma hati (hredaya), selaras dengan alam, badan menjadi instrument tabung (hologram) untuk menerima vibrasi alam semesta sehingga sadar akan asal mula suara Ilahi Nada Brahma. Saat vibrasi selaras dengan paranawa OM atau Nada Brahma suara awal yang melahirkan kehidupan, pranawa dalam diri menjadi sabda, sabda yang bertransformasi mewujud menjadi bija aksara (sacred syllable) Ang, Ah, menjadi dualitas yang hadir untuk keberlangsungan alam semesta, hidup-mati, baik-buruk, atas-bawah, langit-tanah, dewa-buta.
Langkah Awal Sebagai Dasar Mempelajari Dharma Pawayangan
Sesungguhnya bagian manggala teks Dharma Pawayangan telah dengan jelas menyatakan bahwa kesadaran diri, kesadaran akan hakekat diri sejati menjadi sangat penting untuk menjadi sang mangku dalang. Diperlukan persiapan yang matang untuk dapat menyelami dan mengaplikasikan dharmaning sang mangku dalang dengan sadhana atau disiplin yang terjaga dalam laku kehidupan. Pengembaraan ke dalam diri dengan melampaui lapisan-lapisan kesadaran tubuh, emosi, pikiran, intelejensia, sehingga sampai kepada kesadaran diri sejati. Dalam tradisi Bali ini yang disebut dengan Kandan Jagat Daging Awak, Kandan Awak Daging Jagat.

Wayang | Foto: Dok. pribadi
Persiapan awal yang dilakukan dengan mempelajari lontar yang berkaitan dengan kelahiran dan keberadaan manusia. Lontar Anggastia Prana bisa menjadi salah satu acuan disertai dengan lontar Kanda Pat tentang kelahiran manusia dengan saudara empat. Lontar Dasaksara yang membahas tentang suara dan aksara (wreastra, swalalita, modre) dalam tubuh, panunggalan aksara yang berkaitan dengan lapisan kesadaran, aksara sebagai yantra, bija aksara dalam mantra. Pengetahuan, pemahaman dan sadhana yoga perlu dijadikan dasar penting. Karena dalam yoga dijelaskan dengan tuntas tentang keberadaan sang diri, disiplin yama dan niyama brata, memberdaya diri dengan olah pernapasan (pranayama) dan olah tubuh (asana), aliran nadhi dalam tubuh, kundhalini, sapta kandha, sapta Ongkara (tujuh lapisan kesadaran, tujuh cakra).
Gagelaran Dalang
“…mangkana sayogyanira sang dalang utama, siniwi ring jnyananira utama, mangisep tatwa carita, mangisep sarwa sastra ganal alit, ring bhuwana agung tekeng bhuwana alit, panunggalaning wayang ring jnyana ening, Paramasiwa ikana utama….”
Sepatunya seorang dalang yang utama (mangku dalang) beliau Sang Maha Dalang selalu dipuja dalam hati (hredaya, jnyana) yang utama, menyerap tatwa tutur (fisafat) dan cerita, menyerap semua sastra (swara, aksara) dan menyatu dalam diri, penyatuan alam semesta dalam diri, menyatukan wayang dengan diri dalam bathin yang suci, berada dalam kesadaran dan kekuatan Siwa yang tanpa batas itulah yang utama.
“….Sanghyang Menget tengah ing hati, anerius ring sabda, swara prakasa mijil maring hati, swara halus mijil maring nyali, swara galak amanis mijil maring papusuh, swara asih mijil maring tengahing ati, ring Smara Manodbawa. Mangkana sayogyaning swara mijil utama, denira Sanghyang Kawi Swara, murtining utama ring Dharma Pawayangan, binusana de sang amangku dalang.
Sanghyang menget di tengah ati, mengalir pada suara, suara prakasa dari hati, suara halus keluar dari nyali, suara galak manis keluar dari jantung, swara lulut asih keluar dari tengah hati, yang dijiwai keindahan Hyang Smara, demikianlah hendaknya mengeluarkan suara yang utama, yang diwujudkan oleh beliau Sanghyang Kawi Swara, semua perwujudan dari kautamaan Dharma Pawayangan, diketahui dan dijalankan oleh sang amangku dalang.
“…mangkana tingkah dalang utama, wekasira Sanghyang Gururekha, Hyang Saraswati, Hyang Kawiswara anggawa ring bayu sabda idep, ya ta sadenira angregepana, kadi ling aksara iki…”
Demikianlah perilaku seorang dalang utama, perwujudan Sanghyang Gururekha, Hyang Saraswati, Hyang Kawiswara dibawa (manunggal) dalam energi, suara, dan pikiran, itulah yang disatukan dan ditransformasikan, seperti yang diamanatkan dalam aksara ini.
Apa yang diuraikan dalam tiga alinea di atas sudah dengan jelas menyatakan apa yang mesti menjadi gagelaran atau kekuatan, modal dasar yang harus dikuasai oleh sang mangku dalang. Pada suatu kesempatan penulis pernah bertanya kepada Pekak Nyoman Rajeg (almarhum) seorang dalang dari Desa Tunjuk, Tabanan. Pertanyaan saya kepada beliau, apa sesungguhnya yang menjadi gagelaran seorang dalang. Penulis mengharapkan suatu jawaban yang sangat spesial dan rahasia, selain Dharma Pawayangan.
Beliau dengan singkat dan tegas menjawab pertanyaan penulis hanya dengan tiga kata, bahwa gegelaran seorang dalang adalah Ucap-ucap Tatwa Carita. Setelah lama dipikirkan dan direnungkan dengan dalam bahwa apa yang beliau katakan itu juga yang ditulis dalam teks Dharma Pawayangan. Ucap-ucap Tatwa Carita menjadi formula yang sangat efektif untuk sampai kepada Inti Dharma Pawayangan. Dalam phrase Ucap-ucap Tatwa Carita sudah mencakup penerapan teori dan praktis dalam upaya memberdaya diri sehingga menjadi seorang dalang. Dalam proses pembelajaran bertolak dari penguasaan pengetahuan dan ketrampilan seni, filsafat dan spiritual. Selanjutnya dibahas secara ringkas apa yang dimaksud dengan Ucap-ucap Tatwa Carita.
Ucap-ucap
Seorang dalang harus mempunyai modal suara yang bagus. Suara diberdayakan dengan teknik olah vokal yang benar. Pemahaman letak dan fungsi instrument (organ) dalam tubuh yang memproduksi suara menjadi penting. Dengan demikian diketahui sumber suara dan kekuatan kapasitas suara. Setiap orang mempunyai kapasitas (intensitas) suara yang berbeda-beda sesuai dengan organ produksi suara yang dimiliki, ini berkaitan dengan bawaan lahir setiap individu yang menjadi ciri khas dan keunikan warna suara, tonika suara, keras lembut, luas wilayah nada, dan tinggi rendah nada suara yang bisa dicapai.
Menembang (angidung), kemampuan menyanyi yang bagus menjadi suatu keharusan bagi sang dalang. Bagaimana membangun melodi, dengan elaborasi, ornamentasi, dengan teknik yang benar sesuai dengan jenis tembang yang dilantunkan. Kemampuan improvisasi melodi menjadi penting untuk menghadirkan ruang penceritaan, mood, penghayatan dalam imajinasi penonton. Kepekaan nada dan laras menjadi kunci, oleh karenanya penguasaan musik menjadi dasar utama.
Mengolah suara untuk berbagai karakter wayang memerlukan teknik dan latihan khusus dan konsisten. Bagaimana gaya irama (klentum) karakter keras, halus, panasar, dan karakter asura digarap dengan kemampuan bersuara yang memadai. Kemampuan bersuara keras (ngerak, ngelur, gregel gempuk, mengad) untuk kepentingan penggambaran suasana adegan, suasana dramatik dalam keseluruhan alur lakon memerlukan teknik olah vokal yang cukup berat.
Kemampuan berbahasa, baik itu bahasa Kawi dan bahasa Bali merupakan kebutuhan primer. Penguasaan kosa kata, gaya bahasa, aturan sor singgih basa, bagaimana menyusun kalimat yang benar dan efektif sesuai dengan kepentingan dramatic pewayangan. Kemampuan retorika yang baik menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan menyampaikan semua gagasan yang dibangun dalam antawacana, sehingga bisa ditangkap oleh penanggap (audience).
Untuk latihan olah vokal dalang bisa dibarengi dengan latihan pernapasan atau pranayama. Bagaimana penarikan napas, penahanan napas atau napas jeda, dan menghembuskan napas ( puraka, kumbaka, recaka). Latihan pernapasan menjadi penting karena berkaitan langsung dengan prana (life force), yang mempengaruhi ketenangan pikiran dan control emosi. Oleh karenanya sadhana yoga menjadi bagian dalam kehidupan sang dalang yang secara otomatis membangun vitalitas suara dan juga sebagai seni pemberdayaan diri (Patanjali Yoga Sutra, Dharma Patanjala).
Keseluruhan proses olah suara bisa dilakukan bersamaan dengan pembacaan sastra Kawi-Bali. Belajar menembang dilakukan bersamaan dengan pembacaan kakawin (tembang gede), geguritan (tembang macepat), dan kidung (sekar madya). Setiap pembacaan kakawin tentunya langkah awalnya harus mampu menembangkan berbagai metrum wirama. Dalam proses inilah latihan olah suara dilakukan, sehingga dalam belajar menembang memperoleh penguasaan sastra, nilai dan makna kehidupan dalam sastra, filsafat dan spiritual, yang memberikan pencerahan. Pembacaan sastra parwa yang dilakukan dengan palawakia (bahasa berirama) juga bermanfaat untuk olah suara dalang karena palawakia sebagai dasar ucapan antawacana wayang. Ada ungkapan dikalangan praktisi sastra Kawi-Bali “Melajah sambilang matembang, matembang sambilang malajah” yang berarti, belajar (tentang kehidupan) sambil bernyanyi, bernyanyi sambil belajar.
Lebih jauh lagi, setelah segala bentuk olah suara untuk kepentingan pewayangan dikuasai, yang lebih penting lagi harus dipelajari adalah suara kaitannya dengan pengembaraan ke dalam diri untuk sampai kepada hakekat diri sejati. Proses ini dilakukan dengan mendalami aksara (dasaksara), bagaimana suara dari setiap bija aksara menjadi vibrasi yang mengantarkan kepada kesadaran lapisan-lapisan kesadaran dalam tubuh (sapta kanda, sapta Ongkara) sampai kepada suara aksara Pranawa yang menjadi sumber kehidupan.
Tatwa
Sang mangku dalang tentunya harus menguasi tatwa atau filsafat dan Spiritual. Tatwa adalah sistem filsafat yang ada di Bali. Kata tatwa berasal dari bahasa Sanskerta (tattva) yang artinya kebenaran atau kenyataan (Adhi, 2015: 1 dalam Wicaksana, 2018: 265). Dalam lontar-lontar di Bali, kata tattva inilah yang dipakai untuk mengatakan kebenaran itu, karena dalam memandang kebenaran itu berbeda-beda, maka kebenaran itu tampaknya berbeda-beda, sesuai dengan segi memandangnya, walaupun kebenaran itu tetap satu adanya. Lontar-lontar yang memuat tentang tatwa adalah; Bhuwana Kosa, Bhuwana Sangksepa, Jnyana Siddhanta, Ganapati Tatwa, Wrhaspati tatwa, Tatwa Jnyana, dan yang lainnya.
Dalam hemat penulis dalam karya sastra kakawin juga ada yang memuat ajaran filsafat seperti Kakawin Sutasoma, kakawin Dharma Sunia, dan salah satu geguritan yang memuat ajaran yoga dan samkya adalah Geguritan Sucita-Subudi karya Ida Ketut Jelantik (almarhum) dari Geria Banjar, Buleleng.
Ajaran filsafat selalu hadir dalam pertunjukan wayang, dikemas dalam cerita dan antawacana atau dialog wayang, disajikan dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga bisa dipahami oleh penonton. Disinilah wayang hadir sebagai tuntunan yang senantiasa memberikan tuntunan kehidupan yang mengantarkan kepada pencerahan spiritual. Mengalami keindahan (angelung lango) dan mengalami pembebasan, pencerahan jiwa (Janyana hening, mukti, jiwan Mukti).
Carita
Penguasaan berbagai cerita pewayangan merupakan kewajiban bagi sang mangku dalang. Cerita bersumber itihasa Ramayana, Mahabharata, dan Bodha Carita. Cerita Ramayana dan Mahabharata di Bali dapat dibaca dalam lontar kakawin, parwa dan kanda. Bagaimana cerita-cerita tersebut digarap dan ditransformasikan menjadi pertunjukan wayang merupakan keahlian dan kecerdasan imjinasi, dan kreativitas penciptaan sang dalang yang disebut dengan Kawi Dalang.
Ketika mendalami cerita wayang sang mangku dalang juga mendalami filsafat, etika, dan keindahan (lango). Ramayana dan Mahabharata merupakan cerita yang sangat panjang yang di dalamnya memuat berbagai peristiwa dan konflik, fenomena kehidupan seperti; kekuasaan, pemerintahan, politik, percintaan, idialisme, strategi perang, dharma, sebab akibat, pencerahan dan pembebasan (moksa). Juga berbagai mahluk yang terlibat dalam cerita itu seperti; manusia, raksasa, dewa, asura, wenara, denawa, deitya, pisaca, para naga, gandarwa, apsara, kinara, para siddha, wil, danuja, dan yang lainnya. Pencapaian teknologi juga menjadi bagian cerita seperti cupu manik astagina, dibya caksu, berbagai senjata canggih (senjata dewa) seperti Brahma astra, brahma sirah, geni astra, wijaya capa danu, pasupati, cakra sudarsana, dan kendaran terbang canggih wimana. [T]
Daftar Bacaan
Hooykaas, C, 1973. Kama and Kala, Materials for The Study of Shadow Theatre in Bali, Verhandelingen Der Koniklje Nederlandse Akademi van wetenschappen, Afd. Leteerkunde Nieuwe Reeks, Deer 79 North, Holland Publishing Company-Amstredam, Londen.
Krishna, Anand, 2015. Yoga Sutra Patanjali Bagi Orang Modern, PT. Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia, Jakarta.
Shringy, R.K., Prem Lata Sharma, 2018. Sangitaratnakara of Sarngadeva, Text and English Translation Vol. I, Munshiram Manoharlal Publisher Pvt. Ltd.
Sudarta, I Gusti Putu, 2019. Kidung Hredaya Saking Swara Ngarcana Ishwara Mengembara Dalam Diri, Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta.
Sugriwa, I Gusti Bagus, 1963. Ilmu Pedalangan/Pewayangan, Diterbitkan Oleh Konservatori Karawitan Indonesia, Denpasar, Bali.
Wicaksana, I Dewa Ketut, 2018. Implementasi Estetika Hindu Dharma Pawayangan Oleh Dalang Wayang Kulit Di Bali, Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.







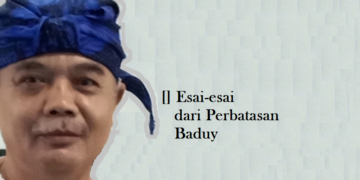















![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)










