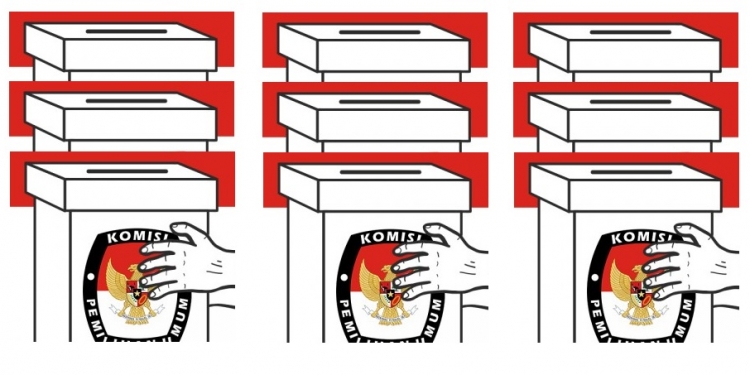“Piye Kabare, Penak Zamanku To….”, tulisan seperti ini biasa kita jumpai jika melintas di jalur protokol nasional, seperti jalur pantura atau jalur jawa – bali. Tulisan seperti ini biasanya terpampang besar-besar di pantat truk, atau tertempel kecil disudut mobil pribadi, menjadi hiburan tersendiri bagi pengendara baik mobil maupun motor. Biasanya disamping tulisan ini terpampang gambar presiden kedua RI, yakni presiden soeharto, yang tampak tersenyum sumringah, sambil melambaikan tangannya.
Salah satu penanda beda antara zaman “ dulu “ dengan zaman “ sekarang “ adalah rutinnya pemilihan langsung, dari pemilihan kepala desa, pemilihan kepada daerah, anggota dewan perwakilan rakyat, hingga pemilihan presiden. Hajatan ini seperti serimonial rutin layaknya hari raya, penuh hiruk pikuk, pesta, namun juga diselingi konflik dan keributan.
Masyarakat sebagai institusi sosial tak pernah sepi dari konflik, layaknya bagian yang melekat dan tak terpisah. Jika zaman Soeharto konflik diminimalisir dan diredam, maka yang tampak dipermukaan hanya stabilitas dan ketenangan. Namun potensi konflik ketika itu tetap ada bersifat laten, yang akhirnya meledak, yang bukan saja menjungkalkan dirinya dari kekuasaanya, namun juga membangkitkan perubahan sosial yakni reformasi. Pada periode awal reformasi segala konflik yang dulunya bersifat laten, muncul kepermukaan. Maka masa lalu digugat, perombakan terjadi disegala bidang.
Dari sudut pandang sosiologi konflik tidak saja bermakna negatif yang bersifat merusak, namun juga bisa bermakna positif, yakni dapat memicu perubahan sosial dan konformitas yang baru. Konflik pada dasarnya berawal dari tidak meratanya distribusi kekuasaan, sumber materi atau kekayaan, dan status sosial atau prestise. Beberapa kelompok terlalu dominan dalam penguasaan sumber kekuasaan, sehingga memiliki kesempatan membentuk tatanan sosial yang diperlukan untuk mempertahan “status quo “ dan mengelaminir pihak-pihak yang menentang mereka.
Mengapa kita menyelenggarakan ritual konflik dan melembagakan konflik ini melelui institusi yang bernama pemilihan langsung?
Sebenarnya tujuan pelembagaan ini bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi konflik yang bersifat positif, yakni bagaimana konflik bisa dijadikan sebagai sarana mekanisme perubahan sosial dan melakukan penyesuaian melalui berbagai konformitas, pendistribusian kembali kekuasaan dan wewenang.
Pihak-pihak yang bertarung dalam pemilihan umum akan mempertarungkan ide dan gagasan, mereka akan saling bantah dan saling tuding, lalu dari sana akan ditemukan suatu formula untuk perbaikan bersama. Seharusnya hanya kandidat yang mampu menemukan masalah sekaligus solusi yang memenangkan kontestasi itu. Pemenang diharapkan juga mampu meredam dan mendamaikan berbagai pihak yang berbeda dengan sebuah konformitas baru.
Namun hal seperti itu tak tampak menonjol saat ini, yang terjadi malah akumulasi sumber-sumber kekuasaan, melalui money politik, mobilitas aparatus Negara, dan politisasi undang-undang, termasuk penyebaran hoak dan penggiringan opini melalui akun-akun buzzer. Dengan kata lain, kekayaan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar, kekuasaan digunakan untuk kekuasaan yang lebih besar lagi atau bersifat akumulatif.
Sasaran dan tujuan pemilihan yang memicu konflik belum sepenuhnya terjadi, konflik masih terlihat bersifat negatif, belum menumbuhkan konflik yang bersifat positif dan membangun. Untuk mengatasi gap ini, pendidikan demokrasi sebaiknya sejak dini diperkenalkan pada generasi muda. Pelatihan kemampuan berorganisasi juga sudah selayaknya dikembangkan, bahkan di tingkat pendidikan dasar, bagaimana sebuah organisasi dikelola, bagaiman sebuah ide dikemukakan dan dikembangkan, dan bagaimana konformitas dilakukan terhadap pihak-pihak yang berbeda.
Demokrasi sejatinya adalah pengorganisasian, baik orang maupun ide dan gagasan. Tanpa kemampuan berorganisasi tampaknya perubahan sosial akan sulit terjadi. Dalam sejarah bangsa kekuatan rakyat dapat tumbuh melalui pengorganisasian elemen rakyat, melalui serikat-serikat, baik serikat buruh, petani maupun serikat yang bersifat modern seperti partai politik. Hal itu dapat dibentuk karena adanya kesadaran yang kuat dikalangan elemen bangsa, meskipun saat itu dalam suasana penuh tekanan akibat penjajahan yang membelenggu kebebasan rakyat.
Saat ini, di era kemerdekaan ini, seharusnya elemen masyarakat lebih mampu dan bisa dibandingkan pendahulu kita dimasa penjajahan itu, apalagi didukung teknologi dan informasi yang nyaris tanpa batas. Menjadi menarik mengapa hal itu tak terjadi? Apakah ada kekuatan status quo yang beroperasi layaknya penjajah kolonial dulu? Mengapa keinginan kembali ke dalam suasana penuh tekanan bisa ada dan muncul, seperti kemunculan gambar dan kata-kata pak harto diatas? Apakah ini pertanda masyarakat tak mampu memanfaatkan kebebasanya, atau malah kebebasan yang didapat sekarang dirasa menyiksa hingga harus perlu kembali hidup dalam kendali dan pengawasan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa menjadi panjang dan berlanjut, namun satu yang pasti; ada yang salah dengan kita.