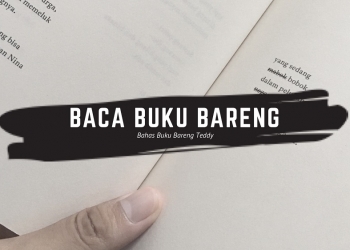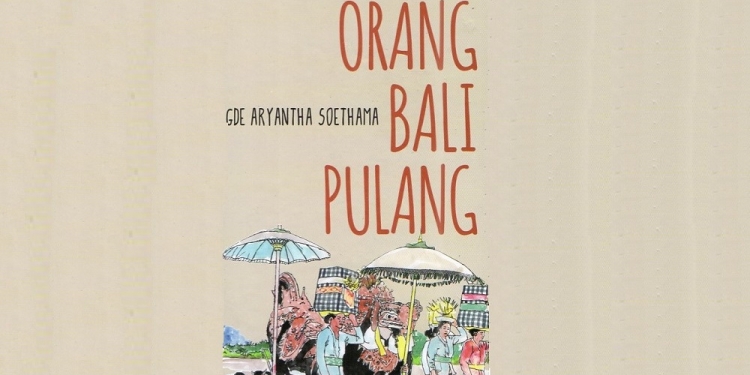Tak selamanya essai ditulis dengan gaya yang kaku dan akademis. Tak jarang essai yang saya temukan memiliki gaya yang begitu santai namun tidak lepas dari substansi pembahasan. Dan, cara penulisan santai tanpa melupakan substansi pembahasan yang sekarang coba saya dalami. Tentu angka-angka, matriks, grafik yang merupakan bagian dari kesatuan yang disebut sebagai data sangat penting dalam penulisan essai—sebagai dasar penulis dalam menyusun argumentasi pula. Tapi hasil pengamatan atau observasi dari penulis pun juga tak kalah penting dilakukan, bisa juga dijadikan dasar dalam menyusun argumentasi. Memang milenials sekali sih saya, karena saya lebih menyukai essai yang penulisannya santai, berdasarkan observasi—tentu karena menurut saya lebih mudah dipahami. Inilah yang saya temui dari buku anyar dari salah satu Sastrawan Bali Gde Aryantha Soethama yang berjudul “Orang Bali Pulang”.
Berkenalan dengan “Orang Bali Pulang”
Buku ini lahir di pertengahan tahun 2020 lewat asuhan Prasasti—penerbit yang notabene diasuh langsung oleh Gde Aryantha Soethama. Buku yang berisikan 70 essai ini terbagi menjadi delapan bagian. Memuat berbagai persoalan tentang Bali, salah satunya soal konsep pulang di konsep Hindu Bali sebagai tema utama. Buku setebal x + 264 halaman ini juga berhasil menyadarkan saya bahwa Bali sebagai daerah wisata menyimpan berbagai kekayaan, juga bersamaan dengan itu menyimpan potensi permasalahan yang begitu kompleks.
Tak hanya soal pulang, di dalamnya juga menghadirkan berbagai essai singkat soal kuliner, filosofi hidup, tata laku, budaya, serta laku spiritual masyarakat Bali. Tentu seperti saya katakan di awal, Gde Aryantha Soethama menunjukkan tajinya dalam menyampaikan hasil observasinya. Ia juga menghadirkan berbagai bentuk cara penulisan untuk menyampaikan substansi pembahasan. Salah satunya hadir pada essai dengan judul “Tahu Bali Lena-Leni” (hal. 54). Dibuka dengan aktivitas kemah budaya, disana diceritakan terjadi pertemuan dua perempuan yang memiliki banyak kemiripan—salah satunya nama. Dilanjutkan dengan dialog imajiner dua tokoh tersebut yang diakhiri dengan dialog solutif. Biar saya kutipkan narasinya:
“Menjelang balik ke Manado, Lina menyodorkan gagasan kepada Leni. “Bagaimana kalau kita kemas tahu bali, dan kita jual ke swalayan?”
Dari kalimat sederhana di atas, secara tidak langsung saya bisa menangkap kalau ada gagasan yang ditawarkan kepada pembaca. Ya, gagasannya adalah mengkemas produk-produk mentah hasil masyarakat sehingga memiliki nilai lebih untuk Kembali dipasarkan. Tentu hal ini menjadi refleksi penulis bahwa sesungguhnya banyak produk yang sebenarnya bisa dipasarkan dengan nilai tinggi, tetapi cara pengemasan yang kurang menarik membuat produk asli Bali seperti tahu sukawati tersebut tak memiliki nilai lebih di mata pasar.
Andai masyarakat mau untuk mengolah lebih lanjut ditambah dengan pengemasan yang ciamik tentu harga akan bisa didongkrak, dan pendapatan masyarakat juga meningkat. Kan lumayan buat beli janur dan kawan-kawan untuk menyambut hari raya.
Menyelami Konsep Pulang
Pulang buat banyak orang menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Apalagi saya pekerja kantoran, tentu sangat menanti waktu pulang. Ya, setelah pulang saya bisa melepas penat dari lelahnya bekerja seharian. Tapi nyatanya, pulang memiliki makna lebih dalam dari definisi sederhana yang saya sampaikan di awal tadi.
Pulang identik dengan rumah, ya biasanya orang pulang pasti ke rumah atau sebutan lainnya. Khusus bagi masyarakat Bali sejak dulu hingga kini nampaknya masih meyakini bahwa pulang tak hanya diperuntukkan untuk rumah di dunia saja, melainkan juga di alam lain (niskala). Sehingga buat masyarakat Bali sendiri, pulang adalah sebuah kepastian—entah pulang ke rumah secara sekala atau pulang secara niskala yang hanya bisa diakses lewat kematian. Sedangkan rumah hanya tempat untuk singgah saja, karena rumah sifatnya sementara bagi masyarakat Bali yang meyakini bahwa pulang merupakan bagian dari satu lingkaran reinkarnasi.
Essai berjudul “Orang Bali Pulang” (hal. 38) menjadi salah satu dari beberapa essai panjang dalam buku ini. Essai ini menggambarkan bagaiman tata laku masyarakat Bali dalam menyambut kepulangannya atau kerabat mereka. Penulis juga mengaitkannya dengan fenomena “dipaksanya” pekerja migran untuk pulang karena Covid-19. Kepulangan yang biasanya disambut riuh dan penuh suka cita kini penuh balutan kesunyian. Hanya tenaga medis yang menyambut memastikan pekerja migran kembali dalam kondisi sehat untuk selanjutnya diantarkan ke tempat karantina. Ada hal menarik yang patut digarisbawahi oleh saya, mungkin juga kalian. Pulang bukan menjadi tanda seseorang menyerah, tetapi pulang menjadi titik awal seseorang merefleksikan apa yang terjadi sebelumnya untuk memulai semuanya dari awal.
Bali Unik Lewat Istilahnya
Tentu buat saya yang memang sejak kecil lahir dari komunitas masyarakat Bali yang kental mengetahui berbagai istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan sebuah maksud. Ungkapan tersebut kalau bahasa Balinya mekulit atau masih harus dimaknai kembali. Tapi, kalau berbagai ungkapan digunakan saat bercengkrama dengan sesama masyarakat Bali yang fasih, tentu tidak akan jadi masalah.
Istilah mekulit yang masyarakat Bali gunakan kini pun sesungguhnya berangkat dari berbagai fenomena. Jadi singkatnya, istilah-istilah tersebut untuk mengungkapkan suatu sikap atau tindakan yang dilakukan. Jadi istilah itu tercipta untuk memperkaya khazanah bahasa dalam pergaulan masyarakat. Menariknya dalam buku ini, penulis menulis keasalmulaan dari beberapa istilah yang kerap kali digunakan dalam pergaulan. Apa saja itu? Tentu saya akan cantumkan beberapa. Karena gak asik kalau semua saya cantumkan.
Pertama ada istilah Ngelawar Capung. Sebagai orang Bali, saya pun baru mengetahui keberadaan istilah ini—istilah yang akrab saya dengar, begitu juga saya gunakan dalam percakapan bertemakan tentang capung ya hanya “Mandi Capung”. Essai ini bisa dibaca pada halaman 13—ringkasnya bahwa Ngelawar Capung memiliki arti sekelompok orang yang melakukan kegiatan tidak efisien, kelihatannya saja wah tapi hasilnya sedikit nyaris nihil.
Istilah menarik lainnya ada “Kopi Ngaben”. Istilah satu ini berhasil membuat saya menyerngitkan dahi, sebab saya harus dibuat berpikir apa sih keistimewaan dari kopi ngaben? Setelah membaca essai Kopi Ngaben (hal. 58) ini secara penuh, maksud dari istilah ini adalah takaran kopi yang didapat. Kalau dipikir-pikir, istilah ini lahir dari tata laku yang sudah mandarah daging di masyarakat adat kita. Setia pada pelaksanaan upacara adat—seperti ngaben misalnya, si empunya acara pasti menyiapkan minuman berupa teh atau kopi untuk para tamu yang hadir menyampaikan bela sungkawa. Ini hanya kemungkinan yang saya munculkan ya, kenapa istilah ini muncul, jadi saat melayani tamu saat menyuguhkan minuman, si empunya acara terburu-buru. Terburu-buru yang dimaksud adalah agar taka da tamu yang menunggu minuman terlalu lama. Jadilah takaran kopi setengah gelas yang oleh penulis diistilahkan sebagai kopi ngaben. Tentu jika saya atau kalian disuguhkan kopi takaran setengah gelas, bisa menyebutnya sebagai kopi ngaben. Hehehe.
Gagah atau Digagahi
Kumpulan essai yang dihimpun dengan baik dalam sebuah buku berjudul “Orang Bali Pulang” buat saya sendiri bisa menjadi bahan evaluasi. Tak hanya buat saya, tapi buat masyarakat Bali secara umum. Pariwisata saat ini sudah menjadi “Panglima Perang” ekonomi di Bali. Setiap jengkal tanah Bali “dipaksa” melayani berbagai aktivitas wisata dan bersamaan dengan itu pula, masyarakat Bali sibuk dengan berbagai upacaranya.
Kini Bali sedang terpuruk di jurang terdalam sejak kali terakhir merasakannya pasca Bom Bali I tahun 2002. Covid-19 berhasil merubah tata laku masyarakat—juga memaksa Bali menepi sejenak dari riuhnya hingar bingar ekspose manca negara. Konsekuensinya ya ekonomi masyarakat lumpuh, sesegera mungkin mencari alternatifnya. Dulu Bali terlihat gagah dengan pariwisata yang moncer, tiap tahun berhasil menyumbang devisa kepada negara triliunan, selalu saja menemukan destinasi wisata baru untuk wisatawan.
Kini? Semua berbalik begitu cepat. Begitu banyak kepemilikan aset wisata berada di tangan asing, masyarakat Bali sebagian besar hanya sebagai penonton—bangga menjadi tim hore dalam gemerlapnya wisata Bali. Merasa tak cukup, anak muda Bali berbondong-bondong mencari peruntungan di Kapal Pesiar dengan harapan ketika pulang sudah membawa jutaan dollar dari kerjanya. Namun yang harus diresapi bersama, sampai kapan saya, anda, kita semua mengandalkan sektor ini? Sektor yang paling rentan karena harus menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan pelayanan di waktu bersamaan. Mari kita renungi bersama.[T]
BACA ULASAN BUKU LAIN DARI TEDDY